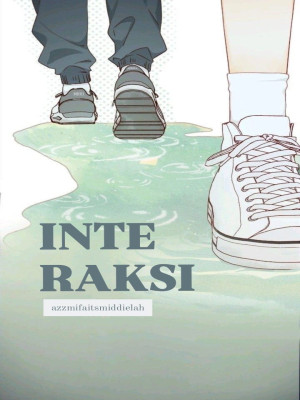Sakura duduk di ruang tamu yang terlalu rapi untuk menyimpan percakapan jujur.
Karpetnya rata, bantal sofanya simetris, dan aroma teh hijau melayang dari cangkir porselen yang dibiarkan dingin.
Namun semua itu tak lebih dari panggung, tempat pertunjukan kepatuhan yang diulang-ulang selama bertahun-tahun.
Kedua orang tuanya duduk di seberang.
Dipisahkan oleh meja rendah dan ribuan kilometer emosi yang tidak pernah dijembatani.
Ayahnya membuka pembicaraan.
“Kami tahu kamu dekat dengan… anak itu.”
Nada suaranya pelan tapi tegas. Bukan nada tanya. Bukan nada diskusi. Itu nada perintah yang dikemas dalam formalitas.
Dia tidak menyebut nama Arya.
Hanya “anak itu”.
Seolah dengan melafalkan namanya saja, reputasi keluarga bisa ternoda.
Sakura tidak menjawab.
Tangannya saling menggenggam di pangkuannya. Ia tidak tahu apakah ia sedang menenangkan diri… atau sedang mencoba bertahan agar tidak pecah di depan mereka.
***
Sakura menunduk. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan, seperti sedang menahan sesuatu agar tidak lepas dan berantakan. Tapi dalam diamnya, ada arus deras yang bergerak di bawah permukaan.
“Kamu tahu ada pameran seni bulan depan,” ibunya berkata sambil tetap menatap layar ponsel. “Kita sudah atur sponsornya. Mereka tidak akan senang jika tahu kamu... bercampur urusan semacam itu.”
Sakura mengangguk pelan. Tidak karena setuju. Tapi karena sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu.
Urutan hidupnya seolah sudah ditulis di agenda keluarga sejak ia bisa memegang kuas: sekolah seni privat, pelatihan musim panas di Italia, universitas di Tokyo, pameran galeri keempat sebelum usia 25. Ia pernah bangga. Tapi hanya karena semua orang bertepuk tangan ketika ia mengikuti rencana.
Bukan karena ia bahagia.
Ayahnya kembali bicara, nada suara lebih tenang, tapi jauh lebih mengancam:
“Kami tidak larang kamu bersahabat. Tapi kami minta kamu menjaga batas. Dan... mulai fokus kembali ke masa depan yang sudah kami bangun sejak kamu kecil.”
Dibangun sejak kamu kecil.
Sakura ingin bertanya, “Kalau semua sudah dibangun... untuk siapa?”
Apakah senyum di katalog seni itu miliknya? Atau milik ibunya yang selalu berdiri paling depan di pembukaan galeri? Apakah sketsa-sketsa yang tergantung di dinding rumah ini pernah benar-benar berasal dari tangan yang bebas, atau hanya tangan yang diajari cara menggambar sesuai selera juri?
Tapi ia tidak bertanya.
Karena di rumah ini, pertanyaan bukan sesuatu yang dicari jawabannya. Pertanyaan adalah gangguan. Kesalahan. Pembangkangan.
“Aku tahu kamu anak baik,” kata ayahnya, lebih pelan sekarang. “Tapi kamu tidak hidup di dunia fiksi. Hidup itu aturan. Aturan melindungi kita. Dan anak itu... dia bahkan tidak punya pijakan di sini.”
Anak itu.
Selalu “anak itu.” Bukan Arya. Bukan manusia. Bukan seseorang yang pernah mengantar Sakura pulang saat demam, yang menghafal cara dia suka tehnya diseduh, yang pernah bilang “kamu boleh marah, asal jujur.”
Bukan seseorang yang, bahkan dengan keterbatasan bahasa dan status, bisa membuat Sakura merasa seperti manusia.
Bukan lukisan.
Bukan piala.
Manusia.
Sakura menarik napas. Dingin. Tipis.
“Aku tidak bisa bohong soal perasaanku,” ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, tapi seperti menembus kaca.
Ayahnya terdiam sesaat.
Ibunya menatapnya untuk pertama kali malam itu.
“Kami tidak bisa melarang kamu memilih. Tapi kami juga tidak bisa terus menopang pilihan yang tidak kami setujui.”
Itu bukan ancaman.
Itu keputusan.
Pernyataan hukum dari institusi yang menyebut dirinya keluarga.
Dan Sakura hanya mengangguk. Tidak memberontak. Tidak menangis. Tapi terasa seperti ada yang retak pelan di dalam dadanya, bukan karena benturan, tapi karena tekanan yang terlalu lama tak diberi ruang.
***
“Kami tidak larang kamu bersahabat,” kata ayahnya.
“Tapi kami minta kamu menjaga batas. Dan... mulai fokus kembali ke masa depan yang sudah kami bangun sejak kamu kecil.”
Sakura diam.
Kata-kata itu membuat sesuatu dalam dirinya mengeras.
Dibangun sejak kamu kecil.
Untuk siapa?
Ia tidak pernah diminta untuk memilih.
Ia hanya diarahkan, seperti anak panah yang sudah ditarik sejak lama dan tinggal dilepas ke arah target yang sudah ditentukan.
Ayahnya menutup pembicaraan dengan satu kalimat dingin:
“Kami tidak bisa melarang kamu memilih. Tapi kami juga tidak bisa terus menopang pilihan yang tidak kami setujui.”
Itu bukan ancaman.
Itu keputusan.
Dan di ruang yang menyebut dirinya “rumah”, Sakura tahu: ini bukan lagi tempat untuk berpulang.
***
Setelah percakapan itu, Sakura kembali ke kamar.
Bukan lari, bukan marah. Tapi langkah-langkahnya seperti melayang di lantai rumah yang terlalu licin, terlalu bersih, terlalu asing, meski sudah belasan tahun diinjaknya.
Pintu ditutup. Bunyi klik-nya terdengar lebih keras dari biasanya.
Ia berdiri di tengah kamar sebentar, lalu duduk di ranjangnya yang selalu rapi seperti katalog majalah. Bantal tersusun presisi. Selimut dilipat simetris. Dinding putih. Karpet abu-abu. Cermin tinggi yang memantulkan wajahnya sendiri tanpa ampun.
Sakura membuka ponsel. Layarnya menyala.
Ada satu pesan dari Arya.
Dikirim dua jam lalu.
“Sampai jam berapa kamu di rumah Om? Perlu dijemput?”
Ia tidak langsung menjawab.
Malah menaruh ponsel itu di atas meja, seperti benda asing yang terlalu berat untuk disentuh.
Kamar itu terasa sunyi.
Sunyi seperti galeri seni yang sudah ditinggal pengunjungnya.
Ia berdiri pelan, berjalan ke meja kecil di pojok ruangan.
Di sana, masih tergantung lukisan kecil yang ia buat saat SMA, pemenang lomba nasional. Gambar sebuah taman musim panas. Penuh warna, penuh teknik, penuh pujian. Tapi Sakura tahu: waktu menggambar itu, ia sedang tidak bahagia. Ia hanya sedang berusaha patuh.
Ia menarik kursi, duduk.
Memandang lukisan itu lama.
Lalu, tanpa sadar, membuka galeri ponselnya.
Foto-foto Arya berderet di layar:
Arya sedang tertawa di depan warung takoyaki.
Arya duduk di tangga belakang restoran, makan onigiri sambil cerita soal telur gosongnya.
Arya yang diam-diam memotret sepatu Sakura dan bilang, “Sepatu ini udah sering nemenin kamu lari dari capek ya?”
Arya yang matanya selalu serius waktu dengar, meski bahasa Jepang-nya kacau, dan bahasa Inggris-nya patah-patah.
Dan entah kenapa, Sakura merasa ingin menangis.
Bukan karena patah hati. Tapi karena terlalu lama hidup di rumah yang tahu cara mencetak anak berprestasi, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana cara mencintai tanpa takut salah.
Ia meraih ponselnya kembali.
Membuka pesan dari Arya.
Membaca lagi.
Lalu menulis balasan:
“Aku masih di rumah. Tapi nggak perlu jemput. Aku cuma... pengen sendiri sebentar.”
Jari-jarinya sempat ragu. Tapi ia kirim juga.
Lalu, diletakkannya ponsel itu di samping bantal.
Ia berbaring. Mata terbuka, menatap langit-langit.
Dan dalam sepi yang mendidih perlahan itu, Sakura mulai sadar:
Mungkin ini bukan tentang memilih antara rumah dan cinta.
Tapi memilih: mana yang benar-benar membuatnya merasa hidup.
***
Pagi berikutnya, langit masih kelabu ketika Sakura turun ke dapur.
Ibunya sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi dari cangkir porselen berwarna pastel, tanpa berkata apa pun. Ayahnya belum tampak. Rumah sunyi. Seperti biasa.
Sakura tidak duduk.
Ia hanya berdiri sebentar, lalu membuka kulkas, mengambil air minum. Tangannya tenang. Tapi dadanya seperti ruang kosong yang tak bisa diisi dengan apapun kecuali satu hal: keberanian.
“Jangan lupa pameran minggu depan,” kata ibunya, masih tanpa menoleh.
Suara itu tidak bernada larangan, juga bukan perhatian. Hanya pengingat dingin, seperti alarm yang diatur tanpa cinta.
Sakura meneguk airnya. Lalu berkata pelan, “Aku nggak ikut.”
Ibunya berhenti menyeruput. Menoleh perlahan. Wajahnya datar, seperti tak percaya kata-kata itu muncul dari putrinya.
“Apa?”
“Aku nggak ikut,” ulang Sakura.
Nadanya tenang. Tapi jelas.
“Kenapa?”
“Karena bukan itu hidupku.”
Ada jeda. Lalu ibunya tertawa kecil, tipis, sinis.
“Kalau bukan itu hidupmu, lalu yang mana? Hidup jadi bayangan dari anak ilegal yang bahkan tidak punya masa depan di sini?”
Sakura tidak menjawab.
Tapi ia memandang lurus. Tidak menunduk.
“Lukisan kamu dipajang di katalog. Galeri siap investasi. Tapi kamu lebih pilih jadi... pengikut cinta picisan?”
Nada suaranya naik.
“Bukan cinta picisan,” kata Sakura. “Ini tentang jadi manusia. Bukan produk.”
Ibunya terdiam sejenak.
Lalu menggeleng. “Kamu tidak tahu apa yang kamu buang.”
Sakura tersenyum kecil. Senyum yang anehnya tidak getir.
“Justru aku tahu,” katanya.
“Aku buang kehidupan yang selalu menolak caraku merasa. Dan aku pilih yang mungkin berantakan… tapi jujur.”
Ia melangkah mundur.
Tanpa sepatu. Tanpa suara.
Naik ke kamarnya, mengambil ransel kecil.
Lalu keluar lewat pintu samping, sebelum ayahnya turun dari lantai dua.
Langkah pertamanya ke jalan terasa ringan. Dingin pagi menyentuh kulitnya, tapi dadanya justru hangat.
Dia tidak tahu akan ke mana malam ini.
Tapi untuk pertama kalinya, dia tahu: Ke mana pun ia pergi, itu adalah jalannya sendiri.
Dan mungkin, seseorang sedang menunggunya di ujung jalan itu.
Seseorang yang tak sempurna. Tapi selalu menatapnya tanpa syarat.


 quietsnowy
quietsnowy