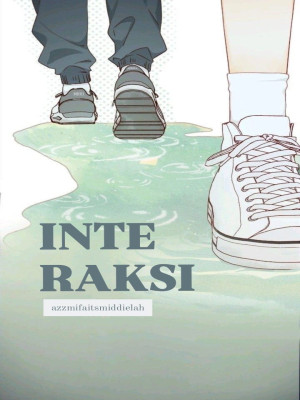MALAM minggu yang sepi seperti biasa
Arien melangkahkan kakinya keluar dari rumah menuju sebuah rumah yang berbeda blok dengannya
Tidak jauh-jauh amat, hanya lima kilometer
Arien memperbaiki posisi ransel kecil nya yang berisi alat tulis dan sabuk, menatap sekelilingnya yang berbeda kontras dengan daerah sekitar rumahnya yang bukan ganga isi rumahnya saja yang sepi, tapi luarnya juga
Kalau disekitar rumahnya ia akan mendapati rumah-rumah besar dengan halaman yang luas ditambah kelenggangan akibat kesenjangan sosial, maka disini ia akan mendapati rumah-rumah dengan ukuran beraneka ragam, kios-kios kecil dari kontainer dan keramaian malam minggu yang khas
Setelah melewati beberapa kerumunan, Arien tiba dirumah yang paling luas halamannya dibanding rumah-rumah disekitarnya
Sebuah rumah yang paling besar diblok itu, walau besarnya mungkin tidak sebesar runah Arien. Rumah milik guru beladiri-nya dengan pembantu-pembantunya
Arien masuk ke halaman yangmemiliki gerbang besi. Mendorongnya dengan mudah. Sebuah halaman luas nampak sejauh mata memandang dihadapannya
Ini tempatnya les pencak silat
Sudah ada beberapa anak murid Pak Dirman yang lain, duduk-duduk, bercengkrama sesekali tertawa. Mengangguk ringkas ketika Arien melewati mereka
Arien Sastra Utomo balas mengangguk. Terus berjalan menuju sudut halaman yang agak sepi, menaruh ransel yang hanya berisi buku sketsa dan sabuk pencak silat nya yang berwarna biru tua. Mulai memasangnya dipinggang begitu mendengar suara kunci dibuka, diiringi anak-anak murid yang lain yang bergegas membuat barisan
Arien mengikuti teladan teman-teman lesnya, bergabung kebarisan
Guru les mereka akhirnya datang, orangtua usia 80-an itu melangkah gagah di hadapan murid-murid nya. Untuk orang setua itu beliau masih mampu mengajar 60 murid dan mengingat dengan detail hal-hal yang terjadi dikehidupan nya.
Beliau sekali lagi mengencangkan sabuk nya yang berwarna hitam.
Semua siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Diantara kesibukan malam ala remaja-pemuda yang lainnya, mereka justru berkumpul dihalaman luas milik gurunya, mengasah kemampuan beladiri mereka.
Terkhusus untuk Arien, yang tadi sempat bertemu tidak sengaja dengan teman-teman nya sesama sirkel ABAS juga ditambah Arsel dan Dilan yang tengah berjalan menuju sebuah tempat makan
Tidak saling sapa, justru saling membuang pandangan. Mungkin merasa malu ada satu temannya yang tidak diajak justru bertemu dijalan
Hari kedua setelah kabut pagi hari itu
***
Seperti biasa
Arien menjadi murid terakhir yang menghadapi simulasi dari guru beladiri-nya
Dua sosok saling berkelit diantara kelebat malam di halaman luas itu yang hanya memiliki satu penerangan dari lampu yang berada di pojok halaman
Set! Suara angin yang dihantam tendangan terdengar
Buk! Disusul pukulan yang mengenai sasaran
Tak! Suara tongkat yang beradu
Dan terakhir, Buk! Sebuah pukulan lagi-lagi berhasil mengenai sasaran
Penonton nyaris bertepuk tangan seiring syara timer yang mendengking menjadi penutup simulasi seorang guru dengan murid beladiri-nya
Arien segera menghampiri gurunya yang dibuat terduduk olehnya, ingin membantunya berdiri. Dia merasa bersalah telah membuat gurunya jatuh.
Tapi, Pak Dirman menggeleng, tak apa, dia bisa sendiri. Begitu maksud gelengannya
"Ya, baik anak-anak. " Pak Dirman menghadap murid-muridnya yang lain "Cukup sekian latihan kita hari ini. Yang sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada Arien Sastra Utomo yang telah berhasil menyelesaikan level sabuk biru. Disaksikan malam, disaksikan kalian semua, saya berikan sabuk merah kepada Arien "
Kali ini teman-teman les Arien tidak bisa menahan tangan mereka untuk bertepuk tangan, satu dua bahkan bersiul. Yang disodorkan sabuk malah menelan ludah dengan berat, seperti orang yang sedang berusaha menelan obat
Arien menghela napas pelan. Baiklah, diterima dulu. Nanti ketika teman-temannya pulang dia akan mencoba bicara dengan Pak Dirman
Arien menerima sabuk yang diserahkan Pak Dirman. Begitu sabuk berada ditangannya ia segera membungkuk ringan memberi ucapan terimakasih, Pak Dirman balas membungkuk ringan
Sepuluh menit kemudian, halaman luas itu telah sepi. Menyisakan Arien dengan gurunya
Arien mengepalkan tangannya, menghela napas, meneguhkan hati untuk memulai bicara dengan gurunya yang bertampang sangar ini
Gadis itu baru membuka mulutnya ketika Pak Dirman tersenyum "aku tahu apa yang hendak kau bicarakan"
Arien menelan ludahnya sekali lagi. Tidak salah orang-orang bilang pria dihadapannya ini sakti, tapi Arien lebih menyukai apa yang Ayah ibunya katakan kalau itu semua insting level tinggi, insting yang telah melewati banyak peristiwa dalam kehidupannya. Semua orang bisa membaca apapun yang hendak orang lain lakukan dari gerak tubuh, kernyitan alis dan tatapan mata. Mungkin dia belum bisa melakukan itu semua sekarang, tapi dewasa nanti dia akan bisa 'membaca' gerakan orang seperti gurunya.
"Kau pasti hendak bilang tidak pantas mengenakan sabuk merah itu"
Arien hanya menunduk, tidak mengangguk tidak juga menggeleng
Pak Dirman tidak menuntut jawaban. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mendongak menatap langit yang mulai ditaburi gemintang
"Aku sudah tahu sejak awal," ujarnya, suaranya tenang tapi terdengar berat. "Kau selalu merasa tak cukup. Terlalu keras pada dirimu sendiri. Tapi kau lupa, pencak silat bukan cuma soal menang atau kuat. Ini soal bertumbuh."
Arien masih diam. Sabuk merah di tangannya terasa lebih berat daripada biasanya. Bukan karena bobotnya, tapi karena arti yang disandangnya.
Pak Dirman melangkah perlahan ke sisi lapangan, memungut sepotong kayu kecil, lalu melemparkannya ringan ke kejauhan. "Kau tahu," lanjutnya, "kadang seorang murid yang terbaik bukan yang paling cepat naik sabuk, tapi yang paling dalam memahami maknanya."
Pak Dirman berjalan pelan menuju teras. Disana ada dua gelas plastik berisi teh manis hangat. Ia menaruh salah satunya di samping kanannya, lalu duduk bersila di atas lantai semen berdebu, tak jauh dari tempat latihan biasa.
“Nduk,” panggilnya, “kemarilah duduk. Malam ini tak perlu terburu-buru pulang.”
Arien menurut. Ia duduk di samping gurunya, sabuk merah masih digenggam di pangkuan.
“Gimana rasanya?” tanya Pak Dirman setelah menyesap tehnya. Suaranya lembut, berbeda dari saat ia memberi instruksi keras di tengah latihan.
Arien butuh beberapa detik untuk menjawab. “Berat, Pak. Saya malah bingung harus merasa apa.”
Pak Dirman tertawa kecil. “Itu bagus. Kalau kamu langsung merasa bangga, saya justru khawatir.”
Mereka diam sejenak. Suara malam menyusup di antara celah-celah nafas mereka. Jauh di ujung halaman, suara jangkrik dan kodok bersahutan.
Arien menatap sabuk merah itu dengan dahi mengernyit. “Pak… saya belum pantas. Saya tahu masih banyak gerakan yang saya belum sempurna. Saya masih sering ragu.”
“Kamu tahu kekuranganmu. Itu yang membuatmu lebih pantas dari banyak orang.”
Pak Dirman menoleh, matanya menatap tajam namun lembut. “Sabuk ini bukan lambang kamu sudah hebat. Tapi tanda bahwa kamu siap mengemban amanah untuk melindungi. Bukan cuma orang lain, tapi juga dirimu sendiri.”
Arien mengangguk kecil. Tapi hatinya masih penuh gemuruh.
Pak Dirman bersandar sedikit, meregangkan punggung. “Dulu saya juga begitu. Waktu naik sabuk, rasanya seperti dapat beban yang lebih besar dari kemampuan saya sendiri. Tapi kadang, justru dari situlah kita belajar menjadi lebih kuat.”
Arien tersenyum kecut. “Saya masih belum bisa membaca gerakan lawan seperti Bapak.”
“Bisa nanti. Pelan-pelan. Yang penting kamu tetap jujur pada dirimu sendiri.”
Lalu, dengan nada yang lebih dalam, Pak Dirman melanjutkan, “Kalau suatu saat nanti kamu merasa harus berhenti, atau mengambil jalan lain… jangan merasa bersalah. Hidup itu bukan soal siapa yang paling lama tinggal. Tapi siapa yang paling tahu ke mana hatinya ingin pergi.”
Kalimat itu menggantung di udara malam.
Arien menoleh pelan. Wajah Pak Dirman tampak tenang, tapi letih. Sorot matanya mengandung sesuatu yang tidak biasa. Seperti orang yang tahu waktunya tak banyak, tapi memilih untuk memberi lebih daripada mengeluh.
“Pak…” gumam Arien, suaranya nyaris tenggelam dalam desir angin.
“Saya bangga padamu, Arien.” kata Pak Dirman. “Bukan karena sabuk ini. Tapi karena kamu tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan.”
Ia menatap Arien lama. "Sabuk merah itu bukan akhir. Tapi awal dari jalan baru. Kau sudah sampai di titik itu, dan itu artinya… aku sudah bisa tenang."
Arien mendongak sedikit, ada sesuatu di dada yang menegang.
"Lanjutkan perjalananmu, Arien. Tak harus selalu di lapangan ini. Bahkan kalau pun kau memilih berhenti, asal kau tidak berhenti belajar, itu cukup buatku."
"Dan jangan lupa, kemampuan ini untuk membela kebenaran, bukan untuk kepentingan keegoisan pribadi"
Arien menunduk. Kali ini bukan karena malu. Tapi karena ada sesuatu yang hangat mengalir di balik dadanya, menyesak, tanpa bisa dijelaskan.
Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka berbincang.
Yang ia tahu, gurunya bicara seperti seseorang yang hendak pamit tanpa benar-benar berpamitan.
Dan sabuk merah itu… untuk pertama kalinya terasa begitu berat—tapi tidak menakutkan. Berat, karena ia tahu siapa yang mempercayakan itu kepadanya.
***
Dua hari setelah malam itu
Langit Bogor mendung sejak pagi. Arien baru saja tiba di rumah sepulang sekolah, belum sempat meletakkan tas ketika suara ibunya memanggil dari ruang tengah, nadanya pelan… terlalu pelan.
“Rien,” kata Ibu. “Bisa sebentar sini?”
Arien menghampiri dengan langkah ringan, masih mengira itu urusan biasa. Jarang-jarang ibunya ada dirumah siang-siang begini. Tapi yang dilihatnya bukan hanya Ibu—di meja kayu itu, ada selembar undangan duka. Hitam putih. Tertulis nama seseorang yang langsung membuatnya terperangah
'Bapak Dirman Suharto.'
Arien berdiri mematung.
“Beliau meninggal pagi tadi,” kata Ibu pelan, “katanya karena komplikasi. Sudah lama tidak bilang-bilang…”
Udara di sekitar Arien seolah mengerut. Ia menarik napas, tapi dadanya terasa kaku. Matanya tak berkedip menatap nama itu—nama yang barusan beberapa hari lalu mengucapkan, ‘Kalau suatu saat nanti, kau lupa semua yang pernah kupelajari padamu…’
Itu…
Itu pesan perpisahan.
Dan dia tidak menyadarinya.
Arien tidak menangis. Tidak langsung bicara. Dia hanya berjalan ke kamar, membuka laci tempat menyimpan sabuk merahnya, dan duduk di lantai. Lama.
Sabuk itu tergeletak di pangkuannya. Lalu dengan pelan, dia mulai mengikatkan sabuk itu di pinggang—diam-diam, rapi, tanpa kata. Bukan untuk latihan. Tapi untuk mengenang.
Untuk mengingat siapa yang telah meletakkan sabuk itu di tangannya.
***
Tempat Pemakaman
Pemakaman berlangsung tenang. Arien datang paling awal. Berdiri sedikit di belakang keluarga Pak Dirman. Tidak membawa bunga. Tapi dia mengenakan sabuk merahnya di balik jaketnya.
Beberapa murid tingkat tinggi lainnya juga hadir. Semua laki-laki, teman-teman sekelas latihan intensifnya.
“Arien.”
Seseorang menepuk bahunya. Itu Candra, yang tertua di antara mereka, juga yang paling dekat dengan Pak Dirman.
“Kau nggak bawa bunga?” tanya Candra pelan, setengah bercanda, mencoba meredakan ketegangan.
Arien menggeleng. “Nggak perlu. Bapak nggak suka bunga.”
Yang lain tertawa pendek.
“Benar juga.”
“Sabuk merahnya masih hangat ya,” gumam Revan, satu teman lainnya sambil menatap simpul sabuk di pinggang Arien.
“Belum seminggu,” kata Arien lirih.
Kemudian ia menatap nisan yang baru ditutup. “Tapi rasanya kayak sudah lama sekali sejak malam itu.”
Mereka diam sejenak. Masing-masing menunduk.
“Gue masih nggak nyangka beliau pergi secepat ini,” ucap Deril pelan.
“Waktu malam itu… beliau udah tahu, ya?” tanya Candra, lirih ke Arien.
Arien mengangguk pelan. “Beliau bilang sesuatu… yang waktu itu kupikir cuma wejangan biasa. Tapi sekarang rasanya beda.”
Candra menepuk bahunya. “Bapak percaya kau bisa jaga warisannya. Kau yang paling keras kepala tapi paling konsisten.”
Arien tersenyum kecil, tapi matanya tetap kosong.
Dan di situ, dikelilingi teman-temannya, Arien merasa kehilangan itu menjadi nyata. Bukan hanya kehilangan seorang guru. Tapi kehilangan suara yang dulu pertama kali bilang, “Tenanglah. Semua orang bisa belajar membaca dunia. Kau pun bisa.”
Dan saat dia pulang dari pemakaman, sabuk merah itu terasa sedikit lebih berat di pinggangnya. Tapi kali ini, Arien membiarkan beban itu tinggal.
***
Beberapa Minggu Setelah Pemakaman
Suasana rumah latihan Pak Dirman tidak banyak berubah. Lantai kayu masih menyimpan aroma minyak kayu putih dan peluh, rak senjata masih rapi di sudut, dan jam tua di dinding masih berdetak lambat seperti biasa. Yang berbeda hanyalah suara.
Bukan suara Pak Dirman.
Sekarang, tempat itu dipimpin oleh anak beliau—Mas Arwan. Orangnya baik, disiplin, dan cukup karismatik, meskipun suaranya tak seberat ayahnya. Tapi bukan itu yang membuat Arien merasa asing. Bukan pula soal teknik. Mas Arwan bahkan menyusun program latihan baru yang lebih sistematis.
Yang membuat Arien merasa kosong... adalah ruang yang tidak bisa diisi siapa pun: kehadiran sosok yang dulu memaklumi diamnya, mengerti ragu-ragunya, dan menyampaikan nilai lewat kata-kata hemat tapi dalam.
Sore itu, setelah latihan selesai, Arien duduk di anak tangga kayu depan rumah itu. Sabuk merah masih terikat di pinggangnya, tapi terasa seperti tali nostalgia, bukan lagi lambang semangat.
Mas Arwan duduk di sebelahnya.
“Kau makin bagus, Rien,” ucapnya sambil membuka botol minum.
Arien hanya tersenyum tipis. “Makasih, Mas.”
“Tapi kamu kelihatan mikir terus. Ada apa?”
Butuh waktu beberapa saat sebelum Arien menjawab.
“Aku rasa… sampai sini aja, Mas.”
Mas Arwan menoleh cepat. “Maksudmu?”
“Aku mau berhenti,” kata Arien, kali ini lebih pelan. “Bukan karena Mas Arwan. Tapi karena aku rasa, pencak silat... buatku, udah selesai.”
Mas Arwan diam. Lalu mengangguk perlahan.
“Bapak pernah bilang, pencak silat itu soal jalan. Bukan garis lurus. Kadang orang berhenti, belok, atau putar balik. Tapi kalau hatimu merasa cukup, maka hormatku tetap sama.”
Arien menunduk. Dalam diamnya, dia ucapkan terima kasih yang tak keluar suara.
***
Malamnya, di Rumah
Ia segera mengutarakan keinginannya, mumpung kedua orangtuanya ada dirumah malam ini
“Berhenti dari pencak silat?” Ayah Arien mengulang dengan alis sedikit terangkat.
“Iya, Yah. Boleh?” tanya Arien.
Ibu yang sedang mengiris tomat di dapur ikut menoleh. Bahkan Ali dan Azura ikut menghentikan kunyahan nya--ini keajaiban dunia yang kedelapan, seorang Arien, Adik dan Kakak yang mereka kenal selalu kokoh berhenti begitu saja.
“Kenapa?”
“Karena… sejak Pak Dirman nggak ada, rasanya beda,” ujar Arien. “Aku masih suka latihan. Tapi bukan buat bertarung. Bukan buat naik tingkat. Aku cuma… pengen berhenti di tempat aku merasa maknanya paling penuh.”
Ayah terdiam sebentar, lalu tersenyum kecil.
“Kalau itu keputusanmu sendiri, kami setuju. Tapi ingat, sabuk merah itu bukan akhir, Rien. Itu pengingat. Tentang ketekunan, rasa hormat, dan keberanianmu untuk maju.”
“Dan untuk mundur, kalau memang perlu, terkadang seseorang harus mundur beberapa langkah untuk melompat lebih jauh” tambah Ibu sambil meletakkan pisau.
Arien tersenyum tipis, menatap sabuk merah yang digulung rapi di tangannya. Kali ini, dia tidak merasa gagal. Tidak merasa lari. Dia hanya tahu bahwa perjalanannya di tempat itu… sudah cukup.
Dan kadang, cukup adalah pencapaian yang paling tenang.


 alkays_honglii
alkays_honglii