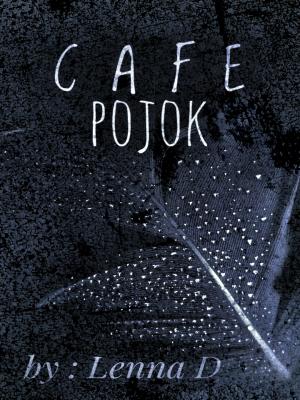Langit dan udara Jogja mendukung keinginanku untuk menuntaskan apa yang harus kutuntaskan. Entah itu akan membuatku senang ataupun tidak, membuat jiwa lain senang ataupun tidak, jika semesta telah mendukung, aku rasa ini akan menjadi hal yang baik.
Seperti biasa, Nela membangunkanku. Dia pasti tidak lupa dengan perbincangan kami semalam, bahwa kami akan mengunjungi Papa. Aku menguatkan diri untuk segera mandi dan bersiap-siap, meskipun kakiku masih terasa sakit saat terlalu digerakan. Tak ada percakapan lebih lanjut antara aku dan Nela, aku tahu dan dia tahu bahwa ada rasa yang sama-sama kita rasakan namun tak bisa gamblang dijelaskan bagaimana rasa itu. Bukan sedih, karena rasanya lebih dari itu. Bukan pula bahagia, karena rasanya lebih dari itu. Ini seperti kolaborasi sedih dan bahagia yang berpadu dengan porsinya yang sama-sama besar.
Memakai pakaian terbaik -menurut versi kami tentunya, bergegaslah kami menuju tepi jalan untuk menunggu angkutan umum, sengaja tak memakai motor Nela karena kami tak ingin repot mengkhawatirkan motor yang terparkir di tepi jalan karena disana tidak tersedia tempat parkir. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk kami menunggu, angkutan datang dengan kursi penumpang yang sudah hampir terisi semua oleh para pelajar yang akan menuju sekolah. Kami hampir putus asa untuk bisa duduk nyaman di kursi angkot, namun ternyata anak baik memang selalu diberi pertolongan. Dua orang anak SMP mempersilakan kami duduk lebih luas karena katanya sebentar lagi mereka akan segera turun. Kami menerima tawaran itu, namun tentunya aku dan Nela pun tak tega jika harus membiarkan dua anak SMP itu berdiri mematung dengan postur tubuh mereka yang sama-sama tinggi, atau membiarkan mereka berjongkok ditemani kaki-kaki para penumpang. Aku dan Nela mempersilakan mereka duduk di atas pangkuan kami, meskipun tak seempuk kursi angkot, tapi setidaknya mereka tidak merasakan pegal karena harus berdiri atau berjongkok di dalam angkot.
Anak yang berada di pangkuanku dan temannya meneriaki sopir agar memberhentikan lajunya. Ternyata, mereka telah sampai di tujuan.
“Bang, ongkosnya di belakang!” ucap Nela saat dua anak SMP itu menuruni angkot.
“Makasih, Mbak!” teriak anak SMP itu sembari melemparkan senyumnya dari tepi jalan, lalu melambaikan tangannya padaku dan Nela yang telah melaju segera setelah mereka turun.
Rasanya secepat kilat, tak terasa kami telah sampai dan segera menuruni angkot itu. Kutatap sekeliling tempat tinggal Papa, seperti banyak penghuni baru di tempat itu, terlihat dari warna coklat khas yang membedakannya dengan yang lain. Tempat tinggal Papa ada di dekat pohon yang rindang, meskipun membuat pengunjung sejuk saat mengunjunginya, namun banyak sekali dedaunan kering yang berjatuhan tepat di atas tempat tinggal Papa. Aku merasa bersalah karena baru mengunjunginya lagi kali ini. Nela hanya menunduk di depan tempat tinggal Papa, aku tahu rasa bersalahnya pun hadir dalam hatinya. Aku menepuk punggung Nela sembari mengelusnya.
“Yuk, kita kirim doa, Nel.”
Kami melantunkan ayat-ayat Al-Quran di depan makam Papa. Sepertinya setiap orang merasakan kesedihan yang hadir kala berziarah, hingga berlanjut dengan tumpahnya segala isi hati yang tertuju untuk orang tersayang yang tak lagi dapat kita temui. Segala rasa hadir dalam jiwaku, sedih, bahagia, rindu, semua hadir beriringan, air mata telah deras mengalir sampai membasahi kerudung yang pertama kali kukenakan. Aku tahu Papa menyambut kami, tapi kami tidak diberikan izin lagi untuk menemui Papa oleh-Nya. Kami hanya mampu mengunjungi tempat peristirahatan terakhirnya. Kusiram makam Papa dengan sebotol air yang kami bawa, dan kusimpan bunga yang masih segar di dekat batu nisannya.
Nela sudah terisak sambil memeluk batu nisan Papa. Kenangan lalu bersama Papa sungguh terputar dalam otakku, sangat berat. Namun, aku tahu Nela menghadapi emosi yang lebih berat lagi karena rasa bersalah yang membebaninya.
***
Di sebuah Rumah bergaya sederhana, dengan jendela kayu yang berventilasi horizontal dan bercatkan biruu langit, tumbuh dua anak perempuan dari seorang Ayah pengusaha, dan seorang Ibu Rumah Tangga. Mereka adalah keluarga yang berkecukupan, anak-anaknya tumbuh dengan sehat dan pintar. Banyak tetangga yang mengangumi keluarga itu karena keberhasilan kepala keluarganya. Itu adalah keluargaku. Aku bangga memiliki Papa seorang pengusaha yang sukses, tiap hari aku selalu makan enak, pakaianku selalu cantik, aku pun disekolahkan di sekolah terbaik di Yogyakarta. Sejak pertama kali menginjak bangku sekolah, yaitu Sekolah Dasar, aku selalu mendapat perhatian lebih dari Papa mungkin karena aku anak pertama dan Papa baru pertama kali menyekolahkan anak. Setiap hari aku selalu diantar Papa untuk berangkat sekolah, sampai pulang pun Papa selalu setia menungguku di gerbang sekolah, padahal jarak dari rumah menuju sekolah sangat dekat, hanya terpisah 3 rumah saja. Setiap tahun aku selalu merayakan hari ulang tahunku, begitu juga Nela. Papa selalu menghadiahi kami kado yang benar-benar kami inginkan.
“Selamat Ulang Tahun anak Papa!” ucapnya sambil membuka pintu kamarku tepat di pukul 00.00.
“Ih Papa, Treela lagi enak-enaknya tidur.”
“Ayo bangun dulu, tiup nih lilinnya!” ajak Mama.
Lilin telah kutiup, Papa dan Mama memelukku sambil mendoakanku.
“Makasih ya, Pa, Ma.”
“Sama-sama, Sayang. Ayo lanjutin lagi tidurnya, besok sekolah!”
Hingga aku bangun di Pagi harinya dan seperti biasa akan diantar oleh Papa, sebuah kado besar tersimpan di garasi mobil Papa, aku yakin itu kado ulang tahunku. Aku berteriak memanggil Papa dan Mama untuk memastikan kado itu.
“Iya Tree itu kado buat kamu, coba buka!” jawab Papa.
“Kok gede banget kadonya?” tanyaku sambil kegirangan.
Aku membukanya dan ternyata itu sebuah sepeda yang benar-benar aku inginkan.
“Waahh! Papa bener-bener beliin Treela sepeda yang kemarin kita lihat! Makasih Papa!”
Aku, Mama, Papa, dan Nela yang masih dalam pangkuan Mama saling berpelukan, aku merasakan pagi hari yang bahagia. Aku pun semakin bersemangat pergi sekolah.
Aku masih ingat dengan jelas, saat aku ikut perlombaan membaca puisi antar sekolah saat SD, Papa hadir memberiku semangat dan begitu sigap merekamku saat tampil di panggung, Papa yang memberiku tepuk tangan meskipun penonton lain tak begitu tertarik dengan penampilanku di panggung. Meskipun aku tak berhasil menjuarai perlombaan itu, Papa tidak menunjukkan kekecewaannya dan tak henti-hentinya menghiburku agar tetap semangat.
***
Kami mengakhiri kunjungan dengan emosi yang sudah benar-benar baik, karena kami tak ingin membawa oleh-oleh yang akan membuat kami semakin tak terkendali. Namun sayangnya, belum lama aku menikmati emosi baik, tiba-tiba seseorang di depanku membuat kegaduhan.
“Ila! Ila!” teriaknya sambil melambaikan tangannya padaku.
Aku menengokkan kepala ke belakang siapa tahu ada orang lain di belakangku. Tapi ternyata hanya ada aku dan Nela saja disana. Lelaki itupun semakin mendekat, hingga wajahnya bisa jelas kuperhatikan. Ah, ternyata, dia lelaki yang tak ingin memberitahukan namanya itu.
“Eh Ila, kita ketemu lagi! Sekarang kamu bisa tahu namaku!”
“Hah?”
“Kamu lupa, ya. Aku ‘kan pernah bilang akan memberitahukan namaku kalau kita ketemu lagi.”
“Oh ya, aku tidak ingat.”
“Kenalin, aku Rio.”
Bagai tersengat listrik, aku dipenuhi keterkejutan dengan pertemuan kami yang tak disangka-sangka dan tak kuharapkan.
Aku tak tertarik untuk lebih dari sekedar membalas perkenalannya dengan senyum tipis dan anggukan kecil. Namun, dia terus memancing responku dengan berbagai obrolannya yang tak perlu. Sebagai seseorang yang baru kenal, aku sih tidak akan bisa seperti dia, membomku dengan berbagai pertanyaannya, perihal mengapa aku ada disini, siapa yang ada di sisiku, mengapa tak menggunakan kendaraan pribadi, hingga dia sampai bertanya dimana aku tinggal. Aku hanya menjawabnya singkat, dan tentu saja aku tidak memberitahukan tempat tinggalku bersama Nela.
“Aku antar kalian pulang, ya, kasihan panas-panas begini masa naik angkot.”
“Eh gak usah, kebetulan kami mau ke suatu tempat dulu.”
“Oh gitu, oke, deh. Semoga kita ketemu lagi!”
Ah untung saja aku selamat dari ajakannya.
***


 wais
wais