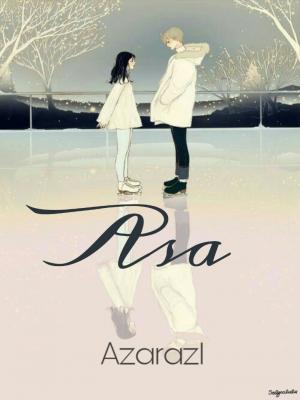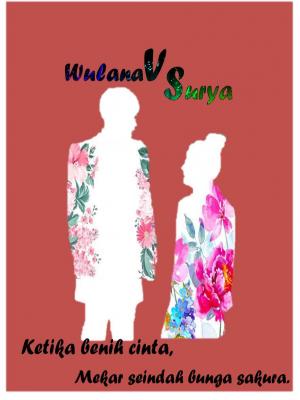Hari itu, kampus sepi. Langit Istanbul menggantung kelabu, seolah ikut merenung bersama bangku-bangku kosong dan lorong-lorong fakultas yang dingin. Perkuliahan dibatalkan karena ada kegiatan universitas yang entah apa isinya. Tapi Ameera sudah terlanjur bangun pagi, menyeduh teh sendiri di dapur dan mengenakan jaket tebal ivorynya.
Ia sempat berdiri lama di depan jendela, menatap jalan raya dari lantai dua. Kota ini, pikirnya, tak pernah benar-benar diam. Bahkan di hari libur pun, Istanbul tetap bernafas, tetap bergerak seperti hati yang berdegup meski sedang tidak jatuh cinta.
Niatnya ke perpustakaan. Tapi ketika sampai di gerbang utama kampus, langkahnya berhenti. Dunia terasa terlalu berat untuk dihadapi di antara rak-rak sunyi dan meja belajar yang kaku. Akhirnya ia belok kanan. Tak ada rencana. Hanya dorongan samar untuk berjalan ke mana pun kakinya mau.
Angin dingin menyambutnya di Eminönü. Pelabuhan kecil itu sibuk seperti biasa. Warung-warung pinggir jalan berjejer dengan asap yang mengepul dari daging panggang dan jagung rebus. Laut bergelombang pelan, dan camar-camar melayang di atas kapal feri seperti potongan mimpi yang tak sempat diucapkan.
Ameera berjalan perlahan. Tak membawa tujuan, tak ada peta. Ia hanya mengikuti suara-suara kota. Tawar-menawar pedagang, derit troli logam yang ditarik tua renta, nyanyian lirih dari toko musik tua yang memutar kaset lawas.
Di gang sempit antara toko rempah dan butik kain, sekelompok anak-anak bermain bola. Bola plastik mereka memantul mengenai kaki Ameera.
“Özür dilerim abla!” seru seorang bocah dengan napas tersengal.
Ameera tersenyum, mengembalikan bola dengan tendangan pelan. Anak-anak itu tertawa dan melanjutkan permainan, tidak peduli siapa yang sedang menonton atau apakah dunia sedang patah hati.
Ia berjalan lagi, kali ini melewati seorang kakek tua yang duduk bersila di atas karpet lusuh, menjajakan lukisan-lukisan air di trotoar. Goresannya sederhana seperti kubah masjid, kapal feri, jalanan sempit berlampu kuning. Tapi ada kelembutan yang nyata di setiap sapuan warnanya.
“İstanbul'u sever misin, kızım?” tanya si kakek tanpa menoleh.
Ameera hanya menjawab dengan anggukan dan senyum kecil.
Ia melanjutkan perjalanan. Semakin jauh dari keramaian, semakin dekat dengan senja. Dan ketika bayangan hari mulai memanjang di tembok-tembok tua, langkahnya tanpa sadar membawanya ke depan sebuah rumah kecil bercat coklat kayu yang mulai retak, rumah kecil yang kini mulai terasa akrab. Rumah Hatice Hanım.
Tapi sore ini, tidak ada suara Hatice dari dapur. Tidak ada aroma simit panggang atau cerita-cerita tentang masa muda yang diucapkan sambil menatap jendela.
Yang terdengar hanya suara pelan dari lantai bawah. Suara denting logam. Bunyi air. Dan musik jazz Turki yang mengalun samar, seperti kenangan yang tidak ingin dilupakan sepenuhnya.
Langkah Ameera melambat. Ada sesuatu yang menariknya untuk menuju ka arah sumber suara. Entah rasa penasaran, atau hanya kebutuhan sunyi yang sama dengan yang pernah Emir katakan.
Ia menuruni tangga perlahan. Lorong bawah tanah itu sempit, dan di ujungnya ada sebuah pintu kayu setengah terbuka. Dari celahnya memancar cahaya merah yang redup dan lembut, seperti ruang waktu yang terlipat di antara masa lalu dan sekarang.
Ameera mengetuk pelan, tapi tak ada jawaban. Maka ia menengok ke dalam.
Di sana, Emir berdiri membelakangi pintu. Ia mengenakan apron hitam yang sedikit lusuh. Tangannya sibuk dan terampil, dengan tenang ia mengangkat selembar foto dari larutan kimia. Kemudian menggantungnya perlahan, penuh ketelitian. Seolah dunia akan runtuh jika sudut foto itu tidak lurus.
Untuk sesaat, Ameera hanya memandangi punggung lelaki itu. Dan dalam diam, ia menyadari bahwa inilah Emir yang sesungguhnya. Bukan yang berbicara seadanya di dapur, atau yang menghindari tatapan saat makan malam. Tapi Emir yang ada ketika tak seorang pun melihat. Yang berdiri sendiri di ruang gelap, mencari cahaya dari selembar kertas basah.
Ia hampir memanggil namanya. Tapi Emir lebih dulu sadar akan kehadirannya. Ia menoleh.
Dan waktu terasa seperti berhenti sebentar.
Tatapan mereka bertemu. Dan Ameera, untuk pertama kalinya, melihat wajah Emir tanpa dinding. Mata itu terlihat lelah, bukan sekadar karena malam. Tapi karena masa lalu yang terlalu berat untuk ditinggalkan begitu saja.
“Kamu sering ke sini?” tanya Ameera pelan.
Emir menatapnya sebentar, lalu mengangguk. “Tempat ini… sunyi. Aku suka tempat sunyi.”
“Aku tidak sengaja.”
“Aku tahu.”
Hening.
Lalu Ameera melihat foto yang tergantung. Sebuah potret jalanan Istanbul. Tapi bukan sekadar jalan. Ada seorang perempuan tua menjual bunga, wajahnya samar namun ekspresinya begitu hidup. Di latar belakang, anak kecil tertawa, dan langit Istanbul tampak seperti lukisan.
“Indah sekali,” gumam Ameera.
Emir menoleh. “Semua orang bisa melihat Istanbul dari matanya. Tapi tak semua bisa melihatnya dari hatinya.”
Ameera diam. Kalimat itu seperti membuka sesuatu dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah Emir menyembunyikan puing-puing duka di balik foto-fotonya, atau justru mencoba menyembuhinya satu demi satu lewat cahaya dan bayangan.
“Apa yang kamu cari dari semua ini?” tanya Ameera akhirnya.
Emir menatapnya. “Bukti bahwa dunia masih layak untuk diabadikan. Bahkan jika kamu sendiri tidak lagi percaya.”
Jawaban itu terdengar seperti milik seseorang yang pernah kehilangan segalanya.
***
Malam turun pelan-pelan seperti tirai beludru gelap yang menutup langit Istanbul. Hujan masih menyisakan jejak di jendela, membentuk pola acak yang bergerak lambat, seperti kenangan yang enggan mengering.
Di kamar lantai atas rumah tua di Fatih, Ameera duduk bersila di ranjang, membungkuk sedikit ke arah jurnal kecil bergaris yang sudah mulai penuh oleh tulisan tangan. Ia menulis dengan pena biru, huruf-hurufnya miring, terburu-buru, seperti ingin mengejar sesuatu yang nyaris hilang.
"Hari ini bukan tentang kampus, bukan tentang Eminönü. Tapi tentang ruang gelap itu, tentang selembar foto yang bisa berbicara lebih dari seribu kata. Dan mata... mata yang menyimpan ribuan musim, tapi tidak satupun benar-benar berlalu."
Tangan Ameera terus bergerak, tapi pikirannya sudah melayang. Ingatannya kembali ke senyum kecil Emir, senyum yang tidak untuk dipamerkan, hanya muncul ketika ia lupa sedang dilihat. Kalimat-kalimatnya yang pendek tapi menghujam. Dan tatapan itu… tatapan yang tidak pernah meminta apa-apa, tapi justru membuat orang ingin bertanya lebih jauh.
Sejenak, Ameera menutup jurnalnya. Ia bersandar pada dinding, mendengar suara kota yang mulai melambat. Hujan telah reda. Ameera berdiri diam cukup lama. Rasa ingin tahu dalam dirinya tumbuh perlahan, seperti embun yang perlahan menutup kaca jendela, di dalam benaknya terbayang Emir di ruang gelapnya. Ia merasa ruang gelap itu bukan sekadar tempat cuci foto. Ia bisa merasakan bahwa ruang itu yang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum diungkap Emir pada siapa pun.
Ia kembali duduk di ranjang, kali ini tidak membuka jurnal. Matanya hanya menatap jendela sambil bergumam "Ada dinding di dalam diri Emir yang dibangun bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk melindungi."
***
Keesokan paginya, saat sarapan bersama Hatice hanım, Ameera memberanikan diri bertanya.
“Emir… dia sering memotret, ya?”
Hatice tersenyum kecil. “Dulu, dia kuliah di seni rupa. Spesialisasi fotografi. Tapi sudah berhenti hampir dua tahun.”
“Kenapa?”
Hatice terdiam sejenak. Suaranya merendah. “Dia kehilangan seseorang yang sangat ia cintai.”
Ameera menunduk, merasa bersalah sudah bertanya. Tapi Hatice menambahkan dengan nada pelan, “Kedua orangtuanya dan adiknya, Elvan Kecelakaan laut di Çanakkale. Sejak itu, Emir berubah. Ia jarang bicara, menutup diri, dan hanya berbicara dengan… kameranya.”
Ameera menggenggam gelas tehnya erat. Mendadak, wajah Emir yang dingin terasa masuk akal. Rasa sunyi yang membayanginya bukan berasal dari sikap sombong, tapi dari kehilangan.
***
Ameera mendekati ruangan itu lagi, ia melihat pintu kecil itu terbuka sedikit. Cahaya redup menyelinap keluar. Entah dorongan apa yang membuatnya melangkah mendekat.
Ia mengetuk pelan.
Tidak ada jawaban.
“Emir?” panggilnya ragu.
Suara di dalam menjawab, “Masuk saja, tapi jangan menyentuh apapun.”
Ameera membuka pintu. Di dalam, ruangan itu seperti museum rahasia. Ada rak berisi gulungan film, dinding penuh cetakan foto hitam putih, dan meja besar dengan lampu kuning redup. Aroma kimia dari cairan pencuci film menyengat, tapi tak mengganggu.
Di tengah ruangan, Emir sedang berdiri di depan selembar foto yang belum sepenuhnya kering. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap hasil karyanya.
“Kamu ingin melihat apa yang kutangkap?” tanyanya tanpa memandang Ameera.
“Boleh?” jawab Ameera pelan.
Emir menggeser beberapa cetakan di atas meja. Foto-foto kota, pelabuhan, anak-anak bermain di lorong sempit, burung-burung di langit senja, dan wajah-wajah asing yang tertangkap jujur dalam lensa.
Tapi di antara semua itu, ada satu foto yang membuat Ameera terdiam.
Itu dirinya. Berdiri di bawah gerbang masjid, payung hitam di tangan, wajahnya menatap hujan yang jatuh, momen sore itu.
“Kamu memotret aku?”
“Aku hanya menangkap cahaya dan bayangan,” jawab Emir tenang. “Tapi… ada sesuatu di sorot matamu yang seperti kota ini. Indah, tapi tidak mudah ditebak.”
Ameera menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata Emir seperti lensa lain yang memaksa dirinya untuk melihat ke dalam. Bukan pada pantulan kaca, tapi pada luka yang selama ini ia simpan rapi.
Malam itu, mereka tidak banyak bicara lagi. Tapi sebuah dinding retak. Bukan oleh kata-kata, melainkan oleh kehadiran. Kadang, dua jiwa yang sama-sama
terluka hanya butuh ruang yang cukup sunyi untuk saling mendengar.
***
Note:
Özür dilerim: Maafkan saya
Abla: Saudara perempuan
İstanbul'u sever misin?: Apakah kamu menyukai İstanbul?


 cha_azra
cha_azra