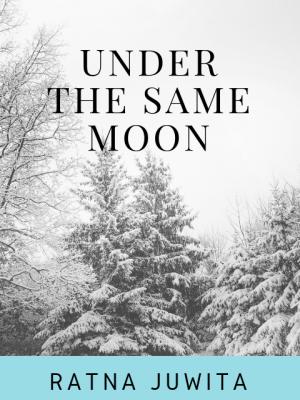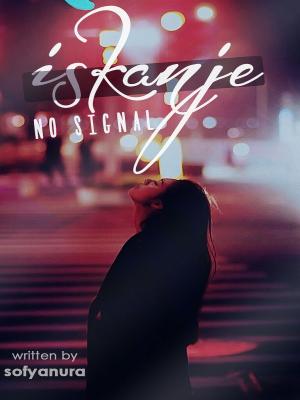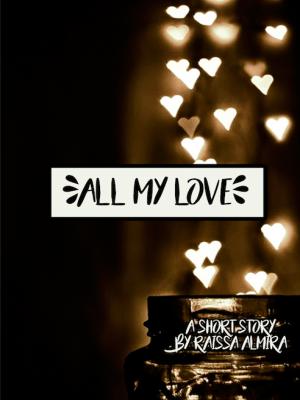Langit Istanbul malam itu seolah menahan napas. Awan menggulung pekat di atas menara-menara tua dan atap merah bata yang basah. Angin berembus lembut di antara gang-gang sempit Beyoğlu, membawa aroma roti panggang dari toko kecil di pojok jalan dan tanah basah yang belum tersentuh.
Ameera baru saja selesai dari kelas diskusi puisi di perpustakaan kampus. Kepalanya penuh dengan kutipan, mulai dari Rumi, Nazım Hikmet, sampai penyair perempuan bernama Didem Madak yang puisinya membuat Ameera terdiam lama.
“Kayaknya bakal hujan nih,” gumamnya sambil melirik langit. Udara mulai lembap, dan angin mengibaskan ujung kerudungnya.
Langkahnya ringan menyusuri trotoar berbatu sambil memeluk bukunya erat-erat. Sesekali ia mengangkat wajah menatap langit yang nyaris tumpah.
“Jangan sekarang, please” bisiknya, lebih pada dirinya sendiri.
Tapi langit Istanbul punya kehendaknya sendiri. Dalam hitungan detik, hujan jatuh dengan deras, menghantam jalanan seperti gulungan nada minor dari lagu lawas.
Ameera berlari kecil, rok panjangnya terseret angin dan hujan. Ia menyeberang jalan dan menumpang berteduh di bawah kanopi sebuah kafe tua. Jendela kayunya berembun, lampu gantung kuningnya redup, dan aroma kopi berpadu dengan bau pel dari dalam.
Sudah ada satu orang di bawah kanopi itu. Seorang gadis yang terlihat seumuran dengannya, berambut ikal sebahu dengan mantel hijau zaitun yang kebasahan.
Begitu mata mereka bertemu, gadis itu tersenyum.
“Hujan di Istanbul itu seperti emosi seni rupa… datang tiba-tiba dan intens,” katanya dalam bahasa Inggris yang fasih, diselingi aksen manis khas orang lokal.
Ameera tertawa, meski setengah menggigil. “Kamu penyair ya?”
“Pecinta seni,” sahutnya ceria. “Namaku Sibel.”
“Ameera.” Ia menyambut jabatan tangan gadis itu. “Dari Indonesia. Mahasiswa pertukaran di İstanbul Üniversitesi, jurusan Sastra Inggris.”
“Aaah, seni bertemu sastra! Harika!” Sibel berseru kecil. “Aku mahasiswa seni di Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Aku sering lihat kamu duduk sendirian di perpustakaan ini dengan notebook coklat kamu itu," ujarnya sambil menunjuk ke arah notebook Ameera. "kamu suka nulis ya?” lanjutnya.
Ameera tersenyum, “Iya. Aku suka menulis jurnal. Kadang nulis fiksi juga, tapi belum berani dibaca orang.”
“Kamu harus ikut workshop mingguan di Galata. Banyak seniman muda ngumpul di sana. Aku kadang bawa lukisanku atau puisi visual. Kadang cuma duduk, minum çay, dan bicara soal warna dan luka,” katanya sambil mengedip.
***
Hujan belum juga reda. Mereka berdiri berdampingan di bawah kanopi sempit itu, berbagi cerita seolah sudah lama kenal.
Sibel menunjukkan foto-foto karyanya di ponsel. Sapuan kuas yang tak rapi, warna-warna tabrak tapi hidup, dan potret perempuan dengan mata tak selesai. Semua lukisannya seolah bicara tentang rindu yang rumit.
“Kamu melukis rasa sedih,” gumam Ameera.
Sibel tersenyum pelan. “Karena senang itu terlalu ramai. Sedih itu… jujur.”
Setelah hampir satu jam, hujan mereda jadi gerimis pelan. Jalanan mengilap, memantulkan cahaya lampu-lampu jalan seperti kaca patah.
“Kamu naik tram?” tanya Sibel sambil menyampirkan syalnya yang basah.
Ameera mengangguk. “Rumahku di Fatih, di rumah tua milik keluarga Turki.”
Sibel mengangkat alis. “Wah, keren. Suasana Ottoman gitu ya?”
Ameera tersenyum. “Tua dan hangat. Kadang misterius juga.”
Sibel menepuk bahu Ameera pelan. “Kalau kamu butuh teman jalan atau penunjuk jalan ke galeri-galeri tersembunyi di Istanbul, aku selalu siap.”
“Teşekkür ederim, Sibel,” kata Ameera lembut. “Sen çok naziksin.”
Sibel tersenyum, senang mendengar Ameera mencoba berbahasa Turki. “Rica ederim. Sampai jumpa, penulis galau dari Timur.”
***
Perjalanan pulang menaiki tram malam itu terasa seperti jeda. Kota perlahan diam, hanya menyisakan cahaya toko yang mulai menutup, suara pelan rem tram, dan wajah-wajah yang kelelahan. Ameera duduk di dekat jendela, memandangi siluet Istanbul yang basah dan diam-diam berubah.
Sesampainya di rumah, aroma sup dari dapur masih tersisa, tapi rumah itu sunyi. Langkahnya pelan menaiki tangga kayu yang mengeluarkan bunyi setiap diinjak. Ia tak ingin membuat suara.
Namun…
Suara pelan terdengar dari arah tangga lantai atas.
“Yeni geldin mi?”
Ameera berhenti. Di sana, berdiri sosok yang membuat detak jantungnya bertambah satu nada.
Emir.
Ia berdiri di lorong, mengenakan hoodie longgar dan celana tidur. Rambutnya sedikit kusut dan masih basah, mungkin baru saja mandi atau baru pulang juga. Lampu kecil dari ruang tamu hanya menyisakan separuh wajahnya yang tertimpa bayangan.
“Iya. Barusan sampai,” jawab Ameera pelan, menggenggam tasnya erat.
Emir mengangguk. “Bukumu tadi siang jatuh di ruang makan. Sudah aku taruh di rak bawah.”
“Oh… makasih,” suaranya lebih lembut dari yang ia kira.
Mereka saling menatap dalam diam. Hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk meninggalkan sesuatu.
Emir tak bicara lagi. Ia berbalik, melangkah perlahan ke arah kamarnya. Ameera hanya berdiri diam, menatap punggungnya menghilang di balik tikungan lorong.
***
Udara di kamar Ameera terasa hangat, meski angin malam Istanbul masih menyelinap dari celah jendela yang sedikit terbuka. Hujan telah reda, menyisakan embun di kaca dan aroma tanah basah yang samar-samar meresap ke dalam kayu tua rumah itu.
Ameera meletakkan buku-buku kuliahnya di sisi meja kecil dekat tempat tidur. Ia mengganti pakaian, membalut tubuhnya dengan sweater rajut abu-abu yang mulai berbulu, lalu menyeduh teh apel hangat, satu-satunya hal yang terasa seperti pelukan di malam-malam lembap seperti ini.
Dari luar, terdengar suara trem berlalu perlahan, dan azan Isya yang menggema dari arah masjid tua di kejauhan. Kota ini tak pernah benar-benar sunyi, pikirnya. Selalu ada suara… entah itu angin, doa, atau langkah kaki di bawah jendela.
Ia duduk bersila di atas tempat tidur, mengambil jurnal bersampul cokelat yang selalu menemani. Ujung penanya sempat ragu, sebelum akhirnya mulai menari di atas halaman kosong.
“Hujan tadi bukan cuma tentang langit yang jatuh. Tapi tentang hal-hal yang datang tiba-tiba seorang teman baru bernama Sibel, tawa yang terasa hangat meski kami baru bertemu.
Dan Emir… hanya satu kalimat, tapi kenapa rasanya seperti gema yang tinggal lama di kepala? Mungkin... beberapa hal tidak butuh banyak kata. Cukup hadir.”
Ia menutup jurnalnya perlahan, menatap keluar jendela yang mulai berembun.
Di seberang, jendela-jendela apartemen mulai ditutup. Lampu-lampu redup menyala seperti bintang-bintang kecil di tengah kabut kota. Ia membayangkan bagaimana kehidupan berjalan di balik jendela-jendela itu. Apakah sebuah keluarga yang sedang makan malam, seseorang yang membaca buku sambil memeluk bantal, sepasang kekasih yang berdebat tentang hal remeh.
Semua orang punya cerita.
Dan dia, Ameera, sedang menulis bagiannya di antara sejarah tua Istanbul.
Ia turun dari ranjang, berjalan ke rak buku kecil di sudut kamar. Di sana, tertata buku-buku kuliahnya, kamus Turki-Inggris, serta satu buku catatan puisi favorit yang kemarin nyaris hilang.
Emir bilang ia menyimpannya.
Saat Ameera menarik buku itu dari rak, sesuatu terjatuh dari sela halamannya. Selembar kertas kecil, agak kusut di tepinya. Ia mengambilnya perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas.
Tulisan tangan berbahasa Turki, singkat tapi menghentikan waktu:
“Bazı sessizlikler, bağırmaktan daha yüksek konuşur.”
Kadang, keheningan lebih lantang daripada teriakan.
Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan.
Tapi tulisan itu… ia mengenal bentuk hurufnya. Emir.
Ameera menatap kertas itu lama, sebelum menyelipkannya ke balik sampul jurnalnya.
Malam semakin larut. Ia kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga sebatas dada. Suara hujan yang tadinya deras kini berubah jadi tetes-tetes lembut dari atap seng di luar.
Ia memejamkan mata.
Tapi sebelum tidur, ia berbisik pelan ke langit-langit kamarnya:
“Teşekkür ederim, İstanbul... untuk malam yang sederhana tapi penuh makna.”
Aku tak butuh adegan besar, cukup hal-hal kecil yang tulus.
Babaanne dan senyumnya.
Lejla dengan keisengannya.
Emir dan caranya hadir tanpa
mengganggu.
Dan kota ini… perlahan menghapus rasa asing dalam diriku.
***
Note:
Yeni geldin mi? : Apakah kamu baru pulang?
Harika: Bagus
Çay: Sejenis teh khas Turki
Sen çok naziksin: Kamu sangat baik hati
Rica ederim: sama-sama
Bazı sessizlikler: Terkadang
bağırmaktan daha yüksek konuşur: Keheningan berbicara lebih keras daripada teriakan


 cha_azra
cha_azra