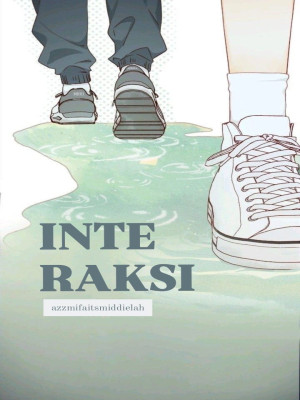Hari itu langit Surabaya mendung. Tidak ada kabar badai, tapi langit seperti ikut menahan napas—seperti aku. HPL tinggal seminggu, tapi tubuhku mulai memberi tanda: punggung pegal tak biasa, perut mengeras seperti batu, dan ada semacam firasat… bahwa ini waktunya.
Pagi-pagi, aku mengecek ulang isi tas persalinan. Masker kain, masker medis, hand sanitizer, face shield, pakaian ganti, sarung tangan sekali pakai, bahkan disinfektan kecil. Semua tampak lebih seperti perlengkapan perang daripada perlengkapan menyambut bayi.
“Kalau aku harus sendiri di dalam, kamu tunggu di parkiran aja, ya,” kataku ke Radit sambil menarik resleting tas.
Radit menatapku. “Aku bakal nunggu di manapun kamu butuh. Bahkan kalau disuruh duduk di trotoar depan IGD pun, aku bakal duduk.”
Aku senyum kecil, menyembunyikan gelisah. Tapi dalam hati, aku takut. Bukan cuma karena rasa sakit. Tapi karena kemungkinan harus melahirkan tanpa genggaman tangan Radit seperti dulu.
***
Sore menjelang malam, air ketubanku tiba-tiba pecah. Tidak disertai kontraksi kuat, hanya rasa nyeri yang datang perlahan. Tapi saat sampai di rumah sakit, tekanan darahku menurun, dan tubuhku mulai melemah. Dokter memutuskan aku harus segera menjalani operasi caesar.
“Demi keselamatan ibu dan bayi, ya, Bu. Kita ambil jalan terbaik,” kata dokter dengan suara tenang di balik masker N95.
Aku mengangguk lemah. Ada rasa hampa yang mengendap. Aku tahu ini keputusan terbaik, tapi tetap saja… aku sempat membayangkan bisa melahirkan normal, bisa mendengar tangisan bayi langsung dari tubuhku yang berjuang sampai detik terakhir.
Radit tak bisa masuk ke ruang operasi. Tapi sebelum aku dibawa masuk, dia menggenggam tanganku erat-erat.
“Kamu hebat, Na. Aku tahu ini bukan seperti yang kita rencanakan. Tapi kamu nggak sendirian. Aku tunggu kamu dan bayi kita di luar, ya.”
Aku menarik napas panjang. “Doain terus, Dit. Aku... takut.”
“Nggak usah takut. Allah bareng kamu. Aku juga.”
***
Ruang operasi dingin dan penuh cahaya putih. Aku menggigil, bukan hanya karena suhu ruangan, tapi karena semua terasa asing. Dokter dan perawat berpakaian seperti astronot. Suara-suara mereka teredam masker dan face shield.
“Tenang, Bu, kami mulai ya. Tarik napas... nanti akan terasa sedikit tekan, bukan nyeri.”
Dan benar saja, yang terasa bukan sakit yang tajam, tapi tekanan luar biasa yang mengguncang tubuh. Lalu...
Tangis bayi.
Tangis yang memecah seluruh kecemasan yang selama ini kutahan. Tangis paling jujur, paling indah yang pernah kudengar.
“Anaknya laki-laki, Bu. Sehat, ya...”
Air mata menetes pelan ke sisi wajahku, menyusup di balik masker.
Kami hanya diperbolehkan skin-to-skin sebentar. Setelah itu, si kecil dibawa untuk observasi.
Saat aku kembali ke ruang perawatan dan masih separuh sadar karena pengaruh obat bius, Radit mengirim pesan:
"Aku lihat dia dari balik kaca. Dia mungil banget, tapi kuat. Kayak kamu."
***
Malam itu aku tak bisa tidur. Luka caesar mulai terasa nyut-nyutan, menjalar pelan dari bawah perut hingga ke tulang punggung. Tapi yang paling membuat sesak bukan hanya rasa sakit fisik—melainkan rasa rindu.
Rindu pada bayi kecilku yang belum bisa lama kupeluk.
Rindu pada pelukan hangat ibuku yang tak bisa datang.
Rindu pada dunia yang dulu tak seasing ini.
Lampu temaram kamar rawat hanya menyisakan bayangan-bayangan lembut di dinding. Suara monitor berdetak pelan, serasi dengan degup jantungku yang pelan tapi tidak tenang.
Radit duduk di kursi plastik di sebelah tempat tidurku, satu-satunya orang yang diizinkan masuk. Tangannya memegang termos kecil berisi air hangat. Ia tampak kelelahan, tapi tetap tinggal. Menemani.
"Aku belum bisa tidur," kataku lirih.
Ia menoleh pelan. "Masih sakit?"
Aku mengangguk pelan. "Bukan cuma lukanya. Tapi... rasanya kayak... kosong banget, Dit."
Radit terdiam sejenak, lalu bangkit berdiri dan menuangkan air hangat ke gelas kecil yang dia bawa sendiri dari rumah. Ia menyodorkannya padaku.
"Pelan-pelan aja. Nggak usah kuat terus. Nggak harus tenang juga, Ra. Kamu baru lahiran. Kamu baru... ngelahirin kehidupan," katanya, suaranya lirih tapi dalam.
Aku menatap gelas itu, lalu menatap dia. Mata kami bertemu dalam diam yang hangat. Bukan canggung, bukan terpaksa. Hanya... mengerti.
"Aku pikir semuanya akan terasa lega setelah bayi lahir," kataku sambil memaksakan senyum.
Radit duduk kembali. "Aku juga pikir begitu. Tapi nyatanya... hidup nggak langsung berubah seindah yang kita bayangkan, ya?"
Aku mengangguk. "Tapi kehadiran dia... bikin semuanya jadi masuk akal, ya?"
Radit tersenyum. "Bayi kecil itu... udah bikin kamu jadi ibu yang kuat, Ra. Aku lihat kamu tadi—waktu di ruang pemulihan. Kamu lemah, tapi matamu tetap nyari dia."
Aku menatap langit-langit. "Aku nggak tahu bisa jadi ibu seperti apa. Tapi malam ini, aku tahu satu hal..."
Aku mengambil ponsel dari meja kecil di samping tempat tidur. Jari-jariku gemetar menulis sesuatu, tapi aku tahu aku harus menuliskannya sekarang. Di tengah luka. Di tengah nyeri. Di tengah kesunyian yang menggema.
Anakku, kamu lahir di masa yang berat. Tapi kehadiranmu membuat semua jadi layak.
"Aku nggak akan hapus kalimat itu," kataku pelan, menunjukkan layarnya ke Radit.
Dia membaca dan mengangguk pelan. "Kamu tahu? Itu satu kalimat paling berani yang pernah aku dengar."
Aku tersenyum. Air mata turun tanpa sempat tertahan. Tanganku menggenggam tangan Radit yang diam-diam mengusap ujung selimutku.
Malam itu kami tidak bicara banyak lagi.
Tapi untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku merasa... tidak sendirian.


 rosadewiita
rosadewiita