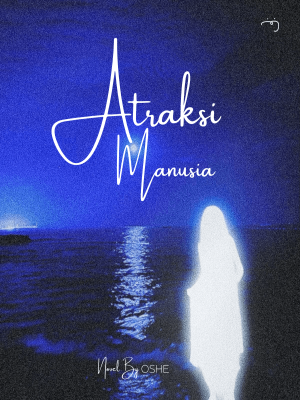Sorry, this chapter has been locked by the author!
Similar Tags
Sebelah Hati
2526
1274
0
Romance
Sudah bertahun-tahun Kanaya memendam perasaan pada Praja.
Sejak masih berseragam biru-putih, hingga kini, yah sudah terlalu lama berkubang dengan penantian yang tak tentu.
Kini saat Praja tiba-tiba muncul, membutuhkan bantuan Kanaya, akankah Kanaya kembali membuka hatinya yang sudah babak belur oleh perasaan bertepuk sebelah tangannya pada Praja?
The Call(er)
3986
2227
11
Fantasy
Ketika cinta bukan sekadar perasaan, tapi menjadi sumber kekuatan yang bisa menyelamatkan atau bahkan menghancurkan segalanya.
Freya Amethys, seorang Match Breaker, hidup untuk menghancurkan ikatan yang dianggap salah. Raka Aditama, seorang siswa SMA, yang selama ini merahasiakan kekuatan sebagai Match Maker, diciptakan untuk menyatukan pasangan yang ditakdirkan. Mereka seharusnya saling bert...
Atraksi Manusia
892
594
7
Inspirational
Apakah semua orang mendapatkan peran yang mereka inginkan? atau apakah mereka hanya menjalani peran dengan hati yang hampa?. Kehidupan adalah panggung pertunjukan, tempat narasi yang sudah di tetapkan, menjalani nya suka dan duka. Tak akan ada yang tahu bagaimana cerita ini berlanjut, namun hal yang utama adalah jangan sampai berakhir.
Perjalanan Anne menemukan jati diri nya dengan menghidupk...
No Life, No Love
2747
1711
2
True Story
Erilya memiliki cita-cita sebagai editor buku. Dia ingin membantu mengembangkan karya-karya penulis hebat di masa depan. Alhasil dia mengambil juruan Sastra Indonesia untuk melancarkan mimpinya. Sayangnya, zaman semakin berubah. Overpopulasi membuat Erilya mulai goyah dengan mimpi-mimpi yang pernah dia harapkan. Banyak saingan untuk masuk di dunia tersebut. Gelar sarjana pun menjadi tidak berguna...
Nemeea Finch dan Misteri Hutan Annora
601
431
0
Fantasy
Nemeea Finch seorang huma penyembuh, hidup sederhana mengelola toko ramuan penyembuh bersama adik kandungnya Pafeta Finch di dalam lingkungan negeri Stredelon pasca invasi negeri Obedient. Peraturan pajak yang mencekik, membuat huma penyembuh harus menyerahkan anggota keluarga sebagai jaminan! Nemeea Finch bersedia menjadi jaminan desanya. Akan tetapi, Pafeta dengan keinginannya sendiri mencari I...
Me vs Skripsi
3592
1487
154
Inspirational
Satu-satunya yang berdiri antara Kirana dan mimpinya adalah kenyataan.
Penelitian yang susah payah ia susun, harus diulang dari nol?
Kirana Prameswari, mahasiswi Farmasi tingkat akhir, seharusnya sudah hampir lulus. Namun, hidup tidak semulus yang dibayangkan, banyak sekali faktor penghalang seperti benang kusut yang sulit diurai. Kirana memutuskan menghilang dari kampus, baru kembali setel...
Dimension of desire
429
330
0
Inspirational
Bianna tidak menyangka dirinya dapat menemukan Diamonds In White Zone, sebuah tempat mistis bin ajaib yang dapat mewujudkan imajinasi siapapun yang masuk ke dalamnya.
Dengan keajaiban yang dia temukan di sana, Bianna memutuskan untuk mencari jati dirinya dan mengalami kisah paling menyenangkan dalam hidupnya
Tebing Cahaya
169
126
1
Romance
Roni pulang ke Tanpo Arang dengan niat liburan sederhana: tidur panjang, sinyal pasrah, dan sarapan santan. Yang melambat ternyata bukan jaringan, melainkan dirinyaterutama saat vila keluarga membuka kembali arsip janji lama: tanah ini hanya pinjaman dari arang. Di desa yang dijaga mitos Tebing Cahayakonon bila laki-perempuan menyaksikan kunang-kunang bersama, mereka tak akan bersatuRoni bertemu ...
The First 6, 810 Day
1756
1098
2
Fantasy
Sejak kecelakaan tragis yang merenggut pendengarannya, dunia Tiara seakan runtuh dalam sekejap. Musik—yang dulu menjadi napas hidupnya—tiba-tiba menjelma menjadi kenangan yang menyakitkan. Mimpi besarnya untuk menjadi seorang pianis hancur, menyisakan kehampaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam upaya untuk menyembuhkan luka yang belum sempat pulih, Tiara justru harus menghadapi ke...
Unexpectedly Survived
296
252
0
Inspirational
Namaku Echa, kependekan dari Namira Eccanthya. Kurang lebih 14 tahun lalu, aku divonis mengidap mental illness, tapi masih samar, karena dulu usiaku masih terlalu kecil untuk menerima itu semua, baru saja dinyatakan lulus SD dan sedang semangat-semangatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Karenanya, psikiater pun ngga menyarankan ortu untuk ngasih tau semuanya ke aku secara gamblang. ...


 rosadewiita
rosadewiita