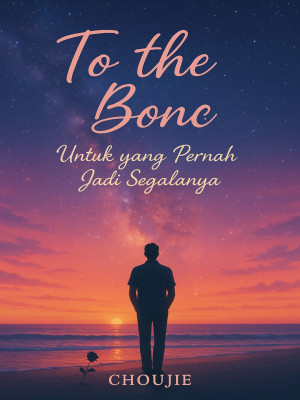Sorry, this chapter has been locked by the author!
Similar Tags
Kainga
2831
1444
13
Romance
Sama-sama menyukai anime dan berada di kelas yang sama yaitu jurusan Animasi di sekolah menengah seni rupa, membuat Ren dan enam remaja lainnya bersahabat dan saling mendukung satu sama lain. Sebelumnya mereka hanya saling berbagi kegiatan menyenangkan saja dan tidak terlalu ikut mencampuri urusan pribadi masing-masing.
Semua berubah ketika akhir kelas XI mereka dipertemukan di satu tempat ma...
My Private Driver Is My Ex
940
640
10
Romance
Neyra Amelia Dirgantara adalah seorang gadis cantik dengan mata Belo dan rambut pendek sebahu, serta paras cantiknya bak boneka jepang. Neyra adalah siswi pintar di kelas 12 IPA 1 dengan julukan si wanita bermulut pedas.
Wanita yang seperti singa betina itu dulunya adalah mantan Bagas yaitu ketua geng motor God riders, berandal-berandal yang paling sadis pada geng lawannya. Setelahnya neyra di...
PUZZLE - Mencari Jati Diri Yang Hilang
1011
682
0
Fan Fiction
Dazzle Lee Ghayari Rozh lahir dari keluarga Lee Han yang tuntun untuk menjadi fotokopi sang Kakak Danzel Lee Ghayari yang sempurna di segala sisi. Kehidupannya yang gemerlap ternyata membuatnya terjebak dalam lorong yang paling gelap. Pencarian jati diri nya di mulai setelah ia di nyatakan mengidap gangguan mental. Ingin sembuh dan menyembuhkan mereka yang sama. Demi melanjutkan misinya mencari k...
H : HATI SEMUA MAKHLUK MILIK ALLAH
72
67
0
Romance
Rasa suka dan cinta adalah fitrah setiap manusia.Perasaan itu tidak salah.namun,ia akan salah jika kau biarkan rasa itu tumbuh sesukanya dan memetiknya sebelum kuncupnya mekar.
Jadi,pesanku adalah kubur saja rasa itu dalam-dalam.Biarkan hanya Kau dan Allah yang tau.Maka,Kau akan temukan betapa indah skenario Allah.Perasaan yang Kau simpan itu bisa jadi telah merekah indah saat sabarmu Kau luaska...
Jalan Menuju Braga
1057
714
4
Romance
Berly rasa, kehidupannya baik-baik saja saat itu. Tentunya itu sebelum ia harus merasakan pahitnya kehilangan dan membuat hidupnya berubah. Hal-hal yang selalu ia dapatkan, tak bisa lagi ia genggam. Hal-hal yang sejalan dengannya, bahkan menyakitinya tanpa ragu.
Segala hal yang terjadi dalam hidupnya, membuat Berly menutup mata akan perasaannya, termasuk pada Jhagad Braga Utama--Kakak kelasnya...
Warisan Tak Ternilai
987
476
0
Humor
Seorang wanita masih perawan, berusia seperempat abad yang selalu merasa aneh dengan tangan dan kakinya karena kerap kali memecahkan piring dan gelas di rumah. Saat dia merenung, tiba-tiba teringat bahwa di dalam lingkungan kerja anggota tubuhnya bisa berbuat bijak. Apakah ini sebuah kutukan?
Segitiga Sama Kaki
1885
894
2
Inspirational
Menurut Phiko, dua kakak kembarnya itu bodoh. Maka Phiko yang harus pintar. Namun, kedatangan guru baru membuat nilainya anjlok, sampai merembet ke semua mata pelajaran. Ditambah kecelakaan yang menimpa dua kakaknya, menjadikan Phiko terpuruk dan nelangsa.
Selayaknya segitiga sama kaki, sisi Phiko tak pernah bisa sama seperti sisi kedua kakaknya. Phiko ingin seperti kedua kakaknya yang mendahu...
Diary of Rana
383
321
1
Fan Fiction
“Broken home isn’t broken kids.”
Kalimat itulah yang akhirnya mengubah hidup Nara, seorang remaja SMA yang tumbuh di tengah kehancuran rumah tangga orang tuanya. Tiap malam, ia harus mendengar teriakan dan pecahan benda-benda di dalam rumah yang dulu terasa hangat. Tak ada tempat aman selain sebuah buku diary yang ia jadikan tempat untuk melarikan segala rasa: kecewa, takut, marah.
Hidu...
Sweet Like Bubble Gum
2640
1553
2
Romance
Selama ini Sora tahu Rai bermain kucing-kucingan dengannya. Dengan Sora sebagai si pengejar dan Rai yang bersembunyi. Alasan Rai yang menjauh dan bersembunyi darinya adalah teka-teki yang harus segera dia pecahkan. Mendekati Rai adalah misinya agar Rai membuka mulut dan memberikan alasan mengapa bersembunyi dan menjauhinya.
Rai begitu percaya diri bahwa dirinya tak akan pernah tertangkap oleh ...
To the Bone S2
1562
886
1
Romance
Jangan lupa baca S1 nya yah.. Udah aku upload juga
....
To the Bone (untuk yang penah menjadi segalanya)
> Kita tidak salah, Chris. Kita hanya salah waktu. Salah takdir. Tapi cintamu, bukan sesuatu yang ingin aku lupakan. Aku hanya ingin menyimpannya. Di tempat yang tidak mengganggu langkahku ke depan.
Christian menatap mata Nafa, yang dulu selalu membuatnya merasa pulang.
> Kau ...


 rosadewiita
rosadewiita