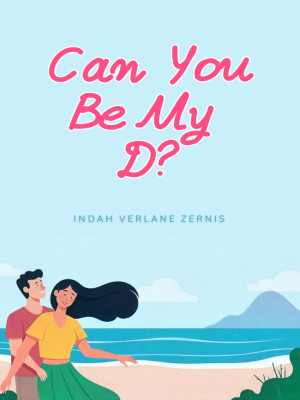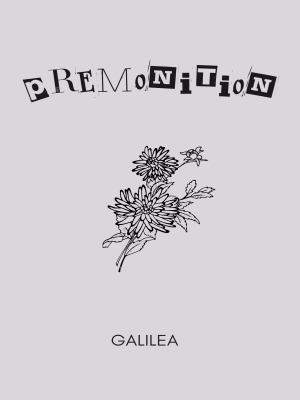Sorry, this chapter has been locked by the author!
Similar Tags
Dalam Satu Ruang
243
183
2
Inspirational
Dalam Satu Ruang kita akan mengikuti cerita Kalila—Seorang gadis SMA yang ditugaskan oleh guru BKnya untuk menjalankan suatu program. Bersama ketiga temannya, Kalila akan melalui suka duka selama menjadi konselor sebaya dan juga kejadian-kejadian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Langkah Pulang
1143
693
7
Inspirational
Karina terbiasa menyenangkan semua orangkecuali dirinya sendiri. Terkurung dalam ambisi keluarga dan bayang-bayang masa lalu, ia terjatuh dalam cinta yang salah dan kehilangan arah. Saat semuanya runtuh, ia memilih pergi bukan untuk lari, tapi untuk mencari.
Di kota yang asing, dengan hati yang rapuh, Karina menemukan cahaya. Bukan dari orang lain, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dan dari Tuh...
sulit melupakanmu
144
109
0
True Story
ini cerita tentang saya yang menyesal karena telah menyia nyiakan orang yang sangat cinta dan sayang kepada saya,dia adalah mantan saya
Lantunan Ayat Cinta Azra
1556
905
3
Romance
Perjalanan hidup seorang hafidzah yang dilema dalam menentukan pilihan hatinya. Lamaran dari dua insan terbaik dari Allah membuatnya begitu bingung. Antara Azmi Seorang hafidz yang sukses dalam berbisnis dan Zakky sepupunya yang juga merupakan seorang hafidz pemilik pesantren yang terkenal.
Siapakah diantara mereka yang akan Azra pilih? Azmi atau Zakky? Mungkinkah Azra menerima Zakky sepupunya s...
Can You Be My D?
199
176
1
Fan Fiction
Dania mempunyai misi untuk menemukan pacar sebelum umur 25. Di tengah-tengah kefrustasiannya dengan orang-orang kantor yang toxic, Dania bertemu dengan Darel. Sejak saat itu, kehidupan Dania berubah.
Apakah Darel adalah sosok idaman yang Dania cari selama ini? Ataukah Darel hanyalah pelajaran bagi Dania?
Glitch Mind
78
70
0
Inspirational
Apa reaksi kamu ketika tahu bahwa orang-orang disekitar mu memiliki penyakit mental?
Memakinya? Mengatakan bahwa dia gila? Atau berempati kepadanya?
Itulah yang dialami oleh Askala Chandhi, seorang chef muda pemilik restoran rumahan Aroma Chandhi yang menderita Anxiety Disorder......
Heavenly Project
987
669
5
Inspirational
Sakha dan Reina, dua remaja yang tau seperti apa rasanya kehilangan dan ditinggalkan. Kehilangan orang yang dikasihi membuat Sakha paham bahwa ia harus menjaga setiap puing kenangan indah dengan baik. Sementara Reina, ditinggal setiap orang yang menurutnya berhaga, membuat ia mengerti bahwa tidak seharusnya ia menjaga setiap hal dengan baik.
Dua orang yang rumit dan saling menyakiti satu sama...
Premonition
2096
1016
10
Mystery
Julie memiliki kemampuan supranatural melihat masa depan dan masa lalu. Namun, sebatas yang berhubungan dengan kematian. Dia bisa melihat kematian seseorang di masa depan dan mengakses masa lalu orang yang sudah meninggal. Mengapa dan untuk apa? Dia tidak tahu dan ingin mencari tahu.
Mengetahui jadwal kematian seseorang tak bisa membuatnya mencegahnya. Dan mengetahui masa lalu orang yang sudah m...
Loveless
13976
6090
615
Inspirational
Menjadi anak pertama bukanlah pilihan. Namun, menjadi tulang punggung keluarga merupakan sebuah keharusan. Itulah yang terjadi pada Reinanda Wisnu Dhananjaya. Dia harus bertanggung jawab atas ibu dan adiknya setelah sang ayah tiada.
Wisnu tidak hanya dituntut untuk menjadi laki-laki dewasa, tetapi anak yang selalu mengalah, dan kakak yang wajib mengikuti semua keinginan adiknya. Pada awalnya, ...
Kamu Tidak Harus Kuat Setiap Hari
4885
2425
0
Inspirational
Judul ini bukan hanya sekadar kalimat, tapi pelukan hangat yang kamu butuhkan di hari-hari paling berat.
"Kamu Tidak Harus Kuat Setiap Hari" adalah pengingat lembut bahwa menjadi manusia tidak berarti harus selalu tersenyum, selalu tegar, atau selalu punya jawaban atas segalanya. Ada hari-hari ketika kamu ingin diam saja di sudut kamar, menangis sebentar, atau sekadar mengeluh karena semua teras...


 rosadewiita
rosadewiita