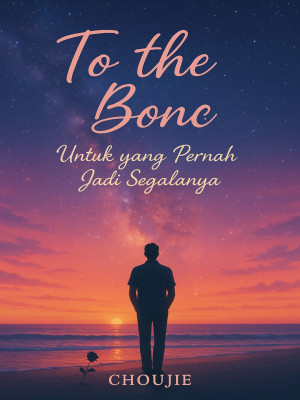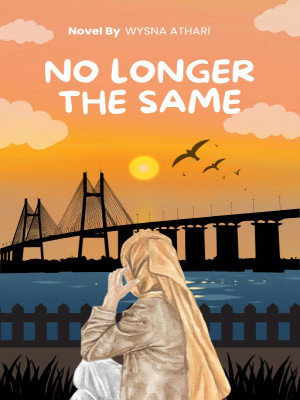6 tahun lalu
Saat itu, aku masih sendiri. Belum menikah, dan belum tahu arah pasti hidupku mau ke mana. Statusku: pegawai tidak tetap di sebuah kantor pemerintahan. Gajinya cukup untuk makan dan bayar kos, tapi tak cukup untuk disebut mapan. Apalagi membanggakan.
Aku pernah berpikir, kalau aku sudah kerja di kantor pemerintah, tinggal tunggu waktu saja sampai semua harapan orang tua tercapai. Tapi ternyata tidak semudah itu. Pegawai kontrak tetaplah pegawai kontrak. Tidak masuk dalam daftar ASN, tidak dapat tunjangan tetap, dan yang paling membuat sakit—tidak dianggap ‘jadi’.
Dulu, aku pikir jadi PNS itu jalur paling aman. Gaji tetap, masa depan jelas, orang tua senang. Dan, sejujurnya... aku juga senang membayangkan diriku pakai seragam dinas, kerja di kantor pemerintah, bawa map coklat, lalu pulang naik ojek dengan perasaan berguna.
Tapi nyatanya, mimpi itu cuma bertahan sampai pengumuman hasil ujian pertama keluar.
“Nama kamu nggak ada di pengumuman?” suara Ibu dari dapur waktu itu terdengar lebih kecewa daripada ingin tahu.
Aku cuma bisa geleng. “Enggak, Bu… belum rezeki.”
Ibu tak menjawab. Tapi langkahnya terdengar berat, seperti menarik napas kecewa dalam diam.
Tahun itu aku mencoba lagi. Tahun berikutnya, juga. Aku bahkan sampai ikut bimbel, belajar dari pagi sampai malam, menghafal materi, mengerjakan latihan soal, menyamakan waktu dengan timer, belajar manajemen waktu, semua demi 100 menit yang menentukan hidupku.
Tapi tetap… gagal.
Tiga kali. Berturut-turut. Di tahun ketiga, aku bahkan tidak bilang siapa-siapa aku ikut ujian. Malu kalau gagal lagi.
Lalu datanglah kesempatan S2. Aku diterima di program impianku. Waktu itu aku merasa: mungkin ini jalanku.
Tapi beasiswa yang kuharapkan baru bisa digunakan mulai semester tiga. Dua semester pertama harus ku biayai sendiri. Mana mungkin? Bahkan untuk bayar kos dan makan saja, aku masih harus pintar-pintar atur uang.
Aku mencari pinjaman. Bertanya ke beberapa teman dan saudara. Tapi entah kenapa, semuanya terasa berat. Aku terlalu lelah untuk memohon lagi.
Akhirnya aku mundur. Kuliah S2 yang sudah di depan mata, tinggal selangkah lagi, lepas begitu saja. Bukan karena aku tidak mampu. Tapi karena aku tidak bisa berdiri cukup kuat untuk berjuang sendirian lagi.
Setiap kegagalan itu seperti coretan kecil yang perlahan-lahan mengaburkan siapa aku sebenarnya. Sampai aku mulai mempertanyakan: kalau aku bukan PNS, bukan mahasiswa S2, bukan anak sulung yang membanggakan—aku ini siapa?
Orang-orang bilang aku pintar. Tapi pintar untuk apa?
Kadang aku bingung, sejak kapan kata “pintar” jadi beban.
“Anak pintar harusnya bisa lebih dari ini,” kata Ibu suatu kali. Bukan dalam nada marah, tapi lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Seperti kecewa atas dunia yang tak memenuhi harapan—dan aku, salah satu harapan itu.
Mungkin menurut Ibu, aku bisa seperti anak temannya yang sekarang sedang kuliah S2, atau seperti anak tetangga yang sudah jadi PNS di kementerian. Mereka tidak lebih pintar dariku, tapi lebih “jadi.” Lebih berhasil. Lebih membanggakan.
Tapi sejujurnya, aku tak pernah benar-benar merasa pintar. Aku hanya cepat memahami pelajaran di sekolah, cepat menyelesaikan tugas. Tapi hidup—hidup bukan sekadar soal pilihan ganda atau rumus logika. Tidak ada kunci jawaban di akhir buku. Tidak ada yang menjamin kau berhasil hanya karena kau mengerti lebih cepat.
Aku punya gelar sarjana, tapi hidupku terasa stagnan. Tidak ke mana-mana. Tidak jadi siapa-siapa.
Kerja dari pagi sampai sore, lalu pulang. Tidur. Ulangi lagi. Kadang aku merasa hanya numpang lewat di hidup sendiri, bukan benar-benar menjalaninya.
Di meja kerja kecilku, aku duduk menatap layar monitor. Excel terbuka. Angka-angka bergerak, grafik naik turun. Tapi di kepalaku, semuanya diam. Hampa. Seperti sedang menjalankan sesuatu yang bukan punyaku, bukan mimpiku.
Beberapa teman lama sudah jadi dosen, pejabat, bahkan ada yang kuliah lagi ke luar negeri. Di media sosial, mereka sering menulis caption seperti, “Trust the process.” Tapi proses macam apa yang hanya berisi kegagalan demi kegagalan?
Aku tahu aku terdengar pahit. Tapi aku cuma... lelah.
Dan di tengah kelelahan itu, aku jadi sering berpikir:
Bagaimana kalau... aku memang biasa-biasa saja?
Bagaimana kalau… aku sudah sampai di tempat tujuanku, hanya saja bukan seperti yang kuharapkan?


 rosadewiita
rosadewiita