Ada yang tumbuh dengan pelukan, ada yang tumbuh dengan diam. Dan kadang, diam lebih menyakitkan daripada bentakan.
**
Pagi di rumah selalu datang dengan pola yang sama—hangat, sibuk, tapi terasa kosong. Jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung detik-detil rutinitas. Dari dapur, suara wajan yang bergesekan dan denting sendok bersahut-sahutan, diiringi aroma nasi goreng yang mulai menguasai ruangan. Bau bawang goreng dan kecap manis menggelitik hidung, membuat perutku ikut bangun sepenuhnya.
Aku menuruni tangga pelan, seragam putih abu-abu sudah rapi di tubuhku. Langkahku berhenti sejenak di anak tangga terakhir, mataku menangkap sosok Mama yang tengah sibuk di dapur. Rambutnya dikuncir seadanya, blus polosnya sedikit kusut, dan tubuhnya bergerak cekatan mondar-mandir menyiapkan sarapan.
Di meja makan, Papa sudah duduk sambil menyeruput kopi dan membaca koran—halaman ekonomi, seperti biasa. Wajahnya serius, alisnya bertaut, seolah berita pagi ini bisa menentukan masa depan negara. Kursi di sebelahnya masih kosong. Bara belum juga turun dari kamar. Mungkin masih tidur atau sengaja menunda pagi seperti biasanya.
“Nasi gorengnya pakai telur ya, Ma?” tanyaku sambil menahan senyum kecil.
Mama menoleh, wajahnya hangat meski tampak lelah. “Tapi Ra... Telurnya tinggal satu.”
Aku menarik kursi dan duduk, lalu pura-pura sibuk menata sendok di piring sambil menahan nada kecewa. “Aku makan nasi gorengnya aja, Ma. Telurnya buat Bang Bara aja. Dia kan suka banget nasi goreng pakai telur setengah matang.”
Mama diam sebentar, lalu tersenyum. “Makasih ya Ra, udah perhatian sama Bang Bara.”
Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Dan entah kenapa, kalimat itu terasa cukup. Padahal… aku bahkan tidak yakin ini soal perhatian. Mungkin aku cuma ingin dengar Mama bilang: “Kamu anak yang baik, Nara.” Tapi aku tahu, Mama jarang bicara begitu. Jadi aku ambil yang ada. Senyumnya, dan ucapan terima kasih. Meski cuma sebentar.
Tak lama setelah itu, Bara akhirnya muncul dengan rambut awut-awutan dan kaus hitam lusuh yang biasa dipakainya tidur. Ia duduk di seberangku, bersamaan dengan Mama yang membawa semangkuk besar nasi goreng dari dapur.
Aku menyendok nasi goreng ke piringku sendiri. Sambil menunduk, mataku melirik ke arah Mama yang dengan sigap menyodorkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur setengah matang ke depan Bara.
“Masih panas, makan dulu sebelum dingin,” ucap Mama dengan suaranya yang hangat.
Bara hanya mengangguk singkat, tanpa terima kasih, tanpa tersenyum. Tangannya meraih sendok, dan langsung menyendok nasi goreng itu dengan malas.
Aku diam. Tak ada yang salah sebenarnya, Mama memang selalu begitu pada Bara. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Aku juga lapar. Aku juga anaknya. Tapi aku harus ambil sendiri.
“Kamu nggak kuliah hari ini, Ra?” tanya Papa tanpa menoleh ke arahku. Suaranya datar, seperti sekedar basa-basi.
Aku mengunyah perlahan sebelum menjawab, “Ini sudah pakai seragam Pa. Sarapan dulu baru berangkat. Lagian aku masih SMA belum kuliah.”
Papa mengangguk, seperti baru ingat. “Oh iya, kamu SMA, ya.” Dia tertawa kecil, lalu memandang ke arah Bara. “Kamu hari ini kuliah, Bar?”
Bara menguap lebar. “Kayaknya siang deh, Pa. Tugas belum kelar.”
Papa mengangguk lagi, kali ini sambil tersenyum. Senyum yang tidak pernah dia berikan ketika bicara denganku tadi.
“Bara, nanti sore ikut sama Papa, ya. Ada rapat di kantor. Sekalian nemenin Papa beli peralatan buat proyek baru,” kata Papa, sambil menyeruput kopinya yang masih setengah mengepul.
Bara diam sejenak, sambil berpikir apa saja yang akan dia lakukan hari ini, kemudian menjawab. “Hmm, kayaknya sih bisa, soalnya kosong nanti sore.”
Mendengar itu, Mama yang sejak tadi sibuk di dapur menghampiri meja makan dengan langkah pelan. Senyumnya masih tersungging, “Boleh gak mama ikut, sekalian mau belanja ke supermarket?”
Papa menatap Mama sejenak, lalu mengangguk pelan. “Iya boleh, sekalian nanti sore makan di luar aja gak usah masak.”
Aku mengerutkan dahi, menatap mereka yang asik menyusun rencana tanpa melibatkan aku di dalamnya.
Lalu, Mama melirikku sebentar, ada senyum tipis di wajahnya. “Nara, nanti sore ada les kan? Nanti makanannya Mama bungkusin aja ya..”
Aku diam. Terlalu banyak protes yang rasanya ingin aku luapkan, tapi kehangatan pagi itu akan membeku jika aku buka suara. Dan tidak ada lagi pertanyaan lebih lanjut. Tidak ada basa-basi apakah aku ingin ikut. Tidak ada tawaran. Bahkan tidak ada yang peduli.
Mama menyudahi percakapan itu, lalu kembali ke dapur tanpa banyak kata. Aku memandangi mereka semua, merasa terpinggirkan dalam keseharian yang biasa. Jika ada yang merasa kehilangan, itu adalah aku, tetapi tidak ada yang menyadarinya.
Setelah sarapan, aku berdiri perlahan, berpamitan sambil mengumpulkan sisa-sisa tenaga dan keberanian untuk melangkah keluar. Pagi masih menggigil di luar sana, udara dingin menyelinap masuk lewat celah pintu. Aku mengenakan jaket abu-abu yang biasa kupakai untuk membungkus tubuhku, ransel biru tua menempel di punggung. Langkahku cepat, seperti ingin buru-buru meninggalkan rasa sesak yang kubawa dari ruang makan.
Di jalan yang dingin dan sepi, pikiranku tenggelam ke dalam dirinya sendiri. Saat itu aku sadar, aku tidak sekadar tumbuh. Aku membentuk diriku sendiri, dari luka, dari ketakutan, dan dari semua hal yang tak sempat kupahami.
Semua orang melihatku sebagai anak yang ideal. Nilaiku bagus, aktif ikut lomba, ikut organisasi, selalu tersenyum sopan dan tertawa ceria, seolah tak pernah ada yang patah. Padahal, semua itu cuma cara… supaya mereka percaya aku baik-baik saja.
Aku sampai di gerbang sekolah saat bel belum berbunyi. Beberapa anak tampak berlarian, sebagian duduk-duduk di tangga dekat taman sambil membuka bekal atau ngobrol soal tugas.
Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namaku dari jauh. Suaranya nyaring dan terdengar familiar. “Naaarrraaaa!”
Aku menoleh. Terlihat Laras—temanku sejak kelas sepuluh setengah berlari ke arahku sambil tersenyum lebar. Tangannya terangkat, melambai-lambai seolah baru saja memenangkan lotre, sementara ranselnya bergoyang-goyang tak seirama di punggung.
“Kamu kenapa sih jalan kayak abis ngubur mantan semalem?” Dia mencubit pelan lenganku.
Aku tertawa kecil, setengah dipaksa. “Biasa. Overthinking pagi-pagi,” jawabku sambil mengangkat bahu.
Laras menatapku dengan mata menyipit. “Overthinking atau overfamily?”
Aku tidak menjawab. Cuma tersenyum dan mengangguk pelan. Laras cukup pintar untuk tidak perlu dijelaskan banyak. Dan cukup tulus untuk tidak menghakimi apapun yang aku simpan.
“Kita ke kelas yuk. Pasti si Intan udah nungguin kamu. Soalnya tadi malam dia bilang ke aku nggak ngerti materi untuk ujian fisika dan cuma percaya kamu yang bisa jelasin tanpa bikin dia nangis,” canda Laras sambil menarik tasku.
Kami berjalan berdampingan menuju lantai dua. Angin pagi masih mengusap pelan wajahku. Sinar matahari pagi mulai menyelinap memenuhi koridor. Aku menarik napas, membiarkan cahaya itu menyentuh tubuhku sebentar, sebelum semuanya kembali bergerak.
Di dalam kelas, suasana sudah lumayan ramai. Intan duduk sambil menggambar sesuatu di belakang bukunya. Begitu melihat aku, dia langsung berseru, “Naraaaa! Kamu harus nyelametin akuuuu!”
Aku tertawa dan duduk di bangkuku, lalu membuka buku catatan.
“Tenang, hari ini aku bawa jimat.”
“Apaan?” tanya Intan polos.
Aku menunjuk ujung penaku. “Pulpen kesayangan. Nggak pernah gagal bikin rumus jadi jinak.”
Kami bertiga tertawa. Hal-hal kecil seperti ini, kadang yang bikin hidupku di sekolah terasa lebih ringan. Mereka pikir aku bahagia karena selalu tersenyum, karena nilaku bagus, karena ikut ini-itu. Padahal, aku bahagia karena hal-hal remeh, seperti tawa di pagi hari, atau pelukan singkat dari Laras waktu aku diam lebih lama dari biasanya.
Waktu pun terus bergulir, tak terasa bel tanda pulang akhirnya berbunyi juga. Suara kursi diseret dan langkah kaki terdengar bersahut-sahutan. Di luar jendela, langit mulai memerah—warna sore yang selalu bikin hati terasa tenang, sekaligus hampa. Hari ini adalah hari terakhir sekolah sebelum liburan dimulai. Jadwal-jadwal ujian sudah selesai, tugas-tugas terakhir sudah dikumpulkan. Kelas kami riuh dengan rencana-rencana liburan, staycation, atau sekadar main bareng di rumah teman.
“Aku mau ke Bandung sama keluarga!” seru Intan sambil mengemasi bukunya.
Laras menyusul dengan semangat, “Aku pengin nyoba camping di kaki gunung! Katanya ada tempat baru yang keren banget!”
Aku ikut tersenyum, bahkan tertawa bersama mereka. Namun di dalam hati, ada getir yang diam—keinginan untuk merasakan liburan seperti itu, yang tak pernah benar-benar menjadi kenyataan.
Kami bertiga berjalan bersama menuju gerbang sekolah. Setelah berpamitan dan berpelukan sebentar, aku berjalan pulang sendiri. Jalanan terasa lengang, dan angin sore membawa bau tanah yang hangat. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar mengalihkan pikiranku dari satu pertanyaan sederhana: “Liburan ini akan jadi seperti apa?”
Di rumah, suasananya tak banyak berubah. Bara masih dengan kesibukannya sendiri, Papa dan Mama seperti biasa tenggelam dalam urusan mereka. Aku masuk kamar, lalu merebahkan diri di tempat tidur.
Dari luar jendela, suara anak-anak kecil bermain terdengar samar. Tapi di dalam kamar, hanya keheningan yang menemaniku.
Aku mengambil ponsel, membuka chat dengan Laras, lalu mulai mengetik.
Nara:
Liburan ini bakal biasa aja kayaknya. Gak tahu harus senang atau sedih. Tapi rasanya sedih sih, kayak… semua orang punya rencana seru, dan lagi-lagi aku cuma di rumah.
Beberapa menit kemudian, balasan datang.
Laras:
Eh, jangan sedih dulu dong! Sebelum camping, aku diajak kakakku ke pameran temennya. Katanya ada sayembara lukisan untuk komunitas difabel. Mau ikut?
Nara:
Mau banget!. Tapi kayaknya gak bakal dibolehin Mama Papa deh. Liburan gini mereka maunya aku di rumah aja, bantu-bantu atau ya... diem aja di kamar.
Laras:
:’( yaaah, padahal aku udah ngebayangin kita duduk di pojokan galeri, komentar sok-sok ngerti seni...
Beberapa detik setelah itu Laras mengirim pesan lagi, notifikasi lain muncul.
Laras mengirim sebuah gambar.
Sebuah lukisan: langit senja dengan sapuan warna lembut, pohon-pohon ramping berdiri diam di pinggir danau, dan di tengahnya, sosok kecil duduk membelakangi, menghadap air yang nyaris tanpa riak.
Aku terdiam. Lama. Ada sesuatu dari gambar itu yang menghentikan segalanya. Seperti saat dunia yang bising mendadak kehilangan suara. Mataku tak bisa berpaling. Sosok kecil itu… aku. Atau entah bagaimana, rasanya begitu. Diam, sendiri, tapi tidak sepenuhnya kosong. Seperti sedang menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan.
Aku memperbesar gambar itu. Menelusuri tiap goresan warnanya. Warna-warna yang tak terlalu terang, tapi lembut. Tenang. Seolah lukisan itu mengerti, perasaan yang selama ini tidak bisa kutaruh ke dalam kata. Seolah, seseorang di luar sana, entah siapa, telah melukis isi kepalaku.
Nara:
Gambar ini… kayak aku. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak… aku ada di situ.
Laras:
Itu salah satu lukisan yang bakal dipajang di pameran, Ra. Yang buat teman kakakku dari komunitas inklusi visual. Aku suka banget suasananya, tenang tapi dalem.
Nara:
Iya aku juga suka banget, Makasih ya, Laras. Lukisan itu… kayak nenangin sesuatu yang dari tadi gak bisa aku jelasin.
Laras:
Siap Ra. Kapan pun kamu butuh tenang, aku kirim lagi gambarnya.
Aku tersenyum kecil, mataku masih terus menatap layar ponsel lekat dan lama. Rasanya... aku tidak merasa sendirian sepenuhnya. Lukisan itu, entah bagaimana, menjagaku.
Tak terasa, malam turun perlahan, membawa hawa yang lebih dingin. Di luar jendela, lampu-lampu mulai menyala satu per satu, menimbulkan pantulan lembut di lantai kamar.
Setelah selesai menyantap makan malam, Papa tiba-tiba membuka suara. “Akhir pekan ini kita liburan, ya. Ke Jogja, naik mobil. Tiga hari dua malam. Udah lama kita nggak jalan bareng, kan?”
Mama tersenyum, matanya membesar, "serius Pa?," tanyanya masih setengah percaya.
Papa mengangguk pasti, "Semua harus ikut, termasuk kamu Bar, kosongkan jadwal weekend ini." Jawab Papa.
Mama tersenyum semakin lebar, menatap Bara yang hanya mengangkat alis sambil mengunyah kerupuk. Aku memandangi mereka satu per satu. Aneh.
Rasanya baru kemarin aku merasa orang tuaku tak adil, menyisakan luka yang kusimpan sendiri. Dan sekarang, mereka mengajak liburan. Seolah luka yang belum sembuh bisa diajak berkemas dan ikut jalan-jalan.
Tapi tak kupungkiri, aku juga bahagia. Bukan karena ini liburan mewah, atau karena destinasi impian yang akan kami kunjungi. Tapi karena akhirnya keluarga kami liburan juga—kayak orang-orang. Rasanya senang membayangkan... bisa duduk bareng tanpa buru-buru, tanpa urusan masing-masing yang saling tumpang tindih.
Dan semoga liburan ini juga bisa jadi jeda untuk kami semua. Untuk luka yang tak sempat dibicarakan, untuk tawa yang tertinggal, untuk kasih sayang yang tak terbagi rata, dan untuk keluarga yang tak sempurna, tapi masih berusaha saling menggenggam. Mungkin itu cukup, setidaknya untuk sekarang. Dan kurasa… aku siap untuk itu.


 bunca_piyong
bunca_piyong








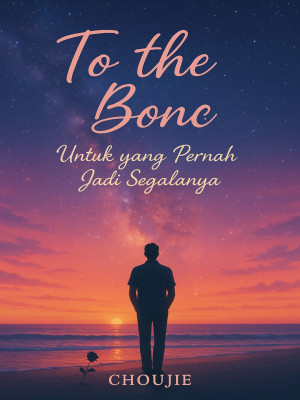









Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .