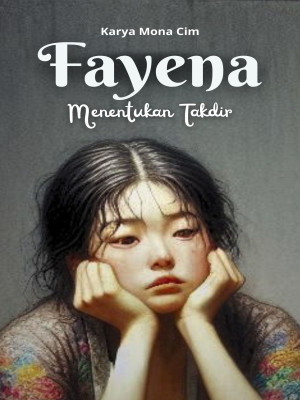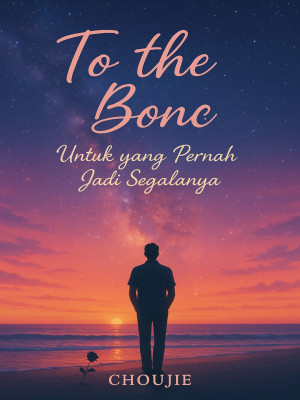Pukul 09.00 WIB, sehari setelah berita viral mengguncang publik
Ruang seminar utama hari ini terasa seperti ruang pengadilan rahasia. Biasanya digunakan untuk seminar atau jamuan internal, kini ruangan berpanel kayu gelap itu dipenuhi ketegangan yang nyaris membekukan udara. Lampu gantung kristal di atas meja panjang berkilau dingin, seolah menghakimi siapa pun yang duduk di bawahnya.
Dokter Nata duduk tepat di pusat meja, sosoknya tegap namun matanya menyimpan kelelahan panjang. Di sisi berlawanan, deretan Dewan Direksi mengenakan jas resmi, lengkap dengan wajah-wajah beku yang tampak lebih seperti hakim daripada kolega.
Di barisan belakang, Rajendra dan Alin duduk menahan napas. Mereka tampak seperti dua pion kecil di tengah pertarungan raksasa.
Pak Rahman, Kepala HRD, membuka sesi dengan nada diplomatis tapi tak menyembunyikan tensi. “Kami berkumpul hari ini untuk mengklarifikasi satu hal besar, Dokter Nata. Berita anonim yang memojokkan institusi kita—dugaan malpraktik dan penculikan anak—telah menimbulkan kerugian besar. Reputasi Rumah Sakit Pelita Harapan, yang kita bangun selama dua dekade... kini berada di ujung tanduk.”
Seorang anggota dewan dengan kacamata tipis menyambung, kali ini tanpa basa-basi “Dan kami memiliki alasan kuat mencurigai Anda sebagai penyebar berita itu. Anda terlalu dekat dengan kasus anak hilang—Arsya. Terlalu vokal. Terlalu emosional.”
Dokter Nata menatap lurus ke depan. Suaranya tenang, tapi terdengar dari rongga dada yang dalam. “Saya tidak menyebarkan berita itu. Saya tidak menjatuhkan institusi ini. Tapi saya tak bisa pura-pura bisu saat anak di bawah perawatan saya hilang begitu saja. Itu bukan desas-desus. Itu fakta medis dan fakta moral.”
“Fakta yang Anda senjatai menjadi peluru publik?” sergah anggota dewan lainnya, bersandar ke depan. “Berita itu terlalu rapi, terlalu teknis untuk sekadar tulisan iseng. Dan siapa lagi yang tahu rincian medis selain Anda dan tim Anda?”
Senyuman kecut muncul di bibir Dokter Nata, bukan karena angkuh—tapi karena terlalu lelah untuk marah. “Justru karena saya tahu fakta medisnya, saya tahu siapa yang bisa memelintirnya.”
Direktur Utama, seorang pria tua dengan tangan yang gemetar tapi mata tajam, akhirnya bicara. Tangannya menyentuh meja, mengetuk dua kali. “Kita butuh bukti, bukan sikap heroik, Dokter Nata. Jika bukan Anda pelakunya, buktikan. Dan jika memang Anda tahu siapa pelakunya, buka sekarang juga. Kami tidak akan terus membiarkan nama rumah sakit dipermainkan.”
Ia berhenti sejenak. Seorang staf IT rumah sakit berdiri di pojok ruangan, lalu maju membawa beberapa berkas dan laptop. Setelah diberi izin oleh Ketua Dewan Direksi, dia kemudian menyampaikan informasi yang berhasil dia dapatkan. “Kami telah memeriksa log sistem internal, riwayat unggahan jaringan, dan semua akses akun staf. Tidak ditemukan unggahan langsung dari perangkat Anda, Dokter. Bahkan akun email dan jaringan rumah sakit Anda… tidak menunjukkan aktivitas mencurigakan. Bahkan metadata unggahan menunjukkan zona waktu di luar negeri—kami menduga server digunakan di Islandia atau India Selatan.”
Ketua HRD menimpali, agak terdengar tidak puas. “Tapi pola bahasanya terlalu mirip. Gaya penulisan dalam berita itu... memakai istilah medis internal yang hanya diketahui tim klinis. Selain itu, hubungan anda sepertinya sudah melebihi hubungan Dokter dan pasien”
Dokter Nata menoleh, suaranya tetap tenang. “Saya tidak menyangkal pernah menyebut itu. Tapi kalau setiap istilah medis dipakai sebagai bukti, semua staf medis bisa Anda curigai.”
Suasana ruangan menegang. Beberapa direktur saling melirik, terlihat jelas mereka kehabisan peluru logika.
Direktur Umum, akhirnya menghela napas pelan.
Tim IT rumah sakit kembali menambahkan informasi “Kami sudah menyelidiki semua pihak. Bahkan jaringan eksternal. Tapi unggahan pertama muncul dari akun anonim—pakai VPN, domain luar negeri, dan tidak bisa ditelusuri. Kami... tak bisa menautkannya langsung ke siapa pun.”
Sekali lagi, hening. Ketidak pastian menggantung seperti kabut di langit-langit ruangan.
“Maka dari itu...” Direktur Utama, mengambil alih “...meski dugaan kami kuat, kami tidak memiliki dasar legal atau digital untuk menjatuhkan sanksi. Investigasi akan tetap berjalan, tapi—untuk saat ini—kami nyatakan Anda tidak bersalah.”
Dokter Nata berdiri. Tak ada pembelaan. Tak ada tepuk tangan. Hanya tatapan yang mengandung kalimat: kita belum selesai.
Saat ia melangkah keluar, matanya menoleh pada Rajendra dan Alin.
“Kedai kopi seberang, 10 menit lagi.”
Mereka mengangguk, memahami perintah Dokter Nata.
Saat pintu ruangan tertutup di belakang mereka, hanya satu hal yang jelas: permainan baru saja dimulai.
Sebuah kedai kopi minimalis bernama “Kopi Senja” terselip di antara deretan toko tak jauh dari Rumah Sakit Pelita Harapan. Tempatnya kecil, dengan hanya beberapa meja kayu dan aroma kopi yang memenuhi udara. Karena lokasinya yang sedikit tersembunyi, karyawan rumah sakit jarang mampir ke sini. Sebuah tempat sempurna untuk berbicara tanpa banyak mata dan telinga.
Dokter Nata sudah duduk di salah satu meja pojok, secangkir latte mengepul di depannya. Ia menyunggingkan senyum tipis saat Rajendra dan Alin memasuki kedai. Mereka baru saja tiba setelah persidangan yang melelahkan.
“Saya tidak menyebarkan berita itu. Saya tidak menjatuhkan institusi ini. Tapi saya tak bisa pura-pura bisu saat anak di bawah perawatan saya hilang begitu saja. Itu bukan desas-desus. Itu fakta medis dan fakta moral.” Rajendra mengikuti gaya Dokter Nata saat proses pembelaan di sidang yang baru selesai mereka hadiri bersama.
“Tadi Dokter terlihat sangat keren” puji Alin.
“Terima kasih, Lin.”
“Tapi itu cuma pembelaan, kan? faktanya memang Dokter yang menyebarkan berita”
“Kamu mengatakan aku baru saja berbohong”
“Yah… kebohongan manis? kayak waktu ngerayu Arsya minum obat?”
Dokter Nata tertawa saat Rajendra mencoba mendesaknya “Yang aku katakan dipersidangan semua adalah perkataan jujur” sanggah Dokter Nata
“Lalu, akun @Mataketiga?” tanya Rajendra, bingung.
“Bukan milikku.” Dokter Nata membela diri dengan percaya diri. “Itu juga Fakta, bukan kebohongan” lanjutnya.
“Apa itu dari keluarga Arsya? tapi… akan lebih meyakinkan kalau itu disebarkan oleh Dokter Nata.” sanggah Rajendra tak kalah yakin.
“Akun bukan miliku, tapi beritanya memang aku yang membuat. Kan tadi aku hanya ditanya apakah anda memposting berita tersebut? tapi faktanya bukan aku yang memposting. orang lain atas wewenangku.”
Rajendra terdiam, mencoba mencerna. Kemudian senyum tipis merekah di wajahnya. Ada kilatan nakal di mata Dokter Nata.
“Dok... maaf menyela. Coba lihat ini!” Alin menyerahkan ponselnya, menampilkan artikel yang baru saja dirilis.
Rajendra membaca headline:
"RS PELITA HARAPAN KLARIFIKASI KASUS PASIEN HILANG."
“Jadi mereka akui Arsya ada, tapi poles image jadi korban penculikan, bukan kelalaian medis,” ujarnya sambil menggeser layar.
“Memang harus seperti itu," sahut Dokter Nata. "Rumah sakit harus menarik simpati publik.”
“Benar sih, dok. Lalu bagaimana sekarang? Berita itu sudah ditarik, akun-akun yang merepost berita itu juga tiba-tiba terkena masalah…”
“Kita nggak perlu melakukan apapun.” Jawab Dokter Nata, singkat “Yakinlah, mulai sekarang kita tidak bergerak sendiri, berita itu hanya umpan, sekarang tinggal kita tunggu hasil dari umpan yang kita lempar.” jelas Dokter Nata dengan nada penuh keyakinan.
***
┌─────────────────────────────────────────────────────
│ KLARIFIKASI RESMI
│ RS PELITA HARAPAN
│
│ FAKTA KASUS PASIEN HILANG:
│ Korban Kecelakaan, Bukan Kelalaian Medis
│
│ Yogyakarta – RS Pelita Harapan menyampaikan
│ klarifikasi resmi terkait pemberitaan viral
│ hilangnya pasien anak berinisial "Arsya."
│
│ FAKTA SEBENARNYA:
│ • Arsya adalah korban tabrak lari tanpa identitas
│ • RS memberikan perawatan medis intensif
│ • Sebelum diserahkan ke Dinsos, terjadi penculikan
│ • Diduga sabotase sistem keamanan RS
│
│ Manajemen meminta maaf atas kegaduhan dan
│ berkomitmen bekerja sama dengan pihak berwenang
│ mengusut tuntas kasus penculikan ini.
│
│ Kontak Media: humas@pelitaharapan.co.id
└─────────────────────────────────────────────────────
***
Keyakinan Dokter Nata disambut baik oleh takdir. Hampir sehari pergerakan Pak Damar dihentikan oleh badai salju. Namun pagi ini, di Bandara Narita, Pak Damar sudah berada di konter check-in. Wajahnya tampak lelah, namun ada tekad kuat di matanya. Penerbangannya menuju Bangkok dijadwalkan pukul 18.00 waktu Jepang. Ini adalah rute transit tercepat yang bisa ia dapatkan, meski harus memutar jauh.
Ia menyerahkan paspor dan tiketnya kepada petugas, sesekali melirik jam tangan. Arsya. Ia harus segera sampai pada cucunya.
28 jam lagi…
***
Sama halnya Pak Damar yang sedang cemas. Di rumah singgah tempat keluarganya berada juga sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Malam itu, rumah singgah terasa dingin dan sunyi. Salju masih turun tipis di luar, menyelimuti taman dan jalanan. Nadhira mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya tegang. Semalaman Pak Damar tidak kembali, dan ponselnya tidak bisa dihubungi.
"Papa kemana sih?!" Nadhira berhenti melangkah, frustasi memuncak. "Semalaman hilang tanpa kabar! Ibu sampai tidak bisa tidur karena khawatir!"
Ibu Nadhira duduk di sofa, mengelus rambut Calita yang tertidur lelap di pangkuannya. Wajahnya pucat, mata bengkak bekas menangis. "Nadhira... jangan keras-keras. Calita baru saja tertidur."
"Tapi Bu..." Nadhira menurunkan suaranya, tapi getaran amarah masih terasa. "Papa tidak pernah seperti ini. Tidak pernah menghilang tanpa bilang ke mana."
Pak Aswan muncul dari arah dapur, ponsel masih di telinga. Setelah menutup panggilan, ia menghampiri istri dan mertuanya.
"Sudah ada kabar," ujarnya pelan, berusaha menenangkan. "Papa terbang ke Bangkok tadi malam."
Nadhira mengerutkan kening. "Bangkok? Bukan Indonesia?"
"Ada urusan mendadak," Pak Aswan menjawab cepat, terlalu cepat. "Bisnis perhotelan. Kalian tahu sendiri, Papa sering begitu kalau ada peluang investasi."
“Ke Bangkok? Bukan kembali ke Indonesia? Setelah menghilang semalaman?” Nadhira tampak curiga, namun demi menenangkan Ibunya dia hanya memberitahu, Pak Damar ada kunjungan ke Bangkok.
***
Kecurigaan Nadhira memang berdasar. Waktu terus berdetak. Tinggal 28 jam lagi hingga Arsya—mungkin—berada dalam pelukan orang yang tepat. Namun sebelum itu, bocah itu harus bertarung bukan dengan monster atau penculik, melainkan dengan tubuhnya sendiri, yang semakin hari semakin menolak hidup.
Sudah berkali-kali ia keluar masuk kamar mandi. Sejak mendengar pikiran Kania tentang obat dari Gesang, tubuh Arsya seolah memutuskan untuk waspada terhadap segalanya. Bukan hanya obat—bahkan makanan pun ikut ditolak.
Setiap suapan berubah jadi ledakan rasa mual. Setiap tegukan seperti alarm bahaya.
“Masih mual?” tanya Alana, khawatir. Ia baru selesai mencuci piring, matanya terus menatap Arsya yang lesu. “Aku bilang ke Kak Kania, ya? Biar kamu dikasih obat…”
Arsya buru-buru menahan tangannya. “Enggak usah... nanti juga sembuh sendiri,” bisiknya cepat. Ia takut Kania akan memaksa obat yang sama lagi.
“Yaudah, kita makan, yuk? Aku lapar banget! Kamu juga pasti, habis muntah-muntah terus.”
Arsya hanya menjawab dengan senyum kecil yang dipaksa, seolah senyumnya bisa menahan perih yang mengaduk di dalam perutnya. Ia sungguh ingin makan. Tapi tubuhnya sudah tak percaya lagi.
***
Di ruang makan, aroma semur ayam memenuhi udara—hari ini panti mendapat sumbangan. Meja-meja penuh suara ceria, tapi Arsya hanya menatap piringnya seperti medan perang.
‘Makanan ini bukan dari orang jahat. Ini dari Ibu Panti... dia orang baik. Kak Kania juga. Mereka nggak akan menyakitiku. Ini aman. Aku harus makan. Harus.’
Ia menyendokkan suapan pertama. Manis. Gurih. Lidahnya menyambut. Satu suap. Dua suap. Tiga suap. Perutnya masih tenang.
“Enak, kan?” tanya Alana sambil mengunyah dengan penuh semangat.
Arsya mengangguk pelan. Suapan keempat masuk. Ia mulai percaya—mungkin tubuhnya bisa diajak kerja sama.
Tapi pada suapan kelima, tiba-tiba mual datang seperti gelombang tanpa peringatan.
‘Tahan… jangan dimuntahkan… aku lapar dan aku perlu makan.… yang masak Ibu panti. Ini bukan dari orang jahat…’
Namun tubuhnya tak bisa dibohongi. Keringat dingin mengalir. Tangan gemetar. Nafas pendek. Ia tahu tanda-tanda ini. Tubuhnya bersiap menolak.
Kania melintas di belakang, meletakkan kerupuk di meja. “Habiskan ya, Dek. Biar cepat sembuh.”
Arsya menunduk. Matanya menatap piring yang kini seperti musuh. Sisa makanan tinggal separuh, tapi perutnya sudah melilit. Ia mencoba meneguhkan diri.
‘Kak Kania baik… dia pasti kecewa kalau aku muntah lagi. Aku harus kuat. Aku… harus tahan.’
Tapi tangan yang gemetar menumpahkan sendoknya ke piring. Kepalanya berat, pandangannya berkunang. Tubuhnya menolak lagi. Kali ini lebih hebat. Lebih menyakitkan. Tak ada waktu.
“Aku harus ke kamar mandi,” katanya lirih, hampir tak terdengar.
Ia berdiri tergesa, bergegas ke kamar mandi sebelum semua isi perutnya tumpah. Tubuhnya mungkin kecil. Tapi pertarungan di dalamnya lebih besar dari yang bisa dilihat siapa pun.
***
Arsya tidak kembali ke ruang makan.
Tubuhnya gemetar, bukan karena lapar, tapi karena dingin yang menjalar dari dalam. Keringatnya dingin, telapak tangan basah, dan perutnya terasa seperti digulung tali tambang. Nafasnya pendek-pendek, seperti sedang dikejar sesuatu yang tak kasatmata.
Sebelum dia pergi dari ruang makan, dia sempat mendengar Alana berteriak. Namun, Arsya tidak sempat menjawab.
Langkahnya tertatih melewati ruang makan. Sempat berhenti sejenak melihat anak lain yang lahap dengan menu malam ini. Namun Arsya melanjutkan langkah, menuju ruang bayi.
Seperti biasa ada Fatma yang berjaga. Melihat Arsya yang berdiri di depan pintu membuatnya melambaikan tangan menyuruhnya masuk. Seolah sudah memahami diamnya Arsa adalah mencari persetujuannya.
“Mbak Fatma, aku kedinginan. Boleh tidur duluan?”
“Kamu sakit lagi? Demam lagi, Nak? sudah minta obat ke Kak Kania?”
“Belum, tapi aku nggak demam. Cuma dingin. Enggak sakit, kok” ujarnya sambil menarik selimut. Dalam diam, tubuhnya masih menggigil meski udara malam tak sedingin itu.
***
Gesang duduk di kamar kos yang sempit, cahaya layar laptop menyinari wajahnya dalam kegelapan. Gambar dari kamera pengintai terpampang jelas—sudut ruang bayi, tempat Arsya kini meringkuk seperti kepompong di antara selimut tipis.
Keningnya berkerut. Jam segini, bukankah anak-anak masih di ruang makan?
Tangannya meraih ponsel khusus—hasil modifikasi Bara. Jarinya memutar rekaman suara yang ditangkap dari perangkat tersembunyi di balik casing ponsel Kania. Kania yang polos itu tak pernah tahu bahwa "hadiah" dari alumni sukses itu kini merekam setiap percakapannya.
Suara-suara familiar mengalir dari speaker kecil:
"Anak barunya kemana, Alana?"
"Kayaknya dia muntah lagi, Kak. Tadi siang juga begitu."
"Muntah-muntah? Seperti masuk angin?"
"Iya! Kayak Mbak Fatma waktu sakit, minta dikerik. Aku mau bilang ke Kak Kania tapi dia nggak boleh. Katanya nanti sembuh sendiri."
"Yasudah, nanti Kakak lihat dia."
Gesang menghentikan rekaman, matanya kembali ke layar. Arsya masih di sana, tak bergerak. Tubuh kecil itu gemetar halus—bukan karena dingin.
"Gangguan makan..." gumamnya pelan, senyum tipis mengembang. "Menarik sekali."
***
Cukup lama Gesang mengamati. Jari-jarinya mengetuk meja dalam ritme yang tak beraturan—kebiasaan lama saat menganalisis pasien dulu, sebelum tuduhan malpraktik menghancurkan kariernya.
"Anak ini... cerdas," bisiknya dengan nada yang hampir seperti kagum. "Terlalu cerdas untuk ukuran delapan tahun."
Ingatannya melayang ke kejadian-kejadian sebelumnya. Saat Arsya baru sadar dan langsung tahu harus menghubungi rumah sakit. Saat bocah itu nekat kabur dengan strategi yang terkalkulasi. Bahkan cara dia menyembunyikan pil-pil obat di bawah bantal, membuangnya saat Fatma tak melihat—semua itu menunjukkan pikiran yang tajam.
"Dewasa sebelum waktunya," lanjut Gesang, matanya menyipit. "Pantas saja mereka takut padamu."
Dia mengingat instruksi-instruksi yang diterimanya. Pak Aswan yang gelisah. Nadhira yang penuh dendam. Bahkan Pak Nohan yang berusaha "menyelamatkan" tapi tak pernah benar-benar mengembalikan anak itu ke keluarganya.
Kenapa seorang anak bisa membuat orang dewasa sebegitu takutnya?
***
Di layar, Arsya bergerak. Bocah itu bangun, menatap kosong ke arah kamera tanpa menyadari sedang diawasi. Wajahnya pucat, mata sayu—tanda-tanda malnutrisi yang mulai mengkhawatirkan.
Gesang merasakan sensasi familiar di dadanya. Seperti dulu, saat mengamati pasien anak yang terbaring lemah di meja operasi. Rasa berkuasa yang memabukkan. Kendali penuh atas hidup dan mati.
Arsya masih hidup sampai sekarang. Saat itu bukan aku yang salah.
Kalimat itu berulang di kepalanya, seperti mantra untuk menenangkan hati nurani yang sudah lama mati.
Tangannya meraih ponsel lain, mengetik pesan singkat: Nama target : _____ Kondisi : Keluhan muntah-muntah, sudha beberapa kali dalam satu hari. Penyebab : Faktor psikologis, (sementara) Giagnosa sementara : Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID),
Kenapa aku jadi mencatat keadaannya? batin Gesang. Bodoh!, kau berniat merawatnya?. Gesang meletakan kembali ponselnya. Pandangannya kembali ke layar.
"Ayo, bocah kecil..." bisiknya pada layar, suaranya seperti bisa menembus jarak. "Tunjukkan padaku seberapa tangguh dirimu. Biarkan aku lihat... mengapa mereka semua begitu takut pada anak sekecil kamu."
Jarinya menyentuh layar, tepat di wajah Arsya yang tak berdaya.
"Kita akan bermain lagi. Segera."
Layar laptop memancarkan cahaya biru dingin, menyinari ruangan kos yang sepi. Di kejauhan, suara hujan mulai turun—seolah alam ikut meratapi nasib seorang anak yang tak tahu bahwa ancaman terbesarnya sedang mengawasinya dari bayang-bayang.


 hanyaselingan
hanyaselingan