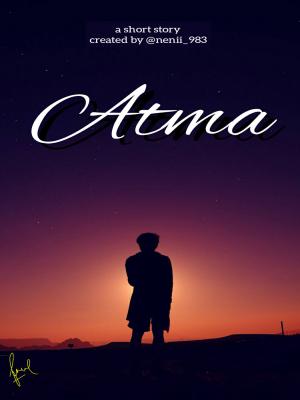“Lo mau latihan lagi? Nggak cape emangnya?”
Aku mengusap keringatku dengan jersey di sebelah April yang bersiap untuk pulang. “Cape, tapi gue mau coba jam tambahan pelatih.”
“Gue denger jam tambahannya gila banget. Lo yakin bakal kuat?”
Aku memang pernah mendengarnya dari senior lain, tetapi aku ingin mengevaluasi cara bermainku yang terasa kurang memuaskan. Aku juga ingin diakui bermain baik oleh pelatih yang selalu mengomeliku ini itu sejak bergabung pertama kali.
“Gue juga mau ikut karena Anbi selalu ikutan jam tambahan pelatih yang dadakan, tapi hari ini ada acara makan sama keluarga besar Ayah.”
“Ada lain kali, kok,” ucapku menabahkan April yang langsung kembali bergembira. Lantas, aku mengantar April hingga ke gerbang dan menyapa Ayah temanku yang menunggu di sana. Jadi, aku mengetahui darimana rambut bergelombang April berasal.
“Gue pulang duluan, ya, Faa.” April berpamitan dan aku melambaikan tangan dengan senyum di wajah.
Jam tambahan yang dikatakan pelatih bebas diikuti siapa saja, tetapi kenapa perempuannya hanya aku dan kak Hilda saja? Justru, lelakinya beranggotakan lengkap. Aku iri karena tim cowok memiliki banyak anggota dibandingkan perempuan yang beranggotakan sepuluh orang.
Aku meluruskan kaki di samping lapangan saat pelatih meminta kami beristirahat sebelum memulai jam tambahan. Langit merona jingga saat pukul lima sore dan aku memandangi awan yang bentuknya seperti lumba-lumba. Aku tertawa sendiri.
“Lo kenapa?”
Aku melirik ke sisi kiri. Cowok dengan jersey bernomor punggung tujuh itu menyodorkan minuman isotonik yang kuterima dengan senang hati. Setelah kukatakan bahwa awan di atas sana mirip lumba-lumba, Anbi Sakardja hanya membeo, “Hah?”
“Lupakan,” kataku enteng. Ternyata topik seperti ini tak dipahami setiap orang. Anbi mengingatkanku pada Hima yang juga berdalih, “Awan ya awan, bukan lumba-lumba.”
“Ngomong-ngomong trik lo nembak bola pas terakhir tuh keren. Tubuh lo ke belakang kayak mau jatuh tapi lo berhasil cetak three point. Ada tips? Ajarin gue dong.”
Aku cukup terkejut mendapatkan pujian. Meski begitu, aku tak memiliki trik khusus. “Mungkin kuncinya ada di lompatan. Harus menyesuaikan sama tinggi lawan juga posisi yang bagus. Posisi tangan saat pegang bola juga harus enak. Yang penting harus yakin bolanya masuk.”
Anbi menganggukkan kepala saat bersila di sebelahku. “Lo udah lama main basket? Kata Danu yang megang shooting guard, cetak poin kayak lo tadi butuh pengalaman. Berarti, lo terhitung orang jago, dong, If.”
Aku mengusap kepala yang tak gatal, tersanjung. “Tau kak Hanif ‘kan?” tanyaku sampai disetujui Anbi yang matanya tak berpaling dariku. “Kak Hanif udah lama pacaran sama kak Hima. Kebetulan waktu diajak main, ketemu sama temen-temen kak Hanif yang lagi main basket. Jadi, gue suka.”
“Temen bang Hanif?”
“Basket,” koreksiku. Kenapa pula kesalah pahaman itu berakhir pada teman-teman pacar kakakku? Anbi tertawa, mata cowok itu sampai memejam dan menurutku itu menggemaskan. “Lo suka basket?” tanyaku.
“Suka. Apalagi ada lo.”
Aku melotot dan menyikut lengannya. Anbi lagi-lagi tertawa tanpa dosa.
“Danu temen gue sejak kecil dan dia yang ajak gue main. Meski pas SMP gue bolong-bolong latihannya, tapi sekarang gue lebih rajin ketimbang dia yang kabur pacaran.”
Danu adalah orang yang pernah satu tim percobaan denganku saat pertama kali ikut perkumpulan. Mengingatkanku akan awal mula mengapa pelatih meragukan posisi shooting guard-ku karena hilang fokus oleh aroma Anbi. Hingga saat ini, aroma khas cendana seperti buku-buku lama perpustakaan selalu dihirup oleh indra penciumanku saat dekat dengan cowok berliontin ruby ini.
“Kamis besok habis band, lo mau ikut gue, nggak?”
Aku menenggak minuman. “Ke mana?”
“Aunty gue buka toko dessert depan Skyline School. Katanya gratis kalo gue bawa temen.”
Aku menengadah melihat langit yang awan seperti lumba-lumba tadi telah berubah bentuk. Dadaku berdesir mendengar seseorang mengakui bahwa aku adalah teman mereka. Sepertinya hubungan pertemananku dengan orang lain mengalami kemajuan. Kuharap ini berlangsung lama.
“Gue boleh ikut?” Aku memastikan, Anbi mengiyakan. “Nggak modus ‘kan?” Aku memastikan lagi, Anbi tertawa.
“Lo curigaan banget sama gue. Hati abang tersakiti.” Dramatis sekali seolah ada tombak yang menghantam dada Anbi. Cowok itu sampai mengusap bawah matanya seolah menangis. Aku hanya menyikutnya sebagai respons agar ia berhenti.
Hening menyelimuti kami, kulirik Anbi lewat ekor mata. Rambutnya terlihat lembut seperti milik April, matanya memandang depan dengan sorot mata lembut, bibir tipisnya terbuka saat minum hingga jakunnya naik turun setiap tegukan. Aku segera mengalihkan tatap dan meraba rambutku yang lepek.
“Kumpul semuanya.” Suara besar ketua basket putra menginterupsi. Kami mematuhi dan berkumpul di tengah lapangan saat sudut mataku melihat pelatih bersama dua orang yang membawa keranjang penuh oleh bola basket.
“Hilda, kamu sungguhan mau ikut turnamen? Junior kamu yang serius main basket tampaknya hanya Iffaa yang nggak bisa defense dengan benar?”
Kenapa aku pula yang kena omelan pelatih? Tampaknya diriku yang seperti serpihan kerikil di lapangan selalu salah di mata beliau. Aku tak mengerti. Kemudian, pelatih mulai menjelaskan metode latihan yang berbeda dari biasanya dan lebih intens. Pelatih menegur berulang kali soal kuda-kudaku yang tak kokoh, posisi lengan saat menembak, atau kepalaku yang sering menunduk, bahkan berteriak saat aku bergerak satu detik lebih lamban dari yang lain.
Kakiku pegal sekali, ingin segera duduk. Aku bahkan diolok pelatih karena tali sepatu lepas dan membuatku jatuh terjerembap. Pelatih bahkan menyuruhku melepaskan sepatu saja setelah dua kali terjatuh. Aku lelah fisik dan batin sekaligus.
Ini penyiksaan. Kami berlatih satu jam setengah tanpa jeda ataupun minum. Aku langsung terkapar setelah selesai dan yang lain pun melakukan hal serupa. Memandangi langit malam yang bintang pun enggan menunjukkan wujudnya. Napasku terengah, kepalaku terasa pusing, dan kakiku berat untuk digerakkan untuk meraih minum.
“Lo sekarat?” Candaan Anbi tak membuatku tertawa. Cowok itu terlihat baik-baik saja meski sama terengahnya. “Minum dulu.”
“Makasih,” ujarku menerima botol minuman tadi dan meneguknya hingga tandas. Rasanya masih kurang.
“Kalian berdua mau ikut makan bareng nggak? Di belakang sekolah ada tempat makan punya keluarga Hilda. Kalau mau kita jalan sekarang aja.”
Aku dan Anbi saling tatap dan segera menyetujui ajakan tersebut dengan anggukan kepala. Anbi telah berdiri, aku kesulitan karena kakiku lelah. Aku mengembuskan napas. Tak ada pilihan lain untuk meminta tolong.
“An, boleh pinjam tangan lo?”
Tentu saja, Anbi menyetujui dengan senyum lebarnya seraya mengulurkan tangan. “Digenggam juga boleh.”
Kalimat biasa ini kuucapkan, “Jangan modus.”


 azzmifaitsmiddielah
azzmifaitsmiddielah