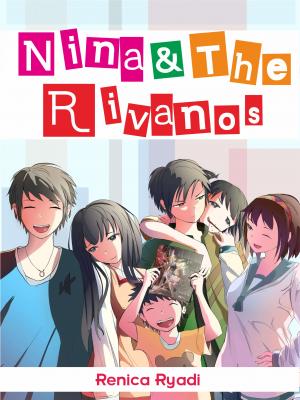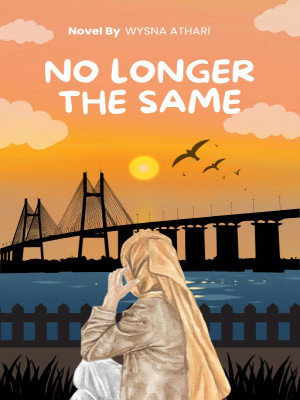Aku menekuni adonan kue di hadapanku sambil terus memastikan takaran yang kumasukkan sudah tepat. Terigu protein rendah, soda kue, keju parut, garam, dan gula. Setelah memberi lubang di tengah adonan yang sudah tercampur, giliran minyak goreng, susu cair, dan lima butir kuning telur yang sudah kusiapkan, masuk dalam adonan. Dengan cekatan tanganku mencampur semuanya sampai licin.
Aku spontan melirik ponsel di samping ketika alarmnya berbunyi, lima menit lagi ovenku siap menerima kehadiran adonan. Aku beralih mengocok putih telur dengan mixer hingga terlihat berbusa, lalu menambahkan beberapa kondimen penting lainnya sambil terus mengaduk hingga adonan membentuk ujung yang tumpul ketika mixer diangkat atau biasa disebut stiff peak. Bergegas aku mencampurkan adonan ini ke dalam adonan pertama secara bertahap dan mengaduknya perlahan menggunakan spatula sampai tercampur rata. Setelah memastikan adonanku jadi, aku mengambil loyang dan memercikinya dengan sedikit air agar adonan tidak lengket ketika sudah matang nanti. Aku juga harus memastikan oven unguku sudah siap memanggang chiffon dengan suhu 180 derajat dalam waktu setidaknya 70 menit atau sampai matang.
Aku memang baru dua tahun menjalani usaha rumahan ini, tapi beruntunglah orderan yang aku terima terus berdatangan, khususnya dari kalangan mahasiswa, kampus, dan juga arisan ibu-ibu kompleks. Untuk itulah aku harus selalu memastikan tidak ada kesalahan adonan, termasuk suhu oven dan waktu pemanggangan. Karena sedikit kesalahan saja bisa membuat hasil olahanku tidak maksimal dan mungkin mereka tidak akan memercayaiku lagi.
Sekali lagi kupastikan timer berada pada posisi yang tepat sebelum aku meninggalkan oven dan beralih merapikan meja serta segala peralatan memasak yang berantakan. Sambil mengangkat bowl, mixer, dan beberapa mangkok kecil ke dalam tempat cucian piring, tiba-tiba bel rumah berdenting diiringi ketukan pintu bernada khas. Kevin. Ya, pria itu selalu datang tiga kali sehari untuk mengambil jatah makan, dua kali dalam sehari untuk menanyakan kabar, serta mengingatkanku agar tidak lupa mengunci pintu. Sebenarnya tujuan dia hanya menghabiskan kuota telepon dan jatah kesabaranku, tentunya.
“Buka pintu, Vi!” teriaknya dari depan.
“Buka sendiri. Pintunya nggak dikun --”
Aku belum menyelesaikan kalimatku, Kevin sudah merangsek ke rumah dan menceramahiku karena tidak mengunci pintu. Spontan aku melempar serbet yang baru saja aku pakai untuk mengelap tangan saat menangkap tatapan penuh penghakiman darinya.
“Tadi pagi gue sudah keluar rumah, Kevin,” ketusku sambil melepas apron dan menggantungnya di sisi kulkas. “Gue baru buang sampah. Makanya pintu nggak dikunci.” Aku mencerocos sambil meraih cangkir di laci, kemudian menyeduh kopi untuk Kevin, sementara pria itu mendekati oven dan sesekali melirik ke dalamnya.
“Jangan dibuka dulu, ovennya! Nanti kempis.”
“Iya. Gue cuma ngintip. Chiffon lagi?”
“Iyalah, masih menu terlaris. Chiffon Sandwich.”
Kevin mengangguk-angguk. “Gue kebagian, kan, kali ini? Tiramisu ya, Vi?”
“Pede banget!”
“Harus pede, lah. Kalo nggak, mana mungkin gue di sini.”
“Ish … dari dulu. Kepedean plus emosian!”
“Gue bukannya emosi tanpa sebab, Vi. Kalo ada apa-apa sama lo gara-gara pintu nggak dikunci, siapa yang repot? Gue juga, kan?” balasnya tak kalah ketus sambil meraih cangkir dari tanganku dan meletakkannya di meja.
“Iya, deh, iya. Lo memang paling repot di dunia ini.”
“Karena Gue nggak rela lo kenapa-kenapa.”
Kevin paling jago melambungkanku ke langit penuh bintang sebelum detik berikutnya melemparkanku kembali ke dasar jurang terdalam bertemu para siluman.
“Nanti siapa yang nyediain kopi buat gue tiap pagi?” selorohnya santai sambil menyeruput kopi.
“Sialan!”
Seketika deretan gigi putihnya terpampang ketika ia tersenyum. Senyum yang selalu mengingatkanku akan awal pertemuan kami dua puluh tahun lalu. Senyum yang membuat semua orang tergerak hati peduli dan berbagi dengannya. Senyum yang membuat siapa pun jatuh hati kepadanya. Setidaknya kalimat yang terakhir aku salin tempel dari ucapan Viona, kembaranku, bukan muncul begitu saja dalam kepalaku.
Sontak aku mengerjap cepat dan bergegas mengintip ke dalam oven untuk mengetahui kondisi cake sebelum beralih melanjutkan adonan lainnya.
*
Aroma gurih butter dan daun pandan memenuhi ruangan ketika aku membuka oven. Untuk menghindari hasil yang keriput, aku segera mengangkat loyang dan membalikkan cake dengan menggantungnya di leher botol sirup sampai benar-benar dingin agar aman ketika dikeluarkan dari loyang.
Terburu-buru aku meraih ponsel yang dari tadi berdering, dan melihat nama Viona terpampang di layar. Saudari kembarku itu memang tidak pernah absen menelepon, untuk menanyakan kabar atau sekadar mengabsen kegiatanku. Katanya demi menjalin komunikasi yang intens antara siblings. Namun, kalau masih pagi namanya sudah berulang kali muncul di layar ponsel, pasti ada kabar yang sangat penting.
“Hai, Sib!” pekik Viona dari seberang. Wajahnya terlihat sangat ceria. Binar di matanya membuatku yakin bahwa kabar yang akan kudengar pagi ini berhubungan dengan calon tunangannya.
“Ada kabar apa, nih, tumben pagi-pagi nelepon?” tanyaku memastikan. Sambil meletakkan ponsel di stand holder, kedua tanganku cepat-cepat merapikan meja, lalu memilih duduk di dekat meja makan sambil menyesap cokelat panas karena bagian sofa dikuasai Kevin.
“Sib, orang tua Alden minta kami secepatnya menikah,” ucapnya sambil terlihat berbisik-bisik.
“Bagus, dong. Kalo memang lo udah siap, terima aja, Sib,” jawabku lantang.
“T-tapi lo ….”
“Gue? Kenapa gue?”
“Ya kalo gue married ntar lo gimana?
“Astaga, Sib. Lo yang mau married, ya pikirin kesiapan lo aja. Cukup. Ngapain mikirin gue. Kecuali lo maunya ada chiffon sandwich yang bakal lo bagi-bagi di hari pernikahan lo, nah gue siap.”
“Gue setuju!” teriakan Kevin mengejutkanku. Tiba-tiba saja dia sudah duduk di sebelahku dan ikut merespons Viona. Bukannya kaget, air muka Viona malah terlihat makin cerah.
“Tadinya gue kepikiran kalo married, lo bakal sendiri. Tapi ternyata gue lupa kalo ada Kevin. Gue sudah lebih tenang sekarang,” celetuk Viona santai yang diiringi acungan jempol Kevin.
“Apa-apaan, sih. Lo married mah married aja, Sib. Gue ada Kevin atau nggak ada Kevin, jangan jadikan acuan.”
“Jangan gitu, Sib. Gue serius. Lo sama Kevin itu bagai lodeh dan sambel teri.”
“Apaan?” tegurku.
“Gue yakin, sih, kalian berjodoh.”
“Betul, Na. Lo tenang aja.” Kevin semena-mena mendorong wajahku menjauh dari kamera. “Gue bakal jagain kembaran lo baik-baik, jauh lebih baik ketimbang usahanya me-resting chiffon cake biar nggak keriput.”
“Woi! Apaan sih, kalian!”
“Muka lo merah, Sib!” pekik Viona, padahal sudah pasti Viona tidak bisa melihat mukaku, karena seluruh layar hanya berisi muka Kevin. “Tapi beneran, lho, asalkan ada Kevin, lo pasti aman.” Viona mencerocos mengumbar kenangan masa lalu ketika kami bertiga masih kecil.
“Ah, udah, deh, Sib. Gue mau lanjut ngerjain orderan, keburu customer gue datang, nih,” putusku agar Viona tidak makin menjadi-jadi menggodaku dengan Kevin. Aku memutuskan menjauh dari ponsel dan membiarkan Kevin berkelakar lanjut dengan kembaranku itu.
Sambil mengayak terigu dan vanili, aku mendengar Viona berusaha menahanku.
“Eh, bentar, dong. Gue masih kangen.”
“Gue juga,” celetuk Kevin menanggapi Viona.
“Ya udah, sih, kalian berdua kangen-kangenan, gih,” celotehku.
Paling juga pembahasan mereka masih sama seperti yang biasa mereka lakukan sejak dulu. Mulai dari memuji-muji Kevin yang selalu benar dalam membedakan kami, padahal bagi kebanyakan orang, kembar identik seperti aku dan Viona sangat susah dibedakan. Setelah itu Viona akan mengungkit-ungkit kepekaan Kevin terhadap apa pun yang kualami dan kurasakan, lalu dilanjutkan dengan menjodoh-jodohkan kami. Memang, sih, Kevin baik, perhatian, dan tulus, tapi buatku itu wajar dilakukan karena kedekatan kami sejak kecil. Kevin juga tidak punya saudara kandung, jadi menurutku hubungan kami sudah seperti saudara, daripada teman.
“Lo sama Viola jelas beda bangetlah!” celetuk Kevin saat Viona lagi-lagi mengulang pertanyaan yang menurutnya masih misteri. “Sekali kenalan juga gue udah bisa bedain kalian. Di bawah kuping kiri Viola ada tahi lalat kecil, lo nggak ada. Bulu mata Viola lebih tebal, sudut bibirnya lebih naik, dan satu lagi. Tatapan lo itu aktif banget, Na. Sedetik aja kita berpapasan, gue udah ngerasa marathon tiga hari tiga malam, saking liarnya. Kalo Viola, kan, tatapannya jelas. Tajam, tapi kalem. Buktinya setiap kali Viola menatap, gue langsung meleleh.”
“Astaga!” hardikku sambil melempar serbet ke arah Kevin. Dengan tangkas ia menangkap, lalu melemparkannya lagi ke arahku.
“Apaan??!” pekik Viona hampir bersamaan dengan suaraku saat menghardik Kevin, sehingga dia mengulang kedua kalinya agar Kevin menanggapi. “Marathon apaan?!”
***


 gavetlou
gavetlou