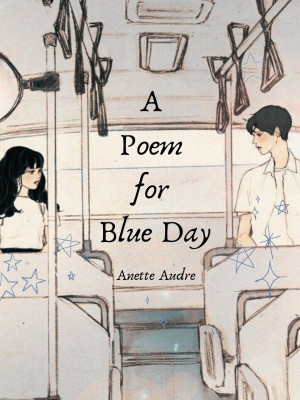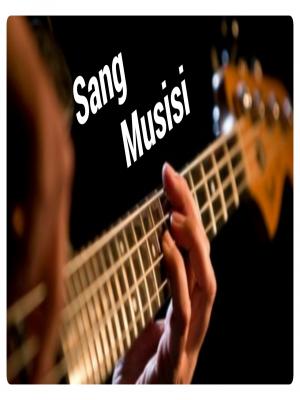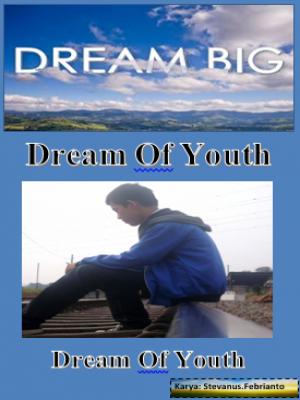Manusia adalah teka – teki hidup yang sesungguhnya. Wajah yang senantiasa memasang beragam ekspresi pun nyatanya tidak seterus terang itu. Lisan yang menyuarakan berbagai kalimat pun tidak selamanya mengucap kebenaran. Bahkan, bibir yang mengukir kurva pun tidak ada jaminan akan ketulusannya. Dari seluruh yang paling ditampakkan raga, hanya sepasang bola mata yang tak mampu berdusta.
Oleh karena itu, ketika sepasang atensi yang biasanya menyorot teduh berubah suram, sebuah cubitan terasa di dada. Bibir tanpa kurva dengan wajah tanpa ekspresi dan mata sayu, entah bagaimana membuat terhenyak. Ada tak nyaman dan rasa sakit di dalam relung dada yang tak bisa dijelaskan, akan tetapi terdapat suara yang berbisik lembut ke dalam rungu.
Dia tidak baik – baik saja, Rin.
Tak lama setelah membuka mata di pagi hari, berbagai pesan rupanya telah datang beruntun melalui aplikasi chatting. Secara garis besar, semua pesan tersebut mencari kabar mengenai surat dan proposal peminjaman tempat untuk kegiatan Majlis Rohis III.
Jangan bilang kalau tempatnya berubah lagi!
Begitu sarkasmeku, namun sayangnya langsung terbantah detik itu juga.
“Sebelum jam sebelas di posko, ya, Rin, aku mau pergi soalnya.”
Pesan Farzan yang meminta agar surat peminjaman siap running sebelum jam sebelas membuatku ber – istighfar berulang kali. Pasalnya, orang ini juga meminta untuk diantarkan hardcopy – nya ke tempat yang memerlukan waktu lebih dari sepuluh menit, padahal hanya tersisa tak lebih dari lima menit dari jam yang dia inginkan.
“Yang bener aja, Mas!”
Untunglah Narendra juga segera merespon pesanku yang memintanya agar datang ke posko untuk menandatangani surat peminjaman. Walaupun dengan tergesa, namun setidaknya aku berhasil mencapai posko lebih tiga menit dari yang dipinta Farzan. Sayangnya, ketika melihat bagaimana air muka Narendra yang juga baru saja tiba karena tadi aku melihatnya naik ke posko di lantai tiga gedung kegiatan mahasiswa, aku mengernyit bingung. Hal itu tentu saja karena melihat bagaimana raut tak enak terukir di wajah Narendra yang biasanya tampak setenang lautan.
“Bentar, ya, aku print dulu, Ren,” ucapku begitu jarak dengan Narendra tak lebih dari tiga langkah.
“Iya, Rin, nggak papa. Itu Mas Farzan juga kayanya masih ada syuro’ di dalem,” jelasnya.
Syuro’ apa?
Niat masuk ke posko untuk mencetak dokumen peminjaman tempat yang dibantu Airra dalam pembuatannya seolah terasa ada yang mengganjal. Kelopak mata berkedip berkali – kali memproses rasa tak percaya akan apa yang tertangkap oleh mata. Ruangan yang biasanya hanya berisi barang – barang administrasi dan inventaris rohis, seketika hampir penuh oleh beragam perlengkapan dan peralatan camping.
“Akhirnya datang! Di – print dulu aja, Rin, habis syuro’ aku tanda tangani, tapi nanti tolong kamu kasih capnya, ya,” ucap Farzan begitu tepat setelah aku mengucapkan salam ketika masuk ruangan.
“Ah … oke, Mas.”
Aku menoleh sebentar ke arah pintu ketika menyadari bahwa Narendra akhirnya turut masuk. Selama menunggu proses booting, diam – diam kuperhatikan Narendra yang duduk tanpa suara di pojok ruangan. Tidak ada ekspresi berarti dari wajahnya, namun entah mengapa aku merasa dia begitu lelah. Bahkan, tidak ada sepatah katapun terucap setelah sapaan basa – basi Arga. Padahal, biasanya tidak ada satupun kader yang bisa mengabaikan sapaan ataupun berbagai jenis ucapan Arga.
“Rin, suratnya udah?” tanya Aisya yang juga berada di dalam ruangan seraya mengemasi berbagai macam perlengkapan.
“Tinggal halaman terakhir aja, Mbak,” jawabku dengan nada sedikit menggantung di akhir kalimat sebelum melanjutkan dengan pertanyaan, “emang Mbak mau pergi juga, ya?”
Aisya mengangguk semangat, “iya, mau camping ke Jogja.”
“Udah hampir siang, lho, Mbak. Emang mau berangkat jam berapa?”
“Bentar lagi, itu nunggu Masmu syuro’ sama nunggu Devi.”
“Wah … berarti pulangnya hari apa, Mbak?” tanyaku seraya menyiapkan surat yang harus ditandatangani Farzan.
“Rencananya Rabu udah pulang, sih, Rin.”
Rabu pulang?
“Nah, Rabu, ikut sekalian, gimana, Ndra?” Arga tiba – tiba menimpali dan melempar pertanyaan pada Narendra yang sedari tadi menunduk sibuk dengan ponselnya.
“Wah, lagi nggak bisa, Mas.”
Tunggu, tunggu, tunggu!
Demi Allah, sungguh aku tidak salah dengar nama hari yang mereka berdua katakan, bukan?
Jikalau boleh aku bertanya dan mengatakan sesuatu secara frontal, rasanya ingin kulakukan sekarang juga. Pasalnya, pada hari tersebut sudah direncakan akan dilaksanakan sosialisasi perdana Majlis Rohis III. Jika orang – orang yang berada di dalam ruangan ini pergi, lantas siapa yang akan membersamai Narendra untuk sosialisasi?
Hei, mereka semua ini termasuk penanggung jawab kegiatan dan juga penanggung jawab sie!
“Rin, ini sekalian surat buat ke lapangan Harda Walika mana?” tanya Farzan setelah menerima surat yang sudah ditandatangani Narendra.
“Ha? Emang mau ke sana, Mas? Nggak bilang dari tadi,” sergahku.
“Yang buat suratnya siapa?”
“Airra, Mas.”
“Nah, ya, sekalian yang Harda sama waktunya tolong dilamain,” titahnya menyerahkan kembali surat itu padaku.
“Lho, terus yang survei ke sana siapa?”
“Buat dulu aja, aku tunggu sekalian, ini juga masih belum selesai syuro’,” pungkas Farza sebelum kembali fokus pada syuro’ daringnya.
Aku menghela napas pelan sambil tetap ber – istighfar dalam hati. Entah bagaimana, begitu campur aduk rasanya. Kepala yang mendadak pening pun seperti minta ditidurkan, akan tetapi sangat tidak mungkin untuk tidur di dalam ruangan ini sekarang. Dan benar pradugaku, bahwa Airra kesal karena penambahan satu jenis surat lagi.
Kala kepalaku tengah merekayasa dan memperkirakan siapa saja yang memungkinkan untuk running surat ke Harda, obrolan kemarin dengan Narendra melalui chatting tiba – tiba muncul dalam benak. Benar, seluruh anak humas bukan orang asli kota ini dan karena sekarang masa liburan, tentu saja pulang kampung adalah tindakan yang mereka ambil. Sehingga, posisi anak humas yang stand by hanya Dafa selaku penanggung jawab. Bahkan, dia yang sedari kemarin menyelesaikan alur proposal bersama Narendra. Jika sekarang Arga juga pergi, jadi Narendra bersama siapa?
Jangan bilang dia sendiri!
“Gimana, sih, jelas – jelas acara di depan mata tinggal satu setengah bulan lagi, tapi nggak ada yang bantu Narendra running?”
Pesan teks Airra seperti memiliki suara di kepalaku. Tentu saja, nada khas geram Airra tidak ketinggalan.
“Al, mau nanya,” suara Narendra menarik perhatianku, “buat peminjaman lapangannya sampai mana diskusinya?”
“Kemarin baru sampai info harus izin perangkat daerah juga, soalnya beda yang ngurus Harda sama lapangan.”
Tidak ada yang salah dari jawaban Ali, sungguh. Akan tetapi, bagaimana cara Ali menjawab membuatku sakit hati sejujurnya. Bagaimana bisa dia menjawab Narendra tanpa menatap lawan bicaranya dan justru atensi tetap pada ponsel di tangan? Bahkan, wajahnya cenderung tidak berekspresi.
Sopankah?
Kesal, aku ingin menangis!
Tepat ketika Airra mengirimkan surat lapangan, aku langsung berdiri. Menarik perhatian semua yang berada di ruangan dan aku sangat yakin bahwa ekspresi wajahku sekarang pasti tidak enak dipandang.
“Mau ke mana, Rin?” tanya Aisya.
“Print surat, Mbak. Pusing aku kalau penuh gini,” jawabku cepat seraya beranjak.
Secepat yang kubisa, pergi dari posko adalah pilihan terbaik. Surat yang dikirimkan oleh Airra pun langsung aku kirimkan ke admin tempat print agar aku tinggal mengambilnya dalam bentuk jadi. Pokoknya, yang ada di kepalaku sekarang adalah aku butuh tempat sendiri. Sungguh, rasanya aku sangat ingin marah sekarang.
Sekembalinya dari mencetak surat peminjaman lapangan, aku cukup terkejut mendapati Narendra berada di luar posko bersama Arga. Akan tetapi, keterkejutan itu tidak berlangsung lama karena sadar bahwa surat ini harus segera diselesaikan. Setelah Narendra membubuhkan tanda tangan, surat tersebut aku berikan pada Farzan yang masih di dalam posko.
“Eh … Ren, berarti ini mau survei lagi buat lapangan, ya?”
“Iya, Rin, paling besok. Kalau hari ini nggak bisa soalnya,” jawabnya.
Dengan hati – hati, Narendra kembali kutanya, “terus, kamu survei sama siapa?”
Jantungku berdebar lebih kencang secara tiba – tiba selama menunggu jawaban Narendra, padahal tidak lama namun entah mengapa terasa sebaliknya.
“Paling sendiri, Rin.”
Jawaban sekenanya Narendra membuat tersentak. Debaran kencang jantungku langsung melambat.
“Ha? Tapi, kan, bukan cuma kamu yang itu … maksudku,” bingung bagaimana harus merespon.
“Enggak, Rin. Besok inn syaa allah bisa sama Eden,” ujarnya mengulas senyum.
Tidak, senyum itu jelas sekali palsunya.
“Halah, tenang, Rin,” ucap Arga yang baru saja keluar, “acaranya aja masih satu setengah bulan lagi. Besok habis liburan juga bisa, santai.”
Jawaban macam apa yang baru saja Dafa katakan!
Tak perlu menunggu Farzan, aku langsung mengucapkan salam dan pergi. Tanpa menunggu salamku dijawab. Sungguh, sudah tidak tertahankan. Air mataku ingin keluar dan dadaku terasa begitu sesak.
Ruangan pojok tersembunyi di lantai tiga masjid kampus adalah tempat menyendiri terbaik. Benar saja, bahkan pada langkah pertama masuk ke masjid, air mataku sudah tidak dapat ditahan. Keberuntungan bagiku karena masa liburan, sehingga masjid sepi, sehingga begitu sampai di tempat yang terbayang dalam benak, air mataku jatuh semakin deras.
Sungguh, aku tidak paham mengapa rasanya begitu sakit melihat ekspresi Narendra. Bagaimana suaranya saat menjawab pertanyaan terakhirku pun sangat membekas dan layaknya hasil rekaman yang diputar berulang kali, terus terdengar di telinga. Kenapa dadaku begitu sakit mengetahui bahwa orang – orang membuat Narendra sendiri di persiapan awal ini?
Hasrat ingin berteriak dan marah naik sampai ubun – ubun, namun hanya air mata yang bisa keluar dengan mulut yang menangis tanpa suara. Rasanya sangat tidak rela jika sampai Narendra melakukan semua hal sendiri.
Mengapa? Demi Allah, dadaku begitu sakit dan kepalaku ingin pecah. Aku sungguh tidak mau jika Narendra melakukan semua sendiri. Bingung, bagaimana aku bisa membantu. Ikut survei tidak akan menyelesaikan masalah karena aturan yang begitu kuat di rohis. Mana mungkin hanya survei berdua, lawan jenis pula!
Bingung! Semua orang sudah pulang, aku harus bagaimana?
Ya Allah, aku tidak mau jika Narendra sampai sendiri. Tolong … aku ingin menemaninya. Mengapa aku mendadak cengeng seperti ini?
Kenapa kalian membiarkan ketuplak kalian sendiri? Kenapa?!


 rhea_adeya
rhea_adeya