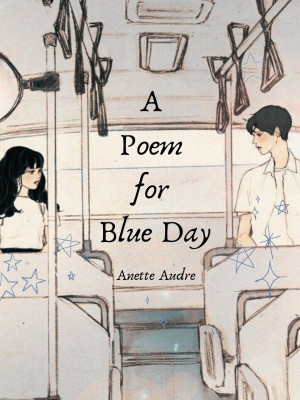Aku sudah mengabari Kazol, Arin, Erni dan Tutun jika aku tidak lagi kembali ke Banda. Erni paling sedih mendengar alasanku, katanya, suaminya sudah memberi rekomendasi dan mempromosikanku pada atasan dan dosen-dosen di kampus. Erni masih berharap aku berubah pikiran dan mempertimbangkan usahanya meyakinkan suaminya.
Tentu saja mengajar di kampus besar di Banda tidak bisa dilakukan sembarangan, orang yang diberi amanah mengajar sudah teruji kelayakannya. Berinteraksi dengan akademisi di kampus secara tidak langsung akan menanjakkan karirku.
Dengan mudah pula aku akan bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi ke luar negeri, mengerjakan berbagai macam proyek, menjadi pembicara di seminar-seminar besar, menulis karya ilmiah atau jurnal yang kemudian dipublikasikan di website kampus dan untuk naik pangkat, ilmuku juga tepat sasaran dan akan terus bertambah karena banyak orang yang tahu arah pemikiran saat diajak diskusi. Aku malah memilih jalan lain.
Erni menghembus nafas kecewa di ujung sana. Entah apa yang dilakukan Erni saat aku menghubunginya melalui smartphone nomor satu di dunia berlogo buah Apel ini.
Arin pun bersikap sama dengan Erni. Arin sangat berharap aku mau berada di antara mereka, memperjuangkan hak-hak perempuan. Arin sudah sangat antusias merancang proposal untuk kami bagikan ke donatur luar negeri.
Bekal gelar master dari perguruan tinggi luar negeri dan jaringan selama berada di Amerika cukup menguatkan posisiku di mata donatur yang tertarik dengan program yang sudah direncanakan. Aku tidak pula menerima tawaran Arin. Dari hela nafasnya, aku tahu Arin tidak senang dengan keputusanku.
Hanya Kazol dan Tutun yang tidak berkata banyak. Posisi mereka sudah sangat kuat sebagai pegawai negeri. Kazol dan Tutun tentu tidak bisa memberi solusi, saban waktu mereka bekerja melayani pemerintah.
Lingkungan mereka hanya itu-itu saja, tidak ada yang bisa mereka promosikan keberadaanku karena mereka tidak punya jaringan dalam hal pekerjaan. Kazol menganjurkan untuk memikir kembali tawaran Erni dan Arin. Tutun malah memintaku bertahan. Bekerja di kampung juga tidak ada salahnya.
“Kota Pesisir Barat besar lho, Nong! Aku pernah dua kali berkunjung ke kotamu. Di sana juga sudah ada kampus kan ya? Nggak ada salahnya mengabdi di kampung halaman sendiri. Mahasiswa di kampung sana butuh sekali orang pintar dan kreatif sepertimu. Karir bisa saja naik dengan cepat jika kamu berkarya nggak diam saja. Aku yakin kamu bisa. Bertahanlah sebentar di kampung ya!”
Tutun banyak benarnya. Tinggal aku saja yang mau atau tidak bertahan di di kampung sendiri. Ibu Kota Pesisir Barat memang bukan lagi kota kecil. Di antara semua kabupaten di wilayah Barat Selatan Aceh, hanya Ibu Kota Pesisir Barat yang terstruktur dengan rapi, bisa kukatakan kota metropolitan kecil.
Restoran cepat saji sudah berdiri di beberapa sudut kota, warung kopi dengan fasilitas internet gratis juga sudah ada, bangunan pertokoan berjejer tingkat dua, di depan kantor perwakilan daerah terdapat air mancur memancarkan gemercik air ke udara, beberapa kampus sudah berdiri dengan akreditasi dari pihak berwenang, masjid berkubah emas pun sudah berdiri dengan kokoh.
Semua kebutuhan kota besar hampir tercukupi di Pesisir Barat, perbaikan di sana-sini akan semakin mempercantik Ibu Kota kabupaten kelahiranku ini.
Saatnya kusimpan emosi dan senyum keempat temanku dalam kotak terkunci rapat di memoriku. Emosi Erni dan Arin yang tidak terima keputusanku, akan kujadikan cambuk agar kubisa buktikan bahwa di kampung aku juga bisa berkarya. Senyum Kazol dan Tutun akan jadi semangat disela-sela kesibukanku mencari kerja. Istirahat sejenak tak apalah, sebelum aku memulai sesuatu yang baru!
***
Di kampung, aku tidak mungkin berdiam diri di rumah terus. Pagi hari aku lari-lari kecil di jalanan berembun, olahraga sekalian menampakkan kepulanganku ke semua orang. Hamparan sawah mulai menguning menimbulkkan makna tersendiri pada alam milik-Nya.
Rasa syukur akan limpahan rezeki tidak akan berhenti sampai padi usai dipanen. Aku memang tinggal di kampung sejak kecil, keluargaku juga berkehidupan di kampung.
Keluargaku punya sawah beberapa petak di belakang rumah, aku tahu kami punya, namun aku tidak tahu berapa hektar karena akut tidak pernah ke sawah, tepatnya kami tidak pernah ke sawah, sejak aku ada sawah itu sudah digarap orang lain.
Kampungku bernama Kampung Pesisi, namanya pesisir tetapi letaknya sangat jauh dari lautan. Jarak yang harus kami tempuh untuk melihat ombak berderu sejauh delapan kilometer ke arah utara. Kampungku dikelilingi sungai dengan jembatan baru siap dibangun tiga tahun terakhir. Di sungai itulah dulu aku mencuci pakaian.
Bahkan sekarang pun masih berderet rakit bambu yang sudah hilang warna hijaunya. Masuk ke dalam kampung, rimbun pohon aneka rupa membuat kampungku teduh. Setengah kilometer ke depan, setelah melewati perumahan penduduk, termasuk rumahku, di sebelah kiri sawah milik warga selebar dua hektar sebelum kulihat anak-anak laki-laki dan laki-laki dewasa menendang bola di lapangan bergelombang sore hari.
Sebelah kanan sawah selebar puluhan hektar sebelum kampung tetangga menampakkan atap rumah mereka. Di belakang rumah sebelah kanan setelah jalan lurus, termasuk rumahku, masih terdapat sawah tiga hektar sebelum sungai melengkung ke kampung tetangga.
Kutarik nafas dalam-dalam menghirup udara pagi. Keringat sudah membasahi baju olahraga putih dengan celana hitam longgar warna hitam. Tak sampai sepuluh langkah ke depan kulihat seorang perempuan menggendong bayi, di depannya seorang anak perempuan berlari-lari kecil. Itukah Asma? Teman masa kecilku?
Dari kejauhan Asma sudah menyunggingkan senyum. Aku juga melakukan hal yang sama. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertamu Asma. Terakhir kudengar Asma sudah menikah lima tahun lalu dari Ibu saat berkunjung ke Banda. Setelah menikah Asma ikut suaminya yang bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit, aku juga tidak tahu alamatnya di mana.
“Asma…” kami saling jabat tangan. Anak perempuan yang kutaksir empat tahun lebih dan seorang bayi dalam gendongannya membelalakkan mata.
“Inong…” Asma tak kalah terkejut melihatku. “Makin kurus kamu, apa ada yang guna-guna di Amerika?”
Aku malah nyengir. Asma juga tahu aku kuliah ke Amerika. Semua orang tahu, seisi kampung ini. Ah, aku jadi bingung sendiri.
“Kamu? Sudah punya dua!” sahutku senang melihat buah cinta Asma dengan suaminya.
“Kamu kapan? Jangan lama-lama lho, umur jalan terus…,”
Entah. Baru sekarang aku sadar pentingnya omongan pernikahan. Melihat wajahnya yang berubah dratis Asma menghibur dengan humornya.
“Jangan bersedih, pasti ada laki-laki yang ingin menikahimu. Pendidikan sudah tinggi, sebentar lagi akan banyak laki-laki yang antre ke rumahmu!”
Aku malah ngakak mendengar ucapan Asma. Asma bisa benar, bisa juga salah. Jodoh bukan aku yang pegang. Perasaan campur aduk begitu bertemu Asma yang sudah beranak dua, hidup bahagia bersama suaminya ditandai dengan makin berisi tubuh Asma semenjak menikah. Tidak pantas rasanya aku mengajak Asma terlarut dalam perasaanku.
Asma menikah muda karena ekonomi keluarga tidak dapat memenuhi biaya pendidikan waktu itu. Seperti kebanyakan perempuan di Kampung Pesisir saat pendidikan tertunda bahkan terputus sama sekali, menikah adalah pilihan tepat.
“Asma, kamu memang sahabatku sejak dulu. Kamu mengerti bagaimana perasaanku, jodoh sudah ditentukan ada untukku walau entah kapan. Sekarang waktuku menunggu kapan waktu itu tiba, bukan?” ujarku sambil menghadirkan senyum penuh makna pada Asma dan pada pagi yang semakin meninggi.
“Iya, jangan pemilih juga. Kalau sudah bagus agama, kelakuan, keturunannya, jangan tunda-tunda menjawab setuju sebelum diambil orang lain!” Asma sudah sangat dewasa. Kehidupan yang keras sebagai istri dan ibu di usia muda membuat Asma banyak menyelami kehidupan yang tidak bisa ditafsirkan selalu memihak pada maunya.
“Rupa rupawan jangan kamu jadikan nomor satu, fisik bukan lagi segala saat kamu berumah tangga. Kamu akan bersama orang yang menikahimu sampai usia terhenti. Sebagai perempuan kita berhak memilih, asal jangan berlebihan, laki-laki itu akan menjadi milik kita, serumah, sekamar, bahkan sepiring bersama kita. Sebagai perempuan kita juga membutuhkan laki-laki sebagai pelindung jiwa lemah kita!”
Aku termangu mendengar nasehat Asma. Ketegaran hati Asma telah teruji selama berumah tangga. Anganku melayang ke peraduan laki-laki yang belum bisa kusentuh fisiknya. Mungkinkah aku bisa mendapatkan laki-laki sesuai kriteria yang dikategorikan Asma?
“Kamu bisa menilai, Nong! Dari gerak tubuh, bahasa maupun cara bersikap dengan orang lebih tua maupun lebih muda. Laki-laki akan menampakkan ego pada tempatnya, dan membuang ego pada tempatnya. Tidak semua laki-laki marah-marah, tidak semua laki-laki tenang dalam menyelesaikan masalah rumah tangga!”
“Suamimu seperti apa Asma?” potongku.
Asma jadi semakin bergairah mendapat pertanyaanku.
“Suamiku salah satu laki-laki paling istimewa yang kutemui, walau kami hidup berkecukupan, gaji sedikit, kerja keras pagi sampai sore, tetapi suami tidak pernah berkata kasar. Aku mengenalnya seperti aku kenal diriku sendiri!”
Asma sudah mendapatkan laki-laki yang memahami dan menghormatinya sebagai perempuan. Asma bahagia dari kata-katanya.
“Kita sama-sama kecil di kampung ini, Nong! Aku masih di sini-sini saja. Tidak pernah melihat dunia luar, tidak pernah bertemu dengan orang pintar, tidak pernah keluar negeri sepertimu, bahkan aku tidak pernah kuliah. Menangku hanya karena sudah menikah dan punya anak. Umur kita sama-sama 25, kamu sudah berhak mendapatkan pendamping di usia produktifmu. Jangan tunggu lama-lama, karir bisa kamu dapatkan setelah menikah nanti. Aku belajar banyak sebagai ibu, nanti kuajarimu bagaimana menjaga suami agar tidak jatuh ke pelukan orang lain!”
Aku mengerutkan kening.
“Kamu boleh belajar di perguruan tinggi, sedangkan aku hanya tamat SMA. Tapi soal rumah tangga aku sudah lebih dahulu mengerti. Kamu yang tahu mau suamimu, kamu yang tahu bagaimana mempercantik dirimu luar dan dalam. Dengan demikian, suamimu tidak akan berpaling, pulang ke rumah ada senyum, bukan wajah cemberut istri yang membuat suami ingin pergi lagi!”
“Bagaimana aku tahu bagaimana mau suamiku?”
Asma mencari kata-kata yang tepat sebelum menjawab pertanyaanku ini.
“Kamu akan kenal suamimu, kebiasaan suami akan kamu hafal di luar kepala, tidak usah kamu tanya suami akan memperlihatkan tabiatnya padamu. Dengan begitu, kamu bisa bertindak menyelesaikan masalah dalam keluargamu!”
Kata-kata Asma yang mengambang akan kucerna lain kali. Aku tidak sepenuhnya paham dengan ucapan Asma. Asma tahu apa yang diucapkannya karena sudah menjalani sebagai ibu dan sebagai istri.
Pertemuanku dengan Asma tidak kusadari membuat pikiranku menewarang ke mana-mana. Aku kembali berpikir rupa dan akhlak suamiku kelak. Menimbang-nimbang laki-laki yang akan serumah denganku tidak terdapat dalam teori ilmu yang kupelajari sampai ke Amerika.
Bagaimana jika suamiku egois? Bagaimana pula jika suamiku pendiam sekali? Bagaimana juga jika suamiku tidak sejalan dengan pemikiranku?
Pertanyan bodoh semestinya tidak terlintas dalam pikiranku. Pertanyaan demi pertanyaan mengurungkan niatku bersuami laki-laki. Tentu saja suamiku laki-laki, laki-laki yang menerimaku dan keluarga. Laki-laki yang menerimaku saja akan membuat keluargaku terpukul, lebih-lebih Ibu yang mewajibkan aku tinggal bersamanya.
Secara tidak tertulis, Ibu sudah mewariskan rumah untukku. Bang Mul yang sekarang tinggal menemani Ibu akan pindah ke rumahnya. Kak Sita tidak mengeluarkan kata-kata protes tinggal bersama Ibu, terlalu lama pun tidak baik untuk Kak Sita menghadapi Ibu selalu menang pendapatnya.
Sudah saatnya pula aku meringankan beban Bang Mul dan Kak Sita. Hidup bahagia mereka selalu ternoda dengan omelan Ibu yang tak pernah habis. Bang Mul tak pernah membantah, selalu mengerjakan kemauan Ibu walau dari tatapan mata Kak Sita begitu keberatan. Apalagi Bang Mul sudah membangun rumah di samping rumah kami.
Biar dekat asal tidak serumah bisa melegakan nafas Kak Sita yang sama-sama penurut seperti Bang Mul akan mau Ibu. Rumah yang tidak berpenghuni itu dirawat Kak Sita setiap hari. Kasihan juga kakak iparku membersihkan debu di rumahnya sedangkan dirinya tidak menetap di sana. Ibu menceritakan itu padaku, namun itu tidak mau melepas keluarga Bang Mul pindah ke rumah mereka.
Padahal Isra dan Asri tidak keberatan tinggal bersama Ibu, rumah mereka pun masih satu pagar dengan rumah Ibu. Ibu tetap pada pendiriannya. Tidak boleh dibantah. Dan Bang Mul tidak membantah.
Kepulanganku setidaknya membawa angin segar untuk Kak Sita yang lama terbelenggu dalam amarah. Kak Sita seperti memakan simalakama, salah kata tersinggung suami, salah suami menyinggung mertua. Sedekat apa pun aku dengan Kak Sita tidak mungkin kakak iparku tinggal bersama kami.
Aku menarik nafas dalam-dalam. Kak Sita seorang perempuan, lebih bisa menyimpan amarah menghadapi Ibu. Suamiku? Maksudnya laki-laki yang akan menjadi suamiku bagaimana berhadapan dengan tabiat Ibu?
***


 bairuindra
bairuindra