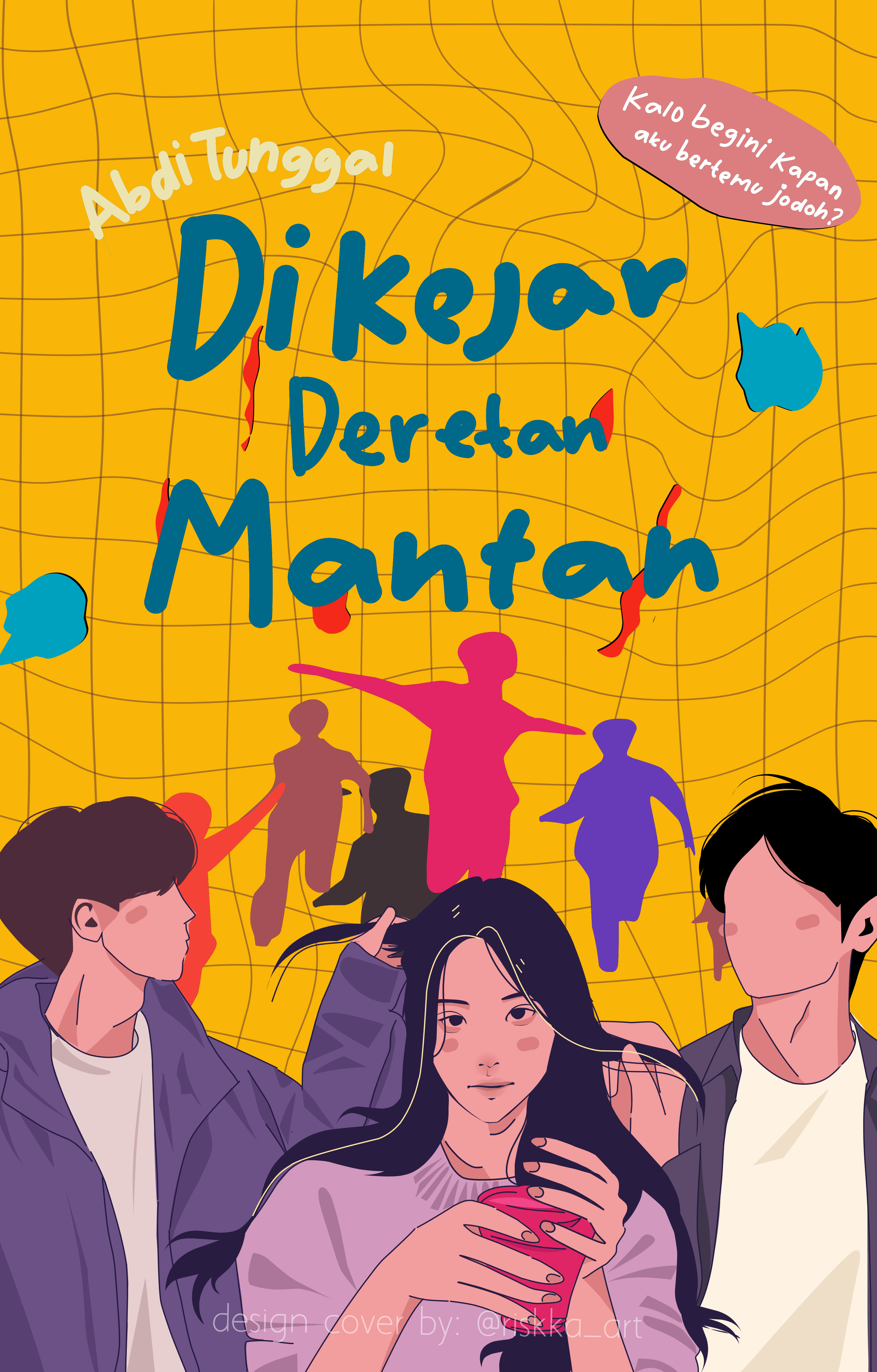Jarum di jam dinding bergerak pelan mendekati pukul tujuh malam. Aku mengenakan batik dengan corak khas Kuansing dipadu dengan celana bahan warna hitam. Aku sudah siap menghadiri acara Kiara malam ini. Tak lupa kurapikan rambut dengan sela-sela jari. Lalu aku sematkan tanjak berbahan kain tenun berwarna merah marun yang juga menjadi pelengkap di kepalaku.
“Wuiiih tampan sekali pengeran kita,” ucap Felix saat melihatku.
Aku tak menggubris Felix. Aku masih merapikan penampilan di depan kaca. Rencananya hari ini aku dan teman-teman akan menghadiri undangan makan malam dari Kiara di Delta Hotels by Marriott Bessborough. Sementara Felix masih dengan kaos dalamnya. Sudah beberapa kali kulihat ia gonta ganti pakaian. Tidak ada yang pas menurutnya. Menunggu Felix berdandan seperti seabad lamanya. Belum lagi cara dia merapikan rambutnya. Tak cukup hanya dengan sisir. Tapi juga pomade dan spray rambut untuk menunjang penampilannya.
“Ini acara pesta di hotel mewah. Masa kau memakai celana seperti orang sedang kebanjiran?” ucap Felix melihat celanaku yang ujungnya ada di atas mata kaki, “mau aku pinjamkan?”
“Tidak. Terima kasih,” jawabku, “aku pakai ini saja.”
“O iya. Aku lupa.”
“Lupa?” heranku.
“Dosa. Ya aku ingat. Dosa kan, Fyan?”
Aku tersenyum melihat wajah Felix. Mata sipitnya dipaksa melotot dengan mulut melingkar bulat sambil mengangguk.
“Hmmm … instal. Hmm … bukan … hmmm ….”
Dahi Felix berkerut. Dia seperti berusaha mengingat sebuah istilah dalam agamaku tentang pakaian yang menjulur hingga di bawah kedua mata kaki.
“Ya, istal, kan namanya kalau tidak salah, Fyan?”
Aku tersenyum melihat Felix yang berulang-ulang kali salah menyebutkannya.
“Isbal,” ucapku.
“Aaa … ya itu. Isbal. Kau pernah bilang padaku kalau seorang lelaki itu tidak boleh memakai celana atau pakaian yang menutupi hingga di bawah kedua mata kaki.”
Aku mengangguk. Ingatan Felix begitu cemerlang. Dia masih ingat kejadian hampir setahun lalu.
***
Sore itu, kami duduk di atas rumput hijau yang menghampar di bibir Sungai Saskatchewan. Udara segar yang berpadu indahnya bias matahari senja di permukaan sungai menemani perbincang ringanku bersama Felix dan Fritz. Sesekali diiringi gelak tawa. Hingga entah apa mulanya tiba-tiba Felix memprotes cara berpakaianku. Tidak cocok katanya.
Sepertinya, Felix kesal melihat dandananku yang selalu memakai celana di atas mata kaki. Aku hanya tersenyum. Wajar saja, Felix tidak tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan tentang hal ini. Tentang bagaimana seorang muslim berbusana. Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, umatnya, bahkan hingga kepada perkara-perkara kecil sekalipun. Sebagaimana ucapan Salman Al Farisi ketika menjawab orang-orang musyrik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam haditsnya.
Saat itu orang-orang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi: “Sesungguhnya Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, bahkan hingga adab buang air.” Mendengar perkataan orang-orang musyrik itu Salman Al-Farisi pun menjawabnya: “Benar. Sesungguhnya beliau telah melarang kami buang air besar atau buang air kecil sambil menghadap kiblat, atau kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Atau kami beristinja dengan batu kurang dari tiga. Atau kami beristinja dengan menggunakan kotoran atau tulang.”
“Setahuku haram jika disertai dengan kesombongan. Jika tidak disertai dengan rasa sombong, hanya sampai maka sebatas makruh saja,” ucap Fritz seolah membenarkan perbuatannya karena celana yang dipakainya menjulur bahkan kadang sampai terinjak dengan tumitnya.
“Apa dengan demikian lantas kita menjadi membiasakan diri melakukan hal yang makruh?” ucapku tidak setuju.
Aku tidak mau berdebat panjang lebar. Sebab para ulama pun berselisih pendapat tentang hal ini. Siapalah aku ini? Aku hanya orang awam yang berusaha menjalankan ibadah semampu yang aku bisa.
***
“Bagaimana menurutmu jika ternyata Kiara menikah dengan orang lain?”
Pertanyaan Felix mendadak menghentikan tanganku yang sedang merapikan tanjak di kepala. Aku menoleh ke arahnya. Kulihat, ia tersenyum.
“Apa urusannya denganku?”
“Yakin, kau tak akan kecewa?” tanya Felix, “Bukankah kau juga suka dengannya?”
Aku hanya tersenyum sambil merapikan kembali bajuku di depan kaca.
“Atau jangan-jangan hari ini sebenarnya hari istimewa?” tebak Felix “Hari lamaran kalian berdua.”
Kulihat Felix sudah siap. Setelah menunggu sekitar lima belas menit berganti pakaian dan merapikan rambut akhirnya ia menyelesaiakan juga penampilannya.
“Ngaco kau. Ayo, cepatlah Fel. Fritz pasti marah besar menunggu kita.”
“Ah ... bukannya sudah biasa kita melihat dia marah-marah?”
“Felix ... Felix ... jangan begitulah. Bagaimana kalau kau diposisi Fritz, harus menunggu?”
“Iya … iya … Aku sudah siap,” ucap Felix.
Handphone-ku berbunyi sebelum Felix menyudahi ucapannya. Fritz meneleponku. Katanya ia dan teman-teman yang lainnya sudah menunggu di loby. Aku berkaca lagi sambil memastikan penampilanku sudah rapi.
“Kau sudah siap kan?” tanyaku ke Felix.
Felix mengangguk. Lalu, aku bergegas keluar apartemen diiringi Felix dari belakang.
“Kunci apartemennya ada di kamu kan, Fel?”
“Yup. Kalau pun itu benar, rasanya keren sekali Fyan. Ada seorang lelaki dilamar seorang wanita di sebuah tempat mewah nan romantis. Wuiih bisa jadi kisah cinta paling hits nih di abad kekinian,” ucap Felix sambil mengunci apartemen.
“Sudah … sudah … jangan berkhayal terlalu jauh. Hari ini itu cuma undangan pesta kelulusan Kiara.”
“I know … I know … tapi kalau ucapanku tiba-tiba terbukti, bagaimana?”
“Sudah … jangan berandai-andai.”
Segera kami menuju lift. Beberapa kali Fritz meneleponku, tapi sengaja tak kuangkat. Aku yakin dia akan marah karena sudah menungguku lama. Tak berapa lama, masuk pesan WhatsApp dari Fritz. Kubuka pesannya. Semua huruf kapital pertanda marah terketik di sana.
“WHERE ARE YOU MR. BRIDEGROOM?”
“Apa-apaan ini?” batinku “Mr. Bridegroom?”
Mereka mengira hari ini adalah hari istimewaku dengan Kiara. Padahal aku sendiri tak tahu apa-apa. Yang aku tahu hari ini adalah acara pesta kelulusan Kiara. Hanya itu. Tapi mereka menuduhku telah menutup-nutupinya. Bahkan saat tadi tahu aku hanya memakai batik dipadu dengan celana bahan warna hitam, Felix mengira bahwa setelan jasku sudah disiapkan keluarga Kiara.
“Jasmu?”
“Jas apa? Memangnya dress code-nya harus pakai jas?”
“O … aku tahu, pasti sudah disiapkan keluarganya Kiara kan?”
“Jas apa sih? Nggak ngerti ah.”
Isu tentang hari ini memang sudah kudengar beberapa hari ini. Entah, siapa yang memulainya.
***
Pintu lift terbuka. Handphone-ku berdering berkali-kali. Kulihat, Fritz yang menelepon. Tak kuangkat. Kami langsung menuju Loby. Dari kejauhan kulihat Fritz duduk di sofa dengan gelisah. Kami melangkah mendekat. Fritz beranjak dari duduknya sesaat setelah melihat kami berjalan ke arahnya. Wajahnya menyiratkan kekesalan. Kedua matanya disipitkan. Kedua alisnya seolah saling terkait. Seperti ada gemuruh di dada yang ingin dikeluarkan.
“Gila … aku mesti menunggu kalian? Kalian pasang bulu mata dulu atau pakai pensil alis sih? Jam berapa nih?” Fritz emosi sambil menunjuk jam tangannya.
“Ya ampun, cuma telat lima menit Fritz,” ucap Felix.
“Cuma lima menit katamu?” suara Fritz meninggi.
“Semakin kau marah-marah, semakin lama kita di sini,” ucapku mencoba menyudahi kemarahan Fritz, “itu artinya kita makin telat datang ke pesta Kiara.”
Fritz tak menggubris. Ia berjalan lurus menuju parkiran. Sepertinya ia masih membawa kekesalannya. Sementara, kami membuntutinya dari belakang.
“Sorry banget Fritz … nggak ada maksud bikin kamu nunggu lama,” tambahku lagi.
“Pasti gara-gara Felix,” tukas Fritz sambil terus melaju.
“Loh kok jadi nyalahin aku?” protes Felix.
“Siapa lagi kalau bukan kamu,” kesal Fritz.
Kami tiba diparkiran, lalu segera masuk ke mobil Fritz. Tepatnya mobil pamannya Fritz. Kebetulan urusan bisnis pamannya di Ottawa diperpanjang. Jadi, mobilnya masih terparkir di apartemen kami. Zahra, Eva dan Olivia sudah berangkat lebih dulu bersama Kiara dan orang tuanya ke tempat yang akan kami tuju.
Aku duduk di sebelah Fritz yang duduk di balik kemudi. Aku memakai seat belt. Sementara, Fritz menyalakan mobilnya. Segera kami meninggalkan halaman apartemen. Dalam sekejap, mobil melucur dengan kecepatan sedang menuju Delta Hotels by Marriott Bessborough.
“Pakai seat belt-mu.” Felix yang duduk di kursi belakang mencoba mengingatkan Fritz.
“Sebentar lagi kalian pasti akan merindukan saat-saat seperti ini,” ucapku.
“Apa? Aku merindukan Felix? NO WAY.”
Fritz langsung mengenakan seat belt. Tampak jelas kekesalan di wajah Fritz. Aku hanya tersenyum melihat Fritz yang kesal pada Felix. Mereka memang selalu demikian. Mudah tersulut. Kadang akur layaknya seorang kawan. Kadang seperti musuh bebuyutan. Anehnya Fritz tidak pernah berani bersuara tinggi kepadaku. Meski aku yang salah. Seperti yang saat ini terjadi. Aku ketiduran. Namun, tetap Felilx yang kena salah. Ada-ada saja alasan yang dibuat-buat Fritz untuk meluapkan amarahnya pada Felix. Walaupun begitu, aku tahu benar sahabatku itu, Fritz hanya marah di bibir saja. Hatinya tetap baik. Berkali-kali aku selalu mendamaikan mereka. Namun, tetap saja kelakuan mereka bagaikan Tom dan Jerry.
Terlebih ketika kami membahas isu-isu terkait keyakinan kami. Jika aku tidak menengahi keduanya, tentu bisa terjadi baku hantam. Bukan hal yang langka melihat perseteruan antara Fritz dan Felix. Bahkan beberapa kali aku mendapati mereka perang dingin hingga berhari-hari setelah membahas suatu tema yang begitu sensitif tentang sebuah doktrin agama.
“Katanya Tuhanmu itu tunggal, Fyan?” tanya Felix tempo hari.
“Memang benar, memangnya kenapa?”
“Tapi saat aku membaca terjemahan Al-Qur’an, beberapa kali aku menemukan penggunaan kata ‘kami’ ketika Tuhanmu menyebutkan dirinya. Bukankah itu berarti Tuhan dalam islam itu ada banyak?”
***


 hadismevlana
hadismevlana