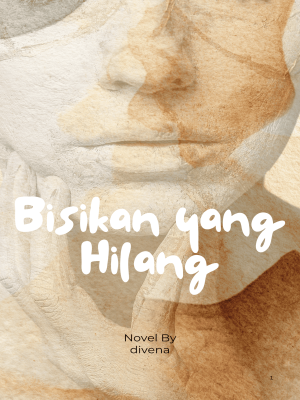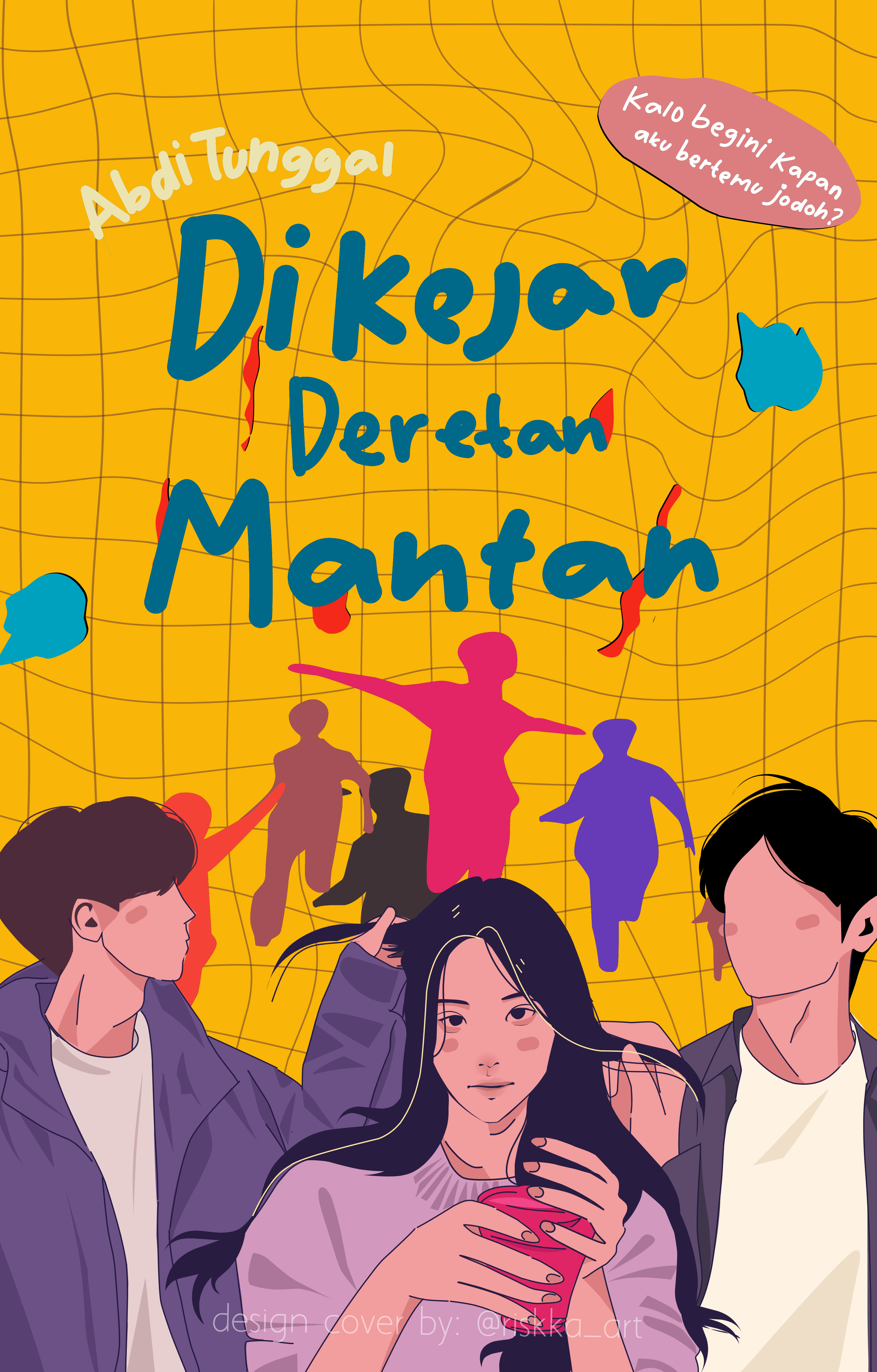Ketika kata sudah tak mampu lagi menggambarkan semua luka
Mungkin sedikit tawa adalah salah satu cara memanipulasinya
***
“Besok kamu nggak boleh berkeliaran kemana-mana. Teman Papa sama anaknya akan ke sini. Ingat, bersikap yang anggun, jangan seperti preman pasar yang nggak punya etika.”
Tangan Caca refleks terhenti, satu sendok nasi goreng yang siap masuk ke dalam mulutnya terpaksa ia kembalikan ke atas piring. Suasana sarapan yang memang dari tadi hening kini semakin sunyi, Bian menatap adik perempuannya itu sejenak, kemudian beralih menatap ke arah papanya.
“Untuk apa, Pa?”
Caca tetap diam, dia yang memang sudah tahu tujuan sang papa tidak akan menghabiskan oksigennya hanya sekedar bertanya untuk apa.
“Adikmu mau Papa jodohin.”
Nampak Bian cukup terkejut, namun kembali menormalkan ekspresinya. Matanya kembali beralih menatap Caca yang masih sibuk menatap nasi goreng di depannya. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh adik perempuannya itu. Tapi Bian tahu dari raut muka yang dia lihat, Caca tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh papa mereka.
“Pa, tapi Caca, kan, masih terlalu kecil. Bian….“
“Caca nggak setuju!” Suara Caca yang terdengar dingin, memotong ucapan Bian.
“Papa, tidak menerima penolakan dari siapa pun!”
Bola mata Caca terasa mulai memanas, terus saja seperti ini setiap papanya mengambil keputusan, laki-laki itu tak pernah mau memikirkan bagaimana perasaannya. Tidak, dia tidak boleh menangis. Mengeluarkan air mata sama dengan menunjukkan kalau sebenarnya dia adalah perempuan cengeng dan hal itu yang tidak pernah diinginkan Caca. Dia tidak mau melihat orang iba terhadapnya.
“Bisa, nggak, Pa. Untuk soal jodoh biar Caca yang tentuin sendiri!”
“Tentuin sendiri, kamu bilang! Tentuin bagaimana masa depan kamu saja, kamu nggak becus! Bagaimana mau nentuin siapa yang terbaik buat kamu!”
Caca memejamkan mata geram, kali ini Papanya semakin keterlaluan. Sebegitu nggak bergunanyakah seorang Caca di mata Ashraf Malik?
“Pa, sudah. Kasihan Caca.” Mawa hanya bisa mencoba meredam emosi suaminya, dia bahkan sama sekali tidak berani hanya sekedar membujuk laki-laki itu untuk bersikap lebih lembut kepada putrinya.
Bian menatap prihatin, jika dia ada di posisi Caca, mungkin dia sudah pergi jauh dari keluarga ini. Bukan, tapi lebih tepatnya pergi untuk menjauh dari papa mereka. Tapi dia bisa apa, dia sendiri tidak mampu untuk menentang kehendak seorang Ashraf Malik.
Caca sudah tidak tahan, semarah apa pun dia, dia tak boleh terlalu berlebihan untuk berkata kasar kepada orang tuanya. Dari pada terus-terusan membatin, Caca bangkit dan melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Anggap saja Caca pengecut, setiap ada masalah dia lebih memilih pergi dari pada terus-terusan mendengar cacian dari laki-laki yang bergelar papanya itu. Kini dia semakin yakin bahwa pilihan yang akan dia ambil sangat tepat.
“Sayang, mau ke mana? Sarapan kamu belum habis!”
Caca tak peduli, nafsu makannya telah menguap sejak tadi. Kalau seperti ini buat apa dia dilahirkan? Kenapa tidak dibuang sekalian ketika dia baru lahir ke dunia. Andai waktu bisa diputar, dan andai dia bisa memilih, lebih baik dia memilih menjadi anak orang miskin akan tetapi kaya kasih sayang dari orang tuanya terutama dari papanya, dari pada seperti ini, berada dalam keluarga yang serba ada namun miskin akan kasih sayang.
Entah firasatnya saja atau bagaimana, tetapi dia merasa papanya lebih memprioritaskan Bian dari pada dirinya. Bukan hanya diprioritaskan, selama ini lelaki itu memang tak pernah memarahi Bian, apalagi untuk mencaci-maki seperti yang telah dilakukan kepada dirinya.
“Biarkan anak itu pergi, biar dia bisa memakai otaknya untuk berpikir.”
Hulu hati Caca rasanya perih, seperti ditikam belati tajam. Kenapa harus sesakit ini setiap dia mendengar ucapan dari papanya yang tak pernah sekalipun memuji dirinya.
Bian marah? Tentu saja. Tapi apa yang bisa dia perbuat, diam adalah pilihan terbaik untuk saat ini.
“Pa, Ma. Bian berangkat.” Bian segera bangkit menyalami kedua orang tuanya. Semoga Caca belum terlalu jauh, Bian tahu adiknya itu pasti tidak memiliki uang jajan, gara-gara pergi tanpa pamitan, kendaraan pribadi juga dia tidak punya, karena papa melarangnya bahkan tidak membelikan adiknya itu sebuah kendaraan, dengan alasan bahwa anak gadis tidak baik menaiki kendaraan sendiri. Jadi, bagaimana bisa dia naik kendaraan umum untuk pergi kuliah.
Bian bernapas lega, ketika menemukan Caca masih di depan gerbang rumah mereka. Dengan muka ditekuk Caca duduk selonjoran di tepi jalan. Suara klakson terdengar, membuat Caca mendongakkan kepala lalu tersenyum lebar ketika melihat Bian-sang kakak yang berada di dalam mobil. Caca segera bangkit kemudian masuk ke dalam mobil.
Bian tidak habis pikir, terbuat dari apa hati adiknya yang satu ini, padahal belum sepuluh menit yang lalu dia mendengar ucapan pedas dari papa mereka, tapi lihatlah sekarang, dia sama sekali tak terlihat sedih. Bahkan sekarang wajahnya kini tengah memberikan senyum lebar kepada Bian.
“Kakak kira, kamu udah sampai kampus.” Bian mulai angkat bicara ketika mobil yang dia kendarai mulai berjalan.
“Iya kali, gue jalan kaki!”
“Kali aja, kamu ngesot.”
Caca tidak menggubris, ia bergerak-gerak tidak nyaman sembari memperbaiki sabuk pengaman.
“Kak, minta Duit.” Caca menatap Bian dengan tampang memelas. Bian pura-pura tidak mendengar, kali ini alasan apa yang akan dilontarkan oleh Caca untuk merayunya, walau sebenarnya tanpa Caca memberi alasan dia akan tetap memberinya uang. Bibir Caca mengerucut, dia mengubah posisi duduknya menghadap Bian.
“Kak Bian yang baik, dan paling ganteng. Hari ini adik lo yang manis ini lagi banyak tugas yang harus diprint dan dicopy. Jadi, butuh duit banyak.”
“So, urusannya sama Kak Bian apa?”
“Karungin Kakak, dosa nggak, sih?”
Bian terkekeh melihat wajah adiknya yang kini semakin kusut.
“Jangan cemberut, muka kamu makin nggak enak dilihat, kusut gitu.”
“Iiiih, Kak Bian!”
Bian mengaduh kesakitan disela tawanya. Menjahili Caca adalah kenikmatan yang tiada tara.
“Udah, udah! Hahaha. Ambil di dompet Kakak sana.”
Caca berhenti memukul, kini wajahnya nampak girang. Tanpa menunggu lama dia segera mengambil dompet Bian yang berada di jok mobil.
“Kak Bian emang the Best! Makasih!” Caca memeluk erat Bian.
“Eh! Jangan peluk-peluk. Lagi nyetir, nih!” peringat Bian.
Caca segera melepas pelukannya sembari nyengir kuda. Dasar Caca, Moodnya benar-benar luar biasa, bisa-bisanya ada anak manusia seperti dia, perasaan tadi di rumah dingin minta ampun, terus ngerengek-rengek tidak jelas dan sekarang sorot matanya penuh kegirangan seperti ini hanya gara-gara melihat uang.
“Kamu, baik-baik saja?” Bian melirik sejenak ke arah samping, dia masih mendapati Caca yang kegirangan menarik beberapa lembar uang seratusan dari dalam dompetnya.
“Menurut Lo? Gue gila gitu?!”
“Kali aja, kewarasan kamu hilang, gara-gara lihat uang!”
“Sembarangan kalau ngomong!”
Bian lagi-lagi terkekeh, sebenarnya bukan itu tujuan dia bertanya, tapi tak apa, saat ini dia tidak ingin menganggu mood adiknya. Dia benar-benar bingung kenapa sikap papa jauh berbeda pada Caca dan dirinya.


 fiasintiya
fiasintiya