Percayalah. Hal yang paling menyebalkan dalam hidup adalah, ada yang mengganggu tidurmu di hari libur. Siapa juga sih, siang-siang bolong begini telepon? Padahal baru saja aku memejamkan mata. Aku benar-benar lelah. Lahir batin lelah. Butuh istirahat.
Bukannya apa-apa. Sabtu kemarin, seharian aku habiskan untuk menguntit Rafa. Dari jam enam pagi aku sudah stand by di depan rumahnya. Berdiam diri di dalam mobil yang sengaja aku sewa dari rental?untuk mengelabuhi Rafa. Ya kalau aku pakai mobilku sendiri atau mobil Mama-Papa, itu namanya bukan menguntit. Tapi terang-terangan.
Kalian tahu? Dari jam enam pagi aku mengamati rumah Rafa, Rafa baru keluar pukul satu siang. Aku mengikutinya. Dari toko kue lanjut ke laundry, dan balik lagi ke rumahnya saat pukul tiga sore. Setelah itu Rafa nggak keluar rumah lagi. Dan akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan rumahnya pada jam sembilan malam.
Gila. Seharian penuh nggak dapat hasil apa-apa. Nggak ada orang yang datang ke rumah Rafa sama sekali. Nggak ada pertemuan Rafa dengan orang yang mencurigakan. Nggak tahu juga sih kalau dia berhubungannya lewat telepon. Apa aku harus menyadap teleponnya? Apa perlu aku menyewa detektif sekalian saja? Ahh, masa sampai segitunya sih.
Mana nggak mandi seharian lagi. Harus rela makan di mobil. Kalian tahu apa yang kumakan? Dari pagi sampai malam yang kumakan adalah roti kemasan dan air mineral yang kubeli saat perjalanan menuju rumah Rafa.
Dan sekarang, disaat aku ingin mengistirahatkan tubuh dan pikiranku, ada saja yang mengganggu. Pagi tadi Bima yang telepon minta tolong bukunya yang ketinggalan di rumah, di kirim ke Bandung. Agak siangan Mama yang teriak-teriak memintaku pergi ke rumah Tante Meike untuk nganter kue bikinannya. Yang akhirnya aku tolak dan Mama nyuruh Bik Yati.
Dengan malas aku bangkit dari tidurku karena teriakan suara Janelle Monáe yang menyanyikan Tightrope. (Iya, lagu lama. Jangan protes!). Aku menyahut smartphone-ku yang tergeletak di nakas samping tempat tidur. Aku melirik sekilas layarnya yang berkedip. Muncul nama Lyana disitu.
“HALOOOO!?” Aku menyapa dengan berteriak. Bisa kutebak, di tempatnya sana Lyana langsung menjauhkan smartphone dari telinga. Karena tercipta jeda yang agak panjang sebelum Lyana menjawab.
“Nggak usah pakek teriak gue juga denger kali, Ra.” Lyana balas menjawab dengan teriakan juga. Kini ganti aku yang menjauhkan smartphone dari telinga. Kemudian balik mengomeli Lyana.
“Lo lupa ya, Yan, kalo hari ini tuh hari Minggu?”
“Enggak! Gue inget banget malah. Dan gue minta lo sekarang buat dateng ke Classico cafe.” Lyana menyebutkan nama sebuah café di daerah Kemang. Café yang biasa kami datangi.
“Aduh, Yan. Ini tuh jam makan siang, lho. Jalanan pasti macet.” Aku mencoba cari alasan. Membayangkan siang bolong begini harus bermacet ria di jalan.
“Halooo? Tara? Hari ini tuh Minggu, ya, seperti yang lo bilang tadi. Nggak akan ada yang namanya macet. Nggak sampek setengah jam lo juga bisa nyampek sini.”
“Lo kayak nggak tahu Jakarta aja sih, Yan. Lagi ada penggalian gorong-gorong lah. Kecelakaan lalu lintas lah?”
“Daripada lo ngoceh terus, mendingan buruan siap-siap dan langsung ke sini. Ada hal penting yang mau gue tunjukin ke elo. Ini soal hidup mati lo.” Potong Lyana kemudian memutus sambungan telepon begitu saja.
Sialan. Mau nunjukin apa sih, sampai bawa-bawa hidup dan matiku segala? Dasar Lyana sableng.
Dan seperti apapun malasnya aku siang ini untuk beranjak dari kasur empukku dan kamarku yang adem ini, akhirnya aku menuruti juga permintaan Lyana.
Dan disinilah aku sekarang. Berjalan santai memasuki Classico café yang disebutkan Lyana tadi. Suara empuk Norah Jones langsung menyambut begitu aku masuk café. Membuat suasana terasa adem disiang hari yang panas ini.
Aku berdiri di depan pintu. Melepas kacamata warna coklatku yang segede piring kemudian memasukkannya ke tas selempangku. Aku mengedarkan pandangan ke penjuru café. Penuh banget.
Yang aku suka dari café ini adalah suasananya yang nyaman. Adem. Banyak ornamen-ornamen khas Italia. Temboknya terbuat dari batako merah. Seperti namanya. Klasik dan terkesan elegan.
Tapi ini Lyana dimana? Dari tadi mengedarkan pandangan ke penjuru café kok bentuk-bentuknya si Lyana nggak kelihatam juga.
Aku mengernyitkan dahi saat mendengar suara desisan. Sampai akhirnya kurasakan sebuah tangan menarik tubuhku kebelakang. Aku berontak.
“Sssst! Ini gue.”
Aku mendengar suara Lyana tepat di belakang telingaku. Sampai aku bisa merasakan napasnya menyentuh kulit tengkukku. Membuatku merinding. Aku menoleh ke belakang untuk menatap Lyana. Dan seketika itu muncul wajahnya tepat di depan mukaku. Aku dan Lyana saling menjauh. Agak risih juga.
“Apaan sih lo?” Bentakku.
“Jangan teriak-teriak.” Lyana menarikku untuk bersembunyi di belakang rak buku tinggi yang terletak di dekat pintu masuk. Aku melihat Dika berjalan mengendap menghampiri kami. Tahu nggak, sebelumnya dia itu ngumpet di samping meja kasir. Ini ada apa sih?
“Jadi lo nyuruh gue ke sini cuma buat diajakin main petak umpet doang?”
“Ck…” Lyana berdecak kesal. “Kasih tau, Dik.” Lyana menatap Dika. Aku mengikuti arah tatapannya.
“Gue punya surprise buat lo. Tapi lo jangan histeris atau gimana, ya?” Kata Dika sambil menarik sebuah buku tebal dari tempatnya. Sehingga menghasilkan celah yang lebarnya sekitar lima senti. “Lihat tuh.” Dika menunjuk celah yang dibuatnya tadi.
Aku mengikuti permintaaanya dengan dahi mengerut. Belum ngeh juga dengan maksud Dika. Ternyata maksud Dika, celah itu untuk mengintip ke dalam café.
“Yaelaa. Nggak usah pakek bikin beginian, kalii. Langsung masuk juga kelihatan semua.” Protesku.
“Berisik lo. Turutin aja kenapa, sih. Lihat baik-baik!” Lyana berkata sambil mendorong kepalaku menuju celah itu. Aku menurut saja.
Seketika itu juga aku mendapati sepasang anak bermuka SMP yang sepertinya lagi pacaran. “Dua anak SMP yang lagi suap-suapan french fries itu?” Aku menoleh untuk menatap Dika dan Lyana.
“Lihat yang bener kenapa, sih?” Lyana kembali mendorong kepalaku menuju celah. Aku kembali mengikutinya tanpa banyak protes.
“Deket tembok sebelah kiri. Pas di bawah lukisan Monalisa.” Dika memberiku instruksi. Aku mengikutinya. Dan?
“ASTAGAA.” Aku berseru tertahan.
Tepat dibawah lukisan Monalisa yang aku yakin itu adalah lukisan palsu karena yang asli pasti berada di Museum Louvre?Ralin lagi ngobrol seru dengan tiga pagar ayu-nya sambil ketawa-ketiwi centil. Yang masing-masing dari mereka membawa cowok. Dan Ralin sendiri? Ini yang membuatku benar-benar surprised. Arda duduk disamping Ralin. ARDA.
Aku merasakan ada desiran halus yang terasa perih didadaku. Aku menoleh untuk menatap Lyana dan Dika. Mengungkapkan apa yang terbersit di kepalaku saat ini. “Apa ini artinya mereka tersangka?”
“Gue sih curiganya begitu.” Jawab Dika.
“Gue sih masih tetep nggak percaya Arda sekejam itu.” Lyana MASIH saja membela Arda.
“Yan, ini bukti di depan mata, lho.” Aku mendebat Lyana. Nggak habis pikir dengan jalan pikiran Lyana. Lyana hanya mengangkat bahunya. Aku kembali mengalihkan tatapanku ke celah tadi.
“Apaan tuh si balon gas? Mana pakek senderin kepala di bahu Arda lagi. Si Arda juga. Diem aja gitu?” Aku mengomel sendiri. Nggak tahu kenapa, kesal banget melihat adegan itu. Aku menoleh ke belakang lagi saat mendengar cekikikan Lyana dan Dika.
“Ada yang lucu?”
“Tara, Tara. Kalo jealous itu ngomong aja, kali.” Dika berkata sambil geleng-geleng kepala. Menyebalkan!
“Siapa juga yang jealous.” Aku kembali ke celah tadi. “Gue cuma?”
“Astagfirullohal’adzim.” Aku berseru tertahan. Aku. Nggak. Percaya. Dengan. Apa. Yang. Kulihat. Barusan. Aku menegakkan punggung seketika. Menatap Lyana dengan pandangan nanar.
“Kenapa, Ra?” Lyana menatapku khawatir. Lalu menggeser tubuhku yang mendadak terasa kaku. Kemudian mengintip melalui celah.
“ASTAGA.” Aku mendengar Lyana berseru histeris.
“Apaan sih, kalian? Minggir coba.” Ganti Dika yang menggeser tubuh Lyana.
“Ngeliat mereka makan doang kalian sampai sehisteris itu?” Dika berbalik. Menatapku dan Lyana bergantian. Aku dan Lyana saling tatap.
Dadaku berdegup kencang. Bisa kurasakan mataku memanas. Perlahan pipiku mulai basah karena air mata. Tanpa berkata lagi aku berbalik dan berjalan meninggalkan Lyana dan Dika.
----
“Gara-gara gue lo harus lihat itu ya, Ra? Gue minta maaf.” Lyana memandangku dengan tatapan bersalah.
“Bukan salah lo juga kali, Yan.” Aku menjawab tanpa menatap Lyana. Sibuk mengaduk-aduk kopi hitamku yang sama sekali belum kuminum. Yeah. Aku butuh kopi hitam untuk meringanku sakit kepalaku saat ini. “Justru gue malah berterima kasih banget sama lo karena udah tunjukin ke gue.” Lanjutku kemudian.
“Bentar deh. Kalian tuh lagi ngomongin apa sih dari tadi? Gue nggak ngerti deh.” Dika menatapku dan Lyana bergantian. Meminta penjelasan.
Lyana menatapku. Seperti minta persetujuan harus atau tidak memberitahu Dika tentang apa yang kulihat dengannya tadi, yang terjadi antara Arda dan Ralin. Ugh, aku benci harus mengingat dua orang itu.
Karena melihatku diam saja, akhirnya Lyana menjelaskan pada Dika. “Tadi gue lihat Arda dan Ralin?” Lyana menggantung kalimatnya. Menggeser duduknya untuk lebih dekat dengan Dika kemudian berbisik. “?ciuman.”
“HAH!? Serius?” Dika menatap Lyana dengan nggak percaya. Kemudian beralih menatapku.
“Jangan menatap gue seolah-olah gue seorang pesakitan kayak gitu.” Aku berkata dengan nada tajam. Sudah berapa kali sih, aku bilang. Kalau aku nggak suka dipandang dengan tatapan mengasihani seperti itu. Aku nggak semenyedihkan itu.
“Terus, sekarang apa yang mau lo lakuin?” Lyana bertanya dengan serius.
“Gantung diri.” Jawabku asal yang langsung membuat mata Lyana dan Dika melotot bersamaan. “Ya enggaklah! Gue nggak segila itu kali. Bunuh diri cuma gara-gara patah hati.” Ralatku kemudian. Aku melihat Lyana dan Dika menghembuskan napas lega.
“Gue nggak tau harus ngapain.” Kataku akhirnya.
Ya, aku akui. Aku tidak rela melihat Arda dekat dengan Ralin. Aku cemburu. Tapi apa sih yang bisa aku lakukan kalau faktanya memang begitu? Arda dekat dengan Ralin. Semua juga bisa melihat.
Dan yang paling menyakitkan adalah, mereka bekerjasama untuk menjatuhkanku. Orang yang aku rasa aku sayang, bekerjasama dengan orang yang paling aku benci, untuk memfitnahku. Apa tidak cukup dengan mereka bersama saja? Kenapa harus lebih menyakitiku dengan fitnah itu juga.
“Gue cabut duluan. Kepala gue pusing.” Kataku kemudian menyahut tas selempang yang kuletakkan di kursi kosong sebelahku. Lalu berdiri dan meninggalkan Dika dan Lyana.
----


 annis0222
annis0222


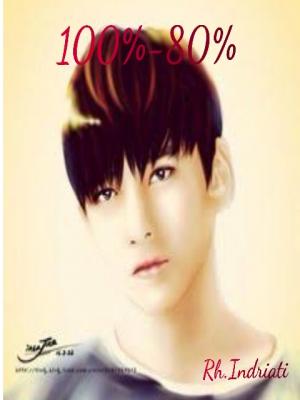

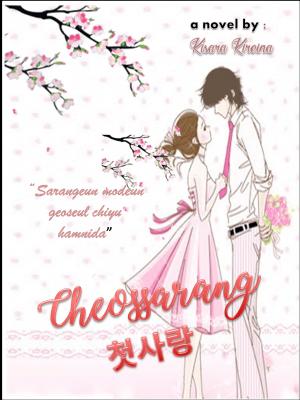



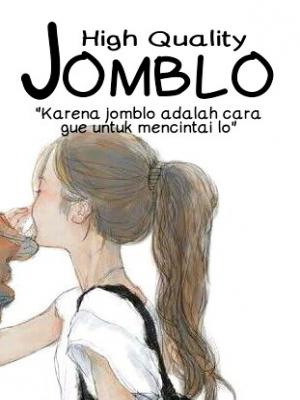

Thank you, kakak.... Cerita kakak lebih keren. Jadi minder... ????
Comment on chapter SATU