Meskipun Ola telah mengusulkan untuk menuda rapat sore ini sampai beberapa hari ke depan, Mora dengan tegas menolaknya. Dia tidak ingin permasalahan keluarganya menjadi penghambat. Ini masalah pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan Amore Karaoke. Dan setelah mengantarkan Mami pulang, di sinilah dia berada mendengar ide Ambar untuk mengganti wallpaper dinding dua dari empat room termasuk ruang tunggu ini. Hanya ada empat room di sini, itulah mengapa gedung Amore Karaoke sangat berbanding jauh dengan tempat karaoke keluarga di ujung jalan sana. Mereka menyetujui dengan anggukan kepala, tapi tidak dengan Mora yang sorot matanya entah ke mana.
“Mendingan lo pulang.” Ucap Devon lirih. Cowok itu sudah berdiri di samping Mora yang duduk di sofa biru. “Nggak akan ada yang berubah ko lo ada di sini atau nggak.”
“Tunggu gue mengisi energi ya. Baru kita mulai perang lagi.” Balas Mora jengkel.
Mora sedikit menggelengkan kepala mengusir bayangan Papi yang berdiri di balik jeruji saat dia mengunjunginya tadi. Papi tampak segar berkat makanan yang dibawa Mami. Beliau terus mencetuskan maaf dan bersikeras bahwa itu bukanlah pembunuhan tapi tindak pembelaan dari bosnya yang hendak memukulnya. Saat itu Papi adu mulut dengan bosnya yang tidak menggajinya seperti yang tertera dalam kontrak, padahal kebutuhan di rumah termasuk uang sekolah Mora dan Mona tidak akan tertutupi oleh gaji itu. Bos Papi sempat pula menghajarnya lalu Papi melawan, tapi energi Papi yang terlampau kuat menyebabkan bosnya terhempas ke guci besar di sudut ruangan. Dia panik hingga sidik jarinya tertinggal di guci besar dan jejak sepatunya tercetak di genangan darah. Terhimpit dengan keadaan ekonomi, Papi mengambil kunci mobil bosnya dan menjualnya ke tempat illegal.
“Lo jangan dulu ngurusin ini. Mendingan temenin nyokap lo sampai proses di pengadilan selesai.”
Mora mendongak, menyelidik Devon yang mengetahui masalah itu.
“Kan lo sendiri yang bilang tentang bokap lo. Ingat? Pas di café itu.” Ucap Devon langsung mengetahui arti muka menyelidik.
“Gue mampu.”
Dua kata yang disampaikan Mora dengan raut meremehkan itu bagai air panas yang menyiram sekujur tubuh Devon. Dua kata yang menyindir telak Devon. Dua kata yang menegaskan bahwa Mora terbiasa hidup di lingkungan berduri dan dia bisa melewatinya tanpa harus berdarah-darah karena sesungguhnya darahnya sendiri telah tersedot habis. Hanya tulang belulangnya yang bertahan dan kian bertambah kuat. Sedangkan Devon, dua kata itu tak pernah mengisi sel-sel tubuhnya. Dia tak mampu hidup tanpa Nanzo. Dia tak mampu menapaki bumi tanpa Nanzo. Yang mampu dia lakukan menyalahkan permainan bodoh cewek itu. Yang mampu dia lakukan hanyalah—
Cukup…
Sekarang dia sedang mengaplikasikan dua kata itu melalui Amore Karaoke ini.
“Justru lo yang harusnya pulang. Wajah lo nggak bisa bohong kalau lo nggak mampu berdiri di sini.”
Telapak tangannya mengepal di atas sandaran sofa empuk itu, tertanam di sana hingga pasti menimbulkan bekas yang dalam. “Ini belum selesai. Ingat tantangan gue. Siapa yang paling bertahan di sini. Lo atau gue. Malahan sepertinya besok pun lo akan mati karena beban lo semakin bertambah.”
Mora menelan ludah kuat-kuat. Kepalan tangannya terbentuk di balik genggaman tangan kirinya. Dia memfokuskan kembali penglihatan dan pendengarannya pada Revi yang mengusulkan akan membantu Ambar. Celotehan Revi setidaknya sedikit mencairkan ketegangan tubuhnya.
***
“Salah satu dari kalian nggak ada yang bisa temenin gue di sini?” Mora memasang raut memohon. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dengan Devon bila tidak ingin Amore Karaoke tahu-tahu ludes dalam sehari karena perang mulut mereka. Dia melirik Devon yang sedang tekun menghadap layar komputer di meja pendaftaran.
“Gue ada kelas satu jam lagi.” Jawab Cecil. “Ini juga gue kepepet banget karena harus ke sini dulu. Kenapa nggak kirim desain ruangannya lewat WA atau email aja sih. Sekarang tinggal pake jari aja, Non!”
“Tapi tadi komentar lo lebih banyak pas lihat langsung dari pada pas di chat.” Mora membela diri. “Lo nggak bisa, La? Gue ikut lo ke bank deh.”
Buku tabungan yang baru diterimanya hari ini dari Devon digerak-gerakkan ke samping, menolak tegas usulan Mora. “Gue mau ke klub dulu baru ke bank. Lo mau nungguin gue ngelatih anak kecil lari? Lebih baik lo gunakan waktu sebaik-baiknya di sini sambil benerin desain ruangan itu.”
“Gue kan anak tekpang bukan anak desain, kenapa harus gue terus kalau masalah ngedit desain.”
“Cuman lo yang ahli gituan di antara kita. Tiga cowok itu aja malah nggak ngerti.” Ambar bermaksud memberi semangat, tapi maksud baiknya tidak mampu memberi suntikan semangat.
“Gue peringatkan lo, Bar. Kalau Revi buat lo nangis, gue nggak mau bantu.” Tandas Mora
Ambar menggeleng kesal. “Ini bukan soal Revi. Lagian sekarang cowok itu nggak tahu ke mana. Masalahnya gue mau ke tokonya Salsa. Ingat Salsa? Yang bikin akun Instagram haters khusus lo.”
Tentu Mora sangat mengingat Salsa. Adik kelasnya yang rupanya bagian dari fans berat Winayasa Band, khususnya yang menggilai Nanzo sang gitaris. Hasil dari serangan akun instagram itu berdampak pada Mora yang enggan lagi berselancar di time line instagram, dan berujung dia menghapus akun instagramnya yang dipenuhi komentar mengerikan.
“Cukup lo berhadapan dulu dengan Devon. Jangan ditambah dengan Salsa.” Imbuh Ambar.
Cecil melirik sesaat ke Devon sebelum membisikkan sesuatu ke telinga Mora. “Kalau dia macam- macam. Kayaknya dihajar sekali langsung kolaps deh.”
“Lo kan pernah ikut karate waktu SMP.”Ola mengimbuhi dengan ikut-ikutan berbisik.
“Wuss..jangan pakai kekerasan. Udah abaikan aja dia. Kalau memang nggak bisa diam, sumpel mulutnya pake Mic!” Nasehat Ambar tidak jauh berbeda hanya beda versi.
Setelah memberikan petuah tak berguna itu, mereka bertiga bergegas menghilang dari pandangan Mora. Tidak memberi Mora kesempatan ketiga kalinya untuk memohon. Dengan tampang riang serta lambaian tangan yang dibarengi acungan kepala tangan meninju udara mereka menghilang di ujung perempatan sana.
“Taki, lo masih di mana?” Semprotan Devon cukup mengagetkan Mora yang berjalan gontai memasuki ruang tunggu.
“Masih di tukang service.” Jawab Taki dan tanpa memberi kesempatan melanjutkan jawabannya, Devon langsung bertindak memutuskan sambungan.
Tak tahan mengunci diri dan bosan menatap kursor dari mouse yang digerakkan sembarang, Devon berdiri lalu mendekati Mora yang bernasib sama seperti dirinya. Devon berdeham. Mora langsung mengalihkan layar yang sebelumnya berderet foto-foto saat di Pesta Rakyat.
“Gue pengen lihat.” Pinta Devon.
Mora termangu. Belum menangkap permintaan cowok itu. Dia mendongakkan kepala, mengernyitkan kening. Folder foto yang baru yang dilihatnya di klik kembali dua kali lalu menampilkan deretan foto yang diambil dari kamera ponsel Taki.
“Desain.” Lanjut Devon kesal. “Lo harusnya tahu, gue mana mungkin tertarik sama foto-foto itu. Lagian di foto-foto itu nggak ada gue—”
“Ya..Ya..Ya..Silahkan nih lihat.” Sela Mora nyaris mencapai oktaf tertinggi. Didorongnya laptop menghadap Devon lalu dia menggeser pantatnya karena cowok itu membungkukkan badannya demi melihat desain room nomor 1.
Akhir-akhir ini yang menjadi korban paling nyata yaitu pita suaranya yang sudah usang. Mora mengelus-ngelus tenggorokannya sambil komat-kamit mengantarkan doa agar selalu diberi kesehatan beberapan bulan atau mungkin beberapa tahun ke depan. Entah sampai kapan nasib bersinggungan dengan cowok ini berlangsung. Entah sampai kapan juga urat mereka tidak saling mengeras setiap bersinggungan.
“Ya..lumayan bagus.”
Sabar Mora.” Batinnya. Jelas sekali cowok itu menyembunyikan kekagumannya. Gengsinya memang sudah akut!
“Lo coba susun menu harian kita. Temen lo yang mau beli wallpaper itu nggak tahu kapan baliknya.”
“Temen gue punya nama.”
Devon berdecak. Dia tak ingin meributkan hal tak penting. “Ya itulah namanya.”
“Lo harus tahu nama orang-orang yang membantu lo.” Mora berusaha menahan pita suaranya tidak menjerit untuk kesekian kalinya. Dia meniupkan napas. Sudah cukup. Persoalan ini tidak boleh memicu peperangan di siang hari yang terik ini. “Lo mendingan kembali ke sana. Pengap dekat-dekat sama lo.” Mohon Mora menahan geraman kesal di balik giginya.
Devon melipat kedua tangannya di dada. Kakinya bergerak berlawanan dengan permintaan Mora. “Harusnya lo yang—”
“Amore Karaoke buka lagi?” Suara cempreng seorang perempuan paruh bayah memotong hasrat Devon yang hendak menyerang Mora. Perempuan itu berbalut rok coklat panjang, dipadukan dengan cardigan berwarna senada yang menutupi kemeja krem di baliknya. Yang membuatnya mencolok yaitu syal berbulu berwarna merah marun melingkari lehernya. Dia melongokkan kepala lalu wedges merahnya berdentuman di ruang tunggu.
“Kalian pemilik baru tempat ini?” Tanyanya tanpa memandang Devon dan Mora yang mengernyit heran karena tanpa permisi perempuan berambut sanggul itu melenggang masuk. Mata perempuan itu menilik setiap sudut ruang tunggu hingga membalikkan badan dan menilik empat kursi besi yang sandarannya berbentuk setengah lingkaran. “Kursinya lucu.” Nada suaranya tak seindah pujiannya, tapi nyaris seperti mencaci.
“Kapan bukanya?” Kelakuannya semakin menyebalkan. Kini dia melenggok hendak memasuki salah satu lorong yang mengarah ke room 1 dan room 2.. Di lorong itu terdapat tangga yang mengarah ke lantai 2, akses menujus room 4 sekaligus gudang yang direncakana menjadi kantor mereka.
“Maaf, ini bukan sesi room tour.” Devon menghadap langkah perempuan itu. Langkah tegasnya membuat perempuan itu mundur hingga menabrak salah satu kursi besi. Alis perempaun itu terangkat sebelah. Mata yang dinaungi bulu mata palsu itu mendelik kesal. Tak kapok, dia melewati meja pendaftaran, menuju lorong lain di sebelah kanan--jalan menuju room 3-- yang langsung dihadang oleh tampang kesal Mora.
“Ada apa ya, Tante?” Tanya Mora. Dia sungguh muak hari ini harus meladeni dua orang menyebalkan.
“Saya hanya ingin melihat-lihat saja.” Balasnya sewot.
“Saya izinkan kalau Tante tidak main masuk seperti tadi.” Devon menyandar ke dinding yang membentuk meja pendaftaran. Dagunya terangkat mengimbangi dagu perempuan itu yang kian menaik ketika berbicara. “Ada apa? Mau nyanyi di sini? Silahkan. Tapi hari ini kami belum buka.”
Si Tante tertawa. Bibir berpoles lipstik ungu tua itu ternganga sangat lebar. Telunjuknya yang dilingkari cincin besar—yang Devon yakini lebih berat dari batu akik—mengusap pelan kelopak matanya yang basah karena saking kuatnya tertawa.
“Saya lebih baik nyanyi di kamar mandi dari pada di sini.” Perempuan itu membalikkan badan sebelum menerima murka yang terpampang dari dua pasang mata itu. Langkahnya terhambat ketika matanya menangkap sesuatu yang menarik dari meja kotak di depan sofa. “Kalian yang harusnya nyanyi di tempat karaoke saya.” Lanjutnya memunggungi Devon dan Mora.
Derap langkah wedgesnya mendekati pintu masuk. Dia berbalik setengah tubuh sebelum benar-benar keluar. “Tempat ini belum layak disebut tempat karaoke kalau tidak bisa melebihi tempat karaoke di ujung jalan sana.”
“Siapa sih tuh? Nenek lampir dari gunung mana?”
Mora bergegas menuju ambang pintu untuk memastikan dugaannya. “Dia pemilik karaoke keluarga di ujung jalan sana.”
Kepala Devon ikut melongok di atas kepala Mora. Terlihat perempuan itu berbelok memasuki gedung besar mewah itu. “Pesaing bisnis.”
“Sekarang musuh besar lo bukan gue lagi.” Ucap Mora serius.
“Hah?”
“Dia. Nenek lampir itu musuh terbesar lo. Dan tentu musuh gue juga. Lo menerima ucapannya tadi?”
Devon mendengus kesal. “Nggak. Tapi musuh gue nambah, jadi ada dua.” Balasnya lalu berlalu ke dalam.
***


 mlounita
mlounita


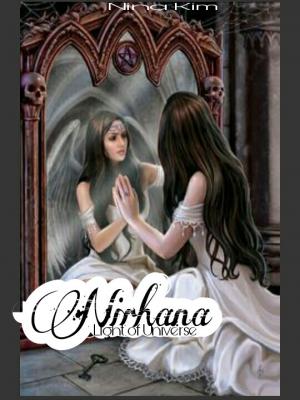


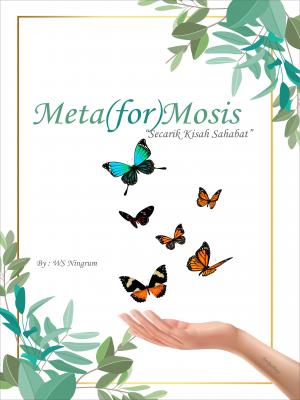




fresh banget ceritanya hehe. ditunggu kelanjutannya ya :)
Comment on chapter Chapter 1