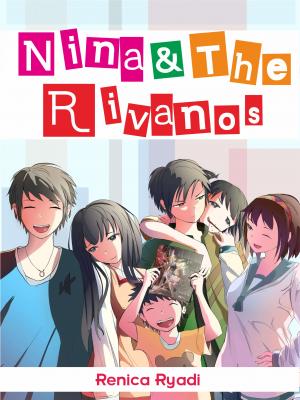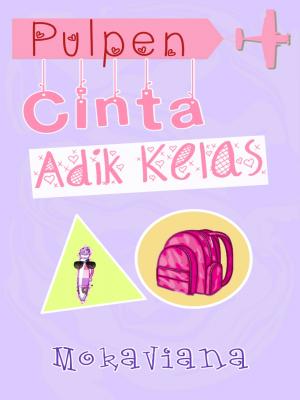Bagi Agni, jika kiamat datang dan satu-satunya cara untuk selamat adalah tinggal seatap dengan Bude Ratmi, maka ia akan memilih menghadapi kiamat dengan kepala tegak. Setidaknya, kiamat tidak akan menyiksa jiwa dan mentalnya seperti menghirup udara di bawah atap yang sama dengan perempuan itu.
Kata “menyebalkan” bahkan terasa terlalu lemah untuk menggambarkan kehadiran Bude Ratmi di rumah. Sejak datang, perempuan itu langsung menyuruh Agni membuatkan minuman dingin, menyuruh keluar membeli ayam bakar kesukaannya, memintanya memasak air panas untuk mandi, dan kini—
“Lagi bikin apaan, Ni?” tanya Bude Ratmi dengan nada sok akrab, muncul tiba-tiba hadapannya saat Agni sedang mencetak adonan macaron di atas loyang.
“Macaron, Bude,” jawab Agni singkat, berusaha tetap fokus pada adonan yang ia cetak dengan hati-hati dan presisi.
“Oh, yang kayak biskuit warna-warni itu ya?”
Agni hanya mengangguk, tidak ingin meladeni lebih jauh.
Tapi ketika ia hampir menyelesaikan satu tray penuh, tanpa peringatan, jari telunjuk Bude Ratmi menyambar salah satu adonan. Ia mencoleknya… dan menjilat jarinya sendiri.
Agni membeku.
“Woeek… manis banget… Uhoekk! Uhoekk!” Bude Ratmi terbatuk keras. Liurnya menyembur ke segala arah, beterbangan di udara seperti aerosol pembasmi serangga—dan tentu saja, jatuh tepat di atas seluruh adonan yang sudah dicetak dengan penuh perjuangan.
Tanpa rasa bersalah, perempuan itu langsung berbalik dan duduk santai di sofa, menyalakan televisi seolah tak ada hal penting yang baru saja ia rusak.
Tangan Agni terkepal. Rahangnya mengeras, giginya bergemelutuk menahan amarah yang nyaris meluap. Godaan untuk melempar spatula ke kepala perempuan tua itu begitu kuat.
Namun, ia memilih jalan yang lebih aman—menyambar ponselnya dan mengetik cepat.
Mama, kapan pulang sih?! Ini Bude Ratmi mulai berulah!!
Beberapa detik kemudian ibunya mengetik dan mengirim pesan.
Iya, ini mama lg jalan ke rumah.
Agni menghela napas keras. Dan akhirnya membuang satu batch macaron yang tadi sudah hampir tercetak semua di atas loyang.
Sial…. Jadi buang-buang bahan, batinnya kesal.
Beberapa menit kemudian Indira—ibunya Agni, masuk ke rumah saat Agni sedang mencuci loyangnya. Dan ketika melihat Indira masuk, Bude Ratmi langsung menghampirinya dengan antusias.
Mereka berpelukan, saling mencium pipi kiri kanan. Namun senyum keduanya menyiratkan ketegangan dingin yang tak terucap.
“Ya ampun Indira… Kamu kurusan ya sekarang? Capek ya tiap hari kerja? Apalagi sekarang Arjuna udah pensiun,” kata Bude Ratmi sambil tersenyum ‘ramah’.
Alis Indira terangkat sedikit. “Iya lumayan… pasien di klinik lagi banyak. Mbak Ratmi sendiri, bisnisnya Mas Endro kayaknya makin sukses ya…”
Indira meremas lengan atas Bude Ratmi yang berlemak. “...makin subur aja nih soalnya…”
Agni mendengus, berusaha menahan tawa ketika melihat sudut bibir Bude Ratmi yang masih terangkat berkedut ketika mendengar komentar tajam ibunya itu yang diikuti dengan senyuman manis.
Bude Ratmi adalah sepupu ibunya Agni.
Dan entah mengapa dari dulu mereka seperti selalu bersaing secara halus—atau lebih tepatnya, Bude Ratmi selalu berusaha menyaingi Indira.
Ketika dia tahu Bumi berhasil diterima di Akpol, entah bagaimana anak pertamanya yang laki-laki juga ikut daftar Akpol tapi tidak lolos.
Saat tahu Sagara diterima di Kedokteran UI, entah bagaimana anak keduanya yang perempuan juga mendaftar di kedokteran tapi tidak lolos juga. Namun setelah itu Bude Ratmi jadi sering membicarakan anak perempuannya itu ke Indira, seperti berusaha agar menjodohkan mereka. Ia bahkan beberapa kali membawa anak perempuannya itu ke rumah yang bahkan tidak dilirik sama sekali oleh Sagara.
Lalu, saat tahu Dirga sampai sekarang tidak bekerja dan hanya menghabiskan waktu di rumah sebagai pengangguran yang nampak tidak memiliki masa depan, Bude Ratmi selalu menyinggungnya dengan nada empatik palsu.
“Ngomong-ngomong Dirga gimana? Sekarang udah kerja belum?” tanya Bude Ratmi dengan nada prihatin ke Indira ketika mereka berdua duduk di sofa.
Rahang Indira terlihat mengeras. “Yah, masih usaha nyari-nyari…”
“Kalau belum dapet, ikut Mas Endro aja itu. Di kantornya dia lagi butuh OB.”
Indira berusaha tersenyum, meskipun sedikit kaku.
“Yahh… zaman sekarang kan nyari kerja susah. Jadi enggak usah gengsi lah milih-milih kerja…”
Indira menarik napas pelan, seolah sedang berusaha mengatur emosinya. “Mbak Ratmi lagi ada acara apa ke sini?” tanya Indira mengalihkan topik.
“Mau dateng ke nikahan temen. Sekalian mau jalan-jalan ke kampusnya Dicky. Kan Dicky sekarang kuliah di Ekonomi UI, udah semester 6. Aduh pusing banget bayar kuliahnya, bisa belasan juta. Tawaran beasiswa sih banyak ya, soalnya kan Dicky pinter. Cuma gimana ya, kasihan sama yang bener-bener butuh. Lagian… kita masih bisa usahalah. Biarpun pinter kan tapi enggak enak kalau disubsidi negara terus…”
Alis Indira terangkat lagi, tipis. Reaksi halus yang tak akan disadari orang luar, tapi Agni yang sudah hafal bahasa tubuh ibunya tahu betul—itu adalah sinyal bahwa komentar barusan telah mengenai sasaran.
Dan ya, Agni juga tahu betul—itu sindiran. Untuk Sagara, yang sejak SMA hingga kuliah spesialis selalu mengandalkan beasiswa.
Agni membiarkan mereka berdua mengobrol ringan di ruang tengah, sementara ia mulai membuat ulang macaron yang terpaksa dibuang tadi karena terkontaminasi aerosol Bude Ratmi. Saat Agni sibuk mengaduk tepung, ia mendengar Bude Ratmi bertanya pada Indira. “Agni sekarang kelas berapa?”
“Kelas XI SMA,” jawab Indira.
“Ohh… kata Mama kamu suka jualan kue ya, Ni?” tanya Bude Ratmi ke Agni yang masih sibuk di dapur.
“Iya Bude,” jawab Agni datar.
“Hebat ya, mandiri. Terus nanti lulus SMA mau ke mana?”
Agni menggeleng pelan. “Belum tahu Bude.”
“Udah enggak usah kuliah. Kasian Mama kamu udah tua, capek kerja sendirian nanti buat bayar uang kuliah. Bumi sama Sagara kan juga pasti mau nikah, nanti mereka bakal fokus sama keluarganya. Dirga enggak kerja… Mending kamu di rumah aja Ni, jagain Mama sambil jualan kue. Atau kalau kamu nanti udah lulus, mau Bude kenalin enggak sama anak temen Bude? Biar kamu langsung nikah aja nanti—jadi Mama enggak beban.”
Mendadak tangan Agni yang sedang sibuk mengaduk terhenti.
Beban?
Biasanya Agni cenderung pura-pura tidak dengar dan tidak terpengaruh dengan ocehan Bude Ratmi. Tapi mendadak kata-kata itu menancap di dadanya lebih dalam dari yang ia sadari.
Ia menunduk. Adonan di baskom yang sejak tadi ia aduk perlahan berubah bentuk di matanya. Bukan lagi impian kecil seorang gadis. Tapi sesuatu yang rapuh. Tak berharga. Seperti dirinya saat ini.
Ia tidak seperti Sagara yang selalu punya jalan. Tidak seperti Bumi yang tahu ke mana harus melangkah. Ia bahkan belum tahu arah, belum tahu tujuan. Beasiswa? Ia tak yakin cukup pintar. Kuliah? Entah. Tapi yang lebih menakutkan adalah… jika ia sungguh akan menjadi beban.
Dan kalau impiannya sendiri dianggap beban…lalu apa yang tersisa darinya?
Tangannya terdiam di atas baskom. Tapi di dalam dadanya, sesuatu seperti gemuruh badai kecil—sunyi, tapi menghancurkan dari dalam.
***
Malam itu, Agni tak jadi melanjutkan macaronnya. Ia harus membantu ibunya menyiapkan makan malam—katanya, anak-anak Bude Ratmi juga akan datang dan ikut menginap.
Sepanjang makan malam, Agni hanya diam. Rasa kesalnya belum surut. Rencana yang sudah ia susun sejak siang kembali tertunda karena tamu yang tidak pernah tahu diri itu.
Ayahnya, Arjuna, sudah pulang. Sagara harus jaga malam di rumah sakit, jadi tidak ikut makan. Sementara Bumi sempat mampir sebentar hanya untuk mandi dan ganti pakaian, lalu pergi lagi karena masih sibuk menangani kasus.
Dirga ikut makan malam dengan wajah santai. Sesekali ia menimpali obrolan dengan lelucon ringan, bahkan tidak tampak terusik saat Bude Ratmi menyindir statusnya sebagai pengangguran.
Agni diam-diam kagum. Andai saja ia bisa punya muka setebal Dirga, mungkin hidupnya akan lebih ringan. Ia tak perlu lagi menghabiskan energi untuk menahan amarah akibat omongan-omongan orang seperti Bude Ratmi.
Setelah makan malam selesai, Dirga langsung masuk ke kamarnya. Arjuna pergi menjemput anak-anak Bude Ratmi di depan gang. Indira kembali duduk di ruang tengah, mengobrol lagi dengan Bude Ratmi seperti tak terjadi apa-apa.
Dan Agni? Ia membereskan meja makan sendirian. Mengangkat piring-piring kotor, membawa baki lauk ke dapur, dan mulai mencuci piring, seolah pekerjaan itu memang sudah sewajarnya menjadi tugasnya. Tak ada yang menyuruh, tapi seakan semua orang tahu—Agni akan melakukannya.
Saat menggosok piring, pandangannya terarah ke sisa adonan macaron yang tadi ia buang. Napasnya terhembus panjang. Tanpa sadar, tangannya menggosok piring terlalu keras.
PRANG!
Sebuah piring tergelincir dari tangannya dan pecah berkeping-keping di lantai.
Agni memejamkan mata. Menarik napas keras.
“Kenapa, Ni?” Indira menoleh dari sofa, suaranya kaget.
“Licin,” jawab Agni datar. Ia jongkok, mengumpulkan pecahan piring tanpa ekspresi.
Bude Ratmi terkikik kecil. “Emang anak gadis zaman sekarang mah nggak biasa kerja rumah kaya zaman kita dulu.”
Alis Agni terangkat.
Ngomong apa sih nenek-nenek ini?
Selama ini, kalau Mamanya tidak ada di rumah, Agni-lah yang mengurus segalanya. Membersihkan rumah, belanja, memasak, mencuci piring, mencuci dan menjemur pakaian. Arjuna kadang membantu, tapi sering sibuk sendiri dengan urusan pos ronda. Sementara tiga kakaknya? Tidak lebih dari tiga monyet yang bahkan tidak mengangkat jari untuk membantu.
Dengan tangan bergetar, Agni membuang pecahan piring ke tempat sampah. Lalu kembali mencuci piring dengan gerakan cepat dan kasar.
Ia mendengar suara lembut ibunya, mencoba meredam suasana. “Agni rajin kok bantu-bantu di rumah.”
Namun Bude Ratmi hanya melambaikan tangan. “Ya emang harusnya gitu dong. Kalau enggak rajin, nanti mana ada cowok yang mau.”
Tawa renyahnya menggema, menyayat telinga Agni seperti pecahan piring tadi.
Agni mengembuskan napas keras. Ia berusaha menahan diri. Tapi baru saja ia hendak mengacuhkannya, pintu depan terbuka.
“Nah… datang juga,” seru Bude Ratmi sambil bangkit dari duduknya, wajahnya berseri menyambut anak-anaknya yang baru tiba.
“Agni, salam dulu ke Mas Dicky sama Mbak Dena,” kata Indira.
Agni memejamkan mata sesaat, menarik napas panjang. Ia mematikan keran, mengelap tangannya, dan berjalan ke pintu depan dengan langkah malas.
Di sana berdiri seorang perempuan berambut ikal panjang dan seorang pria tinggi dengan bahu lebar, mengenakan kaos polo dan kacamata bingkai persegi. Agni menatap mereka sekilas, mencoba mengingat wajah masa kecil yang samar-samar.
“Agni ya? Wah, udah gede sekarang,” sapa perempuan itu ramah. Suaranya lembut, ekspresinya hangat—tapi matanya sibuk. Sesekali melirik ke dalam rumah, seperti mencari sesuatu… atau seseorang.
Agni menyadarinya. Gerakan mata itu halus, tapi cukup jelas bagi orang yang memperhatikan.
Dena.
Sejak tadi, matanya tampak menelisik ruangan—melewati wajah Indira, melewati Arjuna, bahkan melewati dirinya. Ada keraguan samar dalam senyumnya, seolah ia tengah berharap seseorang muncul dari balik lorong.
Agni menyambut uluran tangannya. “Hai, Mbak Dena.”
“Gimana kabar kamu?”
“Baik,” jawab Agni singkat.
Lalu tangan lain menyodok ke hadapannya.
“Halo, Ni,” sapa suara pria di sebelah Dena. Dicky. Suaranya terdengar sedikit lebih berat dan dibuat-buat.
Agni menyalami tangan itu sekilas. Tapi saat ia hendak menariknya kembali, genggaman Dicky justru mengencang sedikit. Tahan. Tidak kasar, tapi cukup untuk membuat napas Agni tercekat.
“Apa kabar?” tanya Dicky dengan senyum miring yang tidak sampai ke matanya.
“Baik, Mas Dicky…” Agni mencoba menarik tangannya pelan, tapi masih tertahan.
“Udah gede, ya, sekarang...” katanya, suaranya turun satu oktaf.
Mata Dicky menatap wajah Agni. Sekilas. Lalu turun. Sekedip.
Dari mata—ke leher—dan semakin ke bawah, sebelum kembali ke matanya.
Agni merinding.
Degup jantungnya melonjak, dan bukan karena gugup. Tapi karena tubuhnya mulai memberi sinyal—ada sesuatu yang salah.
Tangan Dicky masih menggenggam. Panas, lembap, dan tak kunjung dilepas.
Agni berusaha tersenyum kaku sambil akhirnya menarik tangannya dengan paksa.
“Permisi, aku mau balik ke dapur.”
Dicky hanya mengangguk pelan, matanya masih mengikuti punggung Agni sampai gadis itu kembali ke dapur.
Begitu tiba di dapur, Agni menyalakan keran dengan cepat. Mencuci tangannya berkali-kali meski hanya bersalaman.
Air dingin mengalir deras, tapi rasa tak nyaman itu… tetap menempel di kulitnya.


 dwyne
dwyne