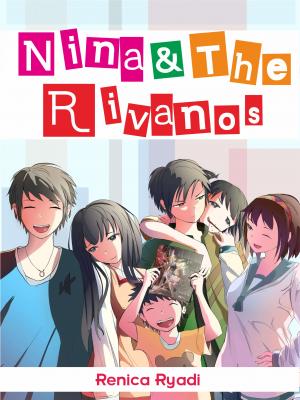Benda itu tergeletak di atas lemari tua, tersembunyi di antara setoples kosong dan kaleng biskuit Khong Guan yang isinya—seperti biasa—sudah berganti jadi benang jahit dan jarum pentul. Radio butut itu sudah lama tak bersuara, tapi keberadaannya tak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Warnanya sudah kusam, antenanya bengkok, dan salah satu tombolnya hilang. Tapi itulah radio yang dulu setiap pagi mengisi rumah ini dengan suara penyiar paruh baya yang menyebutkan suhu kota, lalu menyapa “pendengar setia di rumah-rumah penuh cinta”.
Dulu, setiap pagi, Ibu memutar radio itu sambil menyiapkan sarapan. Suara alat dapur bertaut dengan suara penyiar, lalu menyatu dengan bau nasi goreng dan minyak kayu putih. Sementara itu, aku dan Dira duduk di meja makan, kadang saling rebutan telur mata sapi, kadang pura-pura jadi komentator pertandingan sepak bola, padahal mulut masih penuh nasi.
Kini, radio itu diam. Tapi begitu aku sentuh tombol tuanya, memutar pelan, lalu mendengar suara kresek-kresek khas stasiun tak jelas—dadaku seketika menghangat. Dan ketika suara musik dari tahun entah-berapa mulai terdengar samar, aku menutup mata.
Aku merasa seperti sedang kembali ke pagi-pagi yang penuh cinta.
"Radio ini masih nyala, ternyata," kataku pelan.
Ayah dulu bilang, “Kalau radio itu mati total, artinya kenangan kita benar-benar sudah tamat.” Tapi tidak. Radio ini cuma diam sementara, seperti hati yang butuh disentuh dulu baru mau bicara.
Aku duduk bersila di lantai, radio itu kutaruh di depan. Tangan kananku memutar tombol volume, sementara tangan kiriku menahan napas. Stasiun yang tertangkap hanya sebagian, tapi lagu yang muncul... ah, lagu itu.
"Sepasang mata bola, dari balik jendela..."
Suara penyanyi perempuan dengan vibrato khas era 80-an mengalun lirih. Lagu itu dulu jadi favorit Ibu, dan meski aku dulu terlalu kecil untuk mengerti liriknya, melodi itu selalu berhasil membuat suasana rumah mendadak pelan.
Dulu, ketika Ibu mencuci piring di dapur, lagu itu akan ia nyanyikan pelan. Kadang sambil menggoyang pinggulnya sedikit, kadang sambil memegang gayung, seolah sedang tampil di atas panggung hiburan rakyat. Ayah akan tertawa dan pura-pura menyemangati, sementara aku dan Dira... entah kenapa, selalu ikut tertawa meski tak tahu lucunya di mana.
Kini, suara itu terdengar lagi, dan untuk pertama kalinya, aku merasa—rumah ini tidak sepenuhnya sepi.
Sore itu, aku menaruh radio di meja makan yang berdebu. Kupelankan volumenya, cukup agar rumah mendengarnya tanpa mengganggu. Ibu lewat membawa baskom cucian, menatapku, lalu berhenti.
“Itu... lagu Ibu, ya?” tanyanya, mata setengah menyipit.
Aku mengangguk. “Masih bisa nyala, Bu. Ajaib, ya.”
Ibu tersenyum, lalu duduk. Wajahnya tenang, seolah kenangan yang dulu ia kubur bersama cucian, kini muncul lagi dari lipatan baju.
“Kamu tahu nggak,” katanya, “Ayah kamu dulu nembak Ibu pakai lagu itu.”
Aku kaget. “Serius? Ayah ngungkapin cinta pakai radio?”
Ibu tertawa kecil. “Bukan. Tapi dia pinjam radio tetangganya, kasih kaset rekaman lagu itu, terus dia ngomong sebelum lagunya mulai. ‘Kalau kamu suka lagu ini, berarti kamu juga suka aku,’ katanya.”
Aku tertawa terpingkal. “Ih, gombal banget!”
“Tapi berhasil,” Ibu balas sambil tersipu. “Karena Ibu emang suka lagu itu. Dan... ya, akhirnya suka dia juga.”
Kami diam sebentar. Lagu berganti. Kali ini, sebuah lagu lama yang biasa diputar setiap malam minggu, sebelum acara sandiwara radio dimulai.
Suasana mendadak syahdu. Rumah tua itu seakan kembali ke masa di mana tak ada suara notifikasi ponsel, tak ada deadline, tak ada kecemasan yang bentuknya abstrak tapi melelahkan. Hanya ada musik, teh hangat, dan kursi rotan yang berdecit kalau diduduki.
Dira datang malam itu. Ia membawa martabak manis dan dua anaknya. Suaminya menyusul belakangan.
Begitu melihat radio itu di meja, ia berseru, “Eh, ini radio kita dulu, kan?! Yang kalau diputar keras sedikit langsung mati?”
Aku mengangguk. “Tapi sekarang masih hidup. Kayaknya dia tahu kita pulang.”
Kami bertiga duduk di ruang tengah, menyesap teh jahe buatan Ibu, dan membiarkan suara radio mengisi jeda obrolan kami.
Dira menatap radio itu lama. “Aku inget banget, dulu tiap malam kita rebutan denger sandiwara radio. Kamu sukanya cerita detektif, aku sukanya yang cinta-cintaan.”
Aku tertawa. “Dan akhirnya kita dengerin dua-duanya, sambil tidur-tiduran di karpet, terus ketiduran beneran.”
Radio itu bukan cuma benda. Ia semacam mesin waktu. Membawa kami kembali ke masa di mana suara bisa lebih berarti dari gambar, dan musik bisa menyembuhkan sepi yang tak kita pahami namanya.
Menjelang tengah malam, aku duduk sendiri di ruang tengah. Radio masih menyala pelan. Di luar, jangkrik bersahutan, dan bulan tergantung seperti bola lampu kecil di langit hitam.
Aku memandangi radio itu. Bayanganku memantul samar di permukaan kacanya yang retak. Dan di benakku, aku berkata:
“Kau tak punya layar sentuh,
tak bisa update aplikasi,
tapi kau bisa hidupkan kembali
suara-suara yang pernah membuat kami merasa pulang.”
Radio itu memang butut. Tapi justru karena itu, ia menjadi rumah bagi suara-suara yang nyaris hilang: tawa Ayah, nyanyian Ibu, celoteh masa kecil, dan denting waktu yang tak bisa diulang tapi masih bisa dikenang.
Dan malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu kalimat di halaman buku catatanku:
“Kadang, lagu lama bisa lebih jujur dari semua pesan baru.”


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_