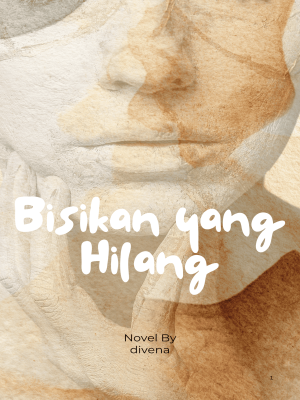Punggungnya terasa lebih ringan pagi ini. Bukan karena ia tak membawa banyak buku, tapi karena beban pikirannya seperti sudah mulai melepuh, mengering, dan mengelupas sedikit demi sedikit. Ada ruang baru di dalam dirinya, tempat napas bisa ditampung tanpa sesak.
Aditya tidak lagi menunduk saat berjalan ke sekolah. Langkahnya tegap, meski tetap pelan. Dan aku, tas tua yang sudah menampung terlalu banyak rahasia, tahu—anak ini sedang menapaki jalannya menuju pemulihan.
Namun seperti luka yang belum sepenuhnya kering, dunia masih menyimpan kejutan yang bisa saja menggores ulang. Dan hari itu, kejutan itu datang dalam bentuk seseorang yang sudah lama tak muncul di hadapan kami.
“Dit.”
Aditya berhenti. Aku pun ikut terhenti di punggungnya. Suara itu pelan, ragu-ragu, tapi tidak asing. Ia menoleh pelan. Dan di sana, berdiri dengan rambut diikat ekor kuda dan wajah yang tampak canggung—Reya.
Bukan Ayu.
Bukan teman dari masa kini.
Tapi Reya. Teman perempuan yang dulu pernah mengisi banyak ruang dalam hidup Aditya. Yang dulu sering duduk di sampingnya saat istirahat, sebelum hilang entah kemana setelah pertengkaran yang tak pernah benar-benar dibicarakan.
“Reya?” suara Aditya nyaris tak terdengar. Bahkan aku, yang selalu ada di dekat mulutnya, hampir tidak menangkapnya.
Reya mengangguk. Ia membawa buku, mengenakan seragam dengan jaket almamater yang sama. “Aku pindah balik... ke sekolah ini,” katanya pelan. “Baru minggu ini resmi.”
Aditya mengangguk kaku. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang.
“Boleh kita ngobrol nanti? Nggak harus sekarang sih. Gue cuma... pengin minta maaf,” lanjut Reya.
Aditya tak langsung menjawab. Tapi kemudian, ia menarik napas panjang.
“Oke,” katanya pendek.
Dan saat Reya berjalan menjauh, aku bisa merasakan sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak di dalam diri Aditya. Campuran getir, penasaran, marah yang sudah melebur jadi sisa-sisa keingintahuan.
Hari itu berlangsung cepat. Aditya hanya diam di kelas, tapi tidak tenggelam. Ia menyimak pelajaran, ikut diskusi, bahkan sempat melempar candaan saat guru Matematika salah tulis angka. Hal-hal kecil, yang dulu terasa berat, kini mulai terasa wajar kembali.
Saat istirahat, ia duduk sendiri di bangku dekat lapangan. Aku terletak di sebelahnya. Ia membuka resletingku dan menarik keluar kertas catatan yang ditulis semalam. Dibacanya pelan, lalu dilipat ulang dan dimasukkan ke saku kemeja.
“Gue mau ketemu dia nanti, cuma mau pastiin diri dulu,” gumamnya.
Yang dimaksudnya tentu Reya. Masa lalu yang datang mengetuk bukan untuk menghancurkan, tapi menagih akhir yang tak pernah selesai.
Sore harinya, mereka bertemu lagi di taman dekat sekolah. Reya duduk duluan. Kali ini, Aditya datang lebih tenang. Aku tetap setia di punggungnya, menjadi saksi yang tak bicara, tapi menyimpan semuanya.
“Gue... salah waktu itu,” kata Reya setelah diam cukup lama. “Waktu kabar soal keluarga lo tersebar, gue malah ikut menjauh. Aku nggak tahu harus gimana. Gue takut... kelihatan sok peduli.”
Aditya menatapnya lama. Lalu tersenyum tipis.
“Lo nggak salah. Gue juga ngejauh. Gue takut semua orang tahu, termasuk lo. Jadi gue mundur duluan.”
Reya menggigit bibirnya. “Tapi gue harusnya tetap jadi temen lo.”
“Udah telat buat balikin kayak dulu,” kata Aditya jujur. “Tapi bukan berarti nggak bisa mulai lagi, kan?”
Reya menatapnya, lalu tersenyum kecil. “Lo berubah ya.”
Aditya tertawa pendek. “Gue ngerasa kayak ganti kulit. Bukan berubah jadi orang lain, tapi jadi versi yang lebih jujur.”
“Gue senang lo bisa sampai sini, Dit,” bisik Reya.
Aditya mengangguk. “Gue juga.”
Mereka tidak banyak bicara setelah itu. Tapi diam yang terjadi bukan canggung. Justru hangat. Seperti dua orang yang pernah saling kehilangan arah, lalu kini memilih berjalan berdampingan lagi. Tidak harus seperti dulu. Tapi cukup.
Di kamar malam itu, Aditya menulis di laptop. Bukan untuk YouTube, bukan juga untuk tugas. Tapi jurnal pribadi. Sebuah kebiasaan baru yang disarankan Bu Ratih sejak ia mulai konseling.
“Hari ini gue ketemu Reya. Ternyata masa lalu nggak seseram yang gue kira. Mungkin karena gue udah nggak lari lagi.”
“Dulu gue pikir, buat jadi kuat, gue harus nutup semua pintu. Tapi ternyata, ada pintu yang kalau dibuka, malah bikin lega.”
Aku tersenyum—ya, sebisa tas tersenyum. Karena aku tahu, anak ini pelan-pelan sedang menyulam dirinya kembali. Benang-benang dari masa lalu tak lagi menjadi jebakan, melainkan bahan yang ia gunakan untuk merajut hari-hari baru.
Besok, mungkin akan ada hujan.
Mungkin juga akan ada pertanyaan baru yang belum bisa dijawab.
Tapi untuk malam ini, Aditya tidur lebih cepat dari biasanya. Dan aku, tersampir di gantungan kamar, merasa... pulang.


 bubblejessz
bubblejessz