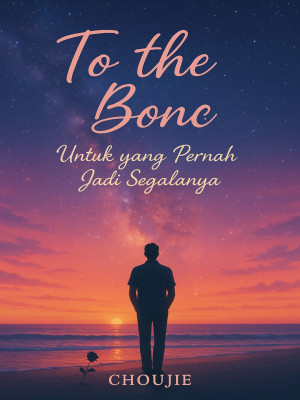Hari ketujuh di Jepang.
Aku melangkah pelan melewati trotoar Shinjuku yang masih dipenuhi lalu-lalang manusia, meskipun jam sudah lewat pukul sembilan malam. Lampu dari papan iklan raksasa memantul di jendela toko-toko yang telah tertutup, sementara suara musik pop Jepang terdengar samar dari salah satu kedai ramen yang masih buka.
Di tengah keramaian itu, langkahku terasa seperti satu-satunya yang berjalan lambat.
"Seminggu. Gila. Udah tujuh hari," gumamku pelan, nyaris tenggelam di antara bising kota.
Beberapa hari pertama berlalu begitu cepat. Waktu terasa seperti dilipat. Pagi menjelajah, siang nyasar, sore mencicipi makanan aneh, malam kembali ke kapsul sempit untuk tidur dan mengirim foto-foto keren ke grup WA. Aku bahkan sudah hafal belokan dari stasiun ke hotel, tahu vending machine mana yang punya teh hijau termurah, dan bisa mengenali suara notifikasi kereta jalur Yamanote hanya dari nada pertamanya.
Tapi malam ini rasanya berbeda.
Langkah kaki orang-orang di sekitarku terdengar jauh. Sorot lampu neon yang biasanya membuatku merasa seperti karakter utama dalam anime, kini terasa menyilaukan dan mengganggu. Bahkan angin malam Tokyo pun membawa dingin yang terasa terlalu dekat malam ini.
Aku berhenti di seberang gang sempit yang menuju hotel. Menatap tulisan kecil "Yume no Koya" yang bersinar lembut dari balik gedung beton. Ada rasa asing yang muncul perlahan. Seperti nostalgia yang datang terlalu dini.
"Tempat tidur terakhir di negara ini," aku bergumam, mencoba bercanda dengan diri sendiri. Tapi cengiranku cepat menghilang. Mulutku kembali diam. Tenggorokanku kering.
Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan membuka galeri. Menelusuri foto-foto sejak hari pertama. Selfie canggung di Harajuku. Onigiri pertama yang gagal kubuka dengan benar. Sandal hotel onsen yang kekecilan. Jalanan sepi di Ueno Park saat matahari mulai tenggelam. Semua itu tampak seperti potongan mimpi. Terlalu rapi untuk disebut kenyataan.
Tapi kenyataan akhirnya datang juga. Menabrak begitu saja. Suara Ibu yang pecah di ujung telepon. Kata-kata "rumah kita dijarah" yang terus berputar di kepalaku.
Aku menatap layar ponsel cukup lama sampai pantulan wajahku muncul. Mata sembab. Hidung kemerahan. Tapi tidak ada air mata. Bukan karena tidak ingin menangis, tapi karena tubuhku belum tahu harus bereaksi seperti apa.
Aku menutup ponsel dan menarik napas dalam-dalam.
"Ya sudah, satu malam lagi," kataku pada diri sendiri. "Tidur. Besok beli oleh-oleh. Terus pulang. Bawa sisa Jepang yang masih bisa dibawa."
Suara klakson taksi menyentak lamunanku. Aku kembali melangkah menuju hotel. Tapi di dalam hati, suara kecil yang sudah sejak tadi diam kini mulai terdengar jelas.
"Tapi pulang ke mana?"
Karena kenyataannya berbeda.
Tiket pesawat yang seharusnya membawaku kembali sudah kurefund, hanya untuk mendapatkan sisa uang demi bisa bertahan satu hari lagi di kota ini.
***
Langkahku makin cepat. Udara Tokyo mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena angin. Mungkin karena pikiranku sendiri. Jalanan Shinjuku masih ramai, tapi aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari arus itu. Orang-orang di sekelilingku berjalan cepat dengan tujuan yang jelas, seolah mereka semua tahu harus ke mana. Aku hanya menuju satu tempat, dan bahkan itu pun sekarang terasa rapuh.
Aku membuka ponsel, seolah masih ada hal penting yang harus kulihat. Tapi layar itu hanya memantulkan wajahku sendiri. Itinerary yang dulu kubuat dengan semangat kini hanya berisi coretan masa lalu. Tidak ada check-in bandara. Tidak ada penerbangan pulang. Hanya ruang kosong yang kupaksa untuk diisi ulang dengan rencana yang belum sempat kubuat.
Lampu dari toko elektronik besar di seberang jalan menyorot wajahku, memantulkan warna-warna mencolok ke mataku yang lelah. Sekilas aku menangkap bayanganku sendiri di kaca toko. Hoodie kusut, ransel menggantung di satu bahu, dan wajah yang lebih tua dari seminggu lalu.
Kupercepat langkah, melewati sekelompok remaja Jepang yang tertawa-tawa sambil makan es krim. Salah satu dari mereka mengenakan seragam sekolah, rambutnya dicat pirang, dan tertawa lepas seperti dunia ini belum pernah menyakitinya.
Aku menoleh cepat dan terus berjalan. Entah kenapa, ironi itu terasa tajam.
"Mereka bisa tertawa. Aku bahkan tidak bisa bernapas dengan tenang."
Memasuki gang sempit menuju hotel, langkahku melambat. Cahaya di sini lebih redup. Suara kota meredam, hanya tersisa dengung AC dari belakang restoran dan suara pintu otomatis minimarket yang terbuka-tutup.
Di ujung gang, papan nama kecil "Yume no Koya" menyala samar di antara bayangan gedung-gedung tinggi. Cahaya putih hangat dari jendela lobi terpancar keluar, membuat bagian depannya terlihat seperti satu-satunya tempat aman di dunia malam itu.
Aku berdiri sejenak di depan pintu kaca. Menatap ke dalam. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dari interiornya yang minimalis. Kursi tunggu warna biru tua, lantai kayu yang bersih, dan aroma samar kayu cemara dari lobi yang terasa bahkan sebelum pintunya terbuka.
"Tempat yang tidak menghakimi. Tempat yang diam saja walau aku pulang larut. Tempat yang tidak bertanya macam-macam," gumamku lirih.
Aku menarik napas dalam dan melangkah masuk. Pintu otomatis terbuka perlahan dengan suara desis lembut, seolah menyambutku kembali.
Di balik meja resepsionis, pria yang sudah sering kulihat selama seminggu terakhir berdiri tegak. Dasi merah hati, jas abu-abu, wajah datar seperti biasa. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ekspresinya lebih tegang. Tangannya tidak segera bergerak seperti biasanya.
Aku mencoba tersenyum tipis dan menyapa dengan sopan, meski suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan.
"Satu malam lagi. Untuk Arya Satya."
Hening. Beberapa detik. Suara ketikan keyboard menjadi satu-satunya yang terdengar. Aku menunggu. Tegang. Lelah. Cemas. Mungkin semuanya sekaligus.
Lalu pria itu mendongak, dan dengan nada yang terlalu tenang untuk kabar seburuk ini, ia berkata:
"Sumimasen... reservasi Anda hanya sampai tadi malam. Malam ini penuh."
Dunia, untuk kedua kalinya hari ini, kembali diam sesaat.
Kata-katanya jelas. Rapi. Datar. Seperti ucapan dari rekaman layanan pelanggan. Tapi untukku, kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam kolam tenang. Menghancurkan sisa ketenangan yang tadi kupegang erat.
Aku menatapnya. Diam. Berharap dia akan tertawa kecil dan berkata, "Maaf, bercanda," atau "Oh, saya salah baca." Tapi tidak. Dia hanya berdiri di balik meja, tangannya terlipat di atas laptop, dan wajahnya tetap netral. Terlalu netral.
Aku memaksakan senyum, seperti ingin meyakinkan bahwa ini pasti cuma salah paham.
"Maaf, mungkin saya salah dengar... saya sudah menginap tujuh malam. Hari ini malam terakhir saya, kan?"
Dia mengangguk sopan. Lalu menunjuk layar komputer tanpa benar-benar memperlihatkannya padaku.
"Benar. Anda check-in tujuh hari yang lalu. Dan check-out pagi ini."
Aku menatap kosong. "Tapi... saya pikir saya extend sampai malam ini."
"Tidak ada permintaan perpanjangan dari Anda. Dan hari ini semua kamar penuh," katanya dengan suara pelan dan datar. Nyaris menenangkan, tapi justru membuatku ingin berteriak.
Aku buru-buru mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi pemesanan. Jariku gemetar, berkeringat. "Kita lihat saja," bisikku. Masuk ke histori transaksi. Scroll ke bawah. Dan... ya.
Check-in: 20 Mei. Check-out: 27 Mei.
Hari ini... 27 Mei.
Dunia runtuh lagi. Meskipun hanya satu milimeter. Aku mengedipkan mata. Mencoba memastikan aku tidak salah lihat. Tapi angka-angka itu tidak berubah. Mereka tidak berbohong.
"Aku... salah hitung..." bisikku lirih.
Petugas itu masih berdiri di tempat. Matanya menatapku dengan empati datar. Bukan simpati, bukan kasihan. Hanya prosedur. Mungkin juga sedikit rasa bersalah karena tidak bisa menawarkan solusi.
"Apa... ada hotel lain dekat sini yang masih ada kamar? Yang harganya tidak terlalu mahal?" tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar, seperti seseorang yang sudah tahu jawaban tapi tetap bertanya.
Dia menggeleng pelan. "Hari ini akhir pekan. Banyak turis. Kami sudah coba bantu cari untuk tamu lain juga. Tapi semua kapsul di area Shinjuku penuh. Bahkan hostel pun sudah padat."
Aku mengangguk perlahan. Tidak yakin sedang menyetujui apa.
"Terima kasih," kataku akhirnya. Lebih sebagai refleks sopan santun daripada rasa syukur.
Aku melangkah mundur. Pintu otomatis terbuka. Udara malam langsung menyambut seperti tamparan dingin.
Aku keluar. Pelan.
Langkah kakiku terasa hampa, seolah tidak ada lagi gravitasi. Seolah tubuhku tahu. Tidak ada tempat untuk pulang malam ini.
***
Aku berdiri di trotoar sempit depan hotel kapsul, tempat yang selama seminggu jadi titik aman, sekarang berubah jadi titik nol. Papan nama "Yume no Koya" masih bersinar hangat, tapi artinya sudah berbeda. Bukan tempat pulang. Bukan lagi rumah sementara.
Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca depan hotel. Wajahku tampak asing. Bukan karena capek, tapi karena kehilangan.
"Satu hari. Hanya satu hari salah hitung."
"Aku cuma lupa nambah semalam. Masa segini doang bikin aku homeless?"
Ponsel masih di tanganku, layar aplikasinya menyala dengan tulisan menyebalkan:
"Reservasi Anda telah selesai. Terima kasih telah menginap."
Terima kasih? Terima kasih apanya?
Aku ingin tertawa, tapi rasanya malah pengin muntah.
Di sekelilingku, dunia tetap berjalan. Sepasang turis asing lewat sambil membawa kantong belanja besar dari toko elektronik. Mereka tertawa, salah satu dari mereka mencoba mengucap "arigatou gozaimasu" dengan logat kacau. Seorang pekerja restoran di seberang sedang menurunkan kursi-kursi lipat, matanya tak menoleh ke mana-mana. Seorang pria paruh baya merokok diam-diam di bawah lampu jalan.
Dan aku cuma berdiri di tengah semuanya. Tidak penting. Tidak kelihatan.
Aku duduk di bangku pendek di depan hotel, koper di sampingku. Kulepaskan napas yang sudah tertahan sejak dari lobi tadi. Kurasakan tubuhku mulai gemetar. Entah karena udara malam atau karena otakku yang mulai panik.
Kupaksa diriku berpikir.
"Oke. Langkah satu: cari hotel lain."
Kubuka aplikasi peta, lalu aplikasi pemesanan hotel. Jari-jariku menggeser layar, satu demi satu ikon merah muncul di layar.
Penuh.
Penuh.
Tutup.
Terlalu mahal.
Hotel termurah yang masih tersedia? Dua stasiun kereta jauhnya, harga dua kali lipat dari budget.
Aku mengecek dompet. Cepat, seperti anak sekolah nyari uang jajan yang nyelip.
Kuteliti lembar demi lembar yen yang tersisa. Tiga lembar seribuan. Beberapa koin receh. Uang di dompet digital? Nyaris habis, dan aku belum aktifkan transfer antarbank internasional.
Total? Bahkan tidak cukup untuk hotel paling murah sekalipun.
Aku mengembuskan napas panjang, kali ini tidak tertahan. Kulepaskan pegangan koper, dan membiarkannya berdiri sendiri di sisiku.
"Ini bukan liburan lagi. Ini nyaris jadi pengungsian."
Kupikir aku datang ke Jepang untuk healing, untuk kabur sejenak dari kenyataan.
Tapi sekarang kenyataan menemuiku di sini. Tanpa sopan santun. Tanpa peringatan.
Kupikir dulu bisa istirahat malam ini, lalu esok pulang dengan tenang. Tapi malam ini belum selesai. Dan kota ini tidak peduli kau capek atau tidak. Shinjuku tetap terang, tetap hidup, tetap berjalan tanpa melambat untuk siapa pun.
Aku tatap langit. Gelap. Tidak ada bintang.
Entah karena lampu kota yang terlalu terang, atau karena malam ini memang tidak menyisakan cahaya untukku.
Setelah lebih dari sepuluh menit duduk diam di bangku kayu yang dingin, aku berdiri lagi. Koperku kubawa menyeret pelan, seperti menarik beban yang lebih besar dari sekadar roda dan tas.
"Aku nggak bisa duduk diam. Nggak malam ini," bisikku pada diri sendiri. Suaraku lirih, seperti takut didengar oleh kehidupan yang masih berjalan di sekelilingku.
Aku kembali membuka peta di ponsel. Layar penuh dengan ikon merah kecil, tanda hotel, hostel, kapsul, semua bertuliskan satu kata yang sama, "PENUH."
Kujelajahi setiap jalan dalam peta digital seperti main teka-teki buta. Masuk satu hotel, keluar, cari berikutnya. Beberapa klik membawa ke harga yang tak masuk akal. Hotel bisnis kecil dengan tarif lebih dari dua belas ribu yen per malam, lebih mahal dari tiket pulangku besok.
"Kalau aku booking hotel itu, besok nggak bisa naik kereta ke bandara. Bisa-bisa tidur di Narita. Dan itu pun kalau bisa masuk," gumamku, separuh bingung, separuh ingin marah.
Aku berdiri di pojok gang kecil, ponsel di satu tangan, koper di tangan lain, dan langit Tokyo di atas kepala. Terlalu terang. Terlalu kosong.
Kuputuskan mencari dengan cara kuno. Jalan kaki.
Mungkin ada penginapan yang belum terdaftar online. Atau warung tua yang mau menyewakan ranjang tua. Apa saja.
Kaki melangkah tanpa rencana. Kutelusuri jalanan di luar jalur turis. Lampu mulai berkurang, suara kota sedikit meredup. Di ujung gang, aku melihat sebuah bangunan tua bertuliskan "Business Hotel" dalam huruf katakana. Plang kecil, dinding abu-abu, dan jendela yang buram.
Harapan muncul sejenak.
Aku masuk.
Di dalam, seorang pria tua duduk di belakang meja resepsionis kecil. Rambutnya hampir sepenuhnya putih, dan kacamatanya turun sampai ujung hidung. Ia menatapku dengan sorot penasaran.
"Sumimasen..." ucapku pelan. "Ada kamar kosong malam ini?"
Ia menatap layar komputer yang tampak usang, lalu geleng kepala dengan lambat.
"Kamar sudah penuh hari ini," katanya datar. Penuh juga. Bahkan di tempat yang hampir tak terlihat di peta.
"Arigatou gozaimasu..." jawabku, lalu keluar lagi dengan rasa gagal yang makin menekan.
Langkah kakiku kembali tak tentu arah. Wajahku sudah tidak tegang, tapi kosong.
Kota ini terlalu besar untuk manusia sepertiku malam ini.
Sampai akhirnya aku menyerah.
Aku kembali ke minimarket yang sama, tempat pertama aku membeli onigiri hitam putih di hari pertama kedatanganku. Tempat yang anehnya sekarang terasa akrab.
Masuk, kulihat rak-rak roti dan makanan instan yang disusun rapi. Cahaya putih terang menusuk mata, tapi setidaknya di sini hangat. Setidaknya di sini tidak ada yang mengusirku.
Aku ambil dua roti isi tuna dan satu botol air mineral. Kulempar beberapa koin ke meja kasir. Petugas hanya membungkuk sopan, dan aku membalas dengan anggukan lelah.
Keluar lagi.
Duduk di bangku kayu kecil di depan toko, seperti adegan ulangan dari hari pertama.
Tapi sekarang wajahku tidak lagi ingin sok cool.
Tanganku gemetar saat membuka bungkus roti. Aku makan perlahan, bukan karena lapar, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan malam ini yang terasa seperti kontrol.
Dan saat roti habis, aku hanya duduk.
Ponselku kuletakkan di pangkuan. Tidak ada selfie. Tidak ada status Instagram. Tidak ada teks dramatis untuk grup WA. Tidak malam ini.
Yang ada hanya suara mobil lewat, dengungan pendingin AC dari dinding minimarket, dan tubuhku yang makin berat tertimpa realita.
Tidak ada tempat yang bisa kupesan. Tidak ada tempat yang bisa kupinjam. Tidak ada tempat yang menungguku.
***
Roti isi tuna sudah habis. Botol air setengah kosong tergeletak di bangku. Tubuhku bersandar pelan ke sandaran kayu, mata menatap langit yang tak menawarkan apa pun selain kilau lampu neon yang tersisa.
Aku menarik napas. Pelan. Dalam.
Tapi tidak ada udara yang terasa cukup. Dada ini tetap berat.
Kuambil ponsel. Kucoba cari alternatif terakhir. Net café dua puluh empat jam dekat Shinjuku.
Hasilnya muncul, ada beberapa, tapi jaraknya lumayan, dan dari ulasan, hampir semuanya penuh atau sudah mengantri. Beberapa bahkan tak menerima tamu baru malam ini. Aku menutup tab itu seperti menutup pintu terakhir.
Kupandangi sisa uang receh di tangan. Terasa ringan dan menyebalkan.
"Mungkin aku bisa, ya, tidur sebentar saja di sini."
Kupalingkan wajah ke taman kecil di sisi minimarket, tempat yang dulunya tak kulirik dua kali. Di tengah hiruk-pikuk kota, taman itu terasa seperti ruang kosong di antara halaman-halaman buku yang terlalu penuh kata.
Bangku panjang dari kayu itu terlihat kosong. Ada lampu jalan menggantung rendah, memberi cahaya hangat yang setidaknya tidak menakutkan.
Kutarik koper pelan-pelan. Ransel kuletakkan di pangkuan, lalu kubuka jaket hoodie dan menyelubungkannya rapat. Aku duduk.
Dan menunggu malam menua.
***
Suasana di sekitarku bergerak cepat. Orang lalu-lalang, suara sepatu hak tinggi di trotoar, dentingan sepeda, gerobak pembersih dari petugas kebersihan kota, suara ambulans jauh di kejauhan. Tapi aku diam. Terjebak di tengah semua itu seperti catatan kaki yang lupa dicetak.
Seorang pria tua duduk di bangku lain, agak jauh. Ia mengenakan mantel lusuh dan menatap lurus ke depan, wajahnya diam. Entah gelandangan, entah hanya seperti aku, seseorang yang kehabisan tempat.
Kupandangi dia. Kupikirkan mungkin kami tidak jauh berbeda malam ini.
Kutelungkupkan tubuhku ke koper, memeluknya seperti guling di kasur lama. Tapi ini bukan kasur. Ini kayu. Dingin. Kasar. Tidak ada selimut, tidak ada lampu tidur. Hanya sisa-sisa tubuhku yang mencoba percaya bahwa esok akan datang.
Aku Arya Satya. Lulusan universitas. Anak semata wayang. Wisudawan penuh harapan.
Dan sekarang aku hanya anak yang tidur di bangku taman kota asing.
Yang telepon ibunya tidak bisa dihubungi.
Yang rumahnya entah masih utuh atau sudah jadi abu.
Yang datang untuk liburan, dan malah kehilangan arah.
Aku menarik napas lagi.
Dan untuk pertama kalinya, kubiarkan mataku menutup.
Tidak untuk tidur. Tapi untuk mundur sebentar dari dunia. Dari kenyataan. Dari semua beban yang rasanya terlalu besar untuk pundakku sendiri.
Kupikir malam ini aku bisa menghilang sebentar.
Tanpa tempat pulang, tanpa tempat menginap, aku tetap ada.
Tapi rasanya tipis. Hampir transparan.


 quietsnowy
quietsnowy