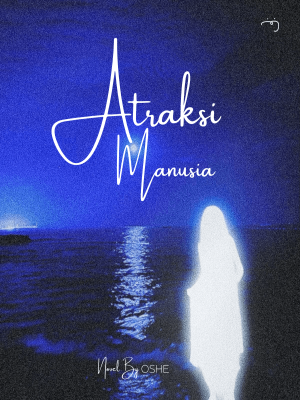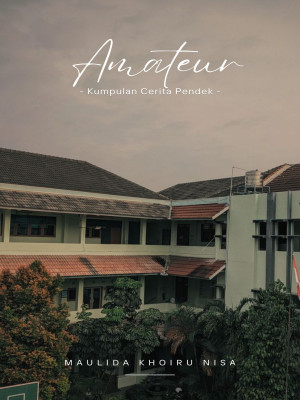Sorry, this chapter has been locked by the author!
Similar Tags
Atraksi Manusia
630
441
7
Inspirational
Apakah semua orang mendapatkan peran yang mereka inginkan? atau apakah mereka hanya menjalani peran dengan hati yang hampa?. Kehidupan adalah panggung pertunjukan, tempat narasi yang sudah di tetapkan, menjalani nya suka dan duka. Tak akan ada yang tahu bagaimana cerita ini berlanjut, namun hal yang utama adalah jangan sampai berakhir.
Perjalanan Anne menemukan jati diri nya dengan menghidupk...
Glitch Mind
55
52
0
Inspirational
Apa reaksi kamu ketika tahu bahwa orang-orang disekitar mu memiliki penyakit mental?
Memakinya? Mengatakan bahwa dia gila? Atau berempati kepadanya?
Itulah yang dialami oleh Askala Chandhi, seorang chef muda pemilik restoran rumahan Aroma Chandhi yang menderita Anxiety Disorder......
Ruang Suara
271
196
1
Inspirational
Mereka yang merasa diciptakan sempurna, dengan semua kebahagiaan yang menyelimutinya, mengatakan bahwa ‘bahagia itu sederhana’. Se-sederhana apa bahagia itu? Kenapa kalau sederhana aku merasa sulit untuk memilikinya? Apa tak sedikitpun aku pantas menyandang gelar sederhana itu?
Suara-suara itu terdengar berisik. Lambat laun memenuhi ruang pikirku seolah tak menyisakan sedikitpun ruang untukk...
CTRL+Z : Menghapus Diri Sendiri
183
160
1
Inspirational
Di SMA Nirwana Utama, gagal bukan sekadar nilai merah, tapi ancaman untuk dilupakan.
Nawasena Adikara atau Sen dikirim ke Room Delete, kelas rahasia bagi siswa "gagal", "bermasalah", atau "tidak cocok dengan sistem" dihari pertamanya karena membuat kekacauan. Di sana, nama mereka dihapus, diganti angka. Mereka diberi waktu untuk membuktikan diri lewat sistem bernama R.E.S.E.T.
Akan tetapi, ...
BestfriEND
59
52
1
True Story
Di tengah hedonisme kampus yang terasa asing, Iara Deanara memilih teguh pada kesederhanaannya. Berbekal mental kuat sejak sekolah. Dia tak gentar menghadapi perundungan dari teman kampusnya, Frada.
Iara yakin, tanpa polesan makeup dan penampilan mewah. Dia akan menemukan orang tulus yang menerima hatinya. Keyakinannya bersemi saat bersahabat dengan Dea dan menjalin kasih dengan Emil, cowok b...
Maju Terus Pantang Kurus
1970
928
3
Romance
Kalau bukan untuk menyelamatkan nilai mata pelajaran olahraganya yang jeblok, Griss tidak akan mau menjadi Teman Makan Juna, anak guru olahraganya yang kurus dan tidak bisa makan sendirian. Dasar bayi! Padahal Juna satu tahun lebih tua dari Griss.
Sejak saat itu, kehidupan sekolah Griss berubah. Cewek pemalu, tidak punya banyak teman, dan minderan itu tiba-tiba jadi incaran penggemar-penggemar...
Langit-Langit Patah
37
32
1
Romance
Linka tidak pernah bisa melupakan hujan yang mengguyur dirinya lima tahun lalu. Hujan itu merenggut Ren, laki-laki ramah yang rupanya memendam depresinya seorang diri.
"Kalau saja dunia ini kiamat, lalu semua orang mati, dan hanya kamu yang tersisa, apa yang akan kamu lakukan?"
"Bunuh diri!"
Ren tersenyum ketika gerimis menebar aroma patrikor sore. Laki-laki itu mengacak rambut Linka, ...
No Life, No Love
1699
1181
2
True Story
Erilya memiliki cita-cita sebagai editor buku. Dia ingin membantu mengembangkan karya-karya penulis hebat di masa depan. Alhasil dia mengambil juruan Sastra Indonesia untuk melancarkan mimpinya. Sayangnya, zaman semakin berubah. Overpopulasi membuat Erilya mulai goyah dengan mimpi-mimpi yang pernah dia harapkan. Banyak saingan untuk masuk di dunia tersebut. Gelar sarjana pun menjadi tidak berguna...
PUZZLE - Mencari Jati Diri Yang Hilang
705
506
0
Fan Fiction
Dazzle Lee Ghayari Rozh lahir dari keluarga Lee Han yang tuntun untuk menjadi fotokopi sang Kakak Danzel Lee Ghayari yang sempurna di segala sisi. Kehidupannya yang gemerlap ternyata membuatnya terjebak dalam lorong yang paling gelap. Pencarian jati diri nya di mulai setelah ia di nyatakan mengidap gangguan mental. Ingin sembuh dan menyembuhkan mereka yang sama. Demi melanjutkan misinya mencari k...
Ameteur
113
95
2
Inspirational
Untuk yang pernah merasa kalah.
Untuk yang sering salah langkah.
Untuk yang belum tahu arah, tapi tetap memilih berjalan.
Amateur adalah kumpulan cerita pendek tentang fase hidup yang ganjil. Saat kita belum sepenuhnya tahu siapa diri kita, tapi tetap harus menjalani hari demi hari. Tentang jatuh cinta yang canggung, persahabatan yang retak perlahan, impian yang berubah bentuk, dan kegagalan...


 rosadewiita
rosadewiita