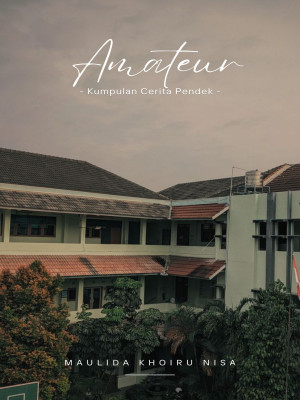Setelah cukup banyak hari-hari yang kulalui dalam diam, akhirnya ada satu malam yang mengubah ritmeku.
Aku iseng membuka akun media sosial usaha yang hampir terlantar itu. Kuketik satu caption sambil mengunggah foto handuk berbentuk kelinci warna pink pastel—hasil iseng-iseng sore tadi. Lalu, entah kenapa, aku terpikir untuk mengunggah juga foto kado bunga sabun yang baru kucoba rangkai. Awalnya iseng ikut tutorial dari YouTube, tapi ternyata cukup menyenangkan. Seperti menyusun warna dan aroma jadi satu cerita kecil yang harum.
“Nggak nyangka bikin bunga dari sabun bisa semenyenangkan ini,” gumamku sambil tersenyum.
Malam itu aku juga mengunggah satu parcel mungil berisi pernak-pernik bayi—hasil eksperimen pertamaku untuk kado ulang tahun anak teman. Ada kaus kaki kecil, sabun cair bayi, boneka mungil, dan stiker nama. Kupotret, kuunggah, dan… kututup ponsel. Tanpa harapan berlebih.
Tapi keesokan harinya, ada DM masuk. Lalu dua. Lalu tiga.
“Bisa kirim ke Jakarta?”
“Kalau bunga sabunnya bisa custom warna, nggak?”
“Saya mau pesen dua parcel bayi, buat kado keponakan.”
Aku menatap layar lama sekali. Rasanya seperti dihampiri kembali oleh harapan yang pernah hilang. Seperti dipeluk oleh semesta yang berkata, 'Ayo, berdiri lagi. Nggak harus sempurna kok.'
***
Hari-hariku kembali sibuk. Kali ini bukan hanya dengan handuk lucu, tapi juga dengan rangkaian bunga sabun dan parcel kado yang kutata dengan hati-hati. Aku kembali mencatat orderan, mencetak label pengiriman, bahkan mulai bikin template invoice sederhana di Excel.
“Hebat juga kamu, Na. Sekarang udah bisa ngatur semuanya sendiri,” ujar salah satu teman kos saat melihat kamar yang penuh kardus kecil dan pita warna-warni.
Aku hanya tersenyum kecil. “Masih belajar. Tapi ya, ternyata menyenangkan juga.”
Kadang aku masih ragu. Masih takut kecewa lagi. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Karena aku nggak cuma jual produk, tapi juga merakit kembali bagian dari diriku yang pernah merasa gagal.
Dan saat paket pertamaku sampai di Jakarta—dibeli seseorang yang sama sekali tidak kukenal—aku menangis kecil.
Bukan karena sedih. Tapi karena lega. Karena tahu bahwa aku masih bisa bangkit. Masih bisa jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Bahkan ketika hubungan dengan Radit masih penuh teka-teki. Bahkan ketika hari-hari belum tentu cerah.
Setidaknya, aku tahu: aku sedang tumbuh. Lagi.
***
Paket ke Jakarta sukses terkirim. Bahkan pembelinya mengunggah foto parcel itu ke Instagram dan menandai akunku.
"Gemes banget parcelll-nyaaa, thank youuuu!"
Aku membaca caption itu berulang kali, tersenyum sendiri sambil memeluk lutut di atas kasur. Rasanya seperti dikasih suntikan semangat yang baru. Aku lalu me-repost unggahan itu dan kembali mengecek orderan. Ada dua pesan baru masuk hari itu. Kecil, tapi cukup membuatku ingin bangun pagi keesokan harinya dengan hati lebih ringan.
Tapi di balik layar senyumku, hubunganku dengan Radit masih seperti benang kusut. Kami jarang bertengkar besar, tapi akhir-akhir ini nyaris selalu saja ada hal kecil yang membuat kami saling mengeluh. Kadang soal waktu. Kadang soal biaya pernikahan yang mulai kami tabung, tapi masih belum cukup juga.
Pernah suatu malam, Radit berkata pelan di ujung telepon,
“Kalau kamu memang belum yakin, Na… nggak apa-apa. Tapi tolong jangan bikin aku nunggu tanpa arah.”
Aku terdiam. Di satu sisi, aku ingin pernikahan ini berjalan. Tapi di sisi lain, aku takut semua ini hanya jadi pengalihan dari hidup yang belum sepenuhnya kupahami.
“Aku bukan nggak mau, Dit. Tapi aku masih nyari irama yang pas,” ucapku pelan. “Kamu sendiri kelihatan makin capek akhir-akhir ini.”
Radit tertawa lirih. “Ya, mungkin karena aku juga bingung, Na. Kerja, nabung, mikirin masa depan. Tapi kamu seperti jalan sendiri, sibuk dengan duniamu. Dan aku takut—takut kita jadi dua orang asing dalam satu acara resepsi nanti.”
Aku tak bisa membantah. Karena di dalam hati, aku pun merasakan itu. Seolah kami memang sedang tumbuh ke arah yang sama sekali berbeda.
***
Minggu sore, tanpa banyak pesan, Radit datang ke kos.
Dia membawa dua kotak makanan dan satu kardus kecil di tangannya. “Coba buka,” katanya sambil menyodorkan kardus kecil itu.
Aku buka perlahan. Isinya: pita-pita warna pastel dan stiker kecil bergambar kelinci.
“Aku lihat kamu mulai rame jualan lagi,” ujarnya sambil duduk di lantai. “Aku nemu ini pas mampir ke toko alat tulis. Kupikir kamu bisa pakai.”
Aku menatapnya lama. Bukan karena isi kardusnya, tapi karena upayanya. Karena ia tetap berusaha hadir. Karena ia mengingat hal-hal kecil yang kusukai. Meski aku tidak selalu mudah untuk dipahami.
“Makasih, Dit.”
Radit tersenyum kecil. “Aku pengen kita tetap bareng-bareng walau kamu lagi nemu sayapmu sendiri. Aku juga lagi nyari caraku sendiri buat bertahan. Tapi kalau bisa, kita jalan bareng. Nggak harus buru-buru, tapi juga jangan saling ninggalin.”
Untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, aku merasa tenang. Mungkin kami memang belum sampai di ujung perjalanan. Tapi untuk sekarang, cukup tahu bahwa kami masih mau saling menunggu.


 rosadewiita
rosadewiita