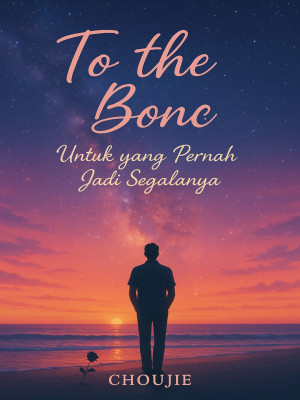Itu adalah awal kepanikanku dan alasan kenapa aku akan melakukan semua ini.
Hari ini, pukul empat sore selepas pulang sekolah, di depan gerbang sekolah, Hortensia Mei, temanku satu-satunya tumbang di hadapanku.
Aku datang membawakan ranselnya yang tertinggal dalam kelas saat dia sedang berjongkok menungguku. Mencurahkan imajinasinya ke dunia nyata dengan menggambar sesuatu tak kasat mata menggunakan ujung rating di permukaan beton yang keras. Dia sedikit lebih dekat dari bayangan gerbang Akademi Riverwood yang jatuh dari atas kepalanya. Wajahnya tampak pucat, tak merona, dan matanya tampak tak fokus sama sekali.
“Kau tidak apa-apa?” tanyaku, mengulurkan ranselnya. Dia agak sempoyongan saat berdiri. Karena itu ranselnya urung kuberikan dan masih kutahan.
“Aku baik,” sahutnya, tapi aku tahu caranya mengatakan adalah kebohongan
“Jangan terlalu memaksa dirimu. Kalau kau tidak sanggup berjalan, aku akan panggilkan taksi.”
“Tidak perlu.” Dia meraih ranselnya, lalu menyampirkannya di pundak. “Aku tidak mau melewatkan ini. Hari ini, temanku yang biasanya tidak pernah mau peduli, akan mengantarku pulang.” Ada semburat warna merah di pipinya saat dia mengatakan itu, lalu mengambil langkah lebih dulu.
Itu memang janjiku. Setelah setengah hari berbaring di ranjang ruang medis sekolah, aku membawakan sepotong roti kesukaannya dan berbincang sebentar, lalu dia menawarkan dirinya untuk kuantar pulang. Memang seperti itu yang terjadi. Sifat gadis itu memang sedikit aneh.
Aku masih di sampingnya saat kami sepuluh meter memunggungi gerbang sekolah dan derap langkahnya tiba-tiba melambat. Dia memegang keningnya dan sempoyongan lagi. Aku bisa melihat jejak keringat yang membasahi dahi dan lehernya, mengilap oleh cahaya matahari petang yang rendah. Aku bahkan belum sempat bertanya keadaannya tapi gadis itu sudah menjatuhkan diri ke arahku. Aku sigap menangkap, memanggil namanya seraya mengguncangkan bahunya berkali-kali, tapi dia tidak memberiku jawaban satu kata pun.
Aku menghubungi ibuku. Dia seorang dokter sebuah klinik di kota. Dengan menahan segala kepanikanku di atas ambulans, akhirnya gadis itu terbaring dengan seragam sekolahnya di ruang rawat inap.
Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku remaja enam belas tahun dengan hormon yang meledak-ledak. Aku bukan siapa-siapa gadis itu, bukan pula saudara. Jadi sudah seharusnya aku bersikap seperti teman sekelas yang mengunjungi temannya yang opname. Mengatakan, “Semoga lekas sembuh,” dengan tampang acuh tak acuh saat melihat selang infus tersambung ke lengan gadis itu. Ataupun, bersikap biasa saja seolah sedang memandangi cuaca, karena bibir gadis itu sekarang sepucat kapur. Akan tetapi, tombol pemicu itu ditekan saat suster yang memeriksa tubuh gadis itu berkata, “Ada luka lebam membiru di bahu dan punggungnya.”
Aku dan ibuku, yang duduk di sofa, bersamaan menoleh ke arah tempat tidur. Ibuku berdiri dan memeriksa. Suster itu bergumam, “Dokter Eliza, luka-luka ini mirip dengan luka-luka dua gadis yang diculik dan diperkosa itu.”
Aku tidak tahu bagaimana dengan berani dia menyimpulkan seperti itu. Padahal tiap hari dia selalu bergelut dalam dunia ilmiah. Tidak bersandar pada opini dan tebak-tebakan semata. Namun akibatnya, seluruh tubuhku terasa disedot dan pijak di bawah kakiku seakan menjeram.
Aku keluar ruangan dan duduk di kursi besi lorong karena mereka akan membuka pakaian gadis itu, memeriksa sekujur badannya. Tak lama, Ibu datang saat pikiranku melayang-layang. Ibu menelungkupkan telapak tangannya di atas punggung tanganku, dan terasa hangat karena jemariku sudah terlalu dingin oleh ketakutan pikiranku sendiri.
“Itu tidak benar,” katanya. “Ibu telah periksa, memang luka dipunggungnya cukup serius, tapi untuk sekarang tidak ada tanda-tanda—“
Ibu menelan kata-katanya dan aku tahu apa lanjutannya. Ibu tidak tahu fakta kalau gadis itu tidak sekolah selama seminggu kemarin dan menghilang di hari yang sama dengan kasus pemerkosaan itu terjadi.
“Ya, semoga,” sahutku. Suaraku lemas, masih bercampur cemas.
“Lebih jelasnya, kita tanya langsung pada Mei setelah siuman nanti.”
Aku tahu Ibu bermaksud menenangkanku, tapi aku tak bisa. Karena itu sekarang, aku berdiri di depan cermin toilet. Menatap separuh bayangan tubuhku yang terpantul. Ditemani oleh suara tetes air yang jatuh dari ujung keran, yang mengalun pelan seperti musik dan membuatku nyaman. Aku bicara padamu, pada pikiranku sendiri seperti orang depresi.
Aku berniat menelusuri ingatku lagi.
Iya. Menurutku juga ini adalah pekerjaan yang sia-sia, sama seperti yang dilakukan gadis itu setiap hari; yang menjaring angin di padang rumput. Benar-benar pekerjaan yang tak berguna. Sudah seperti menunggu bintang jatuh dari langit nun jauh di malam yang kelam. Meski sudah tahu begitu, kurasa ini lebih baik bila dibandingkan menunggu sebongkah kemungkinan palsu jatuh di depan jempol kaki yang ternyata dipenuhi lubang.
Aku tidak ingin berpasrah diri dengan kemungkinan yang dikatakan Ibu.
Aku merasa kalau selama ini ada sesuatu yang telah disembunyikannya, dan itulah penyebab luka-luka di punggung gadis malang itu.
Kata-katanya, caranya tertawa, selama ini, pasti mengandung petunjuk.


 acetonitrile
acetonitrile