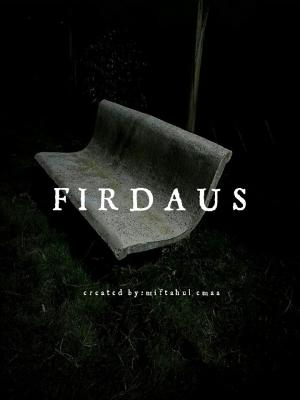Hari itu langit Jakarta tampak seperti hati yang belum siap ditinggal—mendung tapi belum hujan. Di kampus, jam menunjukkan pukul lima sore, dan Aluna masih duduk di bawah pohon ketapang besar dekat fakultas. Bukan karena romantis, tapi karena Wi-Fi kampus lebih cepat di situ, dan baterai HP-nya tinggal dua belas persen. Dua belas persen dan segudang notifikasi yang belum sempat ia buka. Tapi hari ini, notifikasi itu bukan tentang diskon ojek online atau pengumuman rapat organisasi. Salah satu dari notifikasi itu adalah panggilan tak terjawab dari nomor rumah. Ya, nomor rumah. Telepon rumah yang biasanya hanya berbunyi kalau ada tetangga nyasar atau... sesuatu yang lebih serius.
Jantung Aluna berdetak sedikit lebih kencang. Ia menarik napas, lalu menekan tombol panggil ulang.
Drrr... drrr... drrr...
Tiga dering. Empat.
Akhirnya tersambung.
“Halo?”
Suara dari seberang terdengar pelan, agak serak. Itu suara Bapak.
“Pak? Ini Luna.”
“Hm... Luna.” Ada jeda. “Kamu bisa pulang akhir pekan ini?”
Aluna langsung duduk lebih tegak. Hatinya mulai penuh tanda tanya. Bapak bukan tipe yang suka basa-basi. Kalau dia bertanya seperti itu, pasti ada sesuatu yang penting.
“Kenapa, Pak? Ada apa?”
“Pulang aja dulu. Ibu kamu lagi nggak enak badan.”
Aluna terdiam. Ibu. Kalimat itu cukup untuk membuat seluruh dunia yang tadinya sibuk berubah jadi sunyi.
“Nggak enak badan gimana maksudnya?”
“Nanti aja kita cerita pas kamu udah sampai rumah. Jangan panik dulu. Bawa jaket, di rumah lagi sering hujan.”
Dan telepon ditutup begitu saja. Tidak ada salam. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya keheningan yang menggantung, seperti mendung yang belum pecah. Aluna memandangi layar HP-nya yang kini tinggal 8%. Ia merasa ada yang patah di dalam dirinya—sebuah alarm batin berbunyi, mengabarkan bahwa pulang bukan lagi pilihan, tapi panggilan. Kereta ekonomi jurusan Jakarta–Bekasi selalu penuh dengan cerita: ada penjual cilok yang menyanyi lebih merdu dari penyanyi idol, anak kecil yang anteng nonton YouTube, dan ibu-ibu yang ngobrol soal harga cabai naik turun kayak drama Korea. Tapi di tengah semua suara itu, kepala Aluna penuh dengan pertanyaan. Apakah Ibu cuma sakit biasa? Atau... yang lebih dari itu?
Ia membuka galeri foto di HP-nya, mencari foto terakhir bersama Ibu. Ternyata sudah dua bulan lalu, waktu ia pulang lebaran. Di foto itu, Ibu masih senyum. Masih pakai daster bunga-bunga favoritnya. Tapi entah kenapa, saat Aluna melihat foto itu lagi, ada rasa nyesek yang tiba-tiba mampir. Sesampainya di stasiun, ia langsung naik ojek menuju rumah. Sepanjang jalan, langit mendung menggantung seakan menunggu waktu yang tepat untuk menangis. Ia menunduk, melihat jaket yang dibawanya. “Bawa jaket, di rumah sering hujan,” kata Bapak.
Hujan di luar, atau hujan di dalam hati?
Rumah itu masih sama: pagar hijau tua yang berderit saat dibuka, tanaman lidah mertua yang berdiri tegak seperti pengawal, dan bau khas rumah tua—campuran kapur barus dan kenangan masa kecil. Bapak membuka pintu. Wajahnya lebih lelah dari biasanya.
“Assalamu’alaikum, Pak.”
“Wa’alaikumussalam. Cepet banget kamu sampai.”
Aluna memeluknya singkat. “Ibu di mana?”
“Di kamar. Lagi tidur. Capek.”
Mereka duduk di ruang tamu, seperti dua orang asing yang ingin bicara tapi tak tahu harus mulai dari mana.
“Ayah, Ibu kenapa?”
Bapak menghela napas. “Beberapa minggu terakhir Ibu sering pusing. Kami kira tekanan darah. Tapi dua hari lalu, Ibu jatuh di dapur. Sempet pingsan sebentar.”
Aluna merasa dadanya seperti ditindih batu.
“Terus... udah ke dokter?”
“Sudah. Dan hari ini kami dapat hasilnya.”
“Dan?”
“Ibu... ada tumor di kepala. Jinak, tapi harus dipantau ketat.”
Hening.
Aluna hanya bisa menatap ke depan. Matanya perlahan memanas.
“Kalau operasi, katanya masih bisa. Tapi kita butuh waktu, biaya, dan mental yang kuat. Untuk itu, Bapak pikir... kamu harus pulang. Bantu jagain Ibu, ya.”
Air mata Aluna jatuh diam-diam.
---
Malam itu, Aluna masuk ke kamar Ibu. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin dan nafas pelan yang tertidur. Ibu terbaring, wajahnya lebih pucat, rambutnya lebih tipis dari biasanya. Tapi tetap... itu wajah yang selalu membuatnya tenang waktu kecil. Perlahan, Aluna duduk di tepi ranjang. Ia menggenggam tangan Ibu. Dingin. Tapi masih hangat karena cinta yang tidak pernah benar-benar pergi.
“Ibu... aku di sini,” bisiknya.
Ibu membuka mata perlahan, tersenyum kecil.
“Luna... kamu udah datang...”
“Iya, Bu. Maaf telat.”
“Enggak. Kamu pulang tepat waktu.”
Dan malam itu mereka bicara. Bukan tentang tumor, bukan tentang sakit, tapi tentang masa kecil Aluna. Tentang saat dia belajar naik sepeda, jatuh dan menangis, lalu dipeluk Ibu. Tentang waktu Ibu masak sop ayam karena tahu Aluna patah hati pertama kali. Dan tentang hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, tapi kini menjadi alasan Aluna merasa hangat di dunia yang kadang dingin.
---
Keesokan harinya, Aluna duduk di dapur, membuatkan teh untuk Ibu. Ia melihat dinding yang penuh coretan tinggi badan masa kecilnya. Di sana ada tulisan: “Luna umur 6 tahun: tinggi 115 cm”, dan di sampingnya, “Luna umur 10 tahun: 135 cm (masih takut jarum suntik)”. Dapur itu dulu tempat Ibu sering memarahi Aluna karena lupa nyuci piring. Tapi juga tempat di mana Ibu pertama kali memujinya karena bisa masak telur dadar tanpa gosong. Bapak masuk sambil membawa beberapa map berisi hasil cek medis.
“Ayah,” kata Aluna pelan, “Kita bisa atur jadwal dokter bareng-bareng. Aku bisa bolak-balik dari kampus dulu. Tapi kalau Ibu butuh aku tinggal di rumah sementara, aku siap.”
Bapak menatap anak perempuannya. “Kamu yakin?”
Aluna mengangguk. “Pulang bukan cuma soal tempat, kan? Tapi soal tahu ke mana hati harus kembali.”
---
Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Ibu mulai terapi ringan, minum obat rutin, dan setiap pagi, Aluna duduk di sampingnya sambil membacakan koran. Kadang, mereka nonton ulang sinetron lama, tertawa di adegan yang sama. Kadang, mereka hanya duduk diam sambil minum teh. Tapi dalam diam itu, banyak hal terjadi. Luka yang dulu menganga perlahan mengering. Waktu yang pernah terlewatkan perlahan digantikan dengan kebersamaan baru. Dan satu hari, saat sore hampir beranjak malam, Ibu berkata pelan, “Luna, terima kasih ya, udah pulang.”
Aluna tersenyum. “Ibu juga. Terima kasih sudah jadi rumah yang selalu menerima, bahkan saat aku lupa jalan pulang.”


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_