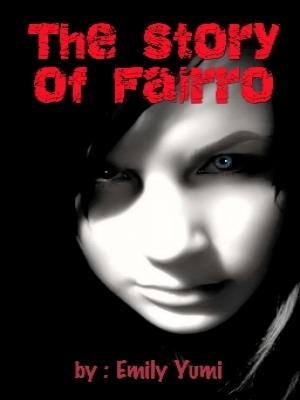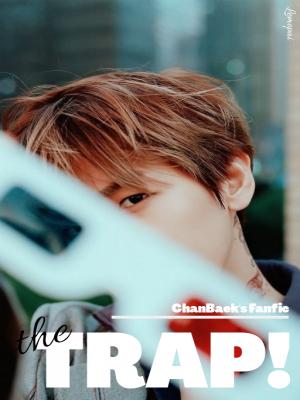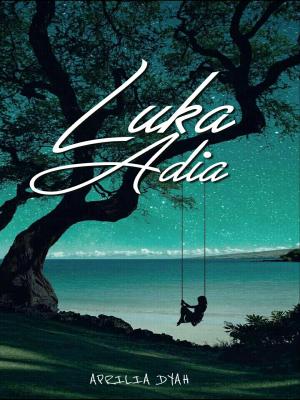Ada satu hal yang tidak diajarkan oleh buku pelajaran, seminar motivasi, atau bahkan dosen favorit di kampus: bahwa saat kamu terlalu lama pergi, rumahmu bisa tetap berdiri, tapi tidak semua di dalamnya akan tetap sama.
Aluna menyadari hal itu pagi ini.
Pagi yang seharusnya biasa—sarapan, suara radio yang masih setia dengan lagu-lagu lawas, dan Ibu yang duduk di meja makan sambil memegang cangkir teh—ternyata terasa berbeda. Bukan karena tidak ada suara, justru sebaliknya. Terlalu banyak suara... di dalam kepalanya.
“Luna, tolong ambilin sendok kecil di rak atas, ya?” suara Ibu pelan, tapi masih hangat.
Aluna berdiri refleks. Tapi saat ia membuka rak, ia tertegun.
Sendok kecil? Rak atas?
Rak itu... sekarang diisi gelas plastik, bukan sendok. Ia keliru.
“Eh, yang itu rak tempat gelas, Bu,” katanya sambil senyum malu. “Aku kira masih kayak dulu.”
Ibu hanya tersenyum lembut. “Sudah tiga tahun kamu nggak tinggal di sini, Luna. Banyak yang udah berubah.”
Tiga tahun. Ternyata waktu sebegitu bisa menggeser banyak hal—letak sendok, warna taplak meja, bahkan posisi pot tanaman di teras. Aluna kembali duduk, canggung dengan dirinya sendiri. Di sekelilingnya tampak familiar, tapi sedikit asing. Ia seperti tamu yang datang ke rumah masa kecilnya, tapi lupa di mana letak kenangan. Setelah sarapan, Ibu masuk ke kamar untuk istirahat. Aluna berjalan ke ruang tengah, membuka lemari tua tempat keluarga mereka menyimpan album foto. Debu tipis menyelimuti permukaan kayu. Ia menyeka pelan, lalu membuka lembaran demi lembaran album. Di sana ada foto kecil dirinya yang masih SD, gigi ompong, rambut pendek, dan senyum terlalu lebar. Di halaman berikutnya, ada foto keluarga saat mereka liburan ke Puncak—wajah bahagia tanpa beban. Dan... di sudut halaman terakhir, ada foto hitam-putih dari Bapak dan Ibu muda, yang berdiri di depan rumah pertama mereka, rumah yang sekarang Aluna duduki kembali. Ia menatap lama foto itu.
Berapa banyak momen yang sudah ia lewatkan? Berapa banyak malam Ibu tidur sendiri saat Bapak lembur? Berapa banyak ulang tahun keluarga yang cuma diwakili dengan ucapan “maaf nggak bisa pulang”?
Waktu itu ia pikir, semua itu bisa ditebus nanti. Tapi “nanti” sering kali berubah menjadi “terlalu lama”.
Sore hari, Aluna duduk di depan rumah sambil menyeduh teh dan melihat jalan kecil yang dulu sering ia lewati naik sepeda. Seorang anak kecil lewat, bersepeda sambil menyanyi. Persis seperti dirinya dulu. Tiba-tiba, tetangga sebelah, Bu Rini, keluar sambil membawa cucian dan melihat ke arah Aluna.
“Luna? Ya ampun, kamu pulang juga akhirnya!” serunya sambil tertawa kecil.
Aluna berdiri, tersenyum. “Iya, Bu. Akhirnya bisa juga pulang.”
“Kamu tuh, ya, lama banget nggak kelihatan. Sampai-sampai Ibu kamu cerita terus, ‘Luna sibuk di kota, kerjaannya numpuk, pulang nanti-nanti.’”
Aluna hanya bisa tertawa lemah. “Hehe, iya, Bu. Maaf ya, saya emang terlalu lama pergi.”
“Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang kamu di sini. Ibu kamu butuh ditemani. Kadang bukan obat yang bikin orang cepet sembuh, tapi kehadiran anaknya.”
Kata-kata itu menempel di kepala Aluna seperti stiker yang susah dicopot. Ia tahu, Bu Rini benar. Setelah mengobrol sebentar, Aluna masuk kembali ke dalam. Ia membuka pintu kamar Ibu dan melihat Ibunya sedang duduk di tepi ranjang, memandangi album foto yang tadi ia tinggalkan.
“Luna, kamu masih simpan foto ini?” tanya Ibu sambil menunjuk satu halaman.
“Iya, Bu. Nggak pernah aku buang.”
Ibu menatap foto itu sejenak. “Itu waktu kamu juara lomba menggambar di TK, kan? Hadiahnya cuma kotak pensil, tapi kamu bangga banget.”
Aluna tersenyum. “Soalnya Ibu datang nonton. Jadi terasa spesial.”
Ibu memegang tangan Aluna. “Kadang kita terlalu sibuk tumbuh, sampai lupa pulang. Tapi rumah ini... selalu ada. Walaupun kamu telat, kami tetap tungguin kamu.”
Air mata Aluna hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia ingin kuat. Untuk Ibu. Malamnya, Bapak duduk di ruang tamu sambil merapikan dokumen-dokumen rumah. Aluna ikut duduk di sampingnya.
“Pak...”
“Hm?”
“Maaf ya, aku terlalu lama pergi.”
Bapak tidak langsung menjawab. Ia menutup map, lalu menatap Aluna.
“Kamu nggak pergi, kamu belajar hidup. Dan itu penting juga. Tapi sekarang kamu pulang, dan itu yang lebih penting.” Aluna menggigit bibirnya. Hatinya seperti diusap perlahan—hangat dan perih sekaligus. “Mungkin aku selama ini takut pulang, Pak. Takut lihat kenyataan di rumah, takut merasa asing, takut merasa bersalah.”
Bapak mengangguk pelan. “Pulang itu bukan soal kembali ke tempat, tapi soal berani hadapi yang pernah kamu tinggalkan.” Malam itu mereka berbincang panjang. Tentang kerjaan, tentang kuliah, tentang cerita-cerita lama yang dulu tidak sempat dibicarakan. Dan di tengah obrolan itu, Aluna menyadari: pulang memang tidak selalu nyaman. Kadang harus canggung dulu, harus diam-diam menangis dulu, harus menyesal dulu.
Tapi setelah itu, pelan-pelan, semuanya mulai terasa utuh kembali.
Keesokan harinya, Aluna memberanikan diri menyapu halaman. Pekerjaan kecil, tapi terasa besar bagi dirinya yang sudah lama tidak menyentuh sapu. Ia mengangkat pot, memotong daun kering, dan mengepel teras sambil memutar playlist lagu-lagu favorit Ibu. Saat ia sedang membersihkan sudut halaman, seorang anak remaja lewat sambil melirik dan berkata, “Eh, Kak Luna, ya?”
Aluna tersenyum. “Iya, kamu anaknya Mbak Tari, ya?”
“Iya! Ibu sering cerita tentang Kakak. Katanya dulu suka ngumpulin anak-anak buat bikin drama-dramaan tiap malam takbiran.”
Aluna tertawa. “Iya, dan kamu pasti masih kecil waktu itu.”
Anak itu mengangguk. “Tapi aku suka denger cerita-ceritanya. Seru banget kayaknya.”
“Dulu seru. Tapi sekarang udah beda. Udah gede, semua sibuk sendiri.”
Anak itu tertawa. “Tapi kalo Kakak mau, bisa bikin lagi. Kami pasti mau ikut.”
Aluna mengangguk pelan. Mungkin, terlalu lama pergi bukan berarti harus terlalu lama menghilang. Masih ada kesempatan untuk kembali... dan membangun ulang yang dulu pernah indah. Sore itu, Aluna duduk di kamar, menulis di jurnal kecil yang selalu ia bawa. Bukan untuk tugas kuliah atau kerjaan, tapi hanya catatan untuk dirinya sendiri:
“Terlalu lama pergi bukanlah kesalahan. Tapi terlalu lama lupa pulang... itu yang bisa menyesakkan. Aku tak bisa memutar waktu, tapi aku bisa memeluk hari ini. Dan mungkin itu cukup.”
Di luar, suara adzan Maghrib berkumandang. Angin sore menyentuh pelan jendela kamar. Dan di dalam hatinya, ada sesuatu yang seperti pintu kecil yang terbuka—sebuah ruang nyaman bernama "rumah", yang selama ini tetap menunggu meski ia tak selalu hadir.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_