Di bawah jam besar Stasiun Centraal, Fabian berdiri gelisah, jaket tipis membalut tubuh tegapnya, sepatu paling nyaman siap melangkah. Senyumnya merekah saat melihat Suci keluar dari trem, meski bayang duka tak sepenuhnya sirna dari matanya.
“Sok-sokan mau naik trem sendiri, padahal berangkat dari rumah bareng kan bisa,” Fabian meledek.
“Biarin, aku mau meresapi pengalaman ini. Supaya berasa pemeran utama di film,” Suci beralasan.
“Gimana? Yakin mau keliling hari ini? Nggak takut capek?” pemuda Amsterdam itu memastikan lagi.
Suci memakai kacamata hitamnya dengan semangat, “Aku nggak ke sini cuma untuk duduk di rumah dan itungin awan. Ayo, aku udah bikin rencana.”
Fabian tersenyum kecil, “Wow, rencana… itu pertanda aku akan dibuat takjub atau dibuat nyasar ya?”
“Mungkin keduanya,” Suci terkekeh sambil berjalan mendahuluinya.
Mereka berjalan berdampingan di kawasan Jordaan. Menelusuri jalan kecil berbatu yang estetik, berpadu dengan rumah-rumah bata merah dengan jendela penuh bunga. Suci menunjuk ke toko roti kecil, lalu menarik Fabian masuk. Mereka membeli stroopwafel hangat dan kopi, lalu duduk di bangku kayu yang rindang tepat di tepi kanal.
“Dulu aku cuma bisa lihat Amsterdam dari layar. Sekarang aku benar-benar di sini, dan ternyata jauh lebih hidup,” Suci berkata takjub.
Fabian menatap riak kanal. “Dulu Oma sering sekali mengajakku ke sini. Kami duduk persis seperti ini, menghitung bebek yang berenang melintas,” bisiknya, suaranya sedikit sendu.
“Sekarang kamu duduk di sini bersama aku. Jadi sekarang aku semacam pengganti bebek nih?” Suci mengernyitkan dahinya.
“Kamu yang bilang ya! Bukan aku,” Fabian tertawa lepas, tawanya yang pertama kali sejak hari pemakaman Oma.
Siang itu di pasar bunga Bloemenmarkt, Suci menatapi indahnya susunan bunga tulip dan lavender.
“Ooh jadi begitu bentuk tulip yang asli,” Suci mengamati lekat-lekat detail bunga itu dari dekat.
“Jangan norak begitu ah, malu,” Fabian memaksanya berdiri tegak lagi.
“Ya aku kan baru pertama kali lihat bunga legendaris ini,” Suci mengemukakan alasannya. Gadis itu kemudian melanjutkan berjalandengan cemberut.
Merasa bersalah, Fabian diam-diam membelikan beberapa kuntum tulip dan lavender kering. Ketika pemuda itu menyodorkannya, Suci tercengang, mulutnya menganga, terpaku oleh kejutan yang tak disangka.
“Hei Suci, kamu kenapa? Kesambet?” Fabian melambaikan tangan di depan wajah Suci yang akhirnya bereaksi.
“Aku terharu, baru kali ini dikasih bunga sama cowok,” ungkap Suci jujur.
Fabian tersipu malu, lalu teringat kejanggalan, “Loh, Tougo?” kemudian ia menutup mulutnya sendiri. “Lupakan lupakan.”
“Ngomong apa tadi Fab?” untunglah Suci tidak mendengarnya.
“Nggak, nggak penting,” pemuda itu menggeleng, lalu mengamati Suci yang kesenangan memegang bunga pemberiannya, meski tidak berbentuk buket yang apik. Diam-diam Fabian memotret Suci yang tertawa riang.
“Kamu… fotogenik juga ya, padahal aku fotoin kamu diam-diam loh!” Fabian mengakui sambil melihat hasil fotonya dengan puas.
“Kamu fotoin aku Fab?” Suci tersipu, “Ya maaf, aku memang terlahir fotogenik, sinematik, artistik,” ia melebih-lebihkan.
“Dan sedikit nyentrik,” Fabian menambahkan sambil mengulum senyum.
Sore itu mereka menyewa perahu kecil. Fabian mengemudikannya dengan tenang, membawa Suci menyusuri kanal-kanal tenang di tengah kota. Cahaya keemasan matahari sore membelai permukaan air, melukis bayangan arsitektur tua yang anggun di sekeliling mereka.
“Fabian, aku nggak bisa menggantikan Oma. Tapi aku harap kamu tahu, kamu nggak perlu berduka sendirian,” Suci tiba-tiba berkata.
Fabian tertegun, ia memandangi air, “Kehilangan ini… terasa jauh lebih ringan… berkat kehadiranmu di sini.”
Wajah Suci merona sejadi-jadinya. Ia menahan senyum kesenangannya dan salah tingkah. “Ada lagi yang bikin ringan,”
Fabian berpaling kepadanya, “Apa?” ia bertanya serius.
“Sambil main ABC lima dasar, yuk! Aku sekalian mau uji kemampuan kosakata bahasa Indonesia kamu,” Suci menyeringai senang.
Fabian menatapnya tak percaya. “Kayaknya baru kamu deh yang ngide main ABC lima dasar di atas perahu!”
Mereka tertawa bersama, tawa hangat yang pecah di tengah tenangnya air kanal.
Mereka berdua mengakhiri jalan-jalan hari ini dengan berdiri di tepi jembatan kecil. Hari sudah malam, lampu kerlap-kerlip menghiasi jembatan itu.
Fabian menyerahkan sepotong stroopwafel terakhir pada Suci, “Kamu datang jauh-jauh untuk aku. Aku belum tahu gimana caranya membalas semua ini.”
Suci menatapnya dengan tatapan kesal, “Kalau kamu masih berpikir mau membalas, artinya kita belum cukup dekat. Kalau begitu, besok kita harus keliling lagi, supaya semakin dekat.”
“Eeh, nggak usah. Nggak jadi!” Fabian mengibaskan tangannya panik. Dia nggak ada capek-capeknya apa ya? herannya di dalam hati. Ia lalu tertawa, tapi tawa itu berhenti ketika pandangannya bertemu dengan mata Suci, sorot matanya berubah. “Mungkin memang… aku cuma butuh alasan untuk membuat kamu bahagia.”
Suci tertegun mendengarnya, ia menunduk, menyembunyikan deru hatinya yang menggempur kesadaran jiwanya. Ia hanya bisa menyembunyikan wajahnya yang memerah dan perasaan hatinya yang semakin berharap balasan. Itu maksudnya apa? pikirnya dalam kekalutan hatinya, bertanya-tanya.
Di bawah temaram lampu Amsterdam, dua siluet itu berdiri, kebersamaan mereka tumbuh perlahan dari benih duka. Kota itu menjadi saksi bisu pertanyaan mendebarkan yang kini bersarang di hati Suci.
Sinar matahari musim panas menyusup masuk lewat jendela besar yang terbuka, menari di permukaan lantai kayu dan permadani Belanda klasik. Aroma teh chamomile dan pai apel panggang memenuhi ruangan. Di tengah ruangan, Suci, Fabian, Mama Fabian, dan Papa Fabian duduk melingkar di sofa empuk, di hadapan meja kayu oval yang kini dipenuhi album foto tua dengan sampul kulit.
Mama Fabian membuka halaman pertama album, memperlihatkan foto seorang bayi montok dengan pipi merah muda yang tertawa lebar.
“Lihat ini… Fabian waktu umur satu tahun. Selalu senang kalau difoto, sampai kita hafal dia selalu tertawa kalau melihat bayangannya sendiri di kaca,” mama Fabian tersenyum bangga, menceritakannya dengan bahasa Inggris yang fasih.
Suci tertawa geli, ia menoleh pada orang yang dibicarakan. “Jadi kamu narsis sejak bayi?”
Fabian meringis, memiringkan tubuhnya sedikit, berusaha menutup album. Untung Papa Fabian dengan cepat menyelamatkannya. “Tunggu sampai kamu lihat dia umur lima tahun. Ada masanya dia yakin bakal jadi penyanyi pop, lalu berdiri di atas meja makan menyanyikan lagu Backstreet Boys dengan sisir sebagai mikrofon,” ia terkekeh.
“Astaga! Aku mau lihat itu, please!” Suci tertawa semakin kencang.
Fabian akhirnya menyandarkan diri di sofa dengan ekspresi menyerah, wajahnya memerah. Tapi matanya menyiratkan senyum kecil yang tak bisa disembunyikan.
“Aku yakin kalian sengaja melakukan ini untuk mempermalukanku di depan tamu,” ia bersungut-sungut manja.
“Suci bukan tamu, dia datang jauh-jauh untuk kamu. Dia pantas tahu segalanya,” mama Fabian menatap Suci lembut sambil sesekali melirik putranya.
Suci menunduk sedikit, pipinya bersemu merah. Ia tersenyum, namun dalam hatinya terasa hangat. Ini adalah keintiman keluarga yang belum pernah benar-benar ia rasakan. Ia melirik Fabian yang kini sedang berusaha merebut album dari tangan ayahnya sambil tertawa setengah malu.
“Aku senang bisa mengenal Fabian lebih dalam, bahkan bagian-bagian yang dia coba sembunyikan,” gadis itu berkata lembut.
Mama Fabian lalu menunjukkan foto Fabian kecil dengan dua gigi depan ompong, memakai mantel kebesaran dan sepatu bot karet.
“Oh ya, ini waktu dia nyasar ke kebun tetangga karena mengejar tupai. Akhirnya malah menangis karena takut tupainya marah,” papa Fabian membocorkan.
“Oke, cukup nostalgia hari ini. Mari kita bahas prestasiku sebagai mahasiswa arsitektur, bagaimana?” Fabian berusaha menyelamatkan harga dirinya.
Suci hanya bisa tertawa. Saat ia duduk di antara mereka, mendengar suara tawa dan percakapan ringan itu, ia merasa seakan tersedot masuk ke dalam dunia hangat dan penuh kasih.
Di tengah tumpukan foto dan riuh tawa yang bersahutan, Suci perlahan menyadari: ada sebuah tempat, lebih dari sekadar negeri asing, jauh melampaui sekadar penghiburan dalam duka. Kehangatan itu meresap pelan ke dalam sanubarinya, sebuah kehangatan yang lahir dari satu hal sederhana—keluarga yang menerima dirinya seutuhnya, bahkan tanpa ia pernah memintanya.
Langit Amsterdam berwarna oranye keemasan, matahari musim panas mulai condong ke barat. Di halaman belakang rumah keluarga Meijer, aroma daging panggang, sayuran bakar, dan mentega menguar dari panggangan bulat hitam besar. Di sisi meja kayu panjang, bunga hortensia biru dan putih tertata dalam toples kaca bening. Sebuah radio tua memutar lagu-lagu jazz lembut.
Papa Fabian sedang membolak-balik daging dengan celemek bergambar sapi. Mama Fabian menata salad dan minuman ke atas meja piknik. Di sisi lain halaman, Fabian dan Suci tertawa kecil sambil membantu menyiapkan alat makan, tangan mereka beberapa kali bersentuhan, lalu saling curi pandang.
Mama Fabian tersenyum hangat dan mendekati Suci, “Kami tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, Suci. Kamu datang seperti cahaya. Oma pasti akan senang melihat Fabian tidak sendirian.”
Suci menunduk sebentar, matanya berkaca-kaca namun tetap menyunggingkan senyum. “Saya cuma ingin memastikan dia baik-baik saja. Dan saya juga beruntung bisa mengenal kalian semua.”
Fabian menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke langit, menahan gelombang perasaan yang masih sulit ia uraikan.
“Ayo ke sini, panggangan sudah siap. Siapa yang sampai terakhir, harus cuci piring nanti malam!” seru Papa Fabian dari arah panggangan.
Mereka tertawa. Suci melirik Fabian, lalu berlari kecil menuju panggangan. Fabian menyusul sambil menggoda, “Aku paling cepat kalau menyangkut makanan loh!”
Mereka berkumpul di bawah cahaya senja, makan bersama sambil membagikan kenangan tentang Oma. Tawa perlahan menggantikan duka. Fabian sesekali mencuri pandang ke Suci yang duduk di samping Mamanya, tertawa lepas sambil mencicipi jagung bakar. Hatinya yang sempat hancur kini menemukan serpihan-serpihan hangat yang mulai merekat, membentuk kembali harapan baru.
Saat malam turun, lampu bohlam taman dinyalakan. Angin membawa aroma bakaran dan tawa yang ringan. Di antara kepulan asap panggangan dan denting gelas minuman musim panas, duka perlahan larut dalam kehangatan. Dan di sanalah Suci, duduk di tengah mereka, tidak sekadar tamu dari negeri jauh, tapi cahaya baru yang tak seorang pun tahu mereka butuhkan.
-oOo-
Ruang kerja Widuri sudah temaram, wanita tua itu duduk di kursi rotan besar dengan selimut di pangkuan. Anya berdiri di hadapannya, gelisah menggenggam tabletnya.
“Nek, aku tahu reputasiku rusak akibat masalah kemarin. Aku juga terima kalau disuruh ke luar negeri dalam waktu lama. Tapi untuk kali ini, tolong dengarkan aku,” Anya meminta perhatiannya.
“Kamu nggak bosan memfitnah orang yang lebih baik darimu, Anya?” Widuri menanggapi dingin.
Anya menahan emosinya, ia menyalakan tablet. “Aku nggak minta dipercaya, tapi Nenek lihat dulu, dari dulu aku curiga Suci orang sisipan di perusahaan, karena kemampuannya di atas kewajaran. Sampai aku menemukan bukti ini. Suci bertemu diam-diam dengan orang dari Arsikonserva dan PT Cipta Agra Konstruksi, perusahaan saingan kita,” Anya mengungkapkan. “Suci mendekati Nenek bukan karena tulus, tapi karena memang sudah ditargetkan untuk mengintai. Pantas informasi internal perusahaan kita bocor ke RumahWaktu.”
Widuri tertegun, lalu melirik tabletnya sekilas meski masih skeptis pada penilaian cucunya itu. “Video bisa direkayasa, apalagi olehmu. Aku cuma perlu bukti konkret, hitam di atas putih!” ucapnya, meski dalam hati khawatir tuduhan itu benar.
Anya bertekad, “Kalau begitu izinkan aku membuktikannya. Tapi tolong fasilitasi aku untuk menjebaknya agar dia perlihatkan siapa dia sebenarnya. Kalau aku salah, aku sendiri yang meminta maaf padanya.”
Widuri menyipitkan mata curiga, “Oke, lakukan seperlunya. Kalau kamu berani macam-macam, bukan Suci yang saya usir dari hidup saya, tapi kamu.”
“Terima kasih, Nek,” Anya membungkuk singkat, lega dengan dukungan Widuri.
“Jadi apa yang kamu butuhkan?” Widuri menanyakan, membuat Anya menyunggingkan senyum.
-oOo-
Bandara Schiphol pagi itu sudah ramai dengan hiruk-pikuk para pelancong maupun pendatang, serta petugas bandara yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mama dan papa Fabian mengantar Suci dan Fabian hingga ke depan pintu keberangkatan, penuh haru.
“Fabian, jaga Suci yang benar. Dia anak baik,” pesan mamanya sambil menyelipkan sesuatu ke kantung jaket Fabian.
“Mama, bukannya khawatirkan aku, malah khawatirkan anak orang lain,” Fabian membuat-buat mulut manyunnya. Semua tertawa melihat gelagat manjanya. “Aku paham itu, nggak perlu diingatkan lagi,” ia menambahkan.
“Jaga diri kamu Fabian, jangan menodai wanita yang tidak boleh dirusak!” papanya menyiratkan pesan.
“Papa! Tolong pikirannya dijaga,” Fabian kesal dengan kecurigaan papanya.
Mereka tertawa melihat kekesalan Fabian. Lalu saling berpelukan, memuaskan rasa rindu yang nanti akan kembali menyerang. Tampak sekali Suci sudah sangat disayang keluarga itu, dari pelukan hangat dan kecemasan yang tampak di raut wajah kedua orang tua Fabian.
Suci dan Fabian melambaikan tangan dengan berat hati ketika memasuki gerbang keberangkatan. Mereka menunggu pesawat di bangku tunggu berdua. Fabian beranjak ke toko roti terdekat, membeli beberapa roti untuk mengganjal perut, sementara Suci tetap duduk di bangkunya, menjaga tas mereka. Sambil menunggu antrian untuk membayar, Fabian merogoh kantong jaketnya. Ia menemukan kotak cincin yang familiar, dari Mama. Ia mengeluarkan kotak itu dan membukanya, berisi cincin dengan rubi merah berbentuk apel warisan keluarganya, senjata untuk melamar calon istri, tapi kali ini ia tak protes. Ia justru tersenyum.
Suci dan Fabian kembali duduk bersama, sambil bersenda gurau mereka menikmati rotinya di keramaian ruang tunggu yang semakin penuh.
Suara pengumuman terdengar membacakan nomor penerbangan keduanya, tanda mereka harus memasuki pesawat. Saat berjalan menuju pesawat, Fabian meraih tangan Suci dan menggandengnya. Membuat Suci tersentak dipenuhi kebingungan, ia melirik wajah Fabian, berusaha menangkap maksudnya.
“Supaya nggak ketinggalan,” Fabian beralasan, meski wajahnya ternyata bersemu kemerahan. Suci mengulum senyum. Mengikuti saja langkah kaki jenjang itu dengan hati berdebar penuh harap.
Di dalam pesawat keduanya duduk berdampingan, mereka sibuk bercerita, mengisi waktu berdua selama perjalanan 18 jam di udara. Setelahnya mereka menonton film bersama dari layar di depan bangku mereka. Setelah lelah berbincang dan bosan menonton, Suci memejamkan matanya. Fabian melirik Suci yang telah masuk ke alam mimpi. Ia selalu menikmati momen seperti ini, diam-diam mengamati lekuk wajah gadis tropis itu. Selalu kagum dengan kulit kecokelatannya yang bersinar sehat. Tanpa sadar Suci menyandarkan kepalanya ke bahu Fabian, lagi. Fabian hanya menahan senyum geli. Kebiasaan! pikirnya lucu, tapi tetap merasa nyaman.
Pada akhirnya Fabian ikut tertidur. Mereka saling bersandar, kepala mereka bertumpu satu sama lain, membuat pemandangan ini semakin menenangkan hati. Pramugari yang melihat mereka hanya tersenyum sambil menyelimuti keduanya.
Suci dan Fabian tiba di Bandara Soekarno Hatta keesokan harinya. Mereka turun dari pesawat dengan kembali bergandengan. Fabian tampak protektif menjaga Suci agar tidak jatuh atau ketinggalan. Suci mencari koper bawaan mereka di ban berjalan, sementara Fabian membawakan troli. Mereka bergotong royong memuat koper dan tas-tas bawaan mereka ke troli, memastikan tidak ada yang kurang. Lalu mereka pun keluar dari gerbang kedatangan berdua.
“Kita pulang ke Bogor langsung nih?” Fabian memastikan.
“Maaf, Fabian. Sepeertinya aku mampir ke rumah Kak Surya dulu deh. Kangen sama keponakan, sekalian kasih oleh-oleh buat mereka juga,” Suci memberitahukan.
“Oh begitu. Mau kutemani?” pemuda Amsterdam itu menawarkan.
“Nggak usah, di Bogor kamu punya banyak kerjaan yang menunggu kan?” tebak Suci tepat sasaran, membuat Fabian terpojok. “Aku naik taksi online aja, bisa kok. Nih lagi aku pesan,” ia memberitahu.
“Oke, kalau begitu aku tungguin mobil kamu datang,” Fabian bersikeras.
“Nggak usah, kamu pakai mobil travel kan? Sana, nanti keburu penuh!” Suci mendorongnya menjauh.
“Jadi kita pisah di sini, nih?” Fabian ragu, separuh hatinya menolak.
“Iya, aku kan bisa diandalkan. Independent woman!” Suci menenangkan Fabian dengan senyum tengilnya.
Fabian akhirnya menyerah, melambaikan tangan ke Suci, masih sedikit khawatir. Meski ia tahu Suci terbiasa mandiri, hatinya tetap tidak tenang.


 serenarara
serenarara 



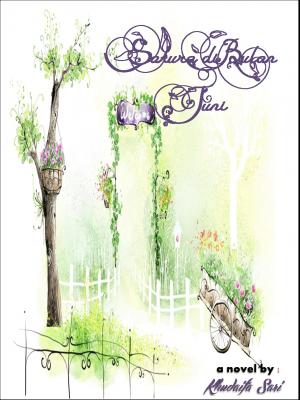








Menarik
Comment on chapter PrologSelalu penasaran kedepannya