Bukan dunia yang berubah warna, tapi aku yang kehilangan kemampuan untuk merasakannya.
**
Hari-hari belakangan terasa seperti salinan satu sama lain. Aku bangun, mencuci muka, mandi, mengganti baju, berangkat kuliah. Duduk di studio atau kelas, mencatat, menggambar, pulang. Semua berjalan sebagaimana mestinya, tapi entah sejak kapan, tidak ada satu pun yang terasa benar-benar bermakna.
Langit pagi tetap biru. Suara burung tetap terdengar dari pohon depan rumah. Tapi tidak ada yang membuatku berhenti sejenak untuk memperhatikan. Bahkan kopi yang biasanya bisa sedikit menyegarkan pikiranku, kini hanya terasa pahit dan hambar di lidah.
Aku tetap menggambar. Tanganku tetap bergerak di atas kertas. Tapi rasanya seperti sedang meniru diriku sendiri, menjalankan rutinitas tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Dan yang paling aneh… aku tidak sedih. Aku juga tidak marah. Aku hanya... tidak apa-apa. Terlalu tenang. Terlalu kosong.
Di kampus, cahaya matahari siang menembus kisi jendela studio, menciptakan bayangan-bayangan tegas di lantai yang dingin. Suasana ramai, teman-teman sekelasku sibuk berdiskusi, tertawa, sesekali mengeluh tentang revisi atau dosen yang terlalu banyak memberi tugas. Suara mereka menyatu menjadi dengungan latar yang tidak benar-benar kupahami.
Aku duduk di pojok meja panjang, mengarsir pelan sketsa yang sudah kering dari semalam. Tanganku bergerak, tapi pikiranku kosong. Dita duduk di seberang, mulutnya sibuk menceritakan sesuatu tentang acara pameran tugas akhir kakak tingkat.
“Eh, kamu mau ikut nonton gak nanti sore? Biar refreshing dikit,” tanyanya sambil memutar pulpen di jarinya.
Aku menoleh sebentar, tersenyum kecil. “Nggak deh. Mau nyicil tugas yang ini dulu.”
“Yakin? Padahal kamu dulu yang paling antusias kalo ada pameran beginian.”
Aku hanya mengangguk. “Males aja sekarang. Capek.”
Dita menatapku beberapa detik. Tidak bertanya lebih lanjut, tapi senyumnya mengendur sedikit, seperti menahan sesuatu.
“Oh iya,” katanya kemudian sambil membuka ponsel, “kamu masuk tim desain buat pameran lintas jurusan bulan depan, kan?”
Aku menoleh pelan. “Hah?”
“Katanya nama kamu dicantumin. Bu Ratih yang masukin. Bagian layout dan konten promo digital.”
Aku mengangguk kecil.
“Gede loh event-nya. Kerja sama tujuh jurusan, kayaknya bakal rame. Banyak tamu dari luar juga. Ada pameran karya, instalasi interaktif, talkshow, booth makanan, bahkan ada konser segala.”
Aku hanya diam. Dita tampak bersemangat saat bicara, tapi rasanya suaranya menggema saja di sekelilingku. Informasi itu masuk ke telinga, tapi tidak menetap. Aku tidak tahu harus merespons apa. Tidak senang, tidak gelisah, tidak bangga. Hanya tahu bahwa sekarang ada satu daftar tambahan yang harus kupikirkan, dan itu saja sudah cukup membuat napasku terasa pendek.
“Kalau kamu nggak bisa, bilang aja ya,” kata Dita. “Tapi kayaknya semua udah fix, sih.”
Aku mengangguk lagi. Tidak janji, tidak menolak. Hanya mengangguk, karena itu hal paling mudah kulakukan akhir-akhir ini.Top of FormBottom of Form
Saat istirahat, aku membeli kopi kaleng dari vending machine dekat tangga. Biasanya, itu jadi penyemangatku. Tapi hari ini, rasanya hambar. Aku menyesapnya dua kali, lalu membuang sisanya ke tempat sampah.
Aku sempat duduk di bangku taman kampus, mencoba memejamkan mata, membiarkan angin lewat di wajah. Tapi bahkan udara segar pun tidak membuat dadaku lebih ringan. Tidak ada yang terasa salah... tapi juga tidak ada yang terasa benar. Seperti layar monitor yang kehilangan saturasi, semuanya ada, tapi tak ada warna.
“Ra, kamu ngelamun ya?” Seorang teman lain menepuk pundakku sambil lewat. Aku mengangguk cepat dan hanya memasang senyum refleks.
Setelah itu, aku kembali ke studio. Duduk lagi. Menggambar lagi. Tapi tidak ada satu pun garis yang terasa penting hari ini. Pensil di tanganku bergerak otomatis. Lengkungan demi lengkungan, bayangan demi bayangan. Tekniknya tepat, presisinya cukup. Tapi hatiku tak ikut serta.
Aku berhenti sejenak, menatap kertas. Ada sketsa bangunan setengah jadi, gaya brutalist dengan kontras garis tebal dan bidang bayangan. Biasanya aku bangga pada detail seperti ini, tapi kali ini... aku hanya menunduk. Kertas itu terasa kosong meski sudah penuh.
Aku mencoba memutar lagu dari ponsel, sesuatu yang biasanya menemaniku menggambar. Tapi bahkan lagu favoritku terdengar datar. Seperti suara latar yang terlalu sering diputar, sampai kehilangan makna. Aku mematikan musiknya. Menarik napas. Menggambar lagi. Menghapus. Menggambar. Menghapus lagi. Tak ada satu pun garis yang terasa benar. Atau mungkin, aku yang sudah tak tahu lagi, bagaimana rasanya merasakan.
Kepalaku mulai berdenyut. Bukan nyeri tajam, tapi berat, seperti beban yang tak punya asal usul jelas. Tanganku gemetar halus saat kuangkat botol minum ke mulut, tapi kutahan agar tak terlihat. Di sekelilingku, suara-suara terus berputar. Tapi aku seperti berada di dalam ruangan kaca: melihat, tapi tak benar-benar terlibat.
Aku menoleh ke jendela. Langit masih cerah. Tapi semuanya terasa jauh. Aku mencoba tersenyum pada diri sendiri. Hanya agar tahu aku masih bisa. Tapi bahkan itu pun... terasa asing di wajahku.
Dalam kekosongan yang semakin melanda, waktu terus bergulir tanpa harus meminta izin. Langit mulai berganti warna ketika aku keluar dari gerbang kampus. Langkah kakiku terasa seperti formalitas, satu-satunya alasan aku bergerak hanyalah karena harus.
Perjalanan pulang terasa seperti lorong panjang yang tak pernah selesai. Di dalam angkot, aku duduk diam sambil menatap jendela. Lalu lintas sore padat, tapi pikiranku tetap sepi. Suara klakson, hiruk-pikuk penumpang lain, semuanya lewat begitu saja, seperti gema di tempat kosong.
Begitu sampai di depan rumah, langit sudah gelap. Lampu teras menyala. Aku membuka pagar dengan hati-hati, mendorong pintu, dan masuk ke dalam rumah yang senyap. Mama ada di dapur. Suara sendok beradu dengan piring terdengar pelan. Aku menaruh sepatu dengan rapi, menggantung ransel, lalu berjalan pelan ke arah dapur.
“Udah makan?” tanya Mama tanpa menoleh. Suaranya lembut, tapi seperti keluar dari kaset lama, mengulang rekaman yang sama.
Aku menggeleng, lalu sadar dia tak melihat. “Belum. Tapi nggak terlalu lapar, Ma.”
Mama menoleh sebentar. Pandangannya singgah di wajahku, lalu turun ke tangan dan bahuku. “Mukamu pucat. Masih banyak tugas, ya?”
Aku mengangguk pelan. “Iya.”
Mama menyendokkan nasi ke piring. Lalu telur dadar hangat dan sayur bening. “Makan dikit, ya. Biar kuat.”
Aku duduk. Makan. Mengunyah perlahan. Tekstur makanan terasa, tapi rasanya kabur.
“Ada yang seru di kampus?” tanya Mama lagi, seolah berusaha membuka ruang bicara.
Aku menatap piringku. Lama. “Nggak ada, sih,” jawabku akhirnya. “Biasa aja.”
Mama tak bertanya lagi. Hanya mengangguk. Mengelap meja. Lalu duduk di seberang, memandangku tanpa berkata-kata. Dan aku hanya terus mengunyah. Bukan karena lapar. Tapi karena tahu… aku harus tetap terlihat seperti anak yang baik-baik saja.
Setelah selesai, aku mencuci piring sendiri. Lalu pamit naik ke kamar. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Punggungku membungkuk, tangan menggenggam ponsel. Kugulir layar perlahan, membuka galeri, lalu folder ‘inspirasi’. Biasanya, di sinilah aku mencari ide untuk menggambar. Tapi malam ini… tak ada satu pun gambar yang menarik perhatianku.
Gambarnya bagus, aku tahu itu. Tapi perasaan yang biasa muncul, seperti rasa kagum, rasa tertantang untuk mencoba, atau sekadar senang melihat estetika, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya pandangan kosong dan napas panjang. Kukunci ponsel dan meletakkannya di meja.
Kupikir menggambar bisa membantu. Maka kubuka map besar berisi sketsa-sketsa lamaku. Karya yang pernah kubanggakan, kususun rapi dan kuberi tanggal. Tapi saat kubuka satu per satu… aku hanya merasa asing. Seperti bukan aku yang menggambarnya. Seperti melihat hasil kerja orang lain, yang hebat tapi jauh.
Kututup map itu perlahan, menekannya dengan kedua tangan agar benar-benar rapat. Aku melirik rak buku. Ada novel yang belum selesai kubaca, padahal dulu aku menantikannya. Kutarik bukunya, kubuka halaman terakhir yang kuingat, lalu kubaca satu paragraf. Dua. Tiga.
Tapi tiap kalimat hanya lewat. Tak ada yang tertinggal di kepala.
Kulemaskan tangan dan menutup bukunya. Diam. Lama. Tak ada dorongan untuk membuka halaman berikutnya. Bahkan ketika kuputar lagu dari playlist favoritku, rasanya seperti mendengarkan suara acak tanpa makna. Padahal lagu itu pernah membuatku ingin menari di tengah malam. Kupeluk lututku, lalu duduk diam di lantai, punggungku kusandarkan ke ranjang.
“Apa yang sebenarnya terjadi,?” gumamku pada diri sendiri.
Aku tahu aku lelah. Tapi ini bukan hanya tentang kelelahan. Ini lebih seperti… kehilangan kemampuan untuk merasakan hal-hal yang dulu membahagiakan. Kupikir ini akan berlalu. Kupikir ini cuma efek samping dari tekanan tugas, kurang tidur, dan semua rutinitas kampus. Tapi semakin lama, yang kurasakan justru sebaliknya, bukan sekadar lelah, tapi juga kosong. Dan aku benci kosong yang diam-diam tumbuh dari dalam.
Aku merasa seakan ruang di sekelilingku semakin merenggang. Aku menunduk, mencoba menulis di buku catatan, tapi tangan terasa kaku. Pensil terasa berat, seperti benda asing yang aku coba genggam. Sesekali mataku melirik jam di dinding, sudah hampir tengah malam, tapi sepertinya tidak ada yang ingin kulakukan.
Tiba-tiba, terdengar suara pintu dapur dibuka. Aku tahu itu Mama. Langkahnya pelan, seolah ragu untuk mengganggu. Tak lama, suara ketukan ringan terdengar di pintu kamarku yang sedikit terbuka.
“Nara, ini air hangatnya Mama taruh di meja, ya,” ucapnya sambil masuk setengah badan ke dalam kamar, membawa gelas kecil. Uap tipis mengepul dari air yang ia letakkan di sisi meja belajarku.
Aku hanya mengangguk, tak menoleh. Tanganku masih menggenggam pensil, tapi ujungnya tak bergerak sedikit pun di atas kertas. Mama diam sejenak. Aku bisa merasakan tatapannya: hangat, khawatir, tapi tak tahu harus berkata apa.
“Kalau capek, jangan dipaksakan, ya,” katanya akhirnya. Suaranya seperti bisikan yang ditelan temaram kamar.
Aku menjawab dengan gumaman pelan, bahkan tidak yakin terdengar. Mengucap terima kasih pun rasanya terlalu jauh dari jangkauan. Mama masih berdiri beberapa detik di sana, lalu perlahan keluar dan menutup pintu kembali. Aku menatap gelas air hangat itu lama. Tidak menyentuhnya, tidak meminumnya. Hanya menatap. Seperti semua hal belakangan ini, ada di dekatku, tapi tak benar-benar bisa kuraih.
Aku duduk kembali di tepi ranjang, menatap dinding kamar yang sepi, berharap menemukan sesuatu yang bisa menggugah perasaan. Tapi yang ada hanya hening, hampa, dan kelelahan yang semakin dalam. Tangan yang tadi kuanggap kuat, sekarang terasa kaku, tak mampu bergerak mengikuti kehendak hati. Tapi meski tubuhku lelah, pikiranku masih terus berputar, berulang-ulang.
Ponselku berbunyi lagi. Dita mengirim pesan tentang tugas yang harus segera diselesaikan. Aku melirik layar, segera ku balas. Tapi rasanya belum cukup, pikiranku terhenti di satu hal: tombol ‘kirim’ di ponselku belum aku tekan, meski sudah dua kali aku mengetik balasan. Keinginan untuk mengirim pesan itu terasa konyol, tapi aku tetap memeriksanya lagi, pastikan aku tidak salah ketik, bahwa kalimatnya sudah benar. Aku kembali membaca pesan itu, lagi dan lagi.
Aku menaruh ponsel ke meja dan meremas tangan. Sesekali, jari-jari kakiku bergerak tanpa sadar, mengetuk-ngetuk lantai kamar, ritme yang sama berulang-ulang. Aku tahu itu hanya satu cara untuk membuat tubuhku merasa lebih nyaman, lebih terkontrol, lebih aman. Tapi di sisi lain, hatiku kosong. Terlalu kosong.
Aku tahu aku harus tidur, tapi rasa kantuk pun seperti ditelan kekosongan malam. Aku berusaha merapikan selimut, memastikan semuanya berada di tempatnya. Ku periksa pintu kamar beberapa kali, memastikan semuanya aman. Tanganku bergerak otomatis, meski pikiranku berteriak meminta istirahat.
Namun aku tahu, aku tidak bisa hanya berdiam di sini, terjebak dalam rutinitas kosong ini, tanpa merasa apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini, atau siapa yang bisa membantuku. Tapi aku juga tahu, aku harus mencoba sesuatu, apa pun itu.
Di tengah keheningan yang menekan, ada satu hal yang mulai terasa lebih jelas daripada sebelumnya: aku tidak bisa terus begini. Aku ingin mencoba beranjak dari sini, keluar dari perasaan yang terus mengulang-ulang ini. Tapi ada sesuatu yang mencegahku, seperti jari-jari ini yang terus mengetuk lantai, atau perasaan harus mengecek ponsel lagi. Tapi, entah mengapa, dalam keheningan malam itu, aku merasa ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah semuanya.


 bunca_piyong
bunca_piyong

















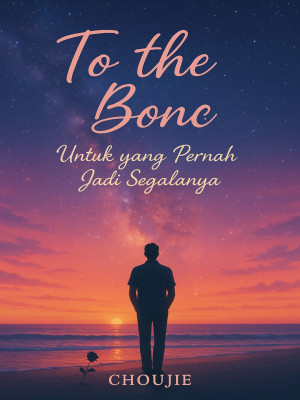
Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .