Ada palu yang akan diketuk. Tapi sebelum itu, ada luka yang akan dibuka. Hari ini bukan soal siapa yang salah. Tapi siapa yang cukup kuat untuk berdiri, bahkan ketika kebenaran tak berpihak. Apa pun yang terjadi, hidup terus berjalan. Mungkin tak semua bisa diselamatkan, tapi selalu ada ruang untuk menebus, untuk berubah, dan untuk tidak menyerah.
**
Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya—bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang menggantung di udara, tak kasat mata. Matahari memang sudah tinggi, sinarnya menembus tirai jendela, tapi tak cukup kuat untuk mengusir hawa dingin yang diam-diam bersarang di ruang perawatan Bara.
Kami duduk bertiga: aku, Mama, dan Papa. Tak banyak bicara. Hanya suara mesin infus dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Bara bersandar lemah di tempat tidurnya, wajahnya pucat, selimut ditarik rapat hingga ke dadanya. Matanya menatap langit-langit, tapi tak benar-benar melihat. Seolah ia sedang jauh dari tempat ini, tenggelam dalam pikirannya sendiri.
Lalu terdengar ketukan di pintu. Seorang suster masuk lebih dulu, lalu memberi kode halus. Dua pria menyusul di belakangnya. Pakaian mereka rapi. Salah satunya membawa map, yang satunya lagi membawa sebuah tas kecil berisi peralatan rekam.
“Selamat pagi. Kami dari unit kecelakaan lalu lintas Polres. Kami di sini untuk mengambil keterangan awal dari saudara Bara Wicaksana terkait insiden yang terjadi hari Jumat lalu.” Kata salah satu dari mereka, nada bicaranya tenang, netral.
Mama menegang. Papa berdiri, mencoba tetap sopan. Bara hanya mengangguk kecil.
“Saya bisa lanjut bicara di sini, atau saudara Bara minta sedikit privasi,” tanya petugas itu pelan.
“Biar saya di sini, keluarga saya boleh dengar” jawab Bara cepat.
Mereka duduk. Mikrofon kecil diletakkan di atas meja dekat tempat tidur. Lalu satu pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan—tenang, prosedural, tapi menusuk.
Jam berapa kamu berkendara? Apa kamu sempat mengantuk? Sudah berapa jam kamu tidak tidur? Apakah kamu dalam tekanan atau pengaruh obat tertentu?
Bara menjawab semuanya dengan jujur. Tidak mencoba membela diri. Tidak membelokan fakta. Hanya menunduk dan menjawab.
Aku bisa melihat matanya mulai memerah, tapi dia tidak menangis. Dia menjawab seperti seseorang yang siap menerima apa pun yang datang setelah ini.
Setelah hampir tiga puluh menit, sesi itu selesai. Salah satu petugas menutup mapnya dan berkata, “Untuk sementara, Saudara Bara akan diminta wajib lapor setelah kondisi medis memungkinkan. Kami juga akan melanjutkan proses sesuai hasil penyelidikan. Akan ada pemberitahuan resmi dalam beberapa hari ke depan.”
“Apakah... apakah dia akan ditahan?” tanya Mama, nyaris berbisik.
Petugas menatapnya lama, lalu menjawab hati-hati, “Kami tidak bisa memastikan sekarang, Bu. Tapi kami akan mengikuti prosedur yang ada.”
Mereka pamit. Ruangan kembali sepi. Bara menunduk, lama. Lalu dia berkata, pelan sekali, “Ra... aku beneran ngebunuh orang?.”
Aku memegang tangannya erat. “Belum tentu Bang, semuanya masih dalam tahap pemeriksaan. Gak usah terlalu merasa bersalan, kamu masih punya waktu buat bertanggung jawab.., dengan cara yang benar.”
Bara hanya diam, tapi dalam diamnya, aku tahu. Ini akan jadi perjalanan panjang yang sulit untuk dilewati.
Sehari hari setelah pemeriksaan awal itu, Bara diperbolehkan untuk pulang. Tapi.. di hari yang sama pula nama Bara mulai muncul di berita lokal. “Mahasiswa Tabrak Kendaraan Lain, Satu Meninggal Dunia.” Ada foto mobilnya yang ringsek. Ada nama lengkapnya. Dan ada komentar-komentar yang menusuk hati.
“Anak pejabat mana lagi yang mau lolos dari tanggung jawab?; Kalau nggak sanggup nyetir, jangan maksa; Berapa nyawa lagi harus melayang karena anak-anak yang cuma tahu kuliah di kertas?” Aku membaca semuanya diam-diam, di pojok ruang keluarga, dengan layar ponsel yang kuturunkan tiap kali Mama lewat.
Papa mulai jarang bicara. Sejak kejadian itu, ia lebih sering duduk diam di teras belakang, memandangi langit yang tak menjawab apa-apa. Tatapannya kosong, seperti mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu bentuknya. Mama sibuk dengan telepon, menjawab pertanyaan keluarga jauh yang mendadak merasa dekat. Pesan-pesan dari tetangga pun berdatangan. Katanya prihatin, tapi nadanya seperti menusuk, penuh rasa ingin tahu yang dibungkus empati setengah matang.
Sementara Bara.., dia hanya bisa mengurung diri di dalam kamar. Pintunya tertutup rapat, seolah memisahkan segalanya—dunia luar, kami, dan dirinya sendiri. Setiap kali Mama mengetuk dan mengingatkan untuk makan, tak pernah ada jawaban. Setiap kali aku lewat di depannya, tak ada suara, hanya bayangan lampu yang menyala dari celah bawah pintu.
Malam itu, dari balik pintu kamar, kudengar suara tangis Mama. Pelan, teredam, tapi cukup untuk membuat dadaku ikut nyeri. Papa mematikan televisi tepat saat berita malam mulai menayangkan cuplikan tentang “kasus kecelakaan mahasiswa tingkat akhir.” Dan aku… duduk sendiri di meja makan, hanya ditemani detik jam dinding dan denting sendokku sendiri. Rumah kami memang tak pernah benar-benar ramai, tapi malam itu… sunyinya terasa lain. Sunyi yang menggantung di udara. Sunyi yang memantulkan semua hal yang tak sanggup kami ucapkan.
Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari teman sekolah: “Ra, itu Abangmu ya yang kecelakaan? Di berita rame banget.”
Aku menatap pesan itu lama. Jemariku ragu ingin membalas, tapi rasanya tak ada kata yang tepat. Bukan karena aku malu, melainkan karena aku sendiri tak tahu harus berkata apa. Kudengar langkah kaki pelan dari ruang tamu. Mama muncul, matanya sembab. Dia duduk di sebelahku tanpa berkata-kata. Hanya menatap piring kosong di depanku.
“Ra, mungkin lebih baik kita tidak keluar dulu untuk sementara. Mungkin sebaiknya kamu izin sekolah dulu sampai keadaan tenang” katanya pelan.
“Jadi sekarang, kita kayak mengurung diri Ma?” tanyaku lirih.
“Iya.. Biar nggak makin ramai. Wartawan makin banyak. Papa juga udah ditanya kantor soal ini.”
Aku menunduk. Rasanya dunia kami yang dulu sederhana dan aman perlahan diacak-acak. Tidak ada ruang lagi untuk bernapas bebas tanpa pandangan, bisik-bisik, atau berita baru yang terus bermunculan.
“Mereka nggak tahu Bara kayak apa sebenarnya,” kataku akhirnya.
Mama mengangguk, pelan. “Iya, mereka cuma tahu yang ditulis orang. Tapi sekarang, kita gak bisa apa-apa selain menghindar dulu Ra.”
Kami diam lagi. Tenggelam dalam pikiran masing-masing.
Setelah makan malam yang sunyi, tiba-tiba Papa berdiri dari kursinya. Tangannya menggenggam ponsel erat, jemarinya tampak menegang. Tak ada banyak kata. Tak ada penjelasan. Hanya satu kalimat lirih yang menjatuhkan sunyi lebih dalam daripada sebelumnya:
“Besok pagi, Bara harus ke kantor polisi. Pemeriksaan pertama.”
Setelah kalimat itu Papa ucapkan, suasana seperti membeku. Aku menahan napas, menatap wajah Mama yang tiba-tiba pucat, matanya berkilat seperti berusaha menahan air mata. Dan Bara, masih diam di dalam kamarnya, tenggelam bersama pikiran dan rasa bersalah.
Mama akhirnya angkat suara, pelan tapi penuh getar, “Kenapa harus begini Pa? Apa tidak ada cara lain?”
Papa menggeleng, wajahnya berat, “Ini harus dilalui. Supaya semuanya jelas.”
Aku hanya bisa duduk terpaku, mencoba merangkum semua rasa yang bergejolak dalam dada. Tak tahu harus berkata apa, selain berharap Bara kuat menghadapi semuanya.
**
Pagi itu datang tanpa senyum. Udara terasa berat, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan ketakutan yang tak bisa kujelaskan. Cahaya matahari menyelinap pelan lewat jendela, tapi tidak mampu mengusir gelap yang menyesak di dada. Di jalan yang lurus dan mulai menyempit, mobil kami melaju menyusuri jalan-jalan sunyi yang seolah berbisik tentang kisah ini. Kami tiba di gedung kantor dengan cat tembok yang mulai pudar, dan papan nama yang berdiri tegak, mengingatkan bahwa semua ini benar-benar nyata: ‘POLRES METRO - UNIT LAKA LANTAS’.
Kami masuk. Petugas menyambut dengan senyum yang dipaksakan sopan. Bara dipersilakan duduk sendiri di ruangan kaca. Aku melihat dari luar. Tak bisa mendengar apa pun, tapi bisa menebak setiap pertanyaan yang dilontarkan.., dan beban di baliknya.
Seorang penyidik muda keluar, menghampiri Papa dan Mama. “Kami akan melakukan pemeriksaan bertahap, Pak. Izin penyitaan SIM dan dokumen kendaraan sudah kami proses. Kami juga sedang menunggu hasil visum dan laporan lengkap dari pihak rumah sakit.”
Papa mengangguk kaku. “Apa Bara akan... ditahan?”
“Untuk saat ini belum, Pak. Tapi jika nanti statusnya berubah menjadi tersangka resmi, itu bisa terjadi.”
Mama menggenggam tanganku. Kuat. Jarinya yang biasanya lembut kini mencengkeram penuh kecemasan, seolah mencoba menahan badai yang mengamuk di dalam hatinya. Wajahnya pucat, matanya memerah menahan air mata yang hampir tumpah, bibirnya bergetar tanpa suara. Ada ketakutan yang dalam terpancar dari sorot matanya—takut kehilangan, takut menghadapi kenyataan yang menggantung di depan kami, dan sedih yang begitu pekat hingga membuat ruang itu terasa sesak.
Pemeriksaan berlangsung hampir dua jam. Saat Bara keluar, wajahnya pucat. Tapi dia memaksakan senyum.
“Nggak separah yang aku kira,” katanya pelan padaku. “Tapi... aku tahu ini baru mulai.”
Tapi setelah kata-kata itu, tak ada lagi tawa. Tak ada lagi canda. Yang ada hanyalah hari-hari panjang yang dipenuhi panggilan, sidang, dan tanya jawab tanpa henti. Setiap langkah Bara menuju ruang pemeriksaan terasa semakin berat, seolah ada beban yang terus ditambah di pundaknya, tanpa ada yang menawarkan bantuan.
Sidang pertama dimulai dua minggu setelah pemeriksaan. Kami duduk di ruang pengadilan yang penuh, namun terasa sangat sunyi. Suara ketukan palu hakim menghentikan keheningan, dan aku merasa detak jantungku ikut berdegup keras.
Bara duduk di sebelah pengacara, matanya redup, seolah tak sanggup menatap siapa pun. Mama, Papa, dan aku berdiri di belakangnya. Kami terdiam. Dan setengah mati berusaha tenang setiap kali hakim bertanya dan Bara hanya menjawab dengan pelan, seperti suara yang hilang di antara kerumunan.
Setelah sidang pertama, ketegangan mulai terasa seperti belenggu yang semakin mengikat. Wartawan terus datang ke pengadilan, mengerubungi kami seperti burung pemangsa. Tanya jawab yang selalu sama. Judul berita yang terus berulang. “Mahasiswa Tabrak Lari, Keluarga Terperosok dalam Krisis.”
Di rumah, suasana berubah menjadi sunyi yang berat, setiap langkah terasa dipantau oleh bayang-bayang ketakutan dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Bara sudah ditahan di Polres Metro, tak ada bagian darinya yang tertinggal di rumah ini, selain sisa-sisa kehadirannya yang menggantung di udara: bau sabun batang kesukaannya di kamar mandi, sandal jepit yang belum sempat disingkirkan dari dekat pintu, dan jaket hitamnya yang dibiarakan begitu saja di atas ranjang kamarnya.
Kemudian, minggu keempat, sidang terakhir itu tiba. Sidang ini bukan lagi tentang penyelidikan, bukan tentang mencari kebenaran. Ini tentang keputusan. Tentang apakah Bara akan menanggung semua akibat dari kecelakaan itu, meski dia tidak sengaja, meski tidak ada niat jahat dalam dirinya.
Di ruang sidang itu, Bara akhirnya dihadapkan pada fakta yang tak bisa dipungkiri, bahwa ia adalah penyebab dari kematian seorang pengemudi. Dan meski tekanan medis dan kecelakaan yang ia alami jadi pertimbangan, keputusan hakim akhirnya membuat semuanya terasa membeku.
“Terdakwa Bara Wicaksana,” suara hakim bergema, “dinyatakan bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan kematian. Karena faktor-faktor yang meringankan, hukuman penjara dijatuhkan selama lima tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah dua tahun.”
Aku tidak tahu harus merasa lega atau justru lebih hancur. Bara terduduk lemas. Dia tidak menangis, hanya menatap kosong ke depan. Mungkin sudah tidak ada air mata yang tersisa lagi dalam dirinya.
Di wajahnya, tergambar jelas tentang Mama, Papa, aku dan skripsi yang hampir selesai, bab terakhir yang hampir siap dia kumpulkan. Seharusnya itu menjadi pencapaian besar dalam hidupnya, titik balik menuju masa depan yang lebih baik, menuju gelar yang selama ini dia impikan. Tapi sekarang, semua itu terasa begitu jauh. Harapan tentang kuliah, yang dulunya memberi arah, kini sirna begitu saja. Semua yang telah dia capai seolah tenggelam dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa dia elakkan.
Kami semua diam. Tidak ada yang bisa mengucapkan apa pun setelah itu.


 bunca_piyong
bunca_piyong











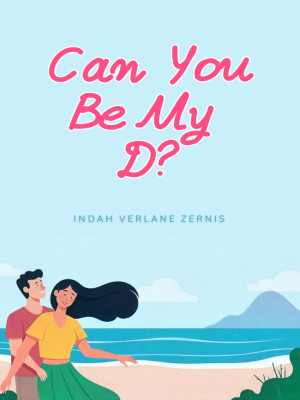



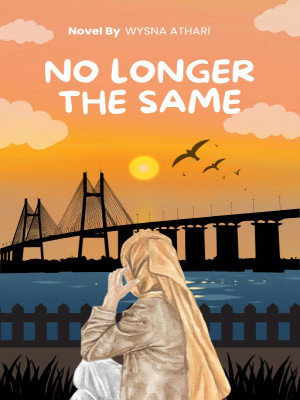


Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .