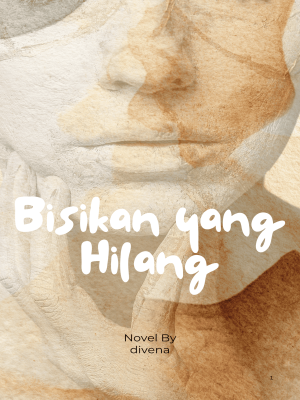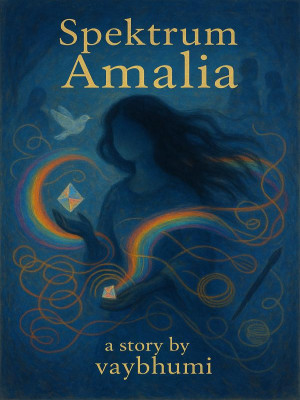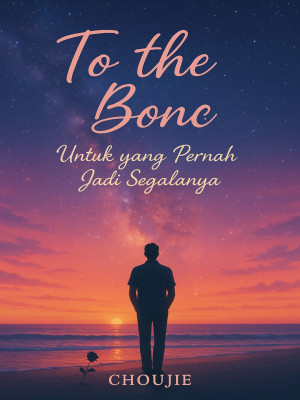Di rumah Nara.
Santi duduk terdiam di ujung ranjang. Tangan yang ia gunakan untuk menggulir layar ponsel hitam milik Faris berhenti dan mematung. Seolah-olah tak percaya dengan semua kenyataan yang ada. Kenyataan itu lah yang membuatnya kini tak bisa bernapas.
Sesak.
Santi mencoba berpikir jernih. Namun, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, ia tidak dapat memikirkan apapun. Ia terpaku melihat kenyataan yang kini ada di depan mata.
Ponsel hitam yang ia pegang menampilkan layar percakapan yang isinya penuh dengan emoji hati. Percakapan tersebut tampak sangat mesra. Percakapan pun intens dan terjadi hingga larut malam.
Santi memencet tombol yang menampilkan foto profil. Matanya terbelalak tak percaya tatkala melihat foto suami yang selama ini ia percayai sedang memeluk seorang wanita. Wanita itu bukan dirinya. Tampak foto tersebut diambil di depan sebuah kaca di dalam kamar hotel. Santi menepuk-nepuk pipinya, apakah ini nyata? Yang ia rasakan pipinya yang memanas karena tepukannya sendiri. Ya, ini semua nyata. Ini semua terang, terlalu terang untuk bisa dibantah.
Sementara itu, kini pemilik ponsel masih berada di dalam kamar mandi. Santi cepat-cepat mengumpulkan semua bukti dengan memotret layar yang ada di hadapannya. Mulai dari semua bukti percakapan, foto-foto yang ada di galeri, hingga bukti transfer di dalam mobile banking. Beruntung Santi dapat berpikir jernih dan tidak tenggelam meratapi kesedihan atas apa yang menimpanya.
Pemilik ponsel membuka pintu kamar mandi bersamaan dengan Santi yang selesai untuk memotret keseluruhan bukti pengkhianatan Faris. Tatapan mereka berdua bertemu. Sorot mata Faris tampak tidak ada masalah apa-apa. Sementara sorot mata Santi sangat tajam menyiratkan kemarahan yang sangat besar beserta wajahnya yang kini pucat.
Dengan tangan bergetar, Santi menyodorkan ponsel Faris. “Faris,” panggilnya datar.
Yang dipanggil kaget. Tidak biasanya istrinya itu memanggil dengan namanya, tanpa embel-embel ‘Mas’.
“Kamu mau jawab apa soal ini?” Tanya Santi dengan nada yang datar. Amat datar.
Faris memicingkan mata. Tanpa menjawab pertanyaan Santi, Faris menyerang balik dengan kata-katanya. Ia mencoba menyalahkan Santi yang mengecek ponselnya tanpa seizin pemiliknya. “Apa lagi, sih? Baru pulang juga udah ngajak ribut. Itu juga cuma teman kerja.”
“Ribut kamu bilang? Teman kerja apa yang mesra-mesraan seperti ini?” Santi sudah hilang kesabaran. Ia tidak bisa diperlukan seperti ini. Ia tidak tahan. 18 tahun usia pernikahan bukanlah waktu yang sebentar. 18 tahun yang ia bangun dinodai begitu saja oleh seorang Faris.
Santi melempar ponsel Faris. Dengan ponsel itu yang masih menyala dan menampilkan ruang obrolan yang penuh dengan emoji hati.
"Tenang dulu dong, San. Dengerin penjelasanku!" Tukas Faris setelah melihat ponselnya dilempar begitu saja oleh Santi.
Napas Santi tersengal. Ia sudah habis kesabaran. "18 tahun pernikahan kita. Selama ini aku nggak pernah minta dan nuntut apa-apa sama kamu. Selama ini aku berusaha jadi istri yang baik dan bantu keuangan keluarga kita. Dengan tidak tahu dirinya, kamu nodai ikatan suci ini."
Santi bukanlah wanita yang sabar. Ia adalah wanita mandiri yang tentu saja bisa berdiri di kakinya sendiri. Ia bisa menghasilkan uang sendiri dengan pekerjaannya sekarang sebagai seorang akuntan di perusahaan swasta. Ia juga telah mengabdi pada perusahaan tersebut selama 15 tahun lamanya. Tentu saja Santi merasa terhina atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Faris. Sebab, sebelum memutuskan untuk menikah dengan Faris, ia telah menolak tiga orang yang merupakan konglomerat demi seorang Faris.
Kala itu, Faris hanyalah pegawai biasa di perusahaan swasta. Gajinya hanya UMR Jakarta, namun Santi menerima Faris apa adanya. Ia bahkan rela melawan restu dari kedua orang tuanya demi mempertahankan hubungannya dengan seorang Faris. Saat ini, ketika Faris sudah sukses menjadi manajer senior di perusahaannya, ia lupa dengan Santi yang setia menemani dari nol. Ia menjadi tidak tahu diri.
Pertengkaran pun meledak. Suara Faris meninggi, diiringi dengan suara Santi yang membalas dengan amarah yang tak tertahan. Tuduhan, bantahan, dan kemarahan memenuhi ruangan.
"Kita cerai!" Ucap Santi dengan tajam. Bukan Santi jika ia menye-menye dan harus memohon-mohon untuk seorang Faris. Sudah cukup ia korbankan masa mudanya untuk seorang Faris. Ia tidak mau berkorban lagi atas perasaannya untuk saat ini. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Santi pergi.
Faris mengacak rambut frustrasi. Diusap wajahnya dengan kasar. Ia menarik napas berat.
#
Langit sudah mulai gelap. Nara merasa hari ini cukup menyenangkan, karena ia bisa menghabiskan waktu untuk bermain di Timezone. Namun, Nara tak kunjung mendapatkan pesan dari ibunya. Ia tidak mau melawan apa kata orang tua. Nara adalah anak baik-baik dan tidak pernah neko-neko dalam hidupnya.
Kini, Nara dan Tania tengah duduk di food court, berbagi kentang goreng sambil memainkan ponsel masing-masing. Tania tengah menyesap segelas thai tea. "Ra, sampai kapan kita nunggu? Kamu udah coba hubungi ibumu? Atau kamu pulang ke rumahku aja?"
Pandangan Nara tak lepas dari layar ponselnya. Ia berharap pesan dari Santi segera masuk, karena sejujurnya ia sudah sangat lelah. Apalagi sepulang dari Timezone. Rasanya Nara ingin segera merebahkan tubuhnya pada kasur kamarnya yang empuk. "Entahlah, Tan. Ibu berpesan buat aku nggak pulang dulu ke rumah sebelum ibu kirim pesan lagi. Tapi, sekarang ibu nggak kunjung-kunjung kirim pesan juga. Hari udah malem juga, aku capek banget."
Tania menghela napas. Ia juga turut merasakan capek. "Ya udah, kamu pulang aja nggak papa deh. Mungkin ibumu belum sempet hubungi lagi, atau lagi sibuk."
Nara mengangguk lemas. Ia langsung memesan taksi online. Sementara Tania segera menghubungi abangnya untuk meminta jemput. Rumah mereka berdua memang berbeda arah. Oleh karena itu, mereka tidak pulang bersama.
10 menit kemudian, abang Tania–Tama–datang menjemput. Disusul oleh taksi Nara yang datang. Mereka berdua berpamitan, tidak lupa Nara juga mengucapkan pamit kepada Tama. Setelah saling mengucapkan hati-hati, masing-masing kendaraan pun melaju meninggalkan mall.
Nara yang berada di jok belakang kini tampak penampilannya sudah lusuh. Ia ingin segera bergegas mengguyurkan air pada tubuhnya yang sudah penuh dengan keringat, lalu merebahkan tubuhnya pada kasur empuk. Jalanan Ibu Kota tidak terlalu macet. Sehingga, hanya perlu waktu 15 menit saja untuk Nara sampai di rumahnya.
Sesampainya di depan rumah, Nara terkejut dengan keberadaan mobil ayahnya. Perasaan lega menjalar pada tubuh Nara tatkala melihat ayahnya pulang. Ia memang tidak dekat dengan Faris sedari kecil. Namun, tidak dipungkiri Nara juga amat sayang kepada ayahnya itu. Terlebih lagi ia tidak memiliki saudara kandung. Seharusnya, ia mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Entah mengapa, anehnya Nara tidak mendapatkan itu. Yang ia tahu, kedua orang tuanya hanya sibuk kerja, sehingga ia jarang mendapat perhatian dari Santi dan Faris.
Nara tersenyum begitu hendak membuka pintu rumah. Akhirnya ia dapat melihat ayahnya setelah beberapa minggu ayahnya melakukan pekerjaan ke luar kota. Namun, setelah pintu terbuka, yang ada adalah senyum Nara memudar. Ia mendapati Santi yang kini tengah menelungkupkan wajahnya pada meja dengan kondisi barang-barang di rumah yang sudah seperti kapal pecah. Setelah dipanggil berkali-kali, Santi baru sadar Nara pulang.
“Eh, Ra, kok baru pulang?” Tanya Santi dengan sedikit linglung.
Nara bingung. “Tadi kan Ibu larang Nara pulang dulu. Tapi setelah ditunggu berjam-jam, Ibu nggak bisa dihubungi, jadi Nara nekat pulang. Maaf ya, Bu. Nara capek banget.”
Santi meremas rambutnya. Ia lupa dengan pesannya kepada Nara. Setelah bertengkar dengan Faris perihal ia memergoki bukti perselingkuhan tadi, Santi melampiaskan amarahnya dengan membuat berantakan seluruh isi rumah. Ia memang memiliki kebiasaan buruk yaitu melampiaskan amarahnya dengan membuat berantakan seluruh barang yang ada di rumah.
“Maaf ya, Ra, ponsel Ibu kehabisan daya.”
Bohong. Nara tahu itu bohong. Jika memang kehabisan daya, ibunya pasti akan langsung men-charge ponsel tersebut. Terlihat sisa tangisan di wajah cantik ibunya. Namun, Nara tidak berani untuk bertanya soal apapun. Selain takut menyakiti hati ibunya, Nara takut jawaban Santi nantinya justru yang membuat ia kecewa. Ia sudah berfirasat buruk, sebab yang ia tahu ayahnya saat ini sedang pulang. Biasanya, ketika Faris pulang, suasana di rumah akan terasa hangat. Namun, Nara bisa merasakan kalau saat ini berbeda. Suasana saat ini justru dingin dan mencekam dengan kondisi rumah yang sedemikian berantakan. Ia tahu ibunya sedang marah.
Nara memilih untuk beralih topik tanpa ingin tahu apa yang terjadi di rumahnya. “Bu, Nara capek. Nara istirahat dulu ya.”
Santi hanya mengangguk pelan. Kemudian, Nara beranjak pergi dari ruang tengah. Saat melewati kamar orang tuanya, Nara melihat sekilas dari celah pintu. Memang pintu tersebut tidak ditutup rapat, sehingga Nara mencoba mengintip.
Ayahnya sedang ada di dalam kamar dan duduk di pinggir ranjang. Ayahnya diam mematung dengan pandangan kosong. Nara tidak berniat untuk mempedulikan apa yang terjadi di rumahnya. Ia pikir itu hanya pertengkaran pasangan seperti umumnya. Dan Nara pikir itu wajar. Ia tidak begitu ingin tahu apa sedang terjadi, terutama yang terjadi pada ayahnya. Sebab, ia bukanlah anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, meskipun ia adalah anak semata wayang.
Setelahnya, Nara pergi ke kamarnya. Ia bergegas untuk mandi. Seusai mandi, ia berganti pakaian dengan pakaian tidur yang nyaman. Lalu, merebahkan diri. Ia hanya ingin mengenang kejadian yang menyenangkan saja di hari ini. Ia hanya ingin mengingat kesenangannya waktu bermain Timezone bersama Tania. Tidak lama kemudian, Nara terlelap dalam tidurnya.
Tanpa tahu, di hari ini, di hari yang sama saat ia tertawa dan merasa bebas, rumahnya mulai retak. Bukan sebab gempa, melainkan sebab kebenaran yang selama ini disembunyikan. Tidak, tidak mulai hari ini. Tetapi, mulai saat sosok laki-laki yang menjadi cinta pertama seorang–anak perempuan–sekaligus menjadi patah hati pertama.
--- TO BE CONTINUED ---


 evaalisya
evaalisya