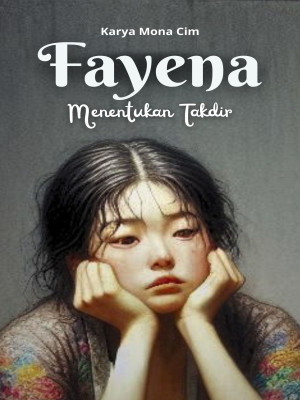“Alvino, Alfinna, Alphiko.”
Ketiga anak berseragam SMA yang berjejer dengan berurutan itu tidak mengindahkan panggilan gurunya yang sedari radi mondar-mandir tak jelas di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan Pak Goyara. Dirinya sedang menghukum si kembar tiga dengan cara dijemur di tengah lapang upacara. Dengan gayanya yang menurut murid lain sok rapi, Pak Goyara tampak membaca biodata triplets melalui tiga lembar kertas di tangannya.
“Kenapa hanya Alvino yang masuk kelas IPA?”
Lelaki itu meneguk salivanya. Cuaca pada jam delapan ini panas sekali, membuat tenggorokannya kering. Vino membenahi arm sling yang melindungi tangan kanannya. Setidaknya dengan cara ini kepercayaan diri Vino bisa meningkat. Orang tak terlalu memerhatikan kecacatan pada tangannya. di samping dirinya masih harus menggunakan kursi roda, sebab untuk memakai kaki palsu harus menunggu empat hingga enam bulan setelah operasi.
“Waktu tes jurusan, saya lagi beruntung aja, Pak. Sebenernya saya juga mau masuk IPS kayak adik-adik saya.”
“Seperti!” Pak Goyara memukul kepala Vino menggunakan kertas di tangannya. Merasa gaya bicara Vino terlalu informal.
“Kamu, Alphiko.” Tatapan Pak Goyara beralih pada Phiko. “Bukankah kamu pintar? Sejak SD sering ikut lomba, menang kejuaraan sains dan sosial. Kenapa bisa masuk IPS? Minatmu di IPA, kan?”
Phiko mengangguk kasar. “Lagi tidak beruntung, Pak.”
Tidak ada lagi jawaban dari Phiko. Hanya empat patah kata. Padahal Pak Goyara mengharapkan jawaban yang lebih intens seperti Vino.
“Pak,” sergap Finna kala Pak Goyara hendak melayangkan pukulan yang diperkirakan lebih keras dari sebelumnya. “Kecerdasan seorang siswa tidak bisa ditakar melalui jurusan yang ia emban selama ini. Balak tidak bisa mengelak bahwa kedua saudara saya memang berada di jalan yang berbeda dalam pendidikan, sebab saya yakin masa depan mereka juga akan berbeda nantinya.”
Pak Goyara mengamati setiap lekukan wajah Finna. Guru muda itu mempertipis jarak. Saat ia mengangkat tangan, Phiko dan Vino langsung melempar tatapan mencekam, membuat nyali Pak Goyara mendadak ciut. Pak Goyara mendengkus kasar.
“Yang tegak!” Lalu Pak Goyara meninggalkan si kembar tiga di tengah lapangan.
Hari sial tidak ada di kalender, begitu kata si triplets. Semalam mereka baru menamatkan drama Korea yang terus rekomendasikan Finna berjudul Weak Hero Class, dua season sekaligus karena lupa esok adalah hari Senin. Mereka baru bisa tidur sekitar pukul empat subuh, pertama kalinya tidur larut bukan karena bekerja. Ketiganya berangkat pada pukul tujuh kurang sepuluh. Sampai di sekolah jam tujuh lewat lima yang seharusnya masih bisa diperbolehkan masuk. Namun, sayangnya guru piket hari ini adalah Pak Goyara. Terpaksa ketiganya harus menerima hukuman dari guru muda menyebalkan itu.
“Phi? Kamu gak apa-apa?”
Phiko menoleh. Menggeleng kuat. “Baik, kok, Fin. Vino tuh yang harus ditanya.”
“Hidung lo berdarah, Phi. Nggak kerasa?”
Mata Phiko membesar. Ia mengusap kasar bawah hidungnya. Benar kata kedua kakaknya, hidung Phiko mengeluarkan darah pekat yang cukup banyak. Phiko pikir hanya keringat, sebab Phiko memang memiliki metabolisme tubuh mudah berkeringat.
“Gue cuci dulu.” Phiko berbalik. Darah di hidungnya makin deras keluar.
“Jangan bergerak!” Guru menyebalkan itu ternyata masih mengawasi dari kejauhan.
“Phiko berdarah, Pak!”
Pak Goyara tidak menanggapi teriakan Finna dan Vino. Dia tetap menuntut Phiko kembali ke posisi. Sekali lagi, hari sial tidak tertulis dalam kalender.
“Nih, pake dasi gue.” Vino mengulurkan dasinya.
Phiko mengambilnya, membersihkan hidung dengan seada-adanya.
Mungkin hanya kelelahan.
Kalian tahu rantang susun tiga yang terbuat dari bahan plastik? Bapak membelikan rantang itu ketika si kembar naik ke kelas 5 SD. Sebab si kembar mulai beranjak besar, sering merengek ingin dibawakan bekal. Maka dari itu, daripada memakai kotak bekal yang entah kapan akan hilang, Bapak pikir memakai rantang akan jauh lebih efektif. Terlebih yang membawa hanya satu orang saja, Finna, dia sangat apik menjaga sebuah barang.
Rantang tersebut sudah teronggok sekitar tiga tahun di dapur, terhitung sejak si kembar hubungannya merenggang. Dan sekarang, rantang dengan warna pastel hijau, biru, dan merah muda itu dipakai lagi. Finna tengah membukanya, membagikan ke kakak dan adiknya. Phiko dengan perkedel kentang kesukaannya, Finna tumis kangkung, dan Vino telur ceplok paling sederhana.
Kelas IPA 3 tidak begitu banyak manusia ketika jam istirahat kedua dimulai. Mereka memilih menghabiskan waktu di luar, kantin atau lapangan. Dahulu, Vino sering bermain basket bersama genk-nya yang sudah menjauh itu, atau sekadar membantu guru Informatika yang komputernya rusak. Vino itu pandai memperbaiki komputer dan laptop. Bahkan pelajaran Informatika adalah satu-satunya pelajaran yang tidak melimpahkan tugasnya kepada Phiko.
“Gue mau kerja lagi.”
“Gak boleh!” kompak Phiko dan Finna dengan mata terbelalak.
Vino mengunyah suapan pertama dari Phiko. Adiknya itu menyodorkan dengan kasar, hampir saja sendok menusuk dinding tenggorokannya. Vino masih belum mau memakai tangan kiri untuk makan, tidak sopan menurutnya. Padahal Bapak dan adik-adiknya sudah memberitahu bahwa Vino boleh makan dengan tangan kiri karena hal yang mendesak.
“Gue tau kalian bakal jawab begitu. Makannya ....” Vino menatap adik-adiknya bergantian. “Gue mau buka jasa servis.”
Phiko dan Finna saling melempar tatap. Memang ide itu tidak terlalu buruk, tapi ... apakah Vino bisa? Hanya dengan satu tangan?
“Mending di rumah atau toko Bapak, ya?”
“Tunggu, tunggu, No,” sela Phiko. Lelaki itu menyimpan rantang berisi telur ceplok milik kakaknya. “Memangnya ... lo bisa? Maksudnya, lo itu kalau benerin komputer selalu pakai tangan kanan lo. Sekarang lo–”
“Tenang aja.” Vino terkekeh. Ia merogoh ponsel dari sakunya, menunjukkan ruang pesan dirinya bersama guru informatika. “Jam satu Pak Jiro nyuruh gue ke ruangan. Kita lihat kemampuan gue. Kalau gue bisa, kalian harus bolehin gue buat buka jasa servis.”
Finna tertawa meremehkan. “Oke. Kita lihat nanti.”
Ketiga anak kembar itu melanjutkan santapannya. Pagi tadi, Bapak memasak ini sendirian dengan penuh kasih sayang. Tahu-tahu tiga makanan kesukaan anak-anaknya sudah tersaji di meja makan. Kata Bapak, spesial karena Vino mau sekolah lagi setelah satu bulan menjadi anak rumahan.
Ada perasaan iri dari dalam hati Phiko. Kembalinya jati diri Vino sebagai anak yang ceria saja, Bapak sampai membuatkan masakan kesukaan untuk mereka. Sementara kembalinya Phiko menjadi anak yang terbuka, mengapa Bapak tidak bereaksi apa pun? Entah hanya Phiko yang berpikir berlebihan atau memang nyatanya begitu. Namun, Phiko sungguh berusaha untuk tidak membenci kedua kakaknya.
“Daftar Ruangguru aja, Phi.”
“Hah?” Phiko mengangkat kepala. Lamunannya membuyar. Ternyata sedari tadi kedua kakaknya sedang membicarakan perihal niat Phiko untuk ikut kelas tambahan.
“Kalau lo mau tetep minat les, ikut Ruangguru aja. Itu lho, tempat les online. Harganya juga lebih terjangkau,” saran Vino.
“Offline-nya juga ada. Itu di deket komplek Permata. Banyak anak sekolah sini yang les di sana.”
Phiko tertawa pelan. “Udah gue bilang. Gue nggak minat lagi ikut les.”
“Sayang, Phi. Lumayan buat kuliah nanti,” ujar Finna.
“Gue bisa ikut jalur prestasi. Gue punya banyak sertifikat olimpiade, kok.”
“Mending diterima, kalau kagak?”
Phiko terdiam mendengar tanggapan kakak sulungnya. Perlahan ia menunduk, mengaduk-aduk nasi miliknya yang tersisa setengah.
“Sebenernya apa yang lagi ganggu pikiran kamu, Phi?”
Ujung bibir Phiko tertarik hingga terukir senyum simpul. Lelaki itu kembali menatap kedua kakaknya. “Gue harap kalian bisa bantu ini.”
“Bantu apa?” tanya kedua kakaknya bersamaan.
“Gue tau, kalian itu udah dapetin jati diri kalian. Vino yang jati dirinya pekerja keras, dan Finna ada di tata rias. Sedangkan gue? Sebetulnya, gue rasa jati diri gue ada di belajar, pendidikan, akademik pokoknya. Tapi, itu semua justru malah ngejauhin gue dari kalian. Makannya, gue nggak minat lagi ikut les atau kuliah. Gue pengen cari jati diri gue yang sebenernya.”
Vino mengangkat alis. Tatapannya terlempar kepada Finna, lebih tepatnya, menyuruh Finna supaya menjawab.
“Sebelum kita bisa menemukan jati diri, kita harus berdamai sama diri sendiri dulu. Aku sama Vino bisa punya jati diri karena kita udah berdamai sama keadaan, kita udah bisa nerima kalau Bapak dan Ibu pisah, maka dari itu kita bisa cepet nemuin jati diri.”
Phiko mengembuskan napas panjang, berulang-ulang. Ia mengedarkan pandangan. Ruang komputer sangat sepi. Ketahuilah, Vino belum juga menyelesaikan pekerjaannya setelah dua jam berlalu, bahkan lelaki itu sampai disusul oleh kedua adiknya setelah bel pulang sekolah berdering.
“Gue yakin, lo jadi pemurung karena Bapak sama Ibu, kan?” tebak Vino tanpa mengalihkan tatapan dari mesin CPU di tangannya.
Phiko hanya diam saja bergeming. Walau sebenarnya dalam hati, ia membenarkan.
“Dan lo mau jadi pinter supaya Ibu lirik lo, dan ngajak lo buat ikut dia tinggal di apartemen?”
“Nggak, nggak! Yang itu gak bener,” elak Phiko.
Vino sampai menghentikan pekerjaannya sejenak, dan Finna juga mengalihkan pandangan dari layar ponsel. “Gue mau jadi pinter demi dapet perhatian kalian, Bapak dan Ibu juga. Gue mau diapresiasi, gue pengen dipuji-puji. Tapi .....”
Phiko menghela napas pelan. “Tapi, ternyata kalian nggak memandang begitu ke gue.”
Vino dan Finna saling melempar pandang kikuk. Finna sendiri terlihat gelagapan, ia menyimpan ponselnya. Sebelah tangannya menggapai bahu sang adik.
“So-sorry, aku pikir kamu gak mau, kupikir kamu gak perlu, kupikir–”
“It’s okay, Fin. Udah lewat juga.” Phiko mengukir senyum teduh, sambil menyentuh punggung tangan kakaknya. “Yang jelas. Sekarang tolong bantu gue buat temuin jati diri gue.”
Phiko hanya berharap, ia akan menjadi sama seperti kedua kakaknya jika jati dirinya yang sesungguhnya telah ditemukan. Phiko hanya berharap, segitiga sama kaki yang orang-orang sebutkan itu, akan berubah menjadi segitiga sama sisi. Phiko hanya tidak ingin dipandang berbeda dari kedua kakaknya.
“Nanti Subuh, gue mau ikut ke pasar.” Vino kembali fokus terhadap CPU. Kali ini menyambungkannya dengan komputer untuk memeriksa apakah hasil kerjanya berhasil atau tidak.
“Buat apa?” sergap Finna dengan nada protes.
“Barangkali jati diri Phiko sama kayak gue. Kerja. Gue mau ngajarin dia caranya ngelayanin pelanggan yang bagus. Armor bilang, banyak pelanggan yang protes karena Phiko terlalu kaku.”
Phiko berdecak, dan Finna justru tertawa sekaligus mengakuinya. Gadis itu menepuk bahu Phiko, masih dengan tawa yang tak kunjung berhenti.
“Tapi, Phi. Yang pasti, kalau kamu mau nemuin jati diri, kamu nggak boleh jadi seperti orang lain.” Finna menyentuh dada Phiko dengan telunjuknya.
“Kamu harus jadi diri sendiri.”
Pesan itu akan Phiko ingat bahkan sampai ia mati. Ibu ... pernah mengatakannya saat mereka kecil, setiap mereka baru masuk sekolah dan diharuskan untuk berkenalan di depan kelas. Kini, Finna malah bertingkah seperti Ibu.
“Pak! Komputernya nyala, Pak!” seru Vino.
Pak Jiro datang menghampiri dengan kacamata di ujung tanduk. Menundukkan tubuh, memeriksa kebenaran ucapan Vino. Tersirat rasa kecewa di wajahnya, mungkin karena Vino memperbaiki selama berjam-jam, tidak seperti dahulu tiga puluh menit langsung beres. Padahal Pal Jiro sudah memperbolehkan Vino untuk meneruskan esok hari, tetapi lelaki itu bersikukuh sampai rela membolos mata pelajaran terakhir.
Pak Jiro merogoh sesuatu dari saku celananya. Uang. Tiga lembar uang berwarna biru diberikan. Sesaat Pak Jiro melirik kedua adik kembar Vino, lalu menambahkan satu lembar lagi.
“Pulangnya beli es krim sana.”
“Ini nggak kebanyakan, Pak?”
Pak Jiro menggeleng. “Bersama adik-adikmu.”
Tiga anak kembar itu tersenyum girang, seperti anak kecil yang dijanjikan es krim. Setelah berpamitan, ketiganya lantas benar-benar pulang dari sekolah. Sesuai amanah Pak Jiro, mereka sempat melipir ke salah satu kedai es krim. Phiko hanya fokus kepada kedua kakaknya ketimbang es krim, terutama Vino. Ia baru tahu kalau guru Informatika itu akan memberikan Vino uang jika ia berhasil memperbaiki komputer. Phiko yakin, guru itu sebenarnya bisa membenarkan sendiri, bukankah beliau guru komputer? Mungkin, mereka atau para guru di sekolah hanya kasihan saja ... kepada mereka. Phiko jadi penasaran, sebenarnya bagaimana pandangan warga sekolah terhadap kedua kakaknya?
“Yakin bakal ikut?”
Phiko tengah memijati lengan kanan Vino supaya lebih rileks, dibaluri minyak zaitun. Hitung-hitung terapi, selagi mereka tidak memiliki biaya terapi sesungguhnya. Kegiatannya setiap jam enam pagi sebelum mereka berangkat sekolah. Namun, sekarang, ia harus melakukannya tepat pada tengah malam.
Padahal Phiko sudah berhati-hati hendak melarikan diri, tapi telinga Vino terlalu sensitif mendengar derap langkahnya. Sehingga Vino memaksa kedua matanya bangun, bersikukuh ikut dengan Phiko berjualan subuh nanti.
“Kalau ngantuk lanjut tidur aja.”
Vino buru-buru menggeleng kuat, menepuk-nepuk pipinya, memaksa matanya agar terbelalak. Padahal sedari tadi ia mangut-mangut karena masih mengantuk.
“Inget, ya, nanti nggak boleh angkat-angkat barang, cuman bantu gue sama Armor jualan daging.”
“Iya.”
“Lo bisa tidur dulu di tempatnya Armor selagi nunggu.”
“Iya.”
“Pake terus jaketnya. Lagi musim hujan, pasti dingin jam segini.”
“Iya, bawel.”
Phiko mengeraskan pijatannya, membuat Vino sedikit meringis kesakitan. Phiko melempar tatapan pedas.
Pijatan sudah selesai. Jika diperhatikan, lengan Vino terlihat sedikit merenggang dari sebelumnya. Jika kemarin-kemarin telapak tangan sampai bisa bersentuhan dengan dada, kini tangan itu sedikit turun dari posisi awal. Phiko tersenyum. Sepertinya mereka tidak memerlukan terapi, pijatan Phiko cukup manjur untuk kakaknya.
“Vino beneran pergi?” Finna menegur di ambang pintu, mengisik kelopak matanya. Gadis itu terganggu karena keributan yang dibuat oleh dua saudaranya di kamar sebelah.
“Hati-hati di rumah ya, Fin. Jaga Bapak,” titip Vino.
“Bapak nggak tau kamu pergi pagi ini?”
“Tau. Semalem udah izin.”
Finna mengangguk paham. Ia mempertipis jarak, mencium kening Vino sebagai tanda perpisahan. Phiko juga, seharusnya. Namun, lelaki itu tapak kikuk saat Finna berada di dekatnya. Maka Finna hanya memeluk erat tubuh kecil Phiko.
“Jam setengah enam langsung pulang ya. Jangan keluyuran,” peringat Finna.
Jika tengah malam orang-orang akan tidur di ranjang empuk mereka, dengan bantal, guling, dan selimut yang hangat. Hal ini jarang sekali dirasakan oleh penghuni pasar. Pada pukul satu malam, mereka berbondong-bondong pergi untuk mempersiapkan dagangan. Ada yang berbelanja, ada yang menunggu kedatangan truk, dan ada seseorang yang berharap diberikan pekerjaan agar bisa dapat pundi-pundi rupiah. Jika bukan karena Armor, mungkin Phiko—dahulu Vino—akan menjadi orang yang menunggu harapan tersebut di tepian pasar. Pasara area barat sangat berbeda ketimbang pasar timur milik Bapak. Di sini becek, bau, lebih banyak kejahatan.
Salah satu toko kecil yang berada di tengah-tengah pasar, seorang lelaki tengah terbaring di sana, menatap langit-langit pasar yang hanya ditutupi oleh asbes. Berbeda dengan toko Bapak, sekelilingnya adalah tripleks, tapi dipadati oleh buku yang belum terjual.
Vino mengangkat kepalanya saat merasa dua orang mendekat dengan kantong plastik besar di kedua tangannya. Mereka peluh oleh keringat. Keduanya baru menurunkan barang dari truk besar. Ah, Vino masih merasa trauma saat melihat truk. Jangankan truk, lihat mobil box saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri seketika.
“Banyak barangnya?” tanya Vino. Ia berusaha bangkit dari tidurnya. Phiko dengan segera membantu setelah menyimpan plastik merah tersebut.
“Tidur lagi aja. Pasar sekarang buka dari jam empatan.”
Vino menatap mata Phiko. Sedari lahir, Vino belum pernah melihat Phiko berkeringat seperti ini. Entah kerasukan makhluk apa, tapi Phiko benar-benar berbeda dari yang ia kenali.
Mungkin, begitupula sebaliknya. Saat pasar sudah buka, para pengunjung mulai berdatangan. Kedai Armor terkenal dengan kemurahan harga dagingnya, juga kemurahan senyuman Vino. Lelaki itu bagaikan penglaris tersendiri untuk memikat hati ibu-ibu. Terlebih mereka menyadari kembalinya Vino, semakin banyaklah orang yang berdatangan. Sebagian dari mereka merasa turut prihatin dengan keadaan Vino yang sekarang, tapi sebagian lagi merasa tetap senang dan bersikap seperti tidak terjadi apa pun kepada Vino. Biasanya, Vino bertugas di bagian pemotongan daging. Tapi sekarang, ia hanya bisa memisahkan daging yang diinginkan para pembeli, lalu menyerahkannya kepada Armor untuk dipotong. Sementara Phiko, ada di bagian menerima dan menghitung uang.
“Bukan taktik jualan. Itu tebar pesona namanya,” sindir Phiko, setelah kedai mereka mulai berangsur sepi. Bukannya tersindir, Vino justru tertawa kegirangan.
“Berapa omset hari ini, Phi?”
Phiko kembali membuka buku kas. “Tiga juta empat ratusan.”
“Wih, dua kali lipat dari biasanya. Ayam juga tinggal tiga biji. Lo keren, No. Kayaknya jadi pajangan juga laku, nih.” Armor menepuk bahu Vino.
Vino mendelik. “Kayaknya, ini hari terakhir gue kerja di sini, Mor. Mungkin sesekali bakal main lah. Tapi, gue mau buka usaha servis di toko Bapak, udah dapet restu juga dari adek-adek gue. Jadi, kayaknya gue nggak bisa bagi waktu buat di sini. Takut jadi beban. Gue juga udah gak bisa begadang atau bangun tengah malem karena kebiasaan tidur lebih awal sebulan kemaren.”
Armor mengangguk-angguk. “Nggak apa-apa, No. Suer. Asalkan lo gak mati. Lo sehat terus dan jangan celaka lagi. Tapi, kira-kira siapa yang bisa gantiin senyuman manis lo itu buat jadi penglaris?”
Vino perlahan menatap adik bungsunya, membuat Armor juga ikut menatap Phiko. Seketika lelaki yang tengah ditatap dua orang itu menjadi kikuk. Alisnya bertaut dan napasnya menderu.
“NGGAK! Gue gak bisa!” Phiko nyaris memuntahkan mi ayam yang sedang dicerna di perutnya saat kedua kakaknya mengungkit perihal niatan menggantikan seorang Vino di pasar—menjadi seseorang yang sangat friendly.
“Tinggal cengengesan gak jelas apa susahnya, sih, Phi?” elak Vino. Baginya memang terdengar mudah, Vino yang terkenal dengan keramahannya di mana pun ia berada. Namun, tidak untuk Phiko yang pendiam dan irit bicara.
“Gue colok mata lo pakai sumpit ini, ya!” Phiko mengangkat sepasang sumpit di tangannya. Yang diancam merungut sambil memajukan bibirnya.
“Jangan dipaksa, No. Orang introvert itu lebih cepet kekuras energinya kalau mereka bicara di depan umum. Jangan bikin Phiko kayak sayuran yang layu, deh.”
Vino hanya terkekeh tak bersalah untuk menanggapi.
“Sore nanti, kamu ikut sama aku aja. Bantu aku jadi asisten perias. Kebetulan aku cukup keteteran dan butuh bantuan. Siapa tau jati diri kamu sama kayak aku.”
Phiko mendelik. “Apa kata orang kalau gue pegang alat rias begituan?”
“Heh, jangan salah! Banyak tau cowok yang suka sama make up! Bahkan sebagian dari MUA tuh cowok. Kamu nggak tau?” Kemudian Finna menyebutkan nama-nama laki-laki yang tentunya tidak Phiko kenali itu, bahwa mereka adalah deretan MUA terkenal.
Phiko menulikan pendengarannya. Tak lama, seorang gadis sebaya dengan mereka datang menghampiri meja triplets. Gadis itu melambaikan tangan.
“Eh, Bel. Ada apa?” Finna balik melambai.
Rupanya itu Bela, siswi kelas IPS 5. Phiko ingat, bukankah gadis itu yang melakukan sebuah joki tugas? Yang sempat Phiko dengar sekilas dari teman sekelasnya tempo waktu.
“Emm, itu, Pak Goyara nyuruh Phiko untuk ke ruang guru,” ucap gadis itu.
Phiko menautkan alisnya. “Buat apa?”
Bela mengangkat kedua bahu. Raut wajahnya menggambarkan harapan Phiko segera bangkit dan menuruti permintaannya. Akhirnya Phiko mengangguk samar, memberikan mangkuk Vino agar suapannya dilanjutkan oleh Finna. Sebelum Phiko benar-benar bangkit, Finna sempat menahan lengan adiknya, menarik kuat agar daun telinga Phiko sedikit lebih dekat dengan bibirnya.
“Hati-hati, Bela itu suka sama kamu. Jadi jangan bikin jantung anak orang gak karuan.”
“Hah? Tau dari mana?”
Finna mengulum senyumnya. “Dia pernah bilang sama aku. Udah sana.” Ia mendorong Phiko. Hei, bukankah dia yang tadi menahannya?
Phiko melangkah melewati Bela. Hingga ia sudah keluar dari area kantin, barulah Phiko tersadar bahwa Bela sedang membuntutinya. Phiko menoleh sekilas ke belakang.
“Kenapa lo ikut?”
Bela tampak berusaha mengimbangi langkahnya. “Ak–aku juga dipanggil Pak Goyara.”
Phiko mengangguk pelan. Hening beberapa menit setelahnya. Phiko tenggelam ke dalam pikirannya, mengapa guru menyebalkan itu mendadak memanggilnya? Padahal nilainya akhir-akhir ini mulai meningkat daripada saat awal. Sementara Bela, ia berusaha mengatur deru napas dan jantungnya. Benar ucapan Finna, Bela menyukai Phiko sejak lama. Dahulu, gadis itu begitu benci kepada Phiko karena lelaki itu selalu menduduki posisi siswa terbaik di jurusan IPS, Bela tak kuasa menaklukkannya. Namun, seiring membesarnya rasa benci, rasa suka mendadak tumbuh di lubuk hatinya.
“Phi, aku posisi dua lho di perankingan kemarin. Selalu posisi dua lebih tepatnya,” celetuk Bela memecah keheningan.
Phiko tidak pernah tahu, tidak mau tahu. Setiap ada pengumuman ranking, asalkan ia masih peringkat satu, selebihnya tidak pernah ia baca satu per satu. Meskipun Phiko mulai terbuka dengan kedua kakaknya, bukan berarti ia bisa membuka hati untuk orang lain. Phiko menyakukan kedua tangan.
“Bagus.”
“Gue pengen ngerasain posisi satu, Phi. Selisih kita beda tipis. Gimana sih rasanya jadi posisi satu empat semester berturut-turut?” Bela mempercepat langkahnya karena Phiko seperti makin jauh.
“Biasa aja. Cenderung stress.”
Bela mengangguk setuju. Ia juga mengakui kalau menjadi seorang pemuja nilai sangatlah menenangkan.
“Lo kenapa open joki tugas?”
Bela sedikit tersentak. Phiko menghentikan langkahnya, ia amat penasaran dengan yang satu ini. Membuat Bela nyaris menabrak punggung lebar Phiko.
“Lo tau, kan, kalau yang begitu adalah curang buat kita? Buat anak pinter lebih tepatnya. Kenapa lo malah ngerugiin diri sendiri?” Phiko membalikkan tubuhnya supaya bisa melihat wajah Bela yang kini memerah. Bukan karena salah tingkah, tapi menahan emosi sendunya.
“Karena ... aku butuh uang, Phi. Ibuku udah nggak ada, Papa sakit kanker kronis. Aku memanfaatkan kepintaranku untuk cari uang tambahan.” Bela mengusap wajahnya. Lalu merogoh saku roknya, menunjukkan beberapa lembar uang. Gadis itu tertawa hambar. “Hasilku hari ini dari tugas yang kukerjakan kemarin malam. Lumayan, bisa beliin obat Papa dan makan untuk malam ini.”
Phiko menatap lekat wajah Bela. Air matanya masih berjatuhan, tapi senyumnya tak memudar. Sepertinya Bela sedang membayangkan reaksi ayahnya saat ia membawa obat dan makanan enak untuk malam nanti. Phiko mengembuskan napas gusar.
“Kenapa lo gak jualan? Atau buka jasa kayak kakak gue, Finna. Maksudnya, pertanyaan gue tetep sama, kenapa lo malah ngerugiin diri sendiri dan ngebuat orang-orang pemalas itu dicap rajin sama guru? Padahal mereka ngerjain pake duit, bukan pake otak. Mau jadi apa mereka kalau ngerjain tugas aja pake jokian? Hm?” Emosi Phiko mendadak meluap-luap. Sejujurnya, ia juga tak mengerti, mengapa dirinya bisa mempermasalahkan hal seperti ini.
Bela kembali menyakukan uang penghasilannya. Ia menghapus jejak air mata. “Aku nggak mau ninggalin Papa di rumah lama-lama. Papa selalu nemenin aku setiap ngerjain tugas. Kalau jualan ... butuh modal, Phi. Buka joki kayak gini, kamu cukup gunain otak kamu. Perihal bener atau nggak, itu urusan mereka. Dari awal, aku sama pelanggan udah ngelakuin perjanjian, berapa pun nilainya, mereka nggak bisa nuntut aku.”
Phiko tak lanjut bertanya. Lagi-lagi dirinya kalah telak. Ia harus benar-benar berhenti menuduh pekerjaan seseorang hanya dari tampilannya saja, atau dari mulut ke mulut orang lain. Ada rasa haru di dalam hati Phiko saat mendengar alasan Bela harus membuka joki tugas untuk pelajar pemalas yang banyak uang. Di satu sisi, Phiko juga merasa kalah. Selama ini, ia hanya belajar untuk dirinya sendiri, memiliki niat bekerja pun setelah menyandang gelar sarjana. Mengapa ia tidak memulai dari sekarang saja?
Bela berjalan mendahului Phiko. Lelaki itu segera menahan lengan Bela, membuat wajah Bela memerah. Kali ini bukan karena ingin menangis, tapi betulan salah tingkah.
“Bel, kita ... kerja sama, gimana?”
Bela tampak terkejut. Terlihat dari alisnya yang berkerut. Ia bahkan menarik kembali tangannya dan melangkah mundur. Merasa ada keraguan, Phiko mencoba meyakinkan lagi.
“Lo suka sama gue, kan?”
Bela semakin tersentak. Dengan cepat ia menangkap aura negatif dari pertanyaan tersebut.
“Kamu mau manfaatin aku?”
Phiko menggeleng kuat. “Nggak, nggak! Jelas nggak, Bel.” Phiko menarik napas dalam. “Gue. Gue ....”
Bela membalikkan tubuh, melangkah meninggalkan Phiko lebih dulu. Aneh, menurutnya. Kenapa Phiko jadi begini? Phiko mengetahui ia suka kepadanya, tidak cukup mengejutkan, sudah pasti tahu dari Finna, ia juga tidak keberatan jika dibocorkan. Tapi, kenapa kesannya Phiko ingin memperalat dirinya?
“Gue mau nyoba bales perasaan lo, Bel.”
Kini langkah Bela terhenti lagi. Ia termenung, mencerna kalimat yang dilontarkan Phiko barusan. Beruntung koridor menuju ruang guru kali ini tidak terlalu sepi, jadi dirinya tak terlalu menaruh malu di muka umum.
“Gue mau balas perasaan suka lo ke gue itu. Tapi, gue gak tau caranya. Gue harap, dengan kita kerja sama, perasaan lo itu bisa sedikitnya terobati.”
“Terobati?” Bela berbalik.
Phiko mengangguk. Ia menggenggam telapak tangannya sendiri. “Karena ... gue tau gimana rasanya ketika kita menyayangi seseorang, tapi orang itu nggak peduli sama perasaan sayang kita.”
Phiko mulai melangkah mendekat. Masih mengunci pandangan dengan Bela. Gadis di depannya ini cantik, rambutnya panjang dan diikat, senyumnya juga manis. Namun, kacamata yang bertengger di batang hidungnya membuat ia terkesan cupu.
“Tapi, gue gak bisa secepat itu buat balas perasaan lo. Rasa suka itu relatif, mungkin seiring waktu gue bisa suka sama lo.”
Bela menundukkan kepalanya. Menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Mungkin jantungnya berdebar tak karuan sekarang. Tapi, ia bisa mempertimbangkan penawaran Phiko.


 thisadciel
thisadciel