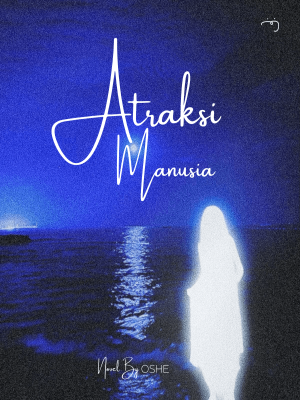“Brush.”
“Complexion.”
“Liptint.”
Hampir selama satu jam Phiko seperti seorang perawat yang tengah menemani dokternya dalam operasi. Saat pulang sekolah, Finna memperkenalkan alat-alat riasnya kepada Phiko. Dalam waktu sekejap, Phiko bisa mengenal semua nama-nama yang ada di dalam tas Finna. Mulai dari foundation hingga glitter. Phiko memang ditakdirkan memiliki ingatan yang kuat. Makannya dia bisa menduduki peringkat satu dalam empat semester berturut-turut.
“Gimana? Seru nggak?” tanya Finna. Keduanya sedang beristirahat di lobi hotel mewah langganan Finna. Biasanya, ada penghuni hotel yang butuh MUA dadakan, maka dari itu Finna siap sedia selama beberapa menit ke depan.
Phiko mengangkat bahu. “Lumayan. Klien lo gak terlalu mentingin kehadiran gue, jadi gue gak harus sok ramah kayak ajaran si Vino tuh.”
Finna tertawa mendengarnya, juga menyetujui. Memang betul kebanyakan klien menengah ke atas ini tidak banyak yang memedulikan asisten MUA. Asalkan hasil riasan sangat memuaskan, mereka tidak akan banyak protes.
“Klien tadi ngasih tip. Malem ini kita bisa makan enak. Mau makan apa? Sekalian beliin buat Bapak sama Vino.”
“Apa aja, mereka pasti makan.” Phiko menatap lantai di bawahnya. “BTW, Fin.”
Panggilan tersebut membuat pandangan Finna tertarik dari lembaran uang yang sedang dihitungnya.
“Pak Goyara tadi tiba-tiba nanya tentang lo. Dia nanya tentang kerjaan lo sebagai MUA, kisaran harga berapa, biasa ngerias ke daerah mana, bisa panggil ke tempat atau nggak.”
Finna berpikir sejenak. Memang terdengar sedikit janggal. “Mungkin, memang lagi butuh MUA. Wajar kan nanya begitu ke kamu?”
“Ada benarnya.” Kepala Phiko terangkat, menatap Finna. “Fin. Apa pun yang terjadi, lo harus telepon gue. Gue pasti bakal nyamperin lo, di mana pun lo berada.”
Phiko menghadapkan tubuhnya ke arah Finna, menggapai kedua tangan Finna dan menggenggamnya. “Gue takut, Fin. Gue ... merasa bersalah sama lo, tentang hari it—”
“Gak usah dibahas lagi, Phi,” sela Finna. Ia mengukir senyum hangat. “Aku nyaris udah lupa sama kejadian itu.”
Tangan Finna terangkat merapikan helai rambut Phiko. “Aku waktu itu nggak diapa-apain, kok. Cuman ditimpa doang. Tapi, kalau Vino waktu itu gak dateng, mungkin perlakuan Mahen sama geng-nya bakal lebih.” Finna kemudian tertawa getir. “Aku nggak nyangka, selama ini suka sama cowok begajul kayak dia.”
“Lo juga punya adik begajul, Fin.” Kantung mata Phiko mulai menggenang bulir air.
Buru-buru Finna menariknya ke dalam pelukan, membiarkan Phiko menumpahkan tangisannya di sana. Finna paham, pasti rasa bersalah masih menghantui lelaki ini. Namun, ia juga tak bisa terus menerus menutupi bahwa hari itu, ia kesal kepada Phiko. Tak bisa lagi dirinya berkata baik-baik saja. Di hati paling dalam, sejujurnya Finna merasa trauma yang mendalam. Nyaris ia tak ingin lagi bertemu dengan seorang laki-laki jika batinnya tidak memaksa untuk melawan.
“Udah, jangan nangis lagi. Mending kita pulang. Kita bawain Bapak sama Vino makanan, yuk?”
Phiko mengangguk-angguk. Merenggangkan pelukan, menghapus jejak air matanya. Tiba-tiba getaran ponsel terasa di saku celananya. Ia pikir, itu Bapak atau Vino karena sekarang sudah menunjukkan pukul sembilan malam. Namun, rupanya Bela. Selepas dari ruang guru tadi, mereka bertukar nomor, niatnya untuk saling berdiskusi.
“Halo, Bel?” Phiko menatap wajah Finna. Gadis itu malah senang bukan main, sampai bertepuk tangan kegirangan.
Akan tetapi, tak lama dari mengangkat panggilan, Phiko mendengar isak tangis di seberang sana.
“Sorry, Phi. Aku, aku nggak tau harus hubungin siapa. Finna teleponnya gak diangkat dari tadi.”
“Hey, tenangin diri lo dulu. Kenapa? Bicara pelan-pelan.”
Raut wajah Finna jelas ikut berubah. Ia mendekatkan telinganya dengan ponsel Phiko.
“Papa, Phi. Papa.” Bela kembali terisak. “Papa nggak bangun-bangun sejak aku pulang sekolah, Phi.”
Mendengar kabar tersebut, Phiko dan Finna bergegas pergi dari hotel menuju rumah Bela. Finna tahu rumah Bela, yang ternyata tak jauh dari kampung tempat tinggal mereka. Hanya saja rumah Bela ini sangat terlihat—bisa dibilang—tak layak untuk dihuni. Terbuat dari kayu yang nyaris rapuh, dekat dengan sawah dan sungai besar, belum lagi timbunan sampah yang berada tak jauh dari rumah. Bagaimana bisa Bela mendapat prestasi sebaik itu di bidang akademiknya?
Finna dan Phiko saling melempar pandang saat mereka tiba di pelataran rumah Bela. Sampai akhirnya Finna kembali mendengar tangis yang menyayat hati dari dalam, dengan segera Finna memasuki rumah tersebut.
Mata Finna membesar, begitu pula Phiko. Seorang gadis memeluk sebuah tubuh yang seluruhnya telah ditutupi oleh kain jarik. Tak jauh dari sana, terdapat dua bungkus makanan yang salah satunya telah dibuka tetapi masih utuh. Jika berdasarkan keterangan terakhir Bela saat di telepon, mereka itu pulang pukul dua siang, dan sekarang pukul setengah sepuluh. Jadi, kurang lebih tujuh jam setengah tubuh papa Bela dibiarkan begini.
“Papa tidur sewaktu aku mau pergi sekolah.” Bela menyeka air mata yang tak kunjung berhenti. “Aku nggak sangka, sejak itu Papa nggak bangun-bangun lagi.”
Oke, berarti genap lima belas jam tubuh tersebut sudah tidak bernyawa. Hal ini dibuktikan saat Phiko memberanikan diri memeriksa secara langsung. Tubuh pria paruh baya itu sudah sangat kaku, dingin, warnanya juga tak lagi seperti warna tubuh manusia pada umumnya. Bola mata jelas tak memberikan reaksi. Seharusnya tubuh ini sudah dimakamkan sejak lama.
“Kamu udah minta tolong tetangga?” tanya Finna. Ia menenangkan Bela, menjauhkannya dari jenazah papanya saat Phiko tengah memeriksa.
“Udah, dua jam lalu para warga udah kumpul di sini. Tapi, karena tau aku atau Papa nggak punya biaya dan tabungan, mereka nggak bisa melanjutkan ke prosesi pemakaman.”
Phiko memejamkan kedua mata. Tak lupa ia sempat menunduk untuk memanjatkan doa. Memang permasalahan orang zaman sekarang memang begitu, uang. Bahkan mati pun membutuhkan uang. Bapak sering mewanti-wanti untuk senantiasa membayar iuran warga, sebab sebagian dari bayaran mereka akan dialokasikan untuk dana kematian.
Bela melepaskan rangkulan Finna. Merangkak mendekati jenazah papanya. Gadis yang masih memakai. “Tapi, kalau Papa nggak dimakamkan juga gapapa. Aku bisa berdampingan dengan Papa meskipun begini, sampai aku mati.”
“Jangan begitu, Bel.”
Bela kembali menangis, mempererat pelukannya dengan jenazah papanya. Sementara Finna terus berusaha melepaskan pelukan tersebut. Tak tega pula ia melihat temannya nelangsa begini. Bagaimana pun Finna mengenal Bela adalah seorang gadis ceria yang berprestasi dan pandai menyembunyikan latar belakang serta rahasianya.
Di belakang, Phiko mencoba memanggil seseorang. Kakak sulungnya. Phiko memberitahu papa Bela telah meninggal dan butuh biaya untuk pemakamannya.
“Gue ngumpulin duit buat lo, buat masa depan lo, buat kuliah lo. Maaf, tapi bukan buat Bela,” sewot Vino di seberang sana.
“Bukan, No. Bukan uang lo, bukan tabungan lo.” Phiko menghirup napas dalam, meski yang tercium adalah bau tak sedap di sekitar rumah.
“Tabungan gue. Tolong bawa ke sini.”
Vino terdiam di seberang sana. Mungkin, ia juga sempat terpikir untuk menolak suruhan Phiko. Tetapi, Vino juga yakin adiknya itu akan keras kepala. Mengingat siang tadi, Phiko memberitahu para kakaknya, bahwa ia memilik niatan untuk membalas perasaan Bela. Bisa jadi ini pengorbanan pertama Phiko untuk Bela.
Vino akhirnya datang diantar Bapak. Dengan berbaik hati, Bapak ikut mengurusi proses pengurusan jenazah, begitu pula dengan Phiko. Memandikan, mengkafani, hingga menyalatkan.
Para warga kembali berkumpul di rumah duka, tetapi lebih sedikit karena hari sudah sangat larut. Proses pemakaman juga terpaksa dilakukan esok hari. Phiko hanya berharap, tabungannya itu tidak dipergunakan atau dikorupsi oleh petinggi kampung ini.
“Sepertinya, besok aku izin. Aku mau nemenin Bela di sini. Kalian pulang aja,” suruh Finna, menghampiri keluarganya yang menunggu di selasar rumah dengan alasan di dalam dipenuhi aroma kapur yang terlalu menyengat.
“Bela itu tinggal sendiri? Keluarganya? Atau saudaranya yang lain, ke mana?” tanya Bapak.
Finna mengangguk. “Bela anak tunggal. Ibunya udah nggak ada sejak dia dilahirkan. Bela diurus sama papanya seorang diri. Katanya, saudaranya yang lain udah nggak peduli sama keluarga Bela. Mungkin karena ... keluarga Bela miskin.”
“Hush, gak boleh ngomong gitu!” peringat Vino.
“Tapi, emang itu yang dibilang Bela barusan.”
Phiko mengalihkan tatapannya, menatap pada Bela yang terlihat dari sini. Ia terbaring di sebelah jenazah papanya, sama seperti tadi. Bedanya kali ini papa Bela sudah siap dimakamkan, dan Bela dilarang meneteskan air mata di atas kain kafan tersebut.
“Ternyata, kita masih kebilang beruntung, ya, Phi. Tetangga kita baik. Kita juga masih bisa bekerja dan ngehasilin uang buat sehari-hari.” Finna berdecak pinggang. Ia memang sengaja menjurus kepada Phiko seorang. Sesaat setelahnya, Finna mendadak memeluk tubuh gempal ayahnya dengan erat. “Bapak jaga kesehatan, ya? Lihat kami sukses ketika dewasa nanti. Kita juga bakal bikin Bapak tinggal di apartemen kayak Ibu.”
Bapak tertawa kecil, membalas pelukan putrinya.
“Iya, Bapak akan sehat demi kalian. Kalian pun harus saling menjaga diri, ya? Saling menyemangati, saling ada satu sama lain.”
Tatapan Phiko kini beralih kepada Finna dan Bapak. Mereka berpelukan penuh kasih sayang. Jelas tersirat bahwa Finna mengkhawatirkan Bapak. Bapak membalas tatapannya, mengulurkan tangan untuk menawarkan pelukan. Jelas Phiko menerimanya, Vino juga ikut masuk ke dalam pelukan Bapak.
Tangan Bapak kini mendarat di pucuk kepala Phiko. “Tabunganmu itu, InsyaAllah ada gantinya nanti ya, Nak. Kamu anak baik.”
Phiko hanya terdiam di dalam dekapan keluarganya. Sesekali matanya mengintip lagi ke ambang pintu rumah Bela. Membayangkan bagaimana jika Phiko berada di posisi Bela, sedangkan satu-satunya keluarga yang dekat dengannya selama ini hanyalah Bapak.
Bapak itu orang baik. Ia menawarkan Bela tempat tinggal. Bukan di rumahnya, tetapi di pasar, menjaga tokonya, menjadi karyawannya. Bapak sadar, anak-anaknya pasti setelah ini akan lebih posesif kepadanya, disuruh menjaga kesehatanlah beristirahatlah, atau bilang jangan sampai kelelahan. Selama Bela berada di toko, Bapak sudah mulai jarang berlama-lama di pasar. Jika biasanya Bapak pulang sekitar jam lima sore, sekarang Bapak bisa pulang jika Bela sudah pulang sekolah. Ia memilih menghabiskan banyak waktunya di rumah, menunggu anak-anaknya pulang dengan selamat, dan menjadi pengurus masjid setempat. Umur Bapak memang belum lima puluh tahun, tapi ia benar-benar memanfaatkan waktunya senjanya mulai dari sekarang dengan kegiatan yang sangat bermanfaat.
Sudah dua minggu Bela tinggal di toko Bapak, sudah dua minggu pula ia kehilangan papanya, dan sudah dua minggu rumah Bela di kampung diratakan oleh warga setempat. Padahal, bisa saja Bela menindaklanjuti masalah ini ke jalan hukum, ia memiliki surat tanah dan surat milik. Namun, apa daya, ia tidak bisa menentang keputusan warga setempat. Kini rumah lapuk tersebut dijadikan sebuah tempat penampungan sampah setelah dihancurkan. Jahat, bukan? Memang sedari awal para warga sudah berniat menjadikan kandang sampah di sana, terlihat dari awal mereka sengaja menimbun sampah di sebelah rumah.
Triplets tidak ingin mengungkit dosa yang telah keluarga Bela lakukan, tapi Bapak inisiatif bertanya kepada ketua RT. Katanya, papa Bela itu dikenal sering meminjam uang kepada para warga. Tetapi, tak lama pasti dikembalikan. Hingga almarhum mulai sakit, uang-uang yang dipinjam tidak bisa lagi cepat kembali karena papanya tidak dapat bekerja. Para warga marah, terlebih warga kampung sana dikenal sebagai warga dengan individualismenya tinggi.
Bisa dibandingkan dengan kampung tempat tinggal Bapak dan anak-anak sekarang. Mereka baik, ramah, dan penyayang. Saat Vino kecelakaan, mereka berbondong-bondong datang dan mendoakan Vino. Hari ini, kampung sedang mengadakan syukuran untuk para petani yang ladangnya sedang ditaburi kesuburan. Bapak sedang membantu di sana sedari pagi. Pada pukul sepuluh, barulah triplets menyusul.
“Panggil Bela, ajak dia ke sini. Tutup aja tokonya,” suruh Bapak setelah melihat anak-anaknya memasuki pelataran rumah Pak RT. Ia sibuk sekali, mondar-mandir, menenteng barang yang akan digunakan untuk syukuran siang nanti, seperti kitab suci, camilan.
Mendengar itu, Finna mendengkus sebal. “Bisa-bisa posisi aku digantikan oleh Bela.”
Phiko dan Vino kompak tertawa. Mana mungkin Bapak tega menggantikan anak kandungnya dengan anak orang yang baru akhir-akhir ini bertemu ... kan? Sungguh tidak mungkin.
Di sekolah, mereka tidak terlalu dekat. Namun, sesekali Bela sengaja menunjukkan kedekatannya. Seperti saat ada orang yang ingin menggunakan jasa joki Bela hari ini, tepat di kantin sekolah.
“Ada dua paket. Paket regular sama premium,” ucap Bela menawarkan.
Phiko menatap Bela dari kejauhan. Kebetulan kantin siang ini tidak begitu ramai, jadi ia bisa mendengar jelas percakapan meski dalam jarak beberapa meter. Herannya, entah sejak kapan Phiko bisa jadi penghuni kantin setiap jam istirahat.
“Bedanya apa? Berapa?” tanya gadis di depannya.
“Kalau regular itu harga normal. Sementara yang premium, tambah dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu. Soalnya ....” Pandangan Bela teralih kepada Phiko, mata mereka bertemu. “Yang premium itu hasil kerja aku sama peringkat pertama angkatan.”
Gadis itu mengulum senyum, pipinya mulai bersemu kemerahan. Phiko juga ikut-ikutan tersenyum. Sepertinya perasaan suka itu mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Sejauh ini, sudah ada dua pelanggan yang memakai jasa premium Bela. Membuat makalah. Lumayan, sudah terkumpul lagi sebanyak enam puluh ribu untuk tabungannya.
Perut Phiko mendadak berputar. Ia mengerutkan keningnya. Phiko meremas perutnya kuat-kuat, menarik perhatian dua kakaknya yang berada di seberang tempat Phiko terduduk.
“Kenapa, Phi?” tanya Finna.
Phiko menggeleng kuat-kuat. Ia memejamkan mata, berharap rasa sakit itu dapat mereda. Dua kali. Namun, makin lama perutnya makin sakit. Lelaki itu bangkit, setengah berlari menuju kamar mandi. Sesampainya di salah satu bilik, Phiko langsung memuntahkan isi perutnya. Sarapan yang ia makan pagi tadi, dan makan siang yang baru termakan setengah di kantin, semua keluar begitu saja. Terasa pahit dan asam. Kepala Phiko juga pening. Ia tak kunjung berhenti memuntahkan isi perut.
“Phi, lo kenapa?”
Akhirnya Phiko berhasil menarik napas. Udara di paru-parunya habis karena sibuk memuntahkan isi perut. Phiko menekan tombol flash. Saat berbalik, Vino sudah ada di belakangnya, menatapnya dengan raut wajah khawatir. Phiko mencoba berjalan mendekat, tapi tubuhnya langsung ambruk karena terlalu lemas.
“Eh, Phi! Phi!”
“Gue, gue gapapa, No.” Phiko berusaha bangkit. Ia merangkak mendekati kursi roda Vino. “Kayaknya masuk angin.”
Vino mengembuskan napas gusar. Ia berupaya meraih tangan adiknya, membersihkan dari kotoran yang menempel di seragam adiknya.
“Jangan banyak pikiran. Gue nggak mau lo sakit, Phi. Lo juga jangan telat makan, gue khawatir lo punya asam lambung.”
Phiko mengangguk mengerti. Lantas lelaki itu berusaha bangkit. Mendorong kursi roda kakaknya agar keluar dari kamar mandi.
Dua kali, dua kali sudah tubuhnya mengalami keanehan seperti ini. Mulai dari mimisan hingga memuntahkan makanan. Tapi untuk mual, sering terjadi berkali-kali. Kepala Phiko sering pula terasa pening. Tidak, Phiko tidak boleh sakit. Kalau Phiko sakit, ia tak bisa mencari uang untuk kakak-kakak dan Bapak.
Mereka sering pulang bersama. Berjalan kaki menuju toko buku Bapak. Vino juga sudah memulai membuka jasa servis komputer dan laptop di toko Bapak. Phiko benar-benar jadi asistennya Finna, ia mulai menyukai pekerjaan ini. Klien juga banyak yang memberikan bonus. Tapi, tetap saja saat dini hari Phiko harus ke pasar untuk membantu Armor. Kasihan lelaki itu, bekerja sendirian. Akan tetapi, meskipun Phiko menyukai pekerjaan sebagai asisten MUA, ia tetap tidak merasa bahwa hal tersebut merupakan bagian dari jati dirinya.
“Tadi kamu kenapa?”
“Hm?” Kepala Phiko terangkat dari fokusnya menatap jalan setapak.
Bela yang ada di sebelahnya memiringkan kepala. “Tadi kamu tiba-tiba lari dari kantin. Finna bilang, kamu muntah di kamar mandi. Kenapa?”
Phiko menyisiri rambut. Jujur lelaki itu tampak gugup menghadapi seorang perempuan yang terang-terangan menyukainya.
“Cuman ... nggak enak badan.”
Bela mengembuskan napas gusar. “Jaga kesehatan, Phi. Aku nggak mau kehilangan orang yang kusayangi lagi.”
Phiko menoleh cepat. “Lo sayang gue?”
Yang ditanya hanya mengulum senyum, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Seharusnya Phiko tidak boleh bertanya seperti itu, jelas membuat jantung anak orang berdegup kencang.
“Lihat tuh adikmu, dia mulai jatuh cinta,” ucap Finna yang berada tak jauh dari sepasang remaja tadi.
Vino hanya tertawa renyah.
Sesampainya di toko buku Bapak, Bapak langsung berpamit pulang setelah menyelesaikan transaksi dengan pelanggan terakhirnya. Finna dan Phiko sempat beristirahat sejenak di toko, sampai pukul lima mereka juga pamit hendak mendatangi pelanggan di salah satu kompleks.
Waktu sudah menunjukkan pukul tujuh malam. Tidak ada pelanggan lagi yang melakukan booking kepada MUA Finna. Hari ini mereka hanya melayani satu pelanggan, tapi hasilnya lumayan. Seorang gadis yang hendak mendatangi dinner party. Kebanyakan pelanggan Finna memang untuk keperluan makan malam yang sangat spesial, sebab waktu yang Finna miliki memang hanya sepulang sekolah saja. Bisa dibilang, Finna adalah spesialis riasan dinner party.
“Mau makan apa?”
“Hah?” Phiko sedikit berteriak. Riuhnya jalanan membuat suara Finna di belakangnya menjadi samar.
“Malam ini, mau maka apa?” Finna meninggikan nada bicara.
“Ohh, nggak usah. Bapak udah masak di rumah.”
“Masak apa?”
“Hah?”
“Bapak masak apa?!”
“Perkedel kentang!”
“Ihh, tumis kangkungnya masak nggak?”
“Hah?”
Habis sudah kesabaran Finna karena harus mengulang-ulang pertanyaan. Refleks ia memukul helm Phiko cukup kuat. Mengedarkan pandangan ke jalanan dan menulikan pendengaran dari Phiko yang terus mengomel karena telah dipukul kepalanya. Tak lama, getaran ponsel terasa di saku jaketnya. Finna segera meliriknya.
“Phi, kayaknya kita harus ke hotel sekarang. Mas Pamma manggil aku nih, katanya ada klien yang nyariin.”
“Okey.” Phiko langsung membelokkan kemudi Si Bekjoel.
Finna mendelik. Giliran urusan uang, Phiko malah cepat tanggap dan bisa mendengar dengan jelas.
Sesampainya di hotel berbintang lima itu, Finna dan Phiko bergegas menghampiri Mas Pamma di resepsionis. Menanyakan tamu dengan kamar nomor berapa yang sedang membutuhkan jasanya.
“Empat puluh lima, Fin.”
“Baik, Mas. Makasih, yaa. Ayo, Phi.” Finna segera menarik tangan adiknya.
Mereka menyusuri koridor, memasuki lift untuk bisa sampai ke lantai empat. Tidak ingin tertinggal makan malam dengan makanan lezat yang sudah terbayang-bayang, Finna harus bergegas merias wajah seseorang yang belum diketahui identitasnya ini.
“Ah, aku lupa!” Finna memecah keheningan di dalam lift. “Belum beli obat buat Bapak bulan ini. Pulangnya kita melipir ke rumah sakit dulu ya, Phi.”
Finna merogohkan tangan ke dalam tas sekolahnya. “Duh, resepnya dibawa nggak ya. Nah, ini ketemu. Tolong sakuin, Phi. Biar nanti nggak perlu buka tas lagi.”
Phiko terdiam memandangi kertas berisi resep obat yang selalu dibeli setiap awal bulan itu. Cukup banyak. Bapak makan obat sebanyak ini? Lebih penting, setiap bulan Finna harus membeli obat sebanyak ini? Sudah pasti harganya tidak murah.
“Gue aja yang beli obat Bapak. Gue punya uang dari hasil kerja gue.”
“Nggak boleh, Phi,” tolak Finna. “Aku sama Vino udah sepakat. Aku urus Bapak, Vino urus kamu. Nggak bisa, nggak bisa! Uangmu itu harus ditabung buat kamu sendiri. Itu, kan, kerja kerasmu.”
“Tapi, ini juga kerja keras kalian. Kalian juga perlu keperluan sendiri, butuh hiburan sendiri. Kalian juga harus makan uang hasil kerja kalian.”
Finna menatap adiknya lekat. Lantas ia tersenyum hangat, menepuk pelan punggung tegap Phiko yang jauh lebih tinggi darinya. “Hiburan kita itu melihat kamu sama Bapak bahagia. Udah cukup.”
Memalukan. Lebih tepatnya, Phiko malu kepada diri sendiri. Ketika kedua kakaknya bekerja keras untuk menghidupi rumah, Phiko malah sibuk dengan menuduh dua kakaknya yang buruk-buruk. Phiko membuang pandangan, menyembunyikan air mata yang hampir membasahi pipi.
“Kapan-kapan, gue mau ajak kalian main ke Dufan,” ujar Phiko. “Gue mau ajak kalian pindah ke Bandung atau Jogja waktu kuliah nanti. Gue mau kalian nyantai di rumah dan nikmatin hasil kerja gue nanti.”
Finna melongok, berusaha menatap wajah adiknya yang berujung nihil. Finna tertawa melihat tingkah adiknya.
Pintu lift pun terbuka tepat di lantai empat. Keduanya segera berjalan menuju kamar yang Mas Pamma sebutkan tadi. Saat tiba di depan, Finna mengetuk-ketuk pintu.
“Jasa rias Finna,” ucapnya.
Entah mengapa jantung Phiko berdebar tak karuan. Perasaannya berkata, bahwa hal buruk akan segera terjadi di depannya. Phiko sempat menggenggam pergelangan tangan Finna, dan gadis itu malah berkata bahwa semua akan baik-baik saja.
Pintu kamar perlahan terbuka, menampilkan seorang wanita dengan postur tubuh cukup proporsional.
“Silahkan masuk dulu. Tolong tunggu di dalam ya, saya mau ke depan untuk membeli sesuatu.”
Phiko dan Finna menurut. Keduanya menunggu di ruang sofa. Mewah sekali hotel ini, ada dapur dan sofa dengan televisi. Sudah bisa dikatakan apartemen. Finna memeriksa perlengkapan riasnya, sementara Phiko terus bersiaga sembari mengawasi sekitar.
“Fin, pulang, yuk. Cewek tadi udah lama banget perginya. Gimana kalau dia mau ngejebak kita?”
“Tenang, Phi. Semua akan baik-baik aja.”
Phiko menghembuskan napas gusar.
Suasana melenggang. Hanya detak jarum jam yang terdengar oleh mereka. Tunggu, sejak kapan hotel memasang jam dinding? Bukankah ini terlalu janggal? Kamar-kamar yang sempat didatangi sebelumnya saja tidak ada yang memasang jam dinding. Phiko menatap jam tersebut yang menggantung di atas televisi. Mengamatinya dengan lekat.
Phiko menyipitkan kedua mata, tepat saat jarum panjang mengarah ke angka dua belas, bersamaan dengan jarum detik, Phiko melihat siluet seseorang di belakangnya. Phiko segera bangkit. Dan ...
Bugh!
Orang itu memukul kepala Phiko dan Finna. Lelaki itu meringis kesakitan. Ia berusaha mengendalikan pandangannya yang sepat memburam.
“Fin, Fin!” Phiko merangkak mendekati kakaknya. Namun, sesaat kemudian kakinya dipukul oleh seseorang. Phiko berteriak kuat.
“Siapa kalian?” Phiko berusaha melihat ke belakang, nyatanya ada lebih dari dua orang berpakaian serba hitam mengitari ia dan kakaknya. Dua orang dari mereka bahkan menarik Finna yang tak kunjung sadarkan diri.
“Cacatkan, jangan dibunuh.”
Mata Phiko membesar saat salah satu orang itu memerintah. Dua orang yang berada di dekatnya mulai menyiksa, tapi pandangan Phiko tertuju pada kakaknya. Orang-orang itu membentur-benturkan kepala Finna ke pegangan kursi yang terbuat dari kayu. Sementara orang di dekat Phiko menendang-nendang tubuh ringkih itu.
Kepala Phiko mula terasa pening. Perutnya kembali berputar. Ia memaksa kepalanya untuk berpikir. Kenapa tidak ada orang yang datang? Kenapa tidak ada yang mendengar jeritannya? Kalau Vino di sini, apa yang akan lelaki itu lakukan? Apa? Apa?
Phiko mengembuskan napas panjang. Dengan keberanian yang telah dikumpulkan, ia menarik kaki pria yang menendang perutnya, lantas digigit dengan sangat kuat. Pria itu terjatuh, Phiko mengambil kunci motor yang berada di sakunya, menusuk luka bekas gigitannya hingga mengeluarkan banyak darah. Tak sampai di situ, Phiko menendang kemaluan orang yang tadi memerintah.
Masih ada tiga orang lagi. Ia tak sanggup jika harus melawan semuanya. Cara terakhir. Phiko bersusah payah berdiri, keluar dari kamar dan berteriak sekencang mungkin.
“TOLONG, ADA PERAMPOKAN DI SINI, TOLONG!”
Lima orang pria itu gelagapan, terlebih saat petugas hotel dan tamu mulai berdatangan. Beberapa ada yang kabur melalui jendela, dua orang mulai dibekuk oleh petugas hotel. Para tamu banyak yang memanggil polisi.
Phiko mendekati kakaknya. Finna bersimbah darah, keluar dari belakang kepalanya. Phiko menangis melihat nasib kakaknya seperti ini.
“Bangun, Fin. Bangun.” Phiko terus mengguncang tubuh Finna yang terkapar lemah tak berdaya. Tangannya yang lain berupaya mencari ponsel dari jaket.
“No, tolong kita, No.”
“Aku pulang.”
“Loh? Sendirian? Phiko sama Finna mana, No?” tanya Bapak terheran melihat putra sulungnya datang seorang diri.
“Hm? Kukira mereka udah pulang duluan dan lupa sama aku, Pak.” Vino mengedarkan pandangan. Ternyata kedua adiknya itu benar-benar tidak ada di rumah. “Tadi aku dianterin Bela, Pak.”
“Terus Bela-nya mana?”
“Udah balik lagi ke pasar.”
“Padahal ajak makan malam di sini. Adik-adikmu itu barusan bilang udah di jalan pulang, tapi nggak ngabarin lagi sampai sekarang.”
Vino mengangguk-angguk. “Mungkin masih di jalan.”
Pandangan Vino teralih kepada kedua tangan Bapak yang kotor dan berminyak, terdapat bulatan adonan juga di tangan kanannya. Terlebih Bapak barusan berjalan dari dapur. Wajah Vino berubah semringah, sepertinya sebentar lagi ia akan menyantap makan malam.
Bapak kembali ke dapur. Vino segera memutarkan roda kursinya untuk mengejar.
“Bapak lagi masak apa?”
“Perkedel kentang untuk Phiko. Kamu mau telur apa?”
Vino mengulum bibirnya. “Kalau aku mau telur balado, boleh, Pak?”
Bapak menatap Vino, memberikan putra sulungnya itu seyuman. Lalu Bapak membuka kulkas kecil yang berada tak jauh dari sana, memeriksa perbumbuan.
“Boleh. Tolong bantu Bapak merebuskan telur-telurnya.”
Vino mengangguk senang. Bersusah payah ia mengambil panci yang berada di rak tinggi. Andaikan ia tidak duduk di kursi roda, mungkin rak tersebut masih mudah dijangkau olehnya. Mungkin, mulai besok Vino harus berlatih memakai kaki palsu. Tak apa belum genap dari jarak setelah operasi, tak apa tangan kanannya juga tidak dapat digunakan. Duduk di kursi roda lebih membuatnya jadi beban untuk orang-orang sekitar ketimbang tangan kanan.
“Rebus berapa, Pak?”
“Lima. Dua untukmu.”
Vino semakin kegirangan. Lelaki itu memasukkan lima butir telur ke dalam panci. Vino berpamit ingin ke kamar dahulu. Ia mengambil kaki palsu yang lama teronggok di bawah kasurnya. Seutas senyum tergambar di wajah. Vino memakai kaki palsu tersebut. Ah, ia bisa membayangkan bagaimana reaksi adik-adiknya dan Bapak saat melihat Vino sudah lihai memakai kaki palsu nanti. Sebenarnya, malam-malam ini Vino sering kali berlatih untuk memakainya, tapi tak cukup serius karena tidak ada yang bisa membantu.
Kaki palsu telah terpasang, perlahan Vino bangkit dari duduknya. Vino mulai melangkah sedikit demi sedikit. Senyumnya mengembang lebar sekali. Sedikit lagi dirinya bisa mengendalikan kaki buatan manusia ini.
Vino dikejutkan oleh getaran ponsel di saku celananya, membuat dirinya terjatuh dengan kasar.
“Kenapa, No?”
“Eng–nggak apa-apa, Pak. Cuman buku-bukuku jatuh.”
“Hati-hati, Nak.”
Vino merogohkan tangan ke dalam saku celana. Mengangkat panggilan yang ternyata dari Phiko.
“Kenapa, Phi? Lo di mana dah? Kenapa belum pulang?”
Wajah Vino berubah mengeras saat mendengar isak tangis dari seberang sana.
“No, tolong kita, No. Kita diserang.”
“Diserang gimana? Lo di mana? Siapa yang nyerang?”
“Gue nggak tau, No. Tolong. Finna nggak bangun-bangun dari tadi.”
“Lo di mana sekarang? Kirim lokasinya. Gue ke sana sekarang.”
Phiko mematikan panggilan sepihak. Vino mengumpat dalam hati. Kesal. Ia memukul kedua kakinya. Andaikan ia tak cacat, mungkin sampai sekarang dirinya masih bisa menjadi pelindung untuk adik-adiknya. Vino menggigit bibir bawahnya dengan kuat, menahan amarah terhadap diri sendiri.


 thisadciel
thisadciel