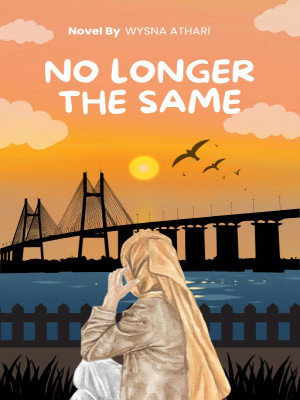“Aku pulang!”
“Stt! Jangan berisik,” peringat Vino, sesaat setelah adiknya masuk ke ruang rawatnya dengan suara yang sangat menggelegar. Vino melirik adiknya yang terbaring di kasur. “Dia baru tidur jam satu siang.”
“Hah? Maksudnya, dari semalem Phiko gak tidur?”
Vino mengangguk membenarkan. Vino semalaman sesekali terbangun karena kedua kakinya merasakan panthom pain yang sangat menyiksa. Dan setiap kali Vino bangun, ia mendapatkan Phiko selalu berada di sampingnya. Apalagi kalau bukan tidak tidur? Anak itu sudah jago menahan kantuk, biasanya demi belajar. Phiko bertanya apa keluhan
“Kantung mata dia item banget, kayak setan.”
“Ngaca!” Finna membelalakkan kedua matanya.
Finna adalah saksi bahwa Vino juga jarang sekali tidur. Adik dan kakaknya ini memang aneh. Padahal, selarut-larutnya Finna pulang ke rumah, ia masih bisa tidur minimal lima jam. Kalau kurang pun Finna akan menyempatkan diri tidur di kelas jikalau jam istirahat atau sedang tidak ada guru. Belum lagi Finna juga sering memakai skincare, jadinya kantung mata Finna tidak berubah hitam.
“Udah makan?” Finna menyimpan dua tas sembarangan di lantai. Lalu menghampiri Vino, mencium keningnya penuh kasih sayang. Phiko tidak tahu, bahwa kedua kakaknya ini masih mempertahankan aktivitas cintanya—saling mencium dengan batas wajar—hingga usia remaja.
“Terakhir tadi pagi. Disuapin Phiko. Belum ada perawat yang dateng nganterin makan lagi.” Pandangan Vino tertarik dengan tas yang barusan dibawa Finna. “Kapan ambil tas Phiko?”
“Barusan, pulang sekolah. Aku nyempetin diri ke apartemen Ibu, jenguk sekalian bawa barang-barang Phiko. Ibu punya bayi, No! Dan Ibu gak kasih tau ke kita. Padahal aku suka bayi, harusnya Ibu tau.”
“Phiko udah ngasih tau aku. Bahkan dia kemarin tidur di gudang karena di sana gak ada kamar lagi.”
Finna mengangguk paham. Ia juga tahu karena saat dirinya meminta barang Phiko tadi, Ibu menyuruh Finna untuk mengambilnya sendiri. Finna perlahan duduk di tepi kasur Phiko, berhati-hati sekali, takut adiknya akan terbangun. Finna mengusap surai hitam Phiko yang menutupi wajahnya. Lelaki itu meringkuk, wajahnya tertutup oleh bantal yang dijadikan guling.
“Jangan pikirin Ibu lagi, Fin. Tugas kita fokus bahagiain Bapak sama Phiko aja. Ibu udah bahagia sama pilihannya.”
Finna mendekatkan wajahnya dengan wajah Phiko. Untuk pertama kali setelah tiga tahun menjaga jarak, Finna akhirnya bisa kembali mencium kening Phiko selayaknya seorang kakak yang menyayangi adiknya.
Awal mula Finna dan Vino bekerja sama menyembunyikan pekerjaan mereka di depan Phiko, ialah ketika melihat Phiko pertama kali menjadi pemurung. Mereka mengenal Phiko sebagai anak yang ceria meskipun cukup pendiam, tidak banyak bicara. Namun, hari di mana triplets ikut hadir di pernikahan Ibu, Phiko tak lagi mau bicara. Phiko lebih banyak mengurung diri di kamarnya, dan berusaha menjadi yang terbaik di setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, Finna dan Vino sepakat untuk tidak mengajak Phiko bekerja seperti mereka. Bapak tahu karena Finna dan Vino tak mungkin merahasiakan perkara ini di depan orang tua sendiri.
“By the way, sirkel kamu bakal jenguk sore nanti, No.”
Vino langsung mengumpat dalam hatinya. Ia mengusap wajah dengan kasar. Sejujurnya, Vino belum siap melihat reaksi kawan-kawan dekatnya yang berjumlah enam orang itu terhadap kondisinya. Tak berkaki, tangan kanan seperti orang stroke. Sementara keenam kawannya adalah manusia yang nyaris sempurna. Tampan rupawan, tajir menawan, dan kepercayaan diri setingkat dewa. Vino masih belum bisa berdamai dengan keadaannya.
Phiko menggeliat dari kasur yang ditidurinya. Bising sekitar kamar mengusik tidur lelapnya. Sebenarnya, Phiko tidak tertidur nyenyak. Ia masih bisa mendengar percakapan kedua kakaknya meski sayup-sayup. Namun, ketika sekelompok manusia yang Phiko lihat di pasar kemarin sore datang, tidurnya tak bisa lagi dilanjutkan. Perutnya juga lapar. Phiko memutuskan tersadar. Phiko melihat ke sekitar, banyak sekali pemuda yang memakai seragam putih abu. Mereka bergelak tawa, sebagian terdengar mengunyah sesuatu. Phiko tak habis pikir, mengapa anak-anak itu bisa terlihat santai? Padahal mereka berada di akhir tingkatan sekolah. Phiko ini sedang belajar merelakan ambisi yang terlalu menggebu.
“Phi? Udah bangun?”
Panggilan itu menyadarkan lamunan Phiko, juga menarik perhatian pemuda di ruangan itu. Seketika semua lelaki menghening, menolehkan wajahnya ke arah Phiko dan Finna yang datang menghampiri.
“Mau makan? Aku beliin kamu nasi padang.” Finna mengulurkan plastik hitam berisi bungkusan makanan.
Phiko mengangguk berterima kasih. “Gue makan di kantin aja.”
“Di sini aja. Kita udah makan kok, gak akan nyolong,” celetuk Armor.
Phiko jadi tidak enak, bingung juga memutuskan harus apa. Semua mata memandangnya sekarang. Phiko hanya bisa mengangguk samar dan beranjak duduk di atas matras.
Phiko mulai melahap nasi padang dengan lauk rendang dan perkedel kentang. Ditemani Finna. Gadis itu sudah makan sejak lama. Finna juga sempat memberitahu jika barang milik Phiko sudah dibawa dari apartemen Ibu. Tiba-tiba Finna mengangkat tangan, membersihkan sudut bibir Phiko.
“Jangan anggap gue anak kecil, Fin. Kita seumuran.”
Finna malah terkekeh geli. “Nggak ada yang liat.”
Phiko tidak mengindahkannya, lanjut melahap nasi padang hingga butir terakhir. Tepat saat itu juga, Armor ikut duduk bergabung.
“Denger-denger, lo udah deket lagi sama kakak lo.”
Phiko tidak menggeleng, tidak juga mengangguk. Ia tak bisa menentukan apakah seperti ini merupakan usaha untuk menjadi dekat dengan kedua kakaknya, atau justru sebaliknya.
“Artinya, gue juga bisa deket lagi sama lo?” tanya cowok berambut ikal itu.
“Yang nyuruh ngejauh siapa?” sindir Phiko, membuat Armor bergidik.
“Gu–gue lebih deket sama Vino karena kita sekelas, Phi. Tapi, lo tetep sahabat gue, kok.” Armor merangkulkan tangannya di atas bahu Phiko.
“Sejak SMA, gue gak punya temen, Mor.” Phiko menyingkirkan rangkulan Armor. “Lo mau deketin gue dan ngejauh dari Vino karena dia cacat?”
Pertanyaan itu jelas didengar oleh Vino dan keenam temannya yang lain, sebab mereka tiba-tiba menghening. Entahlah, Phiko memiliki perasaan tidak enak kepada Armor atau kelima lelaki asing ini. Dari wajahnya saja sudah menunjukkan kalau mereka menjenguk hanya untuk formalitas belaka. Tidak ada buah tangan. Bahkan candaan pun terdengar dipaksakan. Phiko yakin, Vino terlalu baik untuk mereka. Justru yang membuat Phiko sampai berpikiran burik tentang Vino, ialah karena Phiko tahu bahwa Vino bergaul dengan kelompok ini.
“Kita pamit dulu ya, No. Cepet sembuh. Kita semua kangen ada lo di sekolah.” Armor dan kelima temannya berpamitan setelah menghabiskan lima belas menit waktu besuk.
Vino berdecak kasar. “Lebay, baru juga sehari.”
Mereka tertawa kecil, sampai akhirnya benar-benar hilang dari pandangan. Pintu kamar kembali menutup rapat. Tidak ada lagi manusia selain kedua kakaknya di ruangan ini. Akhirnya Phiko bisa merebahkan tubuh di atas kasur tadi. Kalau dipikir-pikir, ini momen pertama setelah sekian lama ketiga anak kembar itu berkumpul kembali. Pasti akan terasa canggung. Phiko mengulurkan tangan, meraba tas untuk mencari laptop miliknya. Setelah ketemu, Phiko meletakkan laptop tersebut di kasur, tepat di atas kepalanya. Phiko lantas membalikkan tubuh sampai tengkurap. Sebuah tindakan yang tidak boleh ditiru!
Phiko belum belajar. Sedari kemarin, Phiko belum belajar. Ini demi belajar. Lagipula, tidak ada lagi meja di ruang rawat ini, selain meja untuk pasien makan yang terhubung dengan brangkar, juga meja nakas. Saat Phiko baru saja menyalakan laptop, Finna tiba-tiba ikut tengkurap di sebelahnya.
“Ada Netflix gak? Coba sini cari, N E T F L I X.” Finna mengejanya sembari menekan huruf. Sebuah web aplikasi untuk menonton film pun muncul di layar laptop Phiko untuk pertama kali. Setelah bertahun-tahun Phiko miliki hanya untuk belajar, sore ini, layar itu menawarkan tayangan video drama. Laptop tersebut bekas, tapi cukup jika hanya mengakses laman belajar. Phiko membelinya menggunakan uang hasil tabungan.
“Weak Hero katanya rame. Kita harus nonton dari season satu, Phi.”
“Gue mau belajar, Fin.”
Finna mengibaskan tangan. “Nanti aja belajarnya. Besok juga jamkos. Kamu harus nonton drakor ini. Tokoh utamanya mirip kamu, culun tapi ambisius ngejar nikai sempurna. Seru pokoknya.”
Phiko menatap wajah samping kakak perempuannya. Cantik. Phiko tak mengira Finna memiliki paras yang nyaris dikatakan sempurna. Dan ... ia pernah membuat paras cantik itu diciumi seorang lelaki tak berperi kemanusiaan seperti Mahen tempo lalu. Phiko tak bisa memaafkan tindakannya.
“Seru? Lo ... udah pernah nonton?”
“Pernah. Di laptopnya Gina. Tapi baru episode satu.”
Bagaimana pun Phiko harus berusaha mendekatkan diri kepada kakaknya. Selama ini Finna dan Vino memberikan rasa kepedulian yang dicampakkan Phiko.
Suara khas opening Netflix mulai terdengar. Phiko belum bisa menikmati tontonannya. Lebih tepatnya, pikiran Phiko masih kalut dengan masa lalu. Phiko selalu menghukum dirinya sendiri—dengan mengerjakan seratus soal latihan—jika semalam saja tidak belajar. Apakah sekarang ... ia sudah boleh menikmati dunia? Tidak apa-apa? Apakah masa depannya masih terjamin? Apa Phiko berhak mendapatkan hiburan ini?
Finna mulai sadar ditatap adiknya. Alis Finna saling bertautan. “Itu yang ditonton, bukan aku!”
Phiko tertawa kecil. Jemari kanannya bergerak tanpa dipinta, menyentuh pipi tirus Finna. Alis Finna makin bertautan, ia menjeda tayangan video, bangkit terduduk sambil memegangi pipinya.
“No, adik kamu aneh!” pekik Finna. “Dia ngira aku setan gitu?”
Phiko kira tindakannya tadi akan membuat Finna salting, padahal Phiko bermaksud menyampaikan kekagumannya terhadap kecantikan Finna. Vino tak menjawab penuturan Finna. Harusnya—bahkan sedari tadi—Vino sudah banyak bicara, apalagi Vino tidak diajak oleh kedua adiknya menonton drama Korea. Vino diam saja, menatap kosong ke depannya.
“No? Jangan ngelamun. Nanti kesambet,” tegur Finna. Gadis itu melambaikan tangan di depan wajah Vino, tapi tak ada respons.
“Lo bener, Phi.” Tiba-tiba air mata sudah menggenang di kelopak Vino. Perlahan lelaki itu menatap Phiko dengan pandangan nanar. “Temen-temen gue kayaknya bakal ngejauh karena gue cacat.”
Phiko dan Finna kompak mempertipis jarak dengan Vino. Kedua adik kakak itu memeluk Vino sangat erat, berharap bisa memberikan sedikitnya energi untuk Vino yang sedang patah semangat. Air mata mulai membanjiri pipi Vino. Selayaknya anak kembar di dunia, rasa sedih Vino juga bisa dirasakan oleh Finna, kali ini Phiko juga turut merasakannya.
“Kenapa gue harus cacat, Phi? Kenapa gue cacat, Fin? Gue harus kerja, gue harus cari duit buat kalian, buat bantu Bapak, buat kuliahin Phiko, buat jadiin Finna artis. Tapi, kenapa gue malah cacat? Kenapa?”
Sangat menyakitkan melihat lelaki tangguh akhirnya menangis juga. Phiko tidak bisa berkutik, sementara Finna terus mencoba menenangkan. Vino mulai berontak, tidak ingin dipeluk. Ia menyakiti dirinya sendiri dengan cara memukul kepala yang masih terbalut perban, menarik selang infus, mencoba melepas kabel pendeteksi yang menempel di dadanya.
“Lepas, Fin, Phi! Harusnya gue mati aja daripada jadi beban kalian!”
“No, jangan ngomong begitu. Kita ada di sini. Walaupun dunia gak memihak kamu, kita tetep di sini.”
Phiko tidak pandai dalam berkata-kata. Ia irit bicara. Jadinya Phiko tak bisa menenangkan seperti yang Finna lakukan. Napas Vino mulai terengah kencang. Tangisannya membeludak tercampur amarah. Ia tak bisa mencerna apa yang sudah dunia lakukan kepadanya, apa yang sudah Tuhan takdirkan untuknya. Namun, apa pun itu, Vino merasa dirinya tak pantas lagi bersanding dengan keluarganya.
Bapak datang dengan plastik hitam di tangan. Melihat dua anaknya sedang memeluk putra sulungnya yang tak mau diam. Sontak Bapak menyimpan plastik tadi, menarik pelan bahu Phiko dan Finna supaya menyerahkan tugas ini kepadanya. Bapak memeluk Vino. Mengusap kepala Vino, mencium keningnya, membacakan doa-doa dan syair yang menenangkan. Bapak penyuka syair, pandai bernyanyi juga. Sehingga Vino yang sedang kalut dalam emosi, mulai tenang. Tersisa isakan yang menyayat hati keluar dari mulutnya.
“Vino nggak mau sekolah, Pak,” lirih Vino. “Vino malu. Tadi temen-temen Vino dateng ngejenguk, mereka ada yang ngetawain karena Vino buntung.”
Bapak mengembuskan napas gusar. Masih dengan memeluk putra sulungnya, Bapak tak menanggapi ucapan Vino.
“Vino gak mau sekolah,” ulang lelaki itu.
Finna dan Phiko saling melempar pandang. Finna menunjuk pintu menggunakan dagunya, mengajak Phiko keluar. Phiko menurut. Keduanya kini duduk di kursi tunggu yang ada di koridor. Awalnya mereka hanya menatap kosong ke depan, sampai akhirnya Finna menepuk paha Phiko.
“Dulu aku kerja sama bareng Vino supaya kamu bisa dapet duit buat kuliah tanpa tau kerjaan kita.”
Pandangan Phiko tertarik menatap kakaknya.
“Sekarang, tolong bantu aku, Phi. Tolong bantu cari cara supaya Vino bisa berdamai dengan dirinya.”
Phiko menyandarkan kepala pada tembok di belakangnya, mengembuskan napas panjang. Berdamai dengan diri sendiri saja masih belum mampu, sekarang harus memikirkan cara untuk orang lain. Bagaimana bisa?
Sesaat setelah hening berkepanjangan, tenggelam dalam pikiran masing-masing, mata Phiko mengerling.
“Aku punya ide!”
“Apa?” Finna lebih antusias tertarik.
“Si Bekjoel!”
Senyum Finna langsung melenyap saat Phiko menyebutkan nama motor kesayangan Vino.
“Vino, kan, gak bisa jalan. Pasti naik motor juga gak bisa lah, Phi!”
“Bukan, Fin.” Phiko mengelak. “Maksudku, kita modif Si Bekjoel biar bisa dipake Vino.”
“Dimodif gimana?”
Phiko mengukir senyum, merasa Finna mungkin tertarik dengan idenya. Lelaki itu mengeluarkan ponsel dari saku, menunjukkan sebuah model motor yang akan sangat cocok untuk kakak sulung mereka.


 thisadciel
thisadciel