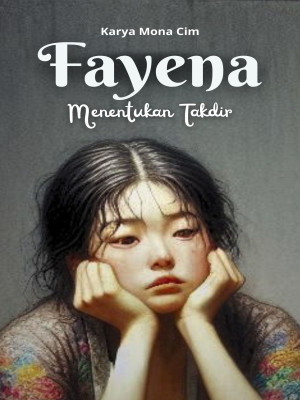Jika ini bukan keputus asaan, Lalu apa lagi?
__Arsya Abiseka Gantari
____________________________________________
Satu jam sebelum kejadian yang akan mengubah segalanya.
Detak jarum jam di kamar Arsya berdetak perlahan—tapi di dada Rajendra, waktu seperti berlari dengan panik. Perawat muda itu berdiri di depan pintu, ibu jarinya menggesek arloji tanpa sadar, seolah dengan itu ia bisa mempercepat segalanya dan segera kembali. Biasanya, rutinitas pemeriksaan bangsal adalah hal remeh yang ia jalani tanpa beban. Tapi malam ini berbeda.
Malam ini, dia harus meninggalkan Arsya sendirian.
Biasanya, kalau Rajendra perlu keluar kamar, ada Dokter Nata atau Kak Alin yang berjaga. Tapi malam ini Dokter Nata sedang mengurus dokumen adopsi—kesempatan langka yang tak bisa ditunda. Sementara Alin sedang libur dinas. Rajendra tahu benar, Arsya tak boleh sendirian terlalu lama. Anak itu sudah cukup banyak menghadapi ketakutan, bahkan saat hanya duduk diam di tempat tidur.
Ia bisa saja mengunci kamar seperti biasa. Tapi melihat Arsya yang tak pernah keluar ruangan sejak dirawat, rasa kasihan merayap pelan di hatinya. Sudah berhari-hari bocah itu hanya menatap langit-langit, menanti seseorang datang, seperti tawanan yang terlalu sopan untuk mengeluh.
Taman di ujung lorong tampak sepi. Tidak ada pengunjung. Tidak ada anak-anak lain. Hanya langit malam dan aroma disinfektan yang tertinggal di dinding.
“Sebentar saja,” pikir Rajendra. “Sepuluh—lima belas menit paling lama. Dia akan baik-baik saja.”
Dengan niat tulus, ia mengajak Arsya keluar dari kamar. “Biar nggak sumpek. Kita coba keluar sebentar, ya? katanya sambil tersenyum.
Arsya ragu. Mata beningnya menatap pintu dengan cemas, lalu kembali pada wajah Rajendra. Ia tak berkata apa-apa, tapi tubuhnya sedikit bergidik saat tangannya digenggam Rajendra.
Rajendra memakaikan jaket hangat dan meletakkan ponselnya di samping Arsya, bersama komik yang baru ia pinjam dari ruang baca rumah sakit. “Kakak nggak akan lama,” bisiknya sambil berlutut, menatap Arsya
Arsya menggenggam tangannya lebih erat. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang menimbang kata. Akhirnya, ia hanya berkata lirih, “Jangan lama-lama, ya?”
Keraguan menggelayuti hati Rajendra, namun tugasnya memaksa dia untuk meninggalkan Arsya. Dengan berat hati, Rajendra melepaskan genggaman tangan Arsya dan bangkit. Dia tersenyum kepada Arsya, berusaha menyembunyikan rasa khawatirnya. “Kakak akan segera kembali,” janjinya.
Ketakutan berkelebat di mata Arsya, yang tidak bisa sepenuhnya dia jelaskan. Mungkin itu dari mimpinya semalam. Atau dari percakapannya dengan Dokter Nata—tentang seseorang yang mungkin mengawasinya diam-diam. Tapi ia tak sanggup membebani Rajendra dengan cerita itu. Anak itu hanya mengangguk pelan, mencoba percaya. Mencoba berani.
***
Setelah lama hanya menghabiskan waktu di kamar, inilah pertama kalinya Arsya melihat dunia luar, meskipun hanya sepotong kecil yang terhampar di hadapannya. Taman kecil tempat Arsya duduk hanya seluas 5x5 meter, sebuah oasis mungil yang diapit oleh bayangan kamar-kamar kosong di lorong lain. Di tengah kegelapan, hanya bintang-bintang yang menjadi temannya.
Arsya memeluk lutut, merasakan dinginnya bangku taman menembus piyama rumah sakitnya, padahal Rajendra sudah mengenakan jaket untuknya.
Dia mengingat kehangatan dekapan Dokter Nata kemarin—bagaimana tubuhnya yang kaku perlahan melemah dalam pelukan itu. Rasa aman yang asing namun dirindukan. Aroma antiseptik dari jas putih yang bercampur dengan wangi parfum samar, yang entah mengapa terasa seperti rumah. Bagaimana jas dokter itu terasa lembab oleh air matanya, dan bagaimana tangan besar itu menepuk-nepuk punggungnya dengan ritme yang menenangkan.
Bintang-bintang itu cukup menyihir Arsya, membuatnya melupakan kepedihan hidup yang dia jalani. Mata Arsya menatap langit, cahaya bintang-bintang memantul di matanya yang penuh kerinduan. Ketenangan yang sudah lama hilang kini perlahan kembali, meskipun hanya sementara.
Matanya menatap bintang-bintang yang berkedip jauh di atas. Bebas. Tak terjangkau. Abadi. Semua hal yang tidak dia miliki. Tapi mereka juga kesepian, terpisah jutaan tahun cahaya satu sama lain. “Seperti aku,” bisiknya pada angin malam, tangannya terulur seolah ingin menggapai langit.
Setiap bintang seolah-olah bercerita, mengajaknya mengembara ke dunia yang penuh keajaiban. Dia tersenyum tipis, merasakan kehangatan di hatinya yang perlahan mengusir kesedihan.
“Kalau dunia ini memang dibuat sama Tuhan, dan Tuhan yang atur semuanya, berarti semua yang aku alami ini juga sudah dipilihkan Tuhan.”
Dia menelan ludah, rasa pahit terasa di tenggorokannya. Kak Jendra pernah bilang bahwa segala ujian adalah cara Tuhan mengajari kita bersyukur. Tapi bersyukur untuk apa? Untuk rasa sakit? Untuk ditinggalkan? Untuk... dibuang?
“Aku sudah capek banget, Tuhan. Mungkin apa yang Dokter Nata tawarkan adalah hadiah dari Tuhan. Tapi…” suaranya tercekat, “bagaimana kalau dokter Nata nggak jadi? Kalau kebahagiaan yang Tuhan kasih batal? Aku... nggak mau, Tuhan. Jadi tolong, jangan diambil lagi, ya?” pintanya sambil melihat langit.
Angin malam bertiup tiba-tiba, membuat bulu kuduknya merinding. Arsya menoleh ke belakang, merasakan tatapan yang tidak terlihat. Kosong. Tapi perasaan diawasi itu tidak hilang. Dia menggosok lengannya, mengusir rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyergap.
Dia mengingat momen setelah melampiaskan emosinya kemarin. Setelah masa permintaan maaf Dokter Nata yang cukup panjang, dan janjinya untuk mempercepat pengurusan adopsi, yang dibuktikan dengan kabar itu benar dilaksanakan Dokter Nata hari ini. Arsya cukup lega, dan berusaha menerima kembali uluran tangan Dokter Nata untuknya. Hal yang sebelumnya ia sangsikan.
Kalimat terakhir Dokter Nata masih meninggalkan kehangatan dalam hati Arsya.
‘Dokter akan berusaha jadi Ayah yang bijak dan baik buat kamu, sampai kamu bosan punya Ayah kayak dokter…’
Senyum Arsya tiba-tiba saja datang. Membayangkan disisinya ada yang menemani saat dia tidur. Yang akan menjawab jika dia berteriak takut di tengah malam. Yang akan ada di sana saat dia membuka mata setiap pagi.
Hatinya mendorongnya untuk menyuarakan satu panggilan.
“Aya—”
Belum lengkap pengucapan itu, bayangan mengerikan datang. Arsya seolah menyaksikan seorang anak yang dicambuk dengan sabuk oleh orang dewasa. Anak lelaki itu meringkuk di sudut, tangannya terangkat melindungi wajah sementara sabuk itu melayang turun lagi dan lagi. ‘Ayah, ampun... Ayah…’
Setiap kali mencoba, bayangan tangan yang terangkat itu muncul lagi. Sabuk yang melayang. Kulit yang perih. Teriakan yang tak didengar.
Kilasan adegan itu seolah nyata, namun hatinya tetap mendorongnya memanggil nama itu. “Aya—” Tidak, tidak bisa.
Arsya segera menggeleng, mengusir bayangan itu dari benaknya. Keringat dingin membasahi dahinya meski udara malam terasa sejuk.
“Dokter Nata orang baik, jadi dia nggak akan mukul aku. Itu cuma bisikan setan. Jangan didengar…”
Matanya menangkap bintang jatuh melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya yang segera lenyap. Mata Arsya melebar, teringat Kak Alin pernah berkata bahwa bintang jatuh adalah saat di mana doa-doa dikirimkan langsung ke Tuhan. Saat itu mereka berdua hanya melihat melalui jendela kamar; malam ini, semua nampak lebih indah dan lebih luas.
Arsya tidak lupa pesan wanita yang menegaskan kalau dia Bundanya, beserta perintahnya. Tapi itu hanya mimpi, di dunia nyata ada yang menawarkan menjadi keluarga untuknya. Jadi menerimanya bukan kesalahan, bukan?
Dia mengangkat wajahnya ke langit yang dipenuhi bintang. Bintang-bintang itu berkedip-kedip, seolah menyampaikan pesan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mendengarkan.
“Aku janji, aku bakal cari kakek. Tapi sekarang, tolong izinkan aku bersama Dokter Nata ya, Bunda?”
Semilir angin kembali menyapu wajahnya, kali ini lebih lembut, seperti belaian. Namun kenyamanan itu tidak bertahan lama.
Dari sudut matanya, Arsya menangkap gerakan samar di ujung taman. Bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Mungkin hanya petugas keamanan yang sedang berpatroli. Atau mungkin kucing liar. Atau mungkin...
Jantungnya berdegup kencang. Napasnya menjadi pendek-pendek. Ia merasakan ketakutan yang familiar merayapi punggungnya.
Arsya pernah mengakui satu hal pada Dokter Nata. Dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah seseorang atau benda yang berjarak jauh darinya. Dia diberi kacamata setelah pemeriksaan, sayangnya benda itu tertinggal di kamarnya. Jantungnya mulai berdebar cepat, telinganya berusaha menangkap ritme langkah kaki yang mendekat. Berbeda dengan langkah Kak Jendra yang biasanya ringan dan berirama, langkah ini terdengar berat dan terencana.
“Kak Jendra?” tanyanya ragu, suaranya sedikit bergetar.
Saat orang itu semakin mendekat, kemampuan khusus Arsya aktif tanpa diundang. Suara hati orang itu terdengar jelas: Aku tidak boleh keterlaluan menyakitinya. Tapi bermain sebentar dengan anak imut ini boleh, bukan?
Seketika, alarm bahaya berdering di benak Arsya. Itu bukan Kak Jendra! Tubuhnya membeku selama sepersekian detik sebelum naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Arsya harus lari, sekarang juga!
Arsya mengingat dengan jelas pesan Kak Jendra:
"Kamarmu di ujung kanan, paling pojok. Tidak jauh. Jadi kalau kamu bosan atau takut, kamu kembali saja ke kamar. Kunci kamar dari dalam. Kakak dan Kak Alin keliling memeriksa pasien dulu. Kakak janji nggak akan lama," Rajendra menjelaskan dengan penuh kasih sayang.
Arsya berlari sekencang mungkin. Jarak ke kamarnya hanya dua puluh langkah, tapi malam ini rasanya seperti maraton. Ponsel dan komik pinjaman Kak Jendra tergeletak di lantai belakang—tak sempat dia pungut.
Pintu kamar mengertak keras saat terkunci, suaranya seperti tembakan peringatan. Napas Arsya tersengal-sengal, paru-parunya terbakar. Dia pikir mengunci pintu sudah cukup, tapi kelegaan itu hancur berkeping-keping ketika—
Tok… tok… tok…
“Arsya, buka pintunya, Sayang…” sapa laki-laki yang mengejarnya, suaranya terdengar sangat licik. “Om punya hadiah spesial…”
Bukan kebahagiaan yang hadir saat orang itu menawarkan hadiah; tawarannya justru membuat Arsya merinding. Arsya menekan telapak tangan ke mulut—gigitan ketakutan membuat rahangnya nyeri. Orang itu masih berdiri di balik pintu. Bahkan bayangannya di celah bawah pintu bergerak-gerak, seperti monster yang sedang mengendus mangsanya.
“Bodoh! Dia nggak mungkin buka. Cepat! Perawatnya bisa kembali kapan saja! Kita lewat jalur kemarin.” Suara kedua menderu, mengungkap ada lebih dari satu ancaman.
“Tunggu ya… Om masuk…” desis suara pertama, menusuk dingin.
"Gawat!" batin Arsya. Mendadak kakinya lemas. Dia hampir membuka kunci pintu, namun seolah ada yang memperingatkan, "Bagaimana jika mereka masih di luar? Mereka hanya memancingmu." Arsya menggeleng. Kemungkinan itu benar. Ia harus sembunyi.
Matanya melirik ke lemari di sudut kamar, tapi lemari itu terkunci. Kamar mandi terlalu terbuka. Hanya kolong ranjang yang cukup rendah untuk menyembunyikan seluruh tubuhnya.
Dia merangkak masuk ke kolong ranjang, lutut sedikit lecet tergesek lantai. Debu beterbangan memenuhi hidung, hampir membuatnya bersin.
“Jangan bersin,” bisiknya dalam hati.
Dia merapatkan badan ke dinding, memeluk lututnya erat, berusaha meredam rasa takut yang berkecamuk di dalam dirinya. Pikirannya berteriak minta tolong, tapi mulutnya dikunci oleh naluri: diam, atau mati. Dia menutup mulut dengan kedua tangan. “Kak Jendra pasti sedang di jalan. Tahan. Tahan.”
Sosok misterius di taman itu terus menghantui pikiran Arsya. Siapa dia sebenarnya? Apa yang dia inginkan darinya? Dan mengapa dia seperti ingin mencelakai Arsya?
Ketika keheningan kembali, Arsya mendengar suara aneh dari langit-langit. Seperti langkah kaki yang sangat halus, atau mungkin hanya tikus. Tapi suara itu terdengar terlalu berat untuk ukuran tikus.
Detak jantungnya semakin cepat. Matanya dipaksa untuk memejam. Pikirannya membayangkan sesuatu atau seseorang sedang bergerak di atas sana. Apa mereka orang-orang yang mengejarku? Bagaimana ini, haruskah aku lari keluar kamar? Bagaimana jika dia malah tertangkap oleh mereka?
Arsya bergeser sedikit, mencoba mengintip keluar dari kolong. Namun belum sempat kepalanya keluar, mata Arsya menangkap dua pasang bayangan kaki yang melangkah masuk ke dalam ruangan. "Suara-suara tadi, itu benar mereka." Rasa takutnya kembali melanda. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuat Arsya terpaku di tempatnya.
Arsya menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, berusaha menahan jeritan yang ingin terlontar dari mulutnya. Dia tahu, jika orang-orang itu menemukannya, dia tidak akan selamat.
Harapannya hanya satu: Kak Jendra. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. "Kenapa Kak Jendra belum kembali?"
Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik bagaikan siksaan, menyiksanya dengan rasa takut yang semakin dalam. Desahan napasnya tercekat di tenggorokan, tak berani mengeluarkan suara sedikit pun.
Bayangan gelap itu semakin mendekat ke arah kolong ranjang tempat Arsya bersembunyi. Setiap langkah terdengar berat dan penuh ancaman, membuat jantung Arsya berdetak kencang. Arsya memejamkan matanya erat-erat. Tiba-tiba, suara serak dan kasar menggema di pendengaran Arsya.
“Hai, anak ganteng,” bisik suara itu.
Tubuh Arsya membeku seketika, napasnya tertahan di tenggorokan. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala, menyeretnya kembali ke jurang yang tak berdasar. Tatapan tajam dari balik bayangan itu menusuk ke dalam kegelapan, seolah-olah ingin menembus jiwanya.
“Kak Jend—” Arsya mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan, bersamaan dengan kakinya yang ditarik paksa keluar dari tempat persembunyiannya, menyeretnya ke dunia nyata yang penuh kengerian.
Tubuhnya diangkat paksa ke atas ranjang, dijepit erat oleh tangan-tangan kasar yang mencengkeramnya tanpa ampun. Bau keringat dan sesuatu yang tajam—seperti pembersih lantai atau obat-obatan—menguar dari tubuh pria itu, membuat Arsya mual. Selembar kain dingin dan kasar diikatkan rapat di mulutnya, teksturnya menyakiti sudut bibirnya, membuat setiap teriakannya hanya bergema sebagai desahan teredam.
“Enggak usah berontak, kami nggak jahat, kok...” ujarnya dengan nada yang hampir bersahabat, kontras mengerikan dengan tangannya yang mencengkeram Arsya kasar. Dia mengetahui arah pandang Arsya, “Kamu nungguin Kakak perawat yang tadi ninggalin kamu?” tanyanya, nada suaranya seolah mengobrol santai dengan teman. “Dia bakalan sibuk sebentar. Teman Om yang itu...” tunjuknya pada temannya, “dia bikin salah satu pasien yang dijaga sama Kakak itu sedikit sakit. Tapi kamu nggak gitu, kok. Jadi tenang saja.”
Tiba-tiba, teman orang yang membekap Arsya berbalik. “Sudah. Siap,” ujarnya pendek. Di tangannya, pria itu memegang sesuatu yang membuat hati Arsya mencelos—sebuah jarum suntik. Cairan di dalamnya berkilau tertimpa cahaya lampu. Ketakutan semakin merayap ke dalam pikirannya, menciptakan bayang-bayang menakutkan tentang apa yang akan terjadi padanya.
Jika benda itu ada di tangan Dokter Nata, Arsya mungkin merasa aman. Tapi di tangan pria ini, jarum suntik itu tampak seperti alat penyiksaan, bukan penyembuhan.
Arsya menggeleng. Menggeliat hebat ketika sadar hendak apa yang akan dilakukan kedua pria itu. Dia meronta. Pendek. Kasar. Putus asa. Kakinya yang masih bebas menendang liar, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Tidak kurang akal, orang itu menindih kakinya serta menekan bahu Arsya dengan keras. Mereka tidak peduli bahwa tubuh mungil Arsya tidak seharusnya diperlakukan dengan begitu kasar.
Pria itu menonton dengan senyuman sadis di balik masker hitamnya. Ada kekejaman dalam senyum itu. Rasa puas yang dingin dan keji, seperti seorang penjahat yang senang melihat mangsanya tersiksa. Arsya tetap berusaha melawan. Tak peduli lagi bahwa cekalan pada tubuhnya kian erat dan menyakitkan, dia meraung kesetanan. Memberontak. Meminta dilepaskan. Walaupun yang keluar hanya pergerakan yang terasa semakin sia-sia. Namun, dia tetap berusaha.
“Ini nggak adil banget, Tuhan,” rintih Arsya, suaranya bergetar di antara isak tangis yang tertahan kain di mulutnya. “Aku cuma pengen hidup tenang. Katanya Tuhan maha penolong, sekarang aku butuh pertolongan-Mu. Tolong aku, Tuhan…”
Namun, Tuhan seakan diam, meninggalkannya dalam kegelapan yang menyesakkan. Arsya terus meronta, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang menyiksa: Apa aku punya banyak salah? Kok ada orang yang nggak suka sama aku? Kenapa semua orang jahat sama aku? Kenapa aku harus ngalamin ini semua?
Kilasan ingatan samar melintas di benaknya—rasa takut yang sama, tangan-tangan kasar yang sama, jarum suntik yang sama. Seperti mimpi buruk yang terulang, tapi Arsya tak bisa mengingatnya dengan jelas.
Laki-laki itu membungkuk dan berbisik di telinga Arsya, suaranya berubah lembut dengan cara yang lebih menakutkan daripada bentakan. “Tenanglah! Jangan banyak bergerak. Kami nggak akan nyakitin kamu. Kami cuma mau kamu tidur… nanti kami bawa kamu ke tempat yang seharusnya.”
Kata-kata itu meresap ke dalam benak Arsya, menambah ketakutan yang sudah menguasai dirinya. Ke mana mereka akan membawaku? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Batin Arsya.
Tangan Arsya dipegang erat oleh teman orang yang menindihnya. Lengan jaketnya digulung dengan kasar, menyingkap kulit tipis lengannya yang gemetar ketakutan.
Di tengah rasa paniknya, suara yang dikenali Arsya terdengar dari balik pintu.
“Arsya, kamu di dalam?” tanya suara lembut Kak Jendra, terdengar khawatir.
“Yah… Kakaknya udah datang, padahal kami belum selesai. Bagaimana dong?” ujar penculik pertama, nada suaranya terdengar kesal namun tidak panik.
“Kakak dobrak ya?” teriak Kak Jendra dari luar, suaranya sangat panik.
Pria itu hanya tersenyum dingin, matanya tetap fokus pada jarum yang kini hampir menempel di kulit Arsya. “Kakakmu itu akan datang,” bisiknya, “tapi terlambat. Seperti biasa, orang dewasa selalu terlambat untuk menyelamatkanmu.”
“Buka pintunya, Kak! Tolong…” jerit Arsya dalam hati, namun suara yang keluar hanyalah gumaman lemah yang tertahan oleh kain. Rasa takutnya memuncak, dia ingin melarikan diri, ingin bebas dari mimpi buruk ini.
Suara dobrakan pintu menggelegar memecah kesunyian, terdengar begitu jauh di telinga Arsya meski hanya berjarak beberapa meter. Namun orang-orang di sekitar Arsya tetap fokus dengan pekerjaan mereka, seolah tak terusik dengan suara bising itu.
“Tahan ya…” ujar orang yang membawa alat suntik. Suara hatinya terdengar oleh Arsya, pikirannya menakutkan: "Setelah ini, amukanmu bakal mereda, badanmu lemas, sesak… ah, lucunya anak-anak saat itu."
Arsya meronta dengan seluruh tenaga, mencoba menarik tangannya dari cengkeraman kasar itu. Teriakannya tertahan di balik kain yang membekap mulutnya, penuh dengan rasa panik dan ketakutan yang tak terkira. Bagai hewan terjebak, dia meronta dan menjerit, memohon untuk dilepaskan.
Pria itu tidak peduli pada penderitaan Arsya, malah tampak menikmatinya. Arsya terus meronta, semakin kuat setiap detiknya, sampai ujung jarum di tangan pria itu menggores kulitnya. Darah segar mulai keluar dari sana.
“Diam, atau jarumnya malah menyakitimu!” ancamnya dengan suara dingin.
Arsya terdiam seketika, matanya terbuka lebar dalam kepanikan.
“Lepasin! Aku mohon… aku nggak mau… jangan… aku nggak mau…!” lirihnya sambil mengemis ketakutan.
“Argh…” teriakan Arsya tertahan saat jarum itu menembus kulitnya, dan terus didorong terasa semakin dalam, membuat rahangnya mengeras, mencoba menahan teriakan yang ingin meluap.
Pria itu dengan sengaja menekannya, memaksa Arsya untuk merasakan penderitaan yang tak terkira. Rasa sakit yang mendera membuat dada Arsya terasa sesak, napasnya tersendat.
Cairan dari suntikan itu menjalar perlahan seperti api yang membakar dari dalam, membuat otot-ototnya seolah mencair. Setiap tarikan napas terasa seperti menarik udara melalui selang sempit, menyakitkan dan tidak pernah cukup. Pandangannya bergoyang, seakan dunia berputar dalam gelombang yang tak beraturan. Wajah-wajah di hadapannya seperti lukisan yang luntur, berubah bentuk dan warna.
Pintu ruang rawat Arsya terbuka. Kak Jendra menerobos masuk, langkah kakinya menghentak dingin di lantai yang kotor. Pemandangan yang tersaji di depannya seperti mimpi buruk yang menjelma jadi kenyataan.
Di atas ranjang, Arsya tergeletak tak berdaya, tubuhnya lemas dan matanya setengah terpejam. Seorang pria dewasa berdiri di sampingnya, wajahnya terbalut masker yang hanya menyisakan senyum sinis. Pria itu baru saja membuka kain yang menutup mulut Arsya, membiarkannya terengah-engah, mencari udara. Jarum beserta tabung suntik masih dibiarkan menempel di tangannya, sengaja. Agar Rajendra melihat senjata terkutuk yang telah menyiksa anak tak berdosa itu.
“Bangsat! Apa yang kalian lakukan padanya?” raung Rajendra, matanya memerah menahan amarah.
Darahnya berdesir di sekujur tubuhnya. Kemarahan membakar akal sehatnya. Tanpa pikir panjang, dia menerjang ke depan. Namun, sebelum tangannya menyentuh Arsya, cengkeraman kuat menahan bahunya.
“Sabar, bocah,” suara berat terdengar dari balik topeng. “Kau ingin melihat lebih dekat apa yang sudah kulakukan pada pasienmu?” lanjutnya. “Dia sudah tidak bisa bergerak!”
Jarum suntik itu dicabut. Dibuang ke sembarang arah. Tangan lemas Arsya diangkat, dipermainkan bagaikan boneka tak berdaya. Setelah itu, pria itu melepaskan tangan Arsya, membiarkannya menggantung di sisi ranjang, tak berdaya dan tak bergerak.
“Lepaskan dia!” teriak Rajendra dengan suara parau, dipenuhi amarah dan keputusasaan.
Dalam benak Arsya yang mulai kabur, terlintas pemikiran menyesakkan. Apakah ini semua adalah konsekuensi dari kesalahanku di masa lalu? Seberat apa kesalahanku? Apakah aku pantas menerima semua siksaan ini?
“Kalau ini hukuman untukku karena dulu aku anak nakal, berarti Kak Jendra nggak perlu ikut ngerasain,” bisiknya dalam hati. Arsya berusaha menengok, air matanya menetes. Dia berharap Kak Jendra segera pergi, menyelamatkan diri.
“Lari… cepat, Kak Jendra…” gumaman Arsya terdengar lirih, hampir tak tertangkap oleh telinga Kak Rajendra.
Suara Arsya yang semakin melemah membuat Rajendra semakin kalap. Dia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman pria yang menahannya. Dengan gerakan tiba-tiba, Rajendra mengayunkan sikunya ke belakang, mengenai rusuk penculik. Cengkeraman sedikit melonggar.
Saat dia berusaha melawan, salah satu dari penculik membungkus Arsya dengan jaket yang dia kenakan.
“Dasar bajingan, kalian! Lepaskan dia! Kalian mau membawanya ke mana!”
Rajendra membentak sambil melayangkan pukulan ke arah wajah penculik yang menahannya. Namun gerakannya terbaca. Penculik itu dengan mudah mengelak, lalu dalam gerakan cepat yang tak tertangkap mata, sebuah jarum tajam menembus kulit leher belakang Rajendra.
“Argh!” Rajendra merasakan sensasi terbakar yang menyebar dari lehernya.
“Diam, perawat kecil,” desis penculik kedua yang tadi berdiri di samping Arsya. Dia mendekat, suaranya dingin dan mengejek. “Kau pikir dirimu apa? Pahlawan?”
Rajendra merasakan kakinya mulai kehilangan kekuatan. Obat itu bekerja dengan cepat. Ini bukan suntikan biasa; pasti konsentrasinya jauh melebihi dosis aman. Pengetahuan farmasinya sebagai perawat justru membuatnya semakin takut.
Dengan sisa tenaga yang ada, Rajendra mencoba meraih kaki penculik yang membawa Arsya, menahannya dengan putus asa.
“Lepas!” geram penculik itu, menginjak tangan Rajendra dengan sekali hentakan. Tulang-tulang jarinya berderak, membuatnya menjerit tertahan. Rasa sakitnya seakan menyalakan alarm terakhir dalam tubuhnya yang semakin lemas.
“Perawat hanya bisa merawat, bukan melindungi,” ejek penculik itu, suaranya penuh penghinaan. “Tahu tempatmu. Kau bahkan tak mampu menyelamatkan dirimu sendiri.”
Rajendra terbaring di lantai dingin ruang VIP yang dulu dianggapnya aman. Matanya bertemu dengan mata Arsya yang sudah nyaris tak fokus. Dia melihat ketakutan di mata anak itu, bercampur dengan keputusasaan dan—yang paling menyakitkan—pengharapan yang masih tersisa.
Maafkan aku, Arsya. Maaf… Rajendra ingin meneriakkannya, tapi lidahnya kelu, tak mampu lagi membentuk kata-kata.
Kepalanya terasa melayang, kesadarannya semakin menipis. Dokter Nata, aku harus memberi alasan apa padanya? Pikiran itu melintas sebelum kegelapan menelannya. Aku gagal melindunginya…
Entah apa yang mereka lakukan pada Kak Rajendra. Suara protesnya yang lantang mulai meredup, perlahan-lahan menghilang. Pandangan Arsya semakin kabur, tapi dia masih bisa melihat sosok perawat favoritnya yang tersungkur di lantai, tak berdaya.
Hati Arsya terasa diremas pilu. Rasa takut dan keputusasaan menyelimuti dirinya. Dia ingin berteriak, ingin menolong Kak Rajendra. Tapi tubuhnya lemas, tak mampu bergerak. Detak jantungnya melambat, udara di sekitarnya seolah semakin tipis.
Di tengah kabut yang menyelimuti pandangannya, Arsya melihat orang yang membawanya mulai berjalan keluar. Dia hanya bisa pasrah, mengikuti ke mana pun orang itu membawanya. Lampu-lampu koridor rumah sakit berkedip-kedip dalam pandangannya yang kabur, seperti bintang-bintang jauh yang perlahan menghilang.
Arsya memejamkan matanya, membayangkan wajah Dokter Nata dan para perawat favoritnya.
“Aku ingin bersama kalian,” bisiknya sambil meneteskan air mata.
“Dokter Nata, aku mau sama dokter…”
Harapannya menghilang ke dalam kegelapan, bersamaan dengan kesadarannya yang perlahan memudar.


 hanyaselingan
hanyaselingan