Langit-langit kamarnya tak pernah terasa sejauh ini. Atha berbaring di tempat tidur, tubuhnya tenggelam di kasur yang lembut tapi terasa seperti pusaran lumpur. Kedua matanya menatap kosong ke atas, tak berkedip. Sudah hampir satu jam sejak ia pulang dari rumah sakit kemarin sore, tapi rasanya seperti satu tahun. Satu tahun sejak ia tahu bahwa semua yang selama ini ia perjuangkan ternyata cuma ilusi, topeng, dan tipu muslihat.
Kepalanya masih berat, seperti baru selesai ditabrak ingatan yang menolak untuk dihapus. Tapi ia tahu harus mulai dari mana.
Perlahan, ia tarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan tangan gemetar, ia raih ponsel yang tergeletak di sebelah bantal. Layar menyala, menyilaukan mata yang bengkak karena menangis terlalu lama semalam. Jari-jarinya langsung membuka daftar kontak. Nama-nama yang dulu terasa dekat kini seperti parasit yang menempel: Dero, Niko. Tak ada getaran, tak ada ragu. Satu per satu, ia tekan ikon tempat sampah.
[Konfirmasi?]
[Ya. Hapus.]
Hilang.
Setelah itu ia masuk ke galeri. Folder berjudul ‘XIII-A’. Folder itu juga lenyap hanya dengan dua sentuhan. Satu-satunya yang tertinggal hanya kekosongan, sepi yang anehnya lebih jujur dari apa pun yang pernah mereka katakan.
Atha mendesah pelan, tapi tidak ada rasa lega. Justru ada sesak baru yang menekan dadanya. Ia menutup mata, dan dari balik gelap itu muncullah potongan-potongan yang dulu ia pikir nyata.
Niko yang nyengir sambil menawarkan earphone, “Dengerin lagu gue, dong. Biar elu ngerti isi kepala gue.”
Dero yang satu-satunya duduk di sebelahnya saat Niko mulai sakit dan menjauh.
Ternyata, semuanya palsu. Mereka palsu. Dan ia? Mungkin hanya pion yang dengan bodohnya percaya semua itu tulus.
Ia duduk perlahan, memeluk lutut, ponsel tergenggam erat di tangan kanan. Kepalanya ditundukkan. Tak ada air mata kali ini, hanya lelah. Lelah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Dalam hati, suaranya terdengar jelas. Dingin. Tegas.
“Mulai hari ini, semua ini selesai.”
Hari itu, rumah terasa senyap. Seperti ikut merasakan luka yang menempel di udara.
Atha tak bergerak dari kamarnya. Tirai jendela masih tertutup sejak pagi. Udara di dalam ruangan lembap, nyaris pengap, namun ia tetap meringkuk di balik selimutnya seperti hendak menghilang. Matanya sembab, pipinya kering oleh bekas air mata yang berhenti mengalir bukan karena sembuh—tapi karena kehabisan tenaga untuk menangis lagi. Nafasnya pendek-pendek, pelan, tapi terasa berat seperti batu menghimpit dadanya dari dalam.
Sejak pagi ia belum makan. Bahkan sejak kemarin malam, satu suapan pun tidak menyentuh bibirnya. Perutnya perih, tapi itu bukan lagi sesuatu yang penting. Ia hanya diam. Diam, seperti potongan sisa seseorang yang pernah percaya bahwa hidupnya akan baik-baik saja.
Di luar, suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Ibunya—yang sejak tadi gelisah karena Atha tak juga keluar kamar, tak terdengar batuk kecilnya, atau bahkan langkah kakinya ke kamar mandi.
“Tha? Nak? Kamu belum makan ya?” suara lembut itu terdengar dari balik pintu.
Tidak ada jawaban.
Tok. Tok.
“Atha?”
Masih hening. Hanya keheningan yang menjawab.
Ibu Atha perlahan memutar gagang pintu. Tak dikunci. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan kamar yang remang-remang dan putrinya yang duduk di tepi ranjang, punggung membungkuk, tangan menggenggam ponsel yang sudah mati kehabisan baterai. Kepalanya tertunduk dalam.
“Atha...?” Suara ibunya mulai goyah.
Atha mendongak perlahan. Matanya kosong. Bibirnya gemetar, seolah ingin berkata sesuatu, tapi hanya udara yang keluar. Ia berdiri pelan, terlalu pelan, seperti tak yakin pada tubuhnya sendiri.
Namun belum sempat ia ambil satu langkah penuh—
bruk.
Tubuhnya ambruk ke lantai. Tangannya tak sempat menopang. Kepalanya terbentur sisi tempat tidur. Suara jatuhnya pelan, tapi cukup membuat jantung sang ibu pecah seketika.
“Atha!! ASTAGHFIRULLAH, ATHA!!!”
Ibu Atha berlari ke arah anaknya yang tergeletak di lantai. Wajah Atha pucat, tubuhnya dingin. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Matanya terpejam rapat, keringat dingin mengalir dari pelipisnya.
“Mas! MAS! TOLONG!!” teriak ibunya sambil memeluk tubuh putrinya yang lunglai. Panik.
Ayah Atha bergegas naik dari bawah, napas terengah. Ketika melihat anak perempuannya tak sadarkan diri, ia langsung merunduk dan mencoba mengguncangnya pelan.
“Tha... Nak, bangun, ini Ayah... bangun, Atha...”
Namun yang terjadi malah lebih menyesakkan.
Tubuh Atha mulai bergetar kecil. Kejang. Bibirnya gemetar hebat. Matanya sedikit terbuka tapi tidak fokus. Tubuhnya melengkung pelan seperti menahan rasa sakit yang luar biasa.
“YA ALLAH! Mas, dia kejang! Dia KEJANG!!” teriak ibunya histeris, air mata mulai membanjiri wajahnya.
Tanpa pikir panjang, ayah Atha mengangkat tubuh putranya yang ringan seperti kain basah. Dipeluknya erat-erat, seolah takut kehilangan. Ia berlari menuju luar rumah, ada motor miliknya di sana.
“Ayo, Bu! Cepat!!” serunya pada istrinya yang masih terisak, panik.
Suara mesin motor meraung keras menembus malam. Hujan mulai turun pelan, Atha tak bergerak. Nafasnya pendek, matanya terpejam. Ibunya memeluk dari belakang sambil berdoa, menggenggam tangan yang dingin itu erat-erat. Mereka bonceng tiga, bukan maksud menyalahi aturan, tetapi keadaan genting yang memaksa mereka harus mengendarai motor bertiga. Yah, keluarga Atha belum memiliki mobil.
“Bertahan, Nak... tolong bertahan...”
Malam itu, rumah mereka penuh tangis. Tangis seorang ibu dan ayah yang tak tahu betapa dalam luka batin yang ditanggung oleh anak remajanya.
Dan tubuh Atha… akhirnya menyerah lebih dulu.
Cahaya lampu rumah sakit begitu terang. Terlalu terang. Putihnya menusuk mata, menusuk ke kepala. Di sekeliling, suara mesin infus berdetak pelan, teratur, seperti detak jam yang lambat—terlalu lambat. Bau antiseptik dan parfum lembut dari tangan perawat masih menggantung di udara. Atha terbaring diam di atas ranjang, tangan kirinya terpasang selang infus, wajahnya pucat seperti kertas basah yang kehujanan lalu mengering setengah.
Selimut rumah sakit menutupi tubuhnya hingga dada. Rambutnya berantakan, kering, sebagian menempel di pelipis karena keringat dingin yang mengering. Bibirnya pecah-pecah. Mata itu—mata yang biasanya jernih dan penuh rasa ingin tahu—kini kosong. Pandangannya menembus langit-langit seperti benda mati yang tak punya tempat berpulang.
Di kursi sebelah kanan tempat tidur, sang ibu duduk sambil menggenggam tangan Atha erat-erat. Mata perempuan itu bengkak. Pipinya merah. Tisu di tangannya sudah remuk oleh air mata yang terus mengalir sejak tadi malam. Ia belum tidur. Belum makan. Tak bisa. Yang ada di pikirannya hanya satu: anaknya.
“Atha...” bisiknya pelan. “Nak, kamu dengar suara Ibu, kan?”
Atha membuka mata. Lambat. Tapi tetap tak mengatakan apa-apa. Bola matanya bergerak sedikit, hanya untuk melihat wajah ibunya sebentar. Lalu kembali menatap langit-langit. Datar. Tak ada isyarat. Tak ada reaksi.
Sang ibu mengusap lembut rambut anaknya, mencoba menenangkan. “Kamu udah di rumah sakit. Aman, ya. Udah enggak apa-apa, Sayang. Ibu di sini... Ibu jagain.”
Tapi Atha tetap diam. Tak mengangguk. Tak menggeleng. Tak ada ucapan “iya” atau sekadar senyum tipis. Tubuhnya memang sadar, tapi jiwanya belum pulang.
Ayahnya datang beberapa menit kemudian. Baru kembali dari ruang administrasi. Di tangannya ada map putih dari bagian pendaftaran dan setumpuk kwitansi. Ia hanya melirik ke arah ranjang, lalu duduk di bangku panjang dekat jendela. Nafasnya berat. Penuh sesal. Tapi ia tak berani banyak bicara.
Beberapa kali sang ibu mencoba mengajak Atha ngobrol. “Nanti kalau udah baikan, kita makan mi ayam kesukaan kamu, ya? Atau mau dibuatin bubur ayam kayak dulu waktu kecil? Atau … mau ibu buatkan oseng tempe kesukaanmu?”
Atha diam.
Hanya satu yang berubah: air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Perlahan. Tidak disertai suara. Tidak ada isak. Tidak ada gerakan. Hanya tangis diam yang jatuh dari wajah seorang anak yang tidak tahu harus memercayai siapa lagi di dunia ini.
Dan itu lebih menyakitkan daripada teriakan atau tangisan keras.
Pintu ruangan dokter tertutup rapat setelah keduanya masuk. Di dalam, cahaya lampu tak seterang di lorong. Ruangannya tenang, netral, seperti mencoba meredam apapun yang terlalu keras—entah suara, perasaan, atau pikiran. Di balik meja kerja, seorang pria paruh baya dengan jas putih menyambut mereka dengan ekspresi serius namun empati. Ia mempersilakan duduk.
“Ibu... Bapak,” katanya perlahan, membuka percakapan tanpa basa-basi. “Kami sudah melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Tidak ada kelainan organ atau cedera. Tapi...”
Kata itu menggantung. Tapi—satu kata pendek yang terasa seperti jurang.
“Atha mengalami kondisi yang kami sebut emotional shock. Ini semacam reaksi tubuh terhadap tekanan psikologis ekstrem yang tidak bisa disalurkan secara sehat. Gejalanya bisa berupa pingsan, kejang ringan, bahkan kehilangan kesadaran jangka pendek seperti yang Atha alami.”
Ayah Atha mengangguk pelan, menggenggam kedua tangan di atas lutut. Ibunya mulai menggigit bibir, menahan sesuatu yang rasanya sudah mendesak di ujung mata.
“Lebih dari itu,” lanjut dokter, “kami melihat tanda-tanda trauma psikologis yang cukup dalam. Ada kemungkinan ini sudah berlangsung beberapa waktu, menumpuk, dan baru meledak sekarang.”
Hening.
“Ia butuh terapi, Bu, Pak. Terapi psikolog rutin. Dan waktu. Banyak waktu. Ini bukan luka yang bisa disembuhkan dengan istirahat seminggu atau sebotol vitamin. Ini luka yang tidak terlihat... tapi nyata.”
Ibunya menunduk, dan akhirnya pecah juga. Tangisnya lirih tapi tak tertahan. Ayahnya bergeser, memeluk pelan bahu sang istri, matanya sendiri memerah. Tak ada yang bicara. Mereka hanya duduk di sana, menelan semua kenyataan pahit yang tak pernah mereka kira akan terjadi pada anak mereka—anak yang selama ini terlihat begitu kuat, begitu sempurna di mata banyak orang.
Sementara itu, di ruang perawatan beberapa meter dari sana, Atha masih terbaring diam. Tidak bicara. Tidak menangis. Tidak meminta siapa-siapa. Hanya diam, seperti sudah tidak tahu lagi apa yang pantas dirasakan.
Dan saat waktu perlahan bergerak ke sore, ketika suara pengumuman rumah sakit sayup-sayup terdengar dari speaker di langit-langit, satu kalimat terakhir terpatri dalam hati kedua orang tuanya:
Anak yang mereka banggakan kini rebah dalam diam—dan luka itu bukan di kulit, melainkan jauh lebih dalam.


 harrisradcliffe
harrisradcliffe









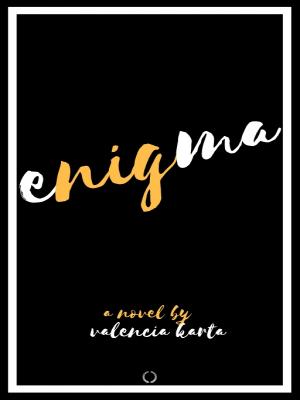
arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN