Anak-anak kelas sebelas itu berjalan melewatinya dengan ekspresi puas, tertawa pelan seolah baru saja melontarkan lelucon jenius. Salah satunya bahkan menoleh sekilas, mengangkat alis dengan senyum congkak.
“Anak Kelas 13, ranking dua nasional, katanya,” ejek si anak itu sambil mengedipkan mata ke temannya. “Hebat banget sampe ngulang, Bang.”
Atha menatap kosong ke arah mereka, tak bicara. Tapi dadanya terasa sesak seperti disumpal kapas basah. Dia tak tahu mana yang lebih menyakitkan—ejekan itu, atau kenyataan bahwa tak ada yang membelanya. Bahkan udara sore pun seolah ikut diam.
Matanya melirik sekeliling. Beberapa siswa yang ada di parkiran menoleh, sebagian cepat-cepat pura-pura sibuk dengan ponsel atau kunci motor. Tidak ada yang tertawa, tapi tidak ada juga yang maju untuk menghentikan. Dunia seperti ikut bersekongkol membiarkannya terdampar.
Lidahnya terasa kaku. Atha, sejujurnya ingin menjawab, melawan. Ingin mengatakan sesuatu, membalikkan keadaan. Tapi yang keluar hanya tarikan napas kasar dan langkah yang dipercepat menuju sepedanya yang terparkir di sudut paling ujung.
“Oi! Gak bales? Cuma bisa ranking doang ya, gak bisa ngomong?” tambah salah satu dari mereka, tapi suaranya segera terhenti saat langkah kaki berat terdengar mendekat.
“Ngapain ribut-ribut di sini?” suara satpam terdengar keras, membuat kerumunan itu bubar secepat mereka datang. Anak-anak itu berhamburan, sebagian pura-pura ngobrol soal hal lain, sebagian cepat-cepat menyalakan motor dan kabur.
Atha masih berdiri diam. Kini, posisinya sudah duduk di jok motor, jari-jarinya menggenggam erat stang sepeda, wajahnya menunduk, mencoba menelan semuanya sekaligus.
“Udah, pulang sana. Gak usah diladenin,” kata satpam itu saat melintas, nadanya datar, tapi tidak jahat. Mungkin karena kasihan, mungkin karena tahu percuma ikut campur lebih jauh.
Atha hanya mengangguk kecil. Lalu dia menyalakan mesin motor maticnya dan melaju perlahan, meninggalkan sekolah yang mulai sepi. Angin sore dengan rintik gerimis menampar pipinya, dingin, dan menampar lebih keras dari kata-kata manapun.
Di depan pagar, lelaki dengan kondisi wajah yang sudah tidak karuan itu sempat menoleh sekali ke arah belakang. Ke bangunan yang dulu dia banggakan. Sekarang tak lebih dari penjara sunyi, tempat dirinya tidak diinginkan. Lalu dia kembali menancapkan gas. Pulang, dengan hati yang berat dan kepala yang lebih berat lagi.
Langit mulai memudar ke abu-abu saat Atha mengayuh motornya pelan melewati gang sempit menuju rumah, ternyata di daerah rumah Atha gerimis sudah mereda. Jalanan itu hanya cukup dilalui satu kendaraan roda dua, dengan tembok-tembok rumah warga berdiri rapat di kanan-kiri.
Seolah-olah sudah khatam, dia pun berhenti di depan sebuah rumah bercat hijau kontras, pagar besi merah yang mulai berkarat berdiri kaku di depannya. Halamannya kecil, hanya cukup untuk sepeda motor dan sepasang pot tanaman lidah mertua yang kini sudah menguning.
Atha turun dari motor, mematikan mesin, lalu mendorongnya masuk ke pelataran rumah dengan pelan. Tak ada suara dari dalam. Ayahnya belum pulang—biasanya baru sampai menjelang malam, apalagi kalau sedang ambil lembur di pabrik. Dia tahu betul suara langkah berat ayahnya saat menapak di teras, dan suara batuk-batuk kecil khas yang sering terdengar dari ruang tengah. Tapi sekarang, hanya suara angin dan derit pagar yang menemaninya.
Begitu membuka pintu depan, Atha disambut aroma hangat masakan rumah. Oseng tempe dan nasi baru matang. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman. Lantainya keramik putih dengan dinding dalam berwarna krem pucat.
Di ruang tengah, pigura-pigura penuh piagam dan foto-foto berjejer rapi: lomba sains, debat, olimpiade, bahkan sertifikat volunteer yang pernah Atha ikuti. Dulu, dinding itu seperti altar pengingat bahwa remaja berusia delapan belas tahun ini sedang menuju tempat yang besar. Sekarang, semuanya terasa seperti sisa-sisa mimpi yang gagal diselamatkan.
Langkah Atha berat, tapi dia tetap masuk.
“Udah pulang, Nak? Ibu masak oseng tempe, kamu suka, kan? Mau makan dulu?” suara ibunya terdengar dari dapur, diiringi bunyi spatula membentur wajan.
Atha menanggalkan tas di sofa tua dekat pintu. “Nanti aja, Bu. Lagi enggak lapar.”
Beberapa detik hening. Lalu suara ibunya kembali, lebih lembut, seolah ingin menyemangati. “Eh, eggak boleh gitu. Jangan biarin apa pun bikin kamu patah. Kamu tuh anak hebat, pinter, Ibu yakin ini cuma ujian kecil. Atha pasti bisa lewatin ini.”
Atha menggeleng pelan meski tahu ibunya tak akan melihat. “Nanti aja, Bu. Aku capek,” jawabnya tanpa menoleh.
“Ya udah, tapi jangan lupa dimakan nanti ya. Jangan sampai masuk angin, kamu tuh, harus tetap jaga stamina.”
Kalimat-kalimat itu, yang dulu selalu membuat Atha bangkit dari keterpurukan, kini terasa seperti beban yang menghantam punggungnya setiap kali dia membungkuk.
“Ya, Bu...,” sahutnya pendek, sebelum menggeret tasnya, masuk ke kamar, dan menutup pintu.
Kamar itu tak luas. Kasur tipis di lantai, meja belajar penuh kertas, dan papan vision board yang masih penuh dengan tempelan target akademik dan universitas impian. Sebuah kalender di dinding menunjukkan tanggal hari ini dengan lingkaran merah besar yang dulu ia buat sendiri—tanggal pengumuman kelulusan. Dia belum sempat mencoret lingkaran itu.
Atha meletakkan ransel dengan gantungan kunci logo Institut Teknologi Bandung ke pojok ruangan dan duduk di lantai. Matanya menatap ke depan, kosong. Lalu beralih ke ponselnya, layar yang masih menyala menampilkan SMS yang tadi siang belum jadi dikirim.
Bu, Atha enggak kuat.
Atha menatap kalimat itu lama. Jempolnya melayang di atas tombol kirim. Tapi dia tak pernah menekannya. Dia takut... takut melihat harapan di mata ibunya berubah jadi kecewa. Dia takut menjadi beban—lebih dari sekadar anak yang gagal lulus.
Tangannya terkulai ke lutut. Nafasnya berat.
Apakah ini salahnya? Apakah semua piagam itu bohong? Apa gunanya dulu jadi juara kalau akhirnya terjebak di ruang yang bahkan guru pun enggan memandang?
Matanya mulai memanas, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Dia terlalu lelah bahkan untuk menangis. Yang tersisa hanya rasa sesak seperti karet yang melilit dada.
Atha merebahkan diri di kasur tipisnya, masih mengenakan seragam sekolah yang mulai kusut dan berdebu. Remaja itu menatap langit-langit kamar, membayangkan dirinya tak pernah bangun. Mungkin itu lebih baik. Mungkin semua orang akan lebih lega. Ibunya bisa bangga pada kenangan, bukan kenyataan.
Tapi Atha tetap bernapas.
Dan tanpa sadar, tubuhnya akhirnya menyerah. Pelan-pelan, kelopak matanya menutup, membiarkan dirinya tenggelam dalam mimpi yang entah mengapa, terasa lebih ringan daripada kenyataan
***
.Esoknya, Atha membuka mata dengan perasaan sakit di kepala. Bumi yang secara harafiah bergerak memutar, dia rasakan benar-benar sedang berputar. Namun, hal itu tidak dapat Atha sangkal, karena dia harus bergegas ke sekolah. Tidak banyak drama di rumah, oseng tempe yang ibunya buat kemarin akhirnya Atha makan, dijadikannya lauk untuk sarapan. Seperti biasanya, sang ibu memberikan beberapa wejangan untuk anak sematawayangnya ini sebelum berangkat.
Setelah urusan di rumah selesai, Atha mulai memanaskan mesin motor, dan melaju ke sekolah dengan perasaan gelisah. Sebenarnya, dia enggan untuk datang lagi, tetapi apa boleh buat? Atha tidak ada alasan untuk tidak datang.
Langit pagi itu cerah nyaris sempurna—biru lembut dengan awan tipis yang terserak seperti kapas basah. Matahari menggantung malu-malu, belum sepenuhnya terik, tapi cukup untuk membuat seragam tipis Atha terasa terlalu hangat. Dia membelokkan motornya ke pekarangan sekolah yang tak seberapa luas, suara mesin motor mengaum pelan sebelum akhirnya berhenti di deretan paling pinggir, tepat di bawah bayangan pohon flamboyan yang daunnya mulai rontok.
Langkahnya menyusuri jalan setapak menuju kelas terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban tas atau lelah fisik, tapi karena perasaan was-was yang tak kunjung reda sejak semalam. Cahaya mentari menyinari rambut dan seragamnya yang masih rapi, tapi tidak satu pun sinar itu terasa menenangkan.
Kelas sudah setengah ramai saat Atha masuk. Dia tak mencari siapa pun dengan pandangannya, hanya berjalan lurus menuju tempat duduknya di paling depan. Remaja itu tak sedang ingin berbasa-basi pagi ini, bahkan dengan Niko yang sedang melipat kakinya di bangku, memasang earphone di satu telinga.
Tak lama setelah Atha duduk, bel berbunyi. Suaranya nyaring dan tak pernah benar-benar enak didengar. Sejurus kemudian, langkah kaki masuk terdengar dari depan. Pak Surya, guru Bimbingan dan Konseling, masuk dengan ekspresi datar dan clipboard di tangan.
Tanpa banyak sapaan atau basa-basi, pria paruh baya itu langsung mengumumkan, “Hari ini kita mulai sesi kelompok observasi. Saya akan membagi kalian jadi kelompok-kelompok kecil, dan masing-masing harus menyusun refleksi pribadi berdasarkan tema yang akan saya berikan.”
Tak ada yang menyahut. Pak Surya membaca daftar nama yang sudah dituliskannya sebelumnya, membagi mereka ke dalam kelompok acak. Tak satu pun dari siswa dimintai persetujuan.
“…Athariel Pradana, Dero Hutahaean, dan Niko Lius Adhiwinarta.”
Atha tak langsung bereaksi, tapi dadanya terasa kosong seperti ditusuk perlahan dari dalam. Dia mengangkat pandangan sedikit menoleh ke belakang secara spontan, hingga matanya tepat bertemu dengan Dero. Tatapan itu jelas tajam, enggan, dan sedikit menghina.
“Wah, bagus banget ya, gue sekelompok sama ranking dua paralel,” gumam Dero, tidak keras tapi cukup untuk didengar oleh siapa pun yang ada di dekatnya. Nada sarkastik itu menggantung di udara, membuat suasana kelas seketika membeku.
Niko yang duduk di samping Atha menatapnya dengan lekat seraya menghela napas panjang.
Pak Surya melanjutkan paparannya, “Kelompok ini akan berlaku sampai akhir semester, semua proyek bimbingan konseling akan dilakukan secara beregu. Topik kalian hari ini adalah: 'Menghadapi kegagalan yang tidak kamu prediksi.' Waktu kalian dua puluh menit, nanti presentasi per kelompok.”
Kalimat itu terasa seperti ejekan. Entah disengaja atau tidak, tapi untuk kelompok ini, topik itu terasa seperti peluru yang sudah disiapkan sejak awal.
Dero bersandar di kursinya, tertawa kecil. “Wah, ini topik favorit lu banget, Tha. Gagal yang enggak terprediksi. Pas banget kan sama cerita hidup lu sekarang?”
Atha menahan diri. Dia tidak membalas.
Niko melirik ke arah Atha, lalu beralih ke Dero. “Lu bisa gak berisik gak, sih?”
Dero terkekeh pelan. “Santai, Nik. Gue cuma bilang fakta.”
Tak ada yang berbicara lagi setelah itu. Tapi tensi dalam kelompok itu menumpuk, seperti kabut panas yang tak bisa ditiup angin.
Atha membuka lembar kerja yang dibagikan, tapi pikirannya kosong. Di kepalanya, suara-suara mulai berisik—Dero, Niko, ibunya, bahkan dirinya sendiri. Refleksi pribadi tentang kegagalan? Dia bahkan belum bisa berdamai dengan hari kemarin.
Waktu terus berjalan, hingga akhirnya Pak Surya melirik jam tangannya. Dengan suara berat yang serak namun tegas, dia menunjuk ke papan. “Kelompok tiga. Athariel, Dero, Niko. Maju.”
Langkah mereka bertiga nyaris tak bersuara, tapi cukup terasa seperti beban yang menyeret. Dero berjalan duluan dengan malas, ekspresi wajahnya seperti orang yang dipaksa bangun dari tidur siang. Niko menyusul di belakangnya, matanya kosong, lesu, seolah sedang memikirkan hal lain. Atha di belakang, menggenggam kertas catatan yang sudah sedikit lecek, jari-jarinya dingin, keringat dingin mengalir dari tengkuknya.
Mereka berdiri di depan kelas. Pak Surya menyandarkan tubuh tingginya ke meja guru. Sosok pria berusia empat puluhan itu selalu tampak kaku—posturnya tegap, kulit sawo matang dengan garis rahang keras dan tatapan tajam di balik kacamata bingkai hitam. Rambutnya rapi, disisir ke samping, dan setiap kali ia bicara, ada nada menghakimi yang sulit dibantah.
“Silakan dimulai,” katanya pendek.
Sunyi.
Tak satu pun dari mereka bicara. Atha memandang ke arah Niko, berharap, tapi tak ada balasan. Dero hanya memainkan ujung baju seragamnya sambil memutar bola mata. Seperti biasa, tidak ada yang peduli.
Atha mencoba menarik napas panjang.
“Kami diberi topik tentang pentingnya kesadaran diri dalam menghadapi tekanan…”
“Lantang!” potong Pak Surya tajam. “Jangan seperti orang yang sedang menggumam untuk dirinya sendiri. Saya tidak punya waktu untuk suara setengah hati.”
Atha menggigit bibir. Dia mengulang lagi kalimatnya dengan suara lebih keras, tapi nada gemetar tetap terasa. Suasana kelas makin menekan. Setiap kata yang keluar dari mulut Atha seolah langsung lenyap di udara, tak berjejak.
Dero menyela, malas. “Gak usah sok presentasi juga, tcih. Kita bahkan gak ngerjain apa-apa. Omong kosong semua ini.”
Atha menoleh cepat ke arahnya, shock. Tapi Dero tidak tampak peduli. Remaja itu menyeringai sinis ke arah kelas, lalu menoleh ke Pak Surya. “Jadi ya… ya gitu deh, Pak. Kami enggak siap.”
Pak Surya tidak langsung bicara. Dia menatap ketiganya satu per satu, lalu menghela napas berat sambil mengangkat dagu sedikit, seolah muak dengan pemandangan di depannya.
“Kelompok gagal ini adalah contoh paling jelas dari kegagalan sistem. Anak-anak sisa. Anak-anak produk gagal. Bahkan untuk kerja kelompok sederhana pun tidak bisa menyatukan otak kalian. Kalau sekadar membaca ulang tugas saja tidak mampu, apa yang kalian harapkan dari hidup ini?”
Beberapa anak tertawa pelan. Yang lain diam karena tahu bisa saja mereka yang jadi sasaran berikutnya.
Atha hanya berdiri. Seluruh darahnya seperti mendidih, tapi dingin di dada. Rasanya seperti ditelanjangi di depan banyak orang. Kata ‘produk gagal’ itu mengiris pelan namun dalam. Kepalanya menunduk, bukan karena takut. Tapi karena terlalu sakit untuk menatap ke depan.
“Duduk,” ucap Pak Surya.
Mereka bertiga kembali ke tempat masing-masing. Niko tetap tak bicara. Dero sempat menepuk-nepuk meja sambil bersiul pelan, seolah semuanya hanya candaan tak berarti.
Saat bel istirahat berbunyi, semua murid keluar kelas. Koridor ramai oleh suara tawa, suara sepatu yang tergesa, suara dunia yang terus berputar tanpa memedulikan siapa pun yang tertinggal.
Tapi Atha diam. Tubuhnya gemetar pelan, entah karena marah, malu, atau takut—atau semuanya sekaligus. Dia jelas tahu, kalau dia tetap tinggal di kelas itu, hari-hari berikutnya akan sama. Atau lebih buruk.
Tidak lama, Atha pun berdiri. Tanpa pikir panjang.
Langkahnya cepat keluar kelas. Tangannya mencengkeram tali tas dengan kuat. Dia bahkan tidak menoleh ke siapa pun. Tidak ke Dero. Tidak ke Niko.
Atha sampai di pekarangan tempat motor-motor siswa terparkir. Pohon flamboyan menaungi sebagian area itu, dengan kelopak merah oranye yang gugur berserakan di atas jok motornya. Atha menyapu kasar kelopak itu seadanya, menyalakan motor, lalu melesat keluar dari gerbang dengan helm yang tidak dipakai, tanpa tujuan pasti.
Atha tidak tahu akan ke mana. Tapi yang remaja frustrasi itu tahu, dia tidak akan kembali. Bukan hari ini. Mungkin tidak besok. Mungkin tidak akan pernah.


 harrisradcliffe
harrisradcliffe
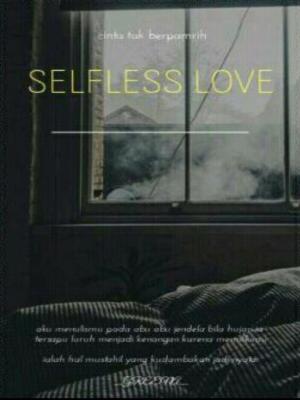







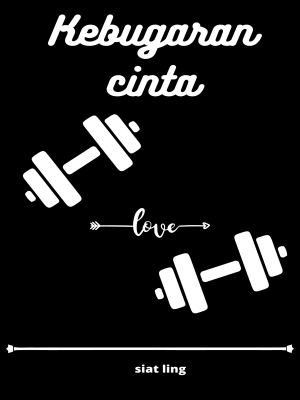

arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN