Bagi sebagian orang, bolos sekolah di jam istirahat mungkin cuma kenakalan kecil—hal remeh yang kelak bisa diceritakan sambil tertawa saat reuni. Tapi untuk Atha, ini lebih dari itu. Ini bukan pelarian dari tanggung jawab, tapi dari luka yang terus disuapkan padanya—oleh kelas, oleh guru, oleh ekspektasi orang-orang yang katanya peduli.
Atha butuh kabur, walau hanya sebentar, sebelum semua runtuh total. Maka dia memilih tempat yang jauh dari keramaian: sebuah lapangan tua di ujung kota, yang hanya ramai saat ada turnamen bola atau lomba tujuh belasan. Namun, hari ini, tempat itu sepi seolah menyambutnya dengan diam yang menenangkan.
Motor tuanya berderak pelan saat melewati jalanan kecil berdebu di sisi lapangan, lalu berhenti di bawah pohon kapuk yang rindangnya menggantung acak, menyaring sinar matahari jam sepuluh yang mulai menyengat kulit. Dedaunan kering dan bulu-bulu halus dari buah kapuk berserakan di tanah, beberapa menempel di jok motor yang sudah mulai mengelupas.
Atha mematikan mesin, menaruh helmnya yang semula menggantung di pergelangan tangan di bawah, tepat di bagian depan jok, lalu turun tanpa suara. Tak ada yang dia bawa, selain tas dan tubuh lelah dan kepala yang berat oleh amarah, malu, dan rasa tidak berdaya yang dipendam sejak pagi.
Langkahnya pelan menyusuri tepi lapangan, lalu berbelok ke tengah, tempat biasa wasit berdiri dalam pertandingan. Tapi sekarang, hanya ada rumput kering yang mencuat liar, bau tanah hangus, dan udara panas yang menempel di kulit seperti dosa yang tak bisa dibersihkan. Remaja itu mendongak sebentar, menatap langit biru yang terlalu cerah—kontras dengan isi dadanya yang kelam. Dunia seperti sedang bersenang-senang tanpa dia.
Atha akhirnya duduk. Di tanah. Di tengah lapangan yang kosong. Lututnya ditekuk, tangannya memeluk kaki, kepala ditundukkan, punggung membungkuk seperti ingin meringkuk dan menghilang. Suara burung di kejauhan terdengar sumbang. Tak ada angin. Tak ada kehidupan.
“Gue salah apa sebenernya? Semua tuduhan itu bahkan gak pernah gue lakuin.” gumamnya lirih, nyaris tak bersuara.
Atha ingin menangis, tapi air mata sudah terlalu sering mengalir dan kini menolak muncul. Dia ingin marah, tapi semua energi habis untuk bertahan. Jadi, dia hanya diam, memeluk dirinya sendiri, mencoba menyatukan potongan-potongan harga diri yang sudah retak sejak hari pertama di Kelas 13. Pikirnya, mungkin kalau dia diam cukup lama, bumi akan membelah dan menelannya.
Deru motor lain muncul dari kejauhan. Tapi Atha tetap diam. Tak peduli untuk sekadar menoleh. Dunia ini bukan miliknya lagi—siapa pun yang datang, biarkan datang. Dia lelah.
Langkah kaki menghampiri, pelan. Tanpa suara panggilan. Tapi Atha tahu siapa itu. Karena langkah itu tidak asing—irama gerakan yang dia kenali di tengah diam sekalipun. Namun, Atha bertanya-tanya, kenapa orang itu bisa ada di sini?
“Atha,” suara itu pelan, seperti rumput yang bergoyang di hadapannya. Tapi cukup untuk membuat Atha mendongak.
Niko berdiri di sana. Masih mengenakan seragam lengkap, rambut sedikit acak-acakan, tubuhnya agak berkeringat. Dia menenteng satu bingkisan di tangan kiri, dan ekspresi lelah di wajahnya berbicara lebih banyak daripada kata-kata.
“Lu ngikutin gue?” tanya Atha, suaranya serak, tapi tidak penuh emosi. Hanya keheranan polos, campur tak percaya.
Niko tidak langsung menjawab. Dia hanya berjalan mendekat, lalu duduk di samping Atha, langsung di tanah, tanpa ragu, tanpa menjaga jarak yang berlebihan. Remaja berkeringat itu meletakkan bingkisan yang entah apa isinya di tanah, menghela napas panjang, lalu berkata, “Gue bolos juga. Gak enak ninggalin lu sendirian.”
Mereka terdiam. Memandangi lapangan yang kini terasa lebih ramai karena keberadaan satu sama lain. Tidak bicara. Tapi tidak canggung.
“Athariel Pradana, kabur di jam istirahat pertama,” gumam Niko, nada suaranya ringan, seperti ingin membuat semuanya terasa tidak seburuk itu. “Catet sejarah.”
Atha menghembuskan napas dari hidung, suara tawa kecil menyelinap di sela-sela sesaknya. “Lu juga kabur.”
“Beda.” Niko menoleh, mata cokelatnya menatap lurus ke wajah Atha. “Lu kabur karena udah enggak kuat. Gue kabur karena gak pengen lu ngelewatin ini sendirian.”
Atha mengalihkan pandangan, tapi kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang dia harapkan. Dia tidak tahu harus bilang apa, jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah hanya menunduk lagi, memeluk lututnya lebih erat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang sedikit menghangat di dalam sana—bukan pengampunan, bukan harapan besar, tapi mungkin cukup untuk bertahan satu hari lagi.
Tidak ada percakapan yang signifikan diantara Atha dan Niko, sampai akhirnya mereka berdua berpindah duduk di bawah pohon kapuk yang menjulang tenang di tepi lapangan. Rimbun daun-daunnya memberi teduh seadanya, cukup untuk melindungi dari sengatan matahari siang yang mulai menyiksa kulit. Angin yang semula lembut kini bertiup kering, menyapu debu dari tanah lapang, membuat Atha menyipitkan mata setiap kali angin melintas.
Niko duduk bersila di atas akar pohon besar, mengutak-atik ponselnya sebentar, lalu mengangkat alis, “Lu suka dengerin lagu?”
Atha menoleh sedikit, menyipit karena silau. “Tergantung lagunya.”
“Gue mau lu dengerin sesuatu.” Niko bicara pelan, lalu mulai memutar rekaman dari ponselnya.
Musik pelan terdengar, diiringi petikan gitar akustik sederhana. Lalu, suara Niko sendiri masuk—jernih, hangat, dan agak serak di bagian akhir setiap bait. Suara yang seandainya diputar di radio, bisa membuat orang diam sejenak dalam perjalanan pulang kerja. Tapi buat Atha, suara itu terdengar seperti dunia lain yang tak pernah dia datangi. Nyaman. Penuh isi.
“Ini suara lu?” Atha bertanya ketika lagu hampir selesai. Niko hanya mengangguk.
“Gimana?” tanyanya dengan nada pura-pura percaya diri, “Bagus, kan?”
Atha menarik napas, membuka mulutnya sebentar, lalu menutupnya lagi. Namun, akhirnya remaja itu berkata pelan, “Suara lu bagus. Tapi...”
“Tapi kayak ada yang hilang?” potong Niko cepat. “Gue juga ngerasa gitu.”
Dia bersandar ke batang pohon, menatap langit sebentar, lalu menoleh ke Atha sambil tersenyum miring. “Makanya... gue butuh lu ikut ke rumah gue.”
Atha mengerutkan kening. “Hah?”
“Gue mau nunjukin karya-karya gue yang lain,” jawab Niko, nada bicaranya berubah sedikit sok santai. “Siapa tahu lu bisa bantu kasih masukan. Atau... mungkin lu bisa nemuin, kenapa lagu gue ini selalu ngerasa kosong di bagian akhirnya.”
Atha masih menatapnya, diam. Matanya seperti berusaha membaca maksud tersembunyi di balik ekspresi santai itu. Tapi Niko tidak memberinya celah.
“Yuk, mumpung hari ini lo udah bolos sekalian,” tambahnya cepat, seperti sedang menawarkan hal sepele. “Gue gak gigit, kok.”
Atha akhirnya menunduk, mengangguk pelan. “Ya udah.”
Dan dengan itu, mereka bangkit perlahan. Tanpa bicara banyak, Niko melangkah lebih dulu ke arah motornya, dan Atha menyusul di belakang. Langkah mereka tenang, tidak tergesa. Tapi dalam hati Niko, ada sesuatu yang bergerak—lega, mungkin, atau cemas. Entahlah. Yang jelas, ini pertama kalinya dia mengajak seseorang masuk ke dunia kecil yang selama ini dia simpan sendiri.
Deru mesin motor terdengar bersahut-sahutan saat keduanya melaju keluar dari lapangan tandus itu. Jalanan di sisi selatan kota tidak terlalu ramai di jam-jam segini, hanya beberapa kendaraan lewat, selebihnya sunyi dan kosong seperti waktu yang lupa lewat di sana.
Atha menyetir motornya perlahan di belakang Niko, mengikuti arah tanpa tanya. Helmnya kini dikenakan, tapi pikirannya masih di tempat tadi, pada lagu yang nyaris utuh namun terasa seperti menyimpan rahasia. Lagu yang membawa perasaan aneh yang entah kenapa ingin ia dengar lagi.
Mereka berbelok di sebuah tikungan kecil menuju jalan perumahan elite. Atha sempat berpikir Niko hanya akan berhenti menjemput sesuatu atau mungkin memutar balik. Tapi motor itu terus melaju, masuk ke dalam sebuah kompleks perumahan dengan jalan mulus, pepohonan rindang, dan rumah-rumah yang seperti keluar dari majalah interior.
Tak lama, mereka berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna krem dengan atap abu-abu tua dan pagar hitam minimalis yang terbuka otomatis. Atha memperlambat laju motornya, matanya menatap sekeliling—rumput halus, taman terawat, dan rumah dua lantai yang jendelanya tinggi-tinggi.
“Masuk aja, parkir di garasi sini,” ucap Niko sambil menepuk pelan jok motornya, santai seolah membawa teman ke rumah sebesar itu adalah hal biasa.
Atha memarkir motornya di sebelah motor Niko, di garasi semi-terbuka dengan lantai keramik abu yang mengilap. Helmnya dia letakkan di jok. Atha menatap rumah itu sejenak. Di dalam pikirannya, rumah ini mungkin empat—atau bahkan lima—kali lipat lebih besar dari rumahnya sendiri. Rumah yang hanya punya dua kamar dan satu ruang tamu yang merangkap ruang keluarga dan ruang makan.
Saat pintu depan terbuka, aroma khas rumah mahal langsung menyapa. Wangi netral yang bersih, pencahayaan hangat, dan segala sesuatu tampak tertata tanpa cela. Ruang tengahnya luas, dengan sofa krem berbentuk L yang empuk, lemari rak kaca penuh piala dan bingkai foto, serta sebuah piano putih berdiri manis di pojok ruangan. Di dindingnya tergantung lukisan besar bertema abstrak dan ornamen-ornamen artistik—beberapa tampak buatan tangan, lainnya terlalu mahal untuk ditebak.
Atha melangkah pelan masuk, nyaris tak berani menginjak karpet tebal di bawah kakinya. Pandangannya menyapu sekeliling, dan semuanya berteriak tentang musik. Ada speaker profesional di tiap sudut ruangan, rak penuh vinyl dan CD, beberapa gitar tergantung dengan rapi, dan bahkan poster konser dari tahun-tahun lalu.
“Gila...” gumam Atha, tanpa sadar.
Niko terkekeh pendek, “Ya, gue hidup di tengah-tengah beginian sejak kecil.”
Mereka tidak lama di ruang tamu. Niko langsung mengajaknya naik ke lantai dua melewati tangga kayu jati yang setiap injakan terasa mahal. Kamar Niko ada di ujung lorong, pintunya putih polos dengan stiker kecil berbentuk not musik di sudut bawah.
Begitu pintu terbuka, Atha hampir tak bisa berkata-kata.
Kamar itu seperti studio mini—separuhnya dipenuhi perlengkapan rekaman. Ada komputer, midi controller, mic condenser, headphone mahal yang digantung dengan rapi, dan dinding kedap suara di satu sisi. Di dinding satunya lagi, ada pajangan berupa sertifikat lomba cipta lagu, piagam-piagam kejuaraan, bahkan kliping artikel kecil yang membahas tentang Niko di majalah sekolah musik.
Atha berdiri kaku di ambang pintu. Dunia ini terasa jauh, sangat jauh, dari lapangan sekolah Kelas 13 yang penuh debu dan ketidakpedulian.
“Masuk aja,” kata Niko, agak kikuk, menggaruk lehernya sambil tersenyum. “Jangan kaget. Ini... ya, tempat gue nyari napas. Yah, agak kayak kapal pecah, sih.”
Atha melangkah masuk, mengamati semua detail dengan takjub yang tak bisa disembunyikan. “Lu... keren banget, Nik.”
Niko cuma nyengir kecil, tapi wajahnya agak kemerahan. Remaja itu berjalan ke rak dekat meja kerjanya, melemparkan tas hitam ke kasur secara acak, kemudian menarik satu buku catatan dan beberapa lembar kertas musik, lalu menaruhnya di meja. Dia tampak sibuk sejenak, lalu berbalik dan melihat Atha yang masih berdiri di tengah ruangan, tampak kecil di antara segala pencapaian itu.
“Lu tinggal di sini sama siapa?” tanya Atha tiba-tiba.
Pertanyaan itu menggantung di udara beberapa detik. Niko, yang tengah membuka laptopnya, menoleh cepat. “Hah? Oh... ya, sama orang tua gue.”
“Mana mereka?”
Sekilas, ekspresi Niko berubah. Ada jeda. Sepersekian detik yang terlalu cepat untuk disebut mencurigakan tapi terlalu nyata untuk dianggap wajar.
“Lagi keluar. Sibuk aja biasanya,” jawabnya sambil mengalihkan pandangan, lalu menyalakan speaker bluetooth di dekat jendela. Musik instrumental pelan mengalir dari situ, seolah jadi pengalih yang disengaja.
Atha memutuskan tidak mendesak. Tapi ia mencatat perubahan itu—senyap dan canggung—seperti irama sumbang dalam lagu yang hampir sempurna.
Suasana kamar Niko sehangat cahaya sore yang merambat pelan dari balik tirai jendela. Lantai kayunya dingin, tapi nyaman. Atha duduk bersila di sana, punggungnya bersandar ke sisi kasur. Di dalam ruangan itu, ada yang menggelegak pelan di dada Atha—perasaan asing yang mendekati kagum, tapi juga getir.
Rumah ini bukan hanya besar, tapi juga punya napas, napas yang hidup dari musik dan impian. Sementara rumahnya sendiri hanya berisi tuntutan dan kenangan masa lalu.
Niko duduk di depan keyboard elektrik yang diletakkan di sudut ruangan, satu kakinya menggoyang pelan mengikuti irama yang dia mainkan. Tangannya menari di atas tuts, memainkan melodi sederhana—cerah, tapi ada sedikit luka di dalamnya. Ketika musik berhenti, dia menoleh ke arah Atha dengan senyum kecil.
“Mau nyoba?” tawarnya sambil menunjuk keyboard.
Atha menggeleng, lalu menjawab pelan, “Gue gak bisa main musik.”
“Siapa bilang harus bisa?” Niko berdiri, mengambil dua stik drum kecil dan menyerahkannya ke Atha. “Lu tepuk beat-nya aja. Ikutin tempo gue.”
Tanpa banyak protes, Atha menerimanya. Niko duduk kembali, kali ini memainkan akor-akor ringan dengan nada jazzy, sesekali menatap Atha untuk memberi aba-aba. Awalnya canggung, tapi lima menit kemudian tawa Atha mulai terdengar. Mereka berantakan, temponya berantakan, melodinya sering meleset. Tapi mereka tertawa.
“Lu tahu enggak, Nik?” kata Atha setelah mereka berhenti karena kehabisan napas. “Ini kali pertama gue ketawa sejak… sejak kelas dua belas akhir.”
Niko tidak langsung menjawab. Dia membuka laptopnya, memperdengarkan potongan-potongan lagu yang pernah dibuatnya. Suara Niko terdengar lebih matang di rekaman, tapi juga lebih sendu.
“Gue kira… gue udah rusak,” Atha tiba-tiba berkata. Pandangannya lurus, tidak menatap siapa-siapa. “Kayak… udah gak layak buat ada di mana pun.”
Niko diam. Lama.
Lalu, sambil memainkan nada rendah di keyboard-nya, dia berucap lirih, “Sama. Tapi… rusak bukan berarti gak bisa bunyi lagi, kan?”
Kalimat itu menggantung di udara. Atha menoleh. Niko tak melihatnya, sibuk menatap tuts yang disentuhnya dengan ringan. Ada luka dalam ucapannya, tapi juga kekuatan yang belum sempat dia bicarakan. Atha tahu, bukan hanya dia yang bertahan. Niko juga. Mungkin mereka semua.
Matahari perlahan tenggelam, menyisakan cahaya oranye di balik jendela kamar. Suara keyboard berhenti. Ruangan jadi hening, tapi tidak canggung. Untuk pertama kalinya sejak lama, Atha tak merasa seperti beban. Hanya remaja biasa, duduk di lantai kamar temannya, tertawa, dan diam dengan hati yang sedikit lebih ringan.
Lalu, ketika Atha hendak bertanya sesuatu—tentang lagu yang tadi diputar, tentang kenapa Niko selalu terdengar sendu saat menyanyi—tiba-tiba ponsel Niko berdering keras memecah keheningan. Nada deringnya nyaring, kontras dengan suasana yang baru saja jadi tenang.
Niko melihat nama di layar, wajahnya langsung berubah. Sekilas saja, tapi cukup untuk Atha menangkapnya.
Tanpa berkata apa-apa, Niko bangkit berdiri dan keluar dari kamar, meninggalkan Atha yang masih duduk terpaku di lantai. Suara langkah kaki Niko menjauh, disusul suara pintu yang dibuka pelan, lalu tertutup kembali.
Atha menoleh ke layar laptop yang masih menyala. Salah satu folder musik masih terbuka. Judul salah satu lagunya mencolok di antara semua file.
Maaf, Aku Gagal Menyelamatkan Dia.
Dan, sebelum Atha sempat menggerakkan kursornya, layar laptop tersebut mati.


 harrisradcliffe
harrisradcliffe
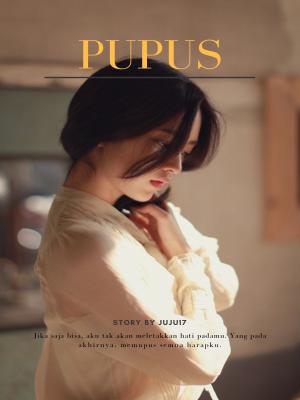

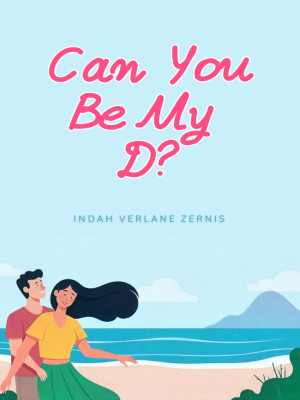







arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN