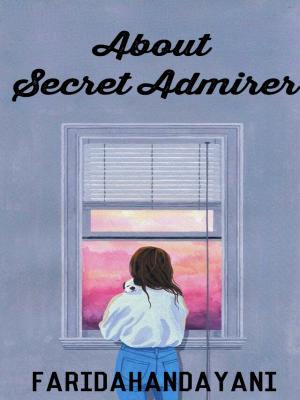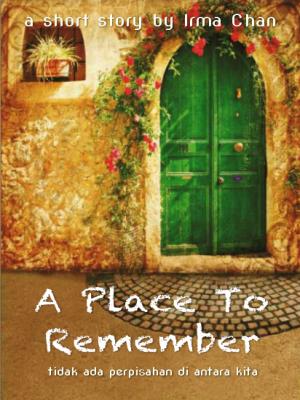Aku tertidur dalam posisi duduk, kepalaku terbaring di sisi ranjang Fahmi. Tidak ada yang membangunkanku selain gerakan halus dari tangannya yang menggelitik punggung tanganku.
"Hmm, masih ngantuk..." gumamku sambil mengibaskan tangannya. Tapi Fahmi kembali menggelitikku, kali ini lebih keras dan lebih mengganggu.
Aku terusik dan akhirnya terbangun. Begitu tersadar, aku melihat diriku sendiri yang tertidur di sebelah ranjang Fahmi dengan air liur menetes di sepreinya. Aku terkejut dan buru-buru menghapusnya dengan punggung tangan. Saat aku menoleh, Fahmi terkekeh ke arahku.
"Kau ngiler, hehe."
"Hah?! Maaf, maaf! Aku nggak sengaja!" Aku panik, langsung mengusap bibirku yang masih terasa basah. Rasanya sangat memalukan kalau Fahmi melihatku dalam keadaan seperti ini.
"Selamat pagi," ucapnya ramah.
"Pagi. Aku ketiduran ya semalam?"
"Entahlah. Semalam aku masih belum sadar sepenuhnya. Tapi pagi ini aku lihat kau sudah ada di samping ranjangku... dengan air liur menetes pula, haha."
"Astaga, aku malu sekali..." Aku ingin sekali menenggelamkan kepalaku ke dalam tanah. Sebagai seorang wanita, tidur sampai meneteskan air liur adalah hal yang sangat menjijikkan—terutama di depan Fahmi.
"Omong-omong, kau sudah baikan?" tanyaku, berusaha mengalihkan pembicaraan.
"Sedikit pusing sih, tapi nggak masalah. Sudah mendingan."
"Syukurlah."
"Omong-omong" Aku membuka obrolan kembali. “Bagaimana ceritanya setelah kau tertangkap sewaktu di gua?”
Fahmi terdiam sejenak, mencoba merangkai kata sebelum mengucapkannya padaku. “Waktu itu, wajahku di tutup oleh kain tebal. Aku tidak bisa melihat. Rasa sakit akibat pukulan di perut begitu terasa. Namun yang mengejutkanku adalah suara tembakan yang bertubi-tubi ketika aku rasakan kapal sudah berlabuh. Aku langsung dilarikan ke suatu ruangan dan disekap disana. Rasanya lama sekali. Mungkin satu bulan atau lebih.”
Aku menelan ludah mendengar cerita Fahmi yang menegangkan. Pasti keadaan saat itu sangat amat kacau.
"Omong-omong, maafkan aku ya, Maya." Nada suara Fahmi tiba-tiba berubah lebih lembut, memutus bayang-bayangku.
"Untuk apa?"
"Karena meninggalkanmu terlalu lama."
Aku termenung. Bukankah dia pergi bukan karena keinginannya sendiri, melainkan diculik. Mungkin dia meminta maaf untuk perasaan rindu yang sudah sangat lama aku tahan. Setidaknya aku ingin menganggapnya demikian.
"Tidak apa," ucapku pelan sambil menunduk. Walau kenyataannya tidak begitu, tapi dalam hati, aku berharap Fahmi terus memperhatikanku. Saat aku kembali menatapnya, dia tersenyum lembut. Ini sudah kesekian kalinya aku melihatnya tersenyum.
Aku ingat saat pertama kali bertemu, dia adalah sosok yang dingin dan hampir tidak pernah tersenyum. Tapi sekarang, dia begitu hangat kepadaku. Aku melihat senyum itu membentuk simpul yang indah di wajahnya. Hati kecilku mengakui betapa mempesonanya dia.
"Hei, melamun ya? Nanti kesambet lho, haha."
Aku tersipu malu. "Hehe."
Dari arah pintu masuk, Ayah dan Ibu Fahmi datang. Mereka berpakaian rapi, mungkin semalam mereka sengaja membiarkanku menemani Fahmi dan memilih pulang untuk berganti pakaian. Betapa pengertiannya mereka.
"Kayaknya ada yang lagi kasmaran nih, hehe," goda Ny. Lena.
Aku dan Fahmi hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus menanggapi bagaimana.
"Tadi ayah bertanya pada dokter. Katanya setelah kondisimu membaik mereka akan melakukan pemeriksaan menyeluruh lagi, jadi bagaimana kondisimu pagi ini?" ujar Pak Yahya.
"Baik, Ayah," jawab Fahmi singkat.
Aku sedikit memundurkan diri, memberi ruang bagi Ayah dan Ibunya untuk mendekati ranjangnya.
"Tidak terasa sakit apapun kan, sayang?" tanya Ibu Fahmi lembut.
"Tidak, Bu.". Jawab Fahmi dingin.
Kulihat raut wajah Ibu Fahmi langsung berubah. Sepertinya dia tidak senang sikap ramahnya dibalas dingin. Aku menduga, Fahmi masih menyimpan rasa kesal terhadap ibunya karena kejadian tamparan itu. Padahal, aku saja sudah memaafkannya.
"Ada apa, Sayang? Kau sepertinya tidak suka Ibu menyapamu."
"Tidak ada apa-apa, Bu."
Pak Yahya mencoba mencairkan suasana. "Sudahlah, jangan tegang begitu. Hari ini hari istimewa, kita akhirnya bisa berkumpul kembali setelah sekian lama berpisah. Ini patut dirayakan."
"Tidak perlu, Ayah," jawab Fahmi lagi dengan nada datar.
"Ayolah, jangan begitu. Ayah akan pesan sesuatu untuk makan bersama. Kau masih suka Somyam, kan?"
"Iya, tapi tidak usah."
Pak Yahya mulai terlihat kesal, namun Ibu Fahmi segera menenangkan situasi. "Sudahlah, Yah. Kalau Fahmi tidak mau, ya jangan dipaksa."
Akhirnya pak Yahya menyerah lalu lanjut membicarakan kondisi Fahmi.
Di tengah percakapan mereka, Pak Yahya menerima telepon dan buru-buru pamit. Dia sempat mencium kening Fahmi, meski anaknya terlihat sedikit enggan. Aku semakin yakin, ada yang tidak beres dalam hubungan mereka.
Setelah Pak Yahya pergi, suasana semakin canggung. Tapi tak lama kemudian, suara pintu terdengar. Seorang dokter dan beberapa perawat masuk untuk memeriksa kondisi Fahmi. Aku dan Ibu Fahmi diminta menunggu di luar.
Saat kami duduk di lorong, Ibu Fahmi menatapku serius. "Maya, karena kasus pengeboman di Palangka sudah menemui titik akhir, aku dan suamiku bersepakat untuk menepati janji kami. Nama baikmu akan kami bersihkan, dan kau bisa kembali menjalani hidup secara normal lagi".
Aku tersenyum lega. "Terima kasih banyak, Bu. Aku sungguh senang".
Namun, senyum itu memudar saat mendengar kata-kata berikutnya.
"Tapi itu berarti kau harus menjauh dari keluarga kami, terutama Fahmi."
Aku terhenyak. "Kenapa, Bu? Aku kira Ibu tidak masalah dengan hubungan kami?"
"Memang, tapi kau tahu sendiri, setelah penjelasan detektif semalam, kasus yang menyeret keluarga kami ini ternyata sangat berbahaya. Nyawa adalah taruhannya. Semakin lama kau berada di dalamnya, semakin besar risiko yang kau hadapi. Aku tidak ingin melihat kalian berdua terluka atau mungkin terbunuh. Jangan sia-siakan masa depan kalian demi cinta sesaat."
Hatiku mencelos. Cinta sesaat? Tidak! Aku benar-benar mencintai Fahmi Sekarang! Kenapa wanita ini melarangku, padahal kami baru saja disatukan setelah sekian lama terpisah?
"Tapi, Bu... Aku tidak bisa! Aku dan Fahmi saling mencintai! Aku ingin hubungan kami bertahan! Ini bukan cinta sesaat!" Aku berusaha meyakinkannya.
“Pikirkan keselamatanmu dan keselamatan Fahmi. Apa kau ingin semuanya berakhir buruk? Aku mungkin bisa menjanjikan keamanan bagi Fahmi, tapi bagi dirimu, aku tidak tahu. Jadi lebih baik kau pertimbangkan lagi hubungan kalian dan mulailah menjalani hidup dengan tenang dan aman”.
“Tapi…”. Kata-kataku tercekat, tidak dapat keluar. Rasanya ada seribu tangan yang menahannya. Hatiku sedih, namun apa yang disampaikan ibu Fahmi memang benar adanya. Jika hubungan kami diteruskan, nyawaku bisa terancam. Bahkan mungkin Fahmi juga. Tapi perasaan cinta yang pertama aku rasakan sekarang jelas sesuatu yang langka. Aku tidak tahu apakah nanti aku akan bertemu dengan pria lain seperti Fahmi atau tidak. Aku bingung.
“Pikirkanlah”. Setelah lama memperhatikan, Ibu Fahmi melihat kedatangan dokter dan perawat yang baru keluar dari kamar Fahmi, mereka memberi tahu bahwa pemeriksaan telah selesai.
"Dokter, bagaimana kondisinya?" tanya Ibu Fahmi menghampiri dengan tergesa.
"Syukurlah, tidak ada luka serius. Hanya memar sedikit akibat benturan. Perawat sudah mengobatinya. Kemudian dia perlu asupan bergizi untuk mengembalikan staminanya yang hilang dan istirahat total beberapa hari. Setelah pulih, dia bisa beraktivitas normal lagi."
"Syukurlah dok".
"Iya, kalau tidak ada pertanyaan lain aku permisi dulu“.
Kami saling mengangguk mengiyakan dan berpisah. Karena Sudah masuk jam besuk, Ny. Lena dan aku masuk ke dalam ruangan dan melihat Fahmi. Kali ini dia tersenyum kembali. Tapi matanya tidak tertuju pada ibunya, melainkan kepadaku. Aku membalas senyumannya.
"Syukurlah, Fahmi. Semuanya baik-baik saja."
"Iya. Ibu“.
Ibu Fahmi duduk di samping ranjang sedangkan aku berdiri di sisi lain ranjang.
"Bu bolehkah aku berdua saja sebentar dengan Maya? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan".
Aku terkejut. Apa yang ingin disampaikan Fahmi? Sepertinya hal penting. "Baiklah”. Ibu Fahmi mengangguk dan melangkah keluar ruangan menyisakan kami berdua. Tapi dia sempat menoleh ke arahku dan memberikan tanda seolah memintaku untuk membicarakan apa yang tadi aku dan ibu Fahmi bicarakan di luar.
Setelah kami berdua, Fahmi memulai percakapan. "Mbak Maya"
"Hus, panggil Maya saja, kan sudah kubilang."
Fahmi terkekeh kecil. "Hehe, baik. Maya, saat aku menghilang... apa kau rindu padaku?"
Aku sedikit terkejut dengan pertanyaanya, sungguh sangat langsung ke intinya. Aku menanggapinya hanya dengan tersenyum dan mengangguk. Fahmi menatapku sejenak kemudian melanjutkan, "Aku pun merindukanmu, bahkan selalu memikirkanmu."
Kali ini aku terdiam, belum langsung menanggapi ucapannya. "Kenapa diam?" tanya Fahmi, menuntut jawaban.
"Ah, tidak. Aku senang kamu merasakan hal yang sama. Hanya saja”.
“Hanya apa?”.
“Hmm Ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya." Aku menarik napas sebelum melanjutkan, "Kenapa secepat itu kamu menyukaiku? Padahal aku bukan gadis yang menarik dan umurku pun lebih tua darimu. Bahkan kita baru sebentar bertemu."
Fahmi tersenyum lembut. "Sejujurnya, di awal pertemuan kita, aku belum merasakan sesuatu. Tapi saat kita bertemu lagi, ketika aku melihat ketulusan dan perhatianmu, rasa itu mulai muncul. Hingga sekarang, perasaan itu semakin kuat karena aku tahu kamu selalu ada disampingku."
Hatiku menghangat. Aku yakin, kali ini cintaku tidak akan bertepuk sebelah tangan.
"Sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan umur dan statusmu, yang kuinginkan hanyalah tetap bersamamu dan menjagamu," lanjutnya.
Aku semakin tersentuh oleh kata-katanya. Akan tetapi, aku sedikit ragu menanggapi.
"Jika aku boleh jujur, aku pun merasakan hal yang sama. Tapi..." Aku menunduk, mengingat perkataan Ibu Fahmi. "Ibumu sangat mengkhawatirkan keselamatan kita”. Aku menghentikan kalimatku lagi.
“Maksudnya?”. Tanya Fahmi keheranan.
“Sebenarnya ibumu menyuruhku untuk menjauh dari keluargamu...dari kamu. Karena kasus kriminal yang menyeret keluargamu sangat berbahaya dan belum terselesaikan, maka bisa saja itu membahayakan kita berdua. Nyawa kita".
Fahmi mengernyit. "Jadi kau tidak mencintaiku?"
Aku tersentak. "Bukan begitu!"
"Lalu kenapa? Kenapa kau tidak membantah saja ibuku dan ikuti perasaanmu".
"Masalah penculikan dan pengeboman ini bukan hal sepele, Fahmi. Ada perseteruan besar di baliknya. Jika kita terus bersama, aku tidak tahu akan seperti apa hidupku dan hidupmu nanti".
Fahmi mengepalkan tangannya. "Omong kosong! Aku tidak terima alasan itu. Ibuku memang tak pernah mengerti aku. Dan kau...kau sama saja rupanya."
Aku menatapnya, mencoba meredam emosinya. "Fahmi, aku hanya ingin melindungimu. Aku rasa ibumu ada benarnya".
Fahmi tercekat, seperti baru saja mendengar penolakan. "Kalau begitu, kita pergi saja dari sini. Meninggalkan kota ini".
Aku terbelalak. "Kau gila? Otakmu terbentur sesuatu kah?".
"Tidak! Kita kabur aja dulu ke kota lain".
Aku mulai kesal. "Ke mana?".
"Bandung," jawabnya mantap.
Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari keseriusan dalam perkataannya. Sepertinya pikirannya sedang kacau. Aku tidak menanggapi ucapannya hingga pintu kamar diketuk. Rupanya Ibu Fahmi masuk dan menghentikan diskusi kami.
"Kalian bicara apa sih? Sepertinya serius sekali," godanya.
Aku mendengus kecil. "Nggak ada, Tante. Cuma obrolan basa-basi. Tapi sepertinya aku ingin pulang dulu untuk mandi dan istirahat. Apa boleh?"
Fahmi menatapku dan menggenggam tanganku. Seperti tidak terima dengan sikapku yang menghindar.
"Tunggu, kita belum selesai bicara, kau mau kemana?".
"Aku mau pulang ke tempatku—maksudku, rumahmu".
"Kau tinggal di sana sekarang?"
"Hanya sementara".
"Kalau begitu, aku akan meneleponmu nanti".
"Aku nggak punya Ponsel ".
"Ambil di laci kamarku, ada ponsel cadangan yang bisa kau gunakan."
Aku mengangguk, lalu berpamitan. Ibu Fahmi memberi tahu bahwa ada pengawal di luar yang bisa mengantarku. Aku pun beranjak pergi.
Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi dengan ucapan Fahmi. Dia benar-benar ingin kabur bersamaku ke Bandung. Itu benar-benar gila. Dia tidak pernah berpikir panjang tentang konsekuensi yang akan terjadi. Itulah Fahmi yang kukenal. Orang yang selalu berpikir untuk kabur-kabur dan kabur.
Saat tiba di kediaman Fahmi, aku melihat tumpukan barang di luar rumah. Semakin aku mendekat, semakin aku mengenali barang-barang itu. Aku terkejut. Itu barang-barangku!
Aku melangkah lebih dekat dan melihat ada barang lain yang ditumpuk. Sepertinya milik para 'aktor' lainnya. Aku menghampiri salah satu penjaga. "Permisi, kenapa barang-barang ini ada di luar?"
"Oh, Anda mbak Maya ya. Ini perintah dari Pak Yahya mbak. Para ‘aktor’ hari ini dipulangkan. Semua barang di kamar masing-masing sudah dikemas dan siap diantar ke tempat asalnya."
"Maksudmu, aku harus pergi hari ini juga? Ke mana?"
Penjaga itu melihat ponselnya. "Ke apartemen mbaknya di Jalan C. Bangas."
Aku tercengang. Itu alamat apartemenku dulu.
“Apartemenku kan?”. Aku memastikan.
“Iya”.
Akhirnya aku bisa kembali ke sana. Sungguh menyenangkan, meskipun caranya terasa kasar. Menumpuk barang-barang orang di luar seperti sampah. Aku sedikit kesal. Terutama pada Pak Yahya.
"Tapi ada barangku yang tertinggal di kamar."
"Tidak ada. Sesuai catatan, semua barang Anda sudah dipastikan terangkut."
Aku sebenarnya ingin mengambil ponsel yang disebutkan Fahmi tadi. Tanpa itu, aku tidak tahu bagaimana caraku menghubunginya nanti.
Aku mencoba bersikeras kepada penjaga, tapi dia mengecek ulang ponselnya dan menegaskan bahwa ponsel itu tidak ada dalam daftar barang yang sempat aku bawa ketika pindah kesini. Dia menolak dan mengisyaratkan agar aku segera pergi.
Aku menghela napas panjang. Tak ada pilihan lain. Dengan hati berat, aku naik ke dalam mobil yang akan mengangkut barang-barangku dan melaju menuju apartemen lamaku.
Diperjalanan aku memikirkan seribu cara bagaimana caranya agar bisa berkomunikasi dengan Fahmi. Walaupun aku membeli ponsel baru, dia belum tentu tahu nomornya. Apakah aku akan terpisah lagi dengannya. Lalu bagaimana dengan rencana kami untuk ‘kabur aja dulu ke Bandung’?. Sungguh sebagian hatiku belum rela untuk berpisah lagi dengannya.


 risyadfarizi
risyadfarizi