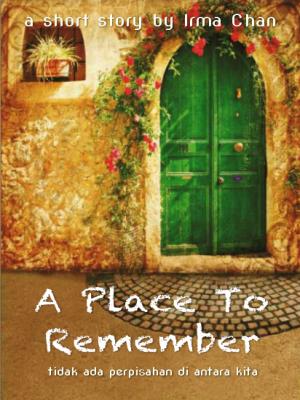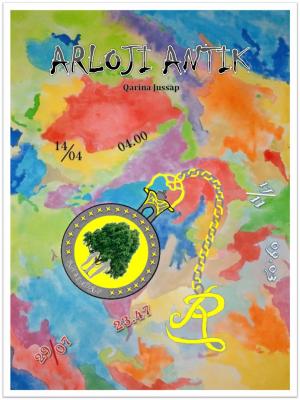Aku mencekik Fahmi dengan borgol di tanganku. Itu adalah reaksi spontan, sebuah pertaruhan hidup yang nekat. Cekikanku tidak kuat, tetapi cukup untuk membuat suaranya tercekat. Ia terbatuk, mulutnya menganga, dan tangannya reflek meraih borgolku yang mengencang di lehernya.
Matanya penuh keterkejutan, tetapi tubuhnya yang lemah tidak bisa melawan. Bekas pukulan dari para penculik telah menyedot habis energinya. Sementara itu, dua pria yang tadi memukulinya kini berdiri terpaku, bingung dengan tindakanku.
"Fahmi, maafkan aku. Aku janji, ini hanya sandiwara..." Aku berbisik, lebih kepada diriku sendiri, mencoba meyakinkan bahwa semua ini tidak salah.
Namun, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara kaki-kaki yang berlari tegas terdengar diikuti teriakan lantang.
"Berhenti! Ini polisi!"
Aku tercekat. Jantungku berdegup berhenti sejenak. Kepanikan melanda, bahkan ke seluruh ruangan. Kedua penculik langsung lari tunggang langgang, meninggalkan aku dan Fahmi.
Polisi datang di saat yang salah. Mata mereka langsung tertuju padaku—aku, yang terlihat seperti penjahat sungguhan yang tengah mencekik seorang remaja tak berdaya.
Beberapa polisi mengejar para penjahat--sungguhan--yang kabur. Sedangkan salah satu polisi mendekat dan langsung meringkusku. Tangannya yang kuat menggenggam tanganku dengan keras. Aku tidak melawan. Apa gunanya? Semuanya sudah selesai.
---
Fahmi diselamatkan oleh polisi, sedangkan aku, di dalam mobil tahanan duduk terdiam. Pandanganku kosong menatap keluar jendela. Banyak sekali kerumunan warga disana-sini. Mereka berkerumun menyaksikan kejadian bom yang meledak tak jauh dari lokasiku di ringkus.
Namun aku tidak peduli semua itu, aku hanya peduli pada nasibku.
"Jadi ini akhirnya?" pikirku. Tidak ada pembelaan, tidak ada cara untuk menjelaskan kebenaran. Yang ada hanyalah kenyataan pahit: aku ditangkap, lagi.
Tiba-tiba mobil berhenti di pinggir jalan. Aku bingung. Ini jelas bukan kantor polisi. Salah satu petugas menerima telepon dan berbicara dengan nada serius. Aku mencoba mendengarkan, tetapi tidak ada yang jelas.
Beberapa saat kemudian, pintu mobil terbuka. "Keluar," perintah salah satu polisi. Aku menurut, meski kepalaku dipenuhi rasa penasaran bercampur takut.
Di belakang mobilku, sebuah mobil hitam mewah berhenti. Pintu mobil itu terbuka, dan seseorang keluar. Aku menahan napas ketika melihat siapa yang keluar. Meski wajahnya lebam dan tubuhnya limbung, aku mengenali sosok itu.
Fahmi.
Dia mendekat, langkahnya pelan, dibantu seseorang. Kami saling tatap. Aku tidak bisa membaca pikirannya, tapi melihat kondisinya membuat hatiku terenyuh.
Ketika jarak kami sudah cukup dekat, dia berkata pelan, "Terima kasih sudah menyelamatkanku."
Lalu dia berbalik, kembali ke mobilnya.
Aku terpaku. Itu saja? Hanya itu?
Kata-katanya berputar di kepalaku seperti gema. Apakah dia tidak akan mencoba membela diriku? Atau paling tidak menjelaskan bahwa aku tidak berusaha mencelakainya?
Aku kebingungan oleh tindakannya.
Aku dipaksa masuk kembali kedalam mobil.
---
Sesampainya di kantor polisi, aku segera diinterogasi. Pertanyaan-pertanyaan tajam terus dilontarkan: nama, umur, pekerjaan, dan tentu saja, tentang pembunuhan Bu Diana.
"Sudah aku tegaskan aku bukan pelaku pembunuhan, aku tidak tahu apapun. Bahkan ketika aku keluar dari bilik toilet bu Diana sudah tak bernyawa". Sergahku, nadaku ketus. "Lagian semua orang di gedung itu sudah mati karena bom. Apa artinya satu pembunuhan jika dibandingkan semua itu?"
"Tindak kejahatan tetap harus diusut, tidak peduli apa pun yang terjadi setelahnya," jawab polisi di depanku dengan datar. kemudian per tanyaan berlanjut tentang keter libatan ku dalam penculikan Fahmi.
Aku kembali membela diri, bersikeras bahwa aku tidak terlibat ataupun bersalah. Namun lagi-lagi polisi itu tidak peduli dan melanjutkan tulisannya di komputer.
Aku menghela napas panjang. Tidak ada gunanya berdebat. Akhirnya dengan perlahan, aku mulai menceritakan semuanya—tentang bagaimana aku menemukan tubuh Bu Diana, tentang keterlibatanku yang tidak sengaja, dan tentang usaha pelarianku.
Ketika tiba di bagian tentang Fahmi, aku menekankan bahwa cekikanku hanya sandiwara.
"Itu caraku untuk menakut-nakuti penculik. Aku tidak pernah berniat menyakitinya, malah hendak menyelamatkannya," jelasku dengan nada penuh harap.
Namun, polisi hanya mengetik tanpa komentar. Ketika akhirnya mereka mencetak hasil interogasi itu dan memintaku membacanya, aku tidak punya pilihan selain menyetujuinya.
Setelah semua aku konfirmasi kebenarannya. aku diminta untuk menunggu
---
Setelah menunggu, dua polwan mendatangiku. Mereka terlihat ramah, bahkan mencoba menenangkanku.
"Mbak aman kok. Percaya sama kami," ucap salah satu dari mereka, menggandeng tanganku lembut.
Aku tersenyum tipis, merasa sedikit nyaman untuk pertama kalinya. Namun kenyamanan itu hancur ketika aku dibawa dan melihat pintu sel tahanan di depan sana.
"Tidak! Aku tidak bersalah! Aku tidak pantas dipenjara!" Aku mencoba mundur, menolak masuk. Tapi kedua polwan itu tetap mendorongku dengan tenang.
"Mbak sementara di sini dulu ya. Semuanya akan baik-baik saja kok."
Baik-baik saja? Aku hampir tertawa getir mendengar kata-kata itu. Tangisku pecah ketika aku masuk kedalam sel dan pintu sel dikunci.
"Arrrgh." Tangisku.
---
Aku terduduk memeluk lutut di pojokan, ku benamkan wajahku diantaranya.
Orang-orang yang pernah kukenal mulai bermunculan di pikiranku—orangtuaku, rekan-rekan kerjaku, dan... Fahmi. Ya, Fahmi. Entah mengapa, wajahnya mulai menghantuiku.
"Kenapa aku memikirkannya?" bisikku, memarahi diriku sendiri. Tapi tidak ada jawaban.
Cukup lama aku meratapi diri dan terbenam dalam kesedihan, suara seorang wanita terdengar dari luar sel mengejutkanku.
"Kau akan bebas, asalkan kau mau bekerjasama denganku."
Aku menoleh cepat. Dan kutatap wajah wanita itu lekat-lekat. Aku tidak mengenalnya.
"Siapa kau?".
"Aku ibu dari Fahmi Al Yahya"
"Ibu Fahmi?" tanyaku memastikan, suara ku bergetar.


 risyadfarizi
risyadfarizi