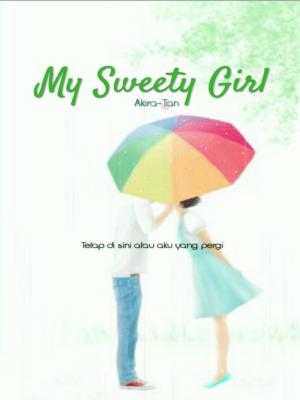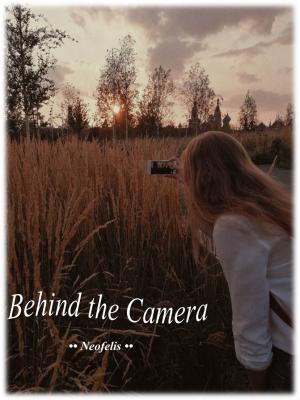Puspa selalu tidur malam lebih awal. Dia hanya menunggu hingga suara azan Isya selesai berkumandang, meskipun tidak diikuti dengan menegakkan salat. Namun, ada yang berbeda malam ini. Puspa menyempatkan diri menoleh ke arah mukena yang selalu terlipat rapi di bawah meja, walau akhirnya tetap memutuskan berbaring istirahat. Efek mengantuk dalam obat antidepresan dosis rendah yang dikonsumsi ternyata masih lebih kuat dalam diri Puspa, dibandingkan motivasi untuk kembali berdialog rahasia sesuai cara yang diminta Sang Khalik.
Usai merapikan letak selimut yang menutupi tubuh Puspa, Jaya melangkah keluar menuju satu titik pasti. Tapak sepatunya terus menyusuri koridor dalam bangunan penjaga sejarah yang telah menyaksikan banyak perjalanan hidup ini.
***
Sepasang sepatu kulit berwarna hitam itu kini telah mengantar pemiliknya memasuki bangunan RSJ Jaya Manah. Bangunan itu terletak di tengah-tengah hamparan hijau yang tenang, seolah-olah menjadi sebuah dunia terpisah dari keramaian luar.
Arsitekturnya menggabungkan unsur klasik dan modern, menciptakan citra yang ramah dan menenangkan. Atapnya berbentuk puncak genteng merah dan dindingnya tersusun dari batu putih yang memancarkan kemegahan.
Memasuki pintu utama bangunan, cahaya lembut dari lentera dinding memancarkan jejak yang memandu pasien dan staf melewati lorong-lorong. Jaya menyempatkan diri mendongak, menatap langit-langit yang tinggi berhiaskan relief berbentuk daun dan bunga yang terbuat dari semen.
Jaya menikmati sejenak karya seni yang memanjakan mata di sekelilingnya, sambil iseng mengingat-ingat RSJ mana lagi yang memiliki detail begitu artistik bahkan hingga ke bagian plafon.
Senyuman dan salam ramah melintas dari staf ke pasien dan pengunjung, menciptakan rasa nyaman yang tidak hanya berasal dari tempat ini, tetapi dari setiap individu yang mengisi ruang-ruangnya. Seperti anggota keluarga yang penuh perhatian, RSJ Jaya Manah membawa kehangatan dalam hal-hal yang paling pribadi dan penuh rahasia. Sangat jauh dari kesan angker, angkuh, dan tertutup.
Langkah Jaya melintasi ruang tunggu yang didekorasi dengan seni dan tanaman hias, memberikan suasana yang santai dan damai. Bunyi gemericik air dari air mancur di taman dalam ruangan membawa efek menenangkan yang mampu meredakan kegelisahan. Bahkan, aroma harum bunga dan lilin yang terselip di sela-sela ruangan mengajak orang untuk menghirup ketenangan.
Hanya tampak dua pengunjung yang sedang berbicara dengan staf yang telaten meladeni setiap pertanyaan mereka. Ruang ini memang sepi seperti biasanya, karena kehidupan sesungguhnya tersembunyi di dalam sana.
Di antara koridor-koridor itu, ada setiap ruangan di sisi kanan dan kirinya menyimpan kenangan masa lalu. Tempat-tempat di mana pasien dulu menemukan dukungan, kenyamanan, dan terapi yang telah membantu mereka mencari jalan menuju pemulihan.
Tiga puluh tahun merupakan waktu yang cukup bagi Jaya untuk menyaksikan bagaimana RSJ Jaya Manah bukan hanya tempat untuk merawat fisik, tetapi juga menghidupkan jejak-jejak perjalanan mental dan emosional.
Sejak kecil, dia selalu mencari alasan untuk bisa mengunjungi RSJ ini, meskipun Profesor Wijaya tidak di tempat. Toh, dia cukup akrab dengan para perawat, karyawan, bahkan pasien di dalamnya.
Langkah Jaya terhenti melihat seorang gadis yang tiba-tiba menyeruak masuk ke ruang terapi kelompok yang ada di dekat posisi Jaya berdiri. Gadis berambut panjang itu terlihat sangat gelisah. Semua mata langsung tertuju padanya, dan suasana dalam ruangan pun menjadi tegang.
Bu Sari yang sedang mengatur berjalannya sesi berbagi itu pun dengan lembut tetapi tegas berkata, “Maaf, sesi ini sedang berlangsung. Mungkin kamu bisa kembali lain waktu."
Gadis itu bukannya mendengarkan, malah terus berbicara dengan cepat dan terdengar begitu cemas. Dia mengatakan dirinya adalah pasien baru yang telah dirujuk ke RSJ dan sangat membutuhkan bantuan.
Jaya dan Bu Sari saling pandang. Seolah-olah saling memahami isi pikiran masing-masing, Bu Sari meminta peserta kelompok untuk tetap tenang sementara Jaya berdialog dengan gadis itu.
"Tentu, kami ingin membantu. Berbicara jauh lebih baik daripada memendam dalam diam, kan? Apa yang bisa kami lakukan untukmu?" ucap Jaya lembut.
Gadis itu mulai menceritakan kisahnya, tentang perasaan putus asa yang dia rasakan, tekanan yang terus-menerus, dan tentang ketakutan yang terus menghantui. Berangsur-angsur, para peserta menunjukkan raut muka penuh empati. Suasana pun berubah menjadi hangat dan akrab. Diam-diam, Jaya pamit meninggalkan Bu Sari yang tak lupa mengucapkan terima kasih.
Sampai juga Jaya di ujung gang. Sebuah ruang minimalis dan rapi tampak dari pintunya yang terbuka. Hanya sebuah lukisan dedaunan karya pribadi yang menjadi sentuhan estetika, sebagai penunjuk kecintaan penghuninya akan seni.
Jaya mengetuk pintu dengan sopan, menunggu hingga sang profesor menengadah dan mengenali siapa yang datang. Profesor itu tampak sangat gembira. Jaya mengucapkan salam dan profesor pun membalas salam sambil mempersilakan duduk.
"Kebetulan sekali kamu datang. Sebenarnya, saya mau menyampaikan ini kemarin. Tapi, segala kesibukan bikin saya lupa mengabarimu," kata profesor penuh semangat. "Bu Nia, psikolog yang mendampingi Bu Puspa, kehamilannya semakin tua. Beliau merasa tidak stabil karena kontraksi yang semakin intens. Makanya, minta cuti dulu."
Jaya mengangguk-angguk prihatin. Profesor melanjutkan ucapannya sambil menatap Jaya penuh selidik. "Bagaimana? Apakah ada rekomendasi psikolog lain yang kamu percaya untuk ibumu?" tanya beliau dengan nada sedikit menantang.
Jaya menangkap sorot mata yang bermakna lain dari ucapan ayah angkatnya itu. Dia menarik napas mengumpulkan kekuatan, lalu menyampaikan jawaban yang sejalan dengan maksud kehadirannya.
“Prof, sebenarnya, saya ingin melakukan serangkaian terapi yang lebih intensif pada Ibu. Saya tahu, ini rawan konflik kepentingan. Karenanya, saya mohon Profesor bersedia memberikan supervisi dan konsultasi."
Bola mata Profesor Wijaya membulat takjub. Nada suara beliau terdengar lega saat berucap, “Sudah lama saya menunggu ini, Jaya. Bagaimanapun, kamu psikolog yang paling memenuhi kualifikasi dan memegang banyak lisensi di kota ini yang pernah saya kenal. Sayang, saya juga tidak bisa mendesakmu memikul tanggung jawab profesi ini. Jadi, apa yang memotivasimu melakukan ini sekarang?”
“Profesor benar, ini tanggung jawab saya juga,” sahut Jaya dengan pandangan menerawang. “Saya sadar sudah menghindar dari ini selama bertahun-tahun agar tidak terjebak pada subyektivitas. Sekarang, saya merasa sudah waktunya mencoba membantu Ibu.”
“Itu sangat mulia, Jaya. Kita semua tentu bisa sampai pada titik di mana merasa siap menghadapi masa lalu dan mengatasi masalah yang belum terselesaikan. Saya akan membantumu menjaga profesionalitas," komentar Profesor Wijaya sambil mengangguk-angguk. "Jadi, bagaimana? Saat ini, kita sama-sama tahu kondisi ibumu, kan?"
Jaya dengan lesu menjawab, "Ya, belum ada perubahan signifikan terkait kemauannya berbicara. Padahal, sudah berbagai terapi dijalani."
"Betul. Apa terapi yang kamu pertimbangkan untuk mengatasi situasi ini?" tanya profesor penasaran.
"Selain biblioterapi yang tampak bisa diterima Ibu dengan baik, saya ingin mencoba terapi seni ekspresif dan musikoterapi. Mungkin dengan ini, Ibu bisa menyampaikan apa yang dia rasakan atau pikirkan," cetus Jaya mantap.
Profesor Wijaya tersenyum bangga dan berujar, "Pilihan yang bagus, Jaya. Sebenarnya, kita pernah memberikan ini ke Bu Puspa, kan? Namun, di tanganmu, saya yakin hasilnya akan lebih baik. Bu Puspa pun tentu lebih nyaman, dan mungkin lebih kooperatif jika menjalaninya bersamamu."


 faridapane
faridapane