Aruna mengetuk-ngetuk ujung telunjuknya pada meja, sedang tangan lainnya menopang dagunya. Kpinya menjadi encer karena batu es di dalam gelas mulai mencair. Pandangannya serong dan jauh terlempar entah kemana, seturut dengan pikirannya yang entah sudah sampai mana. Sudah begitu sejak dia duduk di cafe ini.
“Nasi goreng dan roti bakar.” Seorang pramusaji menghampiri. Selain membawakan pesanan kami, dia juga memutus lamunan Aruna.
“Sudah semua, ya?” tanya pramusaji itu tidak acuh mencoret billet—menandai semua pesanan telah lengkap.
“Selamat makan,” ucap pramusaji itu datar suatu bentuk formalitas pekerjaan.
Aruna mengangguk cepat, secepat perginya pramusaji.
Saat Aruna sedang menyeka sendoknya sekali lagi—memastikan bersih, dia melirik, “ayok, makan.”
Aku segera menyesap kopi hitam selagi masih hangat suam lalu mulai memotong roti bakar. Aruna tenang saat makan, sekali-kali dia melihatku, senyum, lalu kembali menyendok nasi gorengnya.
Sebelum kami sampai di sini, Aruna datang ke studio. Dia masih berseragam perawat karena langsung datang setelah ujian prakteknya selesai. Dia menungguku yang tengah sibuk mengambil video untuk produk makanan bersama Ares. Proses shooting produk makanan lebih sulit karena butuh visual akhir yang benar-benar ‘menggiurkan’. Banyak properti yang digunakan dan sering kali kami membuat dummy –benda lain untuk menggantikan makanan asli demi kebutuhan fotografi. Aku sesekali ke depan untuk mengecek Aruna yang duduk di sofa. Dia dengan sabar menunggu sambil memainkan ponsel dan akan mengatakan, “santai aja, Gam. Lanjut,” sambil tersenyum tiap kali aku melihatnya. Aku juga akan membalas dengan anggukan atau acungan jempol.
Di jalan, Aruna bercerita bahwa ujian praktik justru terasa lebih mudah jika dibandingkan ujian teori sebelumnya. Kali ini dia terdengar lebih percaya diri. Lalu kami sampai pada café ini, tidak jauh dari studio.
“Kamu tumben pesen kopi? Katanya gak suka?” aku mulai membuka pembicaraan.
“Aku mau coba apa yang kamu suka.” Aruna menjawab cepat sambil melirik sebentar, tersenyum dan kembali fokus pada telur dadar yang sedang dia potong.
“Gimana? Enak, gak?”
Aruna mengangguk ragu sambil mengunyah pelan. Lalu dia tampak buru-buru menelan untuk segera bicara.
“Gam? Kamu kalau begini terus, bakalan masalah sama lambung.”
Aku terkekeh, “Iya.”
Dan setelahnya aku yakin akan mendengar rentetan omelan tentang kesehatan.
“Kamu minum kopi bisa sampai tiga kali sehari, itu pun kopi instan, minum air putih jarang, makan juga, tuh!” Aruna menunjuk rotiku dengan dagunya, “gak bener, gak sehat. Roti itu fermentasi, asam. Udah gitu hobi banget begadang. Kamu bisa-bisa dirawat,”
“Yah, kalau sampai kejadian, di rumah sakit, kan dirawat sama kamu. Aman,” ujarku ringan berusaha merubah raut masamnya itu.
“Iya kalau aku kerja di rumah sakit itu. Kalau enggak?” Aruna menantang.
“Kamu kan bakalan ada di rumah.”
“Rumah siapa?” dahi Aruna mengerut melihatku.
“Rumah kita, dong,” ujarku dengan percaya diri. Terdengar seperti gombalan walau sebenarnya itu harapan.
Namun reaksi Aruna sungguh tidak terduga, dahinya yang mengerut kini dia lepaskan bersamaan dengan hembusan nafas, “Yah, kita gak bisa pastiin juga,” ucapnya pelan. Lalu kembali fokus pada piringnya dengan nasi goreng tersisa setengah.
Walau rasanya tidak puas dengan reaksi yang diperlihatkannya, namun aku berusaha menimbang. Memang benar masa depan tidak bisa dipastikan. Aku mengangguk menyetujui pikiran Aruna, memahami bahwa Aruna tidak bermaksud menolak, dia hanya berusaha realistis.
“Jadi kamu melamun tadi karena mikirin lambung aku?”
Aku mencoba mengalihkan pembicaraan yang mulai terasa tidak menyenangkan.
“Enggak.” Aruna tampak ingin melanjutkan kata-katanya, tetapi langsung terdiam, “nanti aja sampai rumah aku cerita. Aku juga belum mikirin bener-bener juga,” sambungnya. Dia menatapku sesaat sambil tersenyum enggan.
“Rumah siapa?” dahiku sengaja mengerut, mengulang persis raut wajahnya tadi saat melontarkan pertanyaan yang sama.
Aruna tertawa, “Kamu bisa aja!”
Suasana kembali menyenangkan. Sambil makan, aku menceritakan hal-hal lain, kebanyakan tentang studio, cara aku dan Ares mendapatkan klien, mencoba memberanikan diri ikut tender yang tidak kami menangkan dengan alasan “masih bau kencur”, mengejar usaha-usaha baru yang butuh vendor penyedia materi iklan. Semuanya. Aku ceritakan pada Aruna seluruhnya. Menyenangkan berbagi cerita bersamanya, dia mendengarkan dengan perhatian sepenuhnya.
“Jadi, yah, gitu walau belum banyak, tapi tiap hari kerja. Karena satu produk itu pengambilannya bisa beberapa kali, belum masuk proses edit,” ujarku menjelaskan.
“Bagus dong! Kalian berdua tuh keren banget tau kalau mode kerja,”jawab Aruna.
“Kok ‘kalian berdua’, sih?” aku cemberut. Bukan protes yang sebenarnya, hanya berusaha bertindak lebih lucu saja.
“Iya, deh! Kamu. Kamu paling keren!!!” Aruna berseru sambil mengacungkan kedua jempolnya.
Kami kembali dengan membawakan Ares makan siang. Aruna yang memang menunggu untuk pulang bersama terkadang dia melihat-lihat kami bekerja, sedikit-sedikit dia membantu, lalu dia berkeliling dan berada sangat lama di lantai dua. Saat aku datangi, ternyata dia tengah sibuk membereskan barang-barang dan membersihkan ruangan yang sudah mulai berdebu karena jarang digunakan.
“Istirahat aja, nanti kamu capek,” aku membujuknya sambil ikut-ikutan duduk di lantai, persis di sampingnya yang tengah menyeka reflektor dengan kain lap yang entah dari mana dia dapatkan.
“Gak apa-apa. Aku juga bingung mau ngapain.”
Aku melihat arloji, “setengah jam lagi aku selesai, kita pulang.”
Aruna mengangguk cepat kekanak-kanakan.
“Aku ke bawah dulu, bantuin Ares beresin properti, oke?”
“Iya sana …,” Aruna menjawab tanpa melihat. Kini sebuah tripod lipat berada di tangannya untuk dibersihkan. Aku berdiri sambil mengacak rambut halusnya.
“Hati-hati hantu!” candaku saat menuruni tangga, lalu tertawa.
“Gak takut! Yeee!” Aruna berseru dan menoleh ke belakang, melihatku yang tertawa usil.
Tidak lama dengan sedikit mengendap aku kembali naik, mengintip dia yang toleh kiri toleh kanan, mengawasi sekitar. Dia takut. Aku terkekeh.
-oOo-
Aku baru saja kembali dari membeli kabel flash sync saat Ares dan seorang wanita yang merupakan klien tampak sedang berbantah-bantahan. Saat aku masuk, mereka berdua diam dan secara bersamaan melihatku. Ares memberikan isyarat padaku agar mengikutinya ke ruangan kerja. Sebelum berbicara, Ares tampak menggertakkan gigi, dia selalu begitu jika sedang dongkol.
“Kan? Dateng dia, bener dugaan gua!” Ares berseru pelan dengan mata melotot. Dia tampak sangat kesal. Aku mencoba memahami situasi.
Saat aku pergi menjemput Aruna setelah ujian dan membawanya makan es krim, klien datang. Seorang wanita berusia kira-kira tiga puluh tahun berkonsultasi mengenai pembuatan materi foto dan video untuk sosial media khusus toko kue yang baru saja dia buka. Wanita sebagai pemilik toko kue itu membutuhan materi iklan dan promosi lengkap dengan desain logo. Dengan anggaran awal yang ditawarkan Ares, wanita itu tampak keberatan, lalu setelah cukup lama, akhirnya mereka menemukan jalan tengah, yaitu Ares menerima anggaran yang sesuai dengan kemampuan wanita itu dengan keterbatasan materi yang akan diterima olehnya. Kesepakatannya adalah: revisi logo hanya sampai tiga kali, sepuluh foto varian kue dan dua video dengan durasi tiga puluh detik. Semua pengambilan gambar dilakukan dalam satu hari di toko kue tersebut dan wanita itu harus mempersiapkan kue-kue dengan baik. Lalu kesepakatan ditandatangani langsung saat itu, yang aku ketahui nama klien itu setelah membaca MoU adalah Lin dan toko kue ‘TinyTreats Delight’. Kami datang ke toko itu seminggu setelah MoU itu dibuat –sesuai isi pada salah satu poin perjanjian. Saat datang, itu pun sudah sore, hanya tersedia enam varian kue dari yang seharusnya sepuluh. Lalu Bu Lin beralasan dalam keadaan kurang baik untuk membuat sisanya. Setelah berbicara, akhirnya saat itu dia menyetujui bahwa enam kue saja yang nanti dikembangkan menjadi sepuluh foto dan hanya enam kue juga yang akan masuk dalam dua video. Untuk masalah logo, kami selalu mengirimkan melalui email setiap satu logo sudah selesai, namun email itu tidak mendapatkan respons, Ares bahkan sudah berusaha menelepon namun tidak mendapatkan jawaban, akhirnya kami memutuskan untuk langsung membuat tiga pilihan logo yang akan diperlihatkan saat kami datang. Bu Lin memilih desain logo kedua, dengan tone warna bernuansa merah muda. Aku dengan jelas-jelas melihat dia menunjuk tanpa ragu logo pilihannya itu, mengalahkan dua logo lainnya.
Hari ini Bu Lin datang saat tenggat waktu hanya tinggal satu hari dengan membawa satu kotak kue berisi empat varian yang waktu itu tidak sempat dia persiapkan. Bu Lin menghendaki empat kue itu harus masuk dalam materi, sesuai isi MoU. Lalu tanpa rasa bersalah dia mengatakan ingin mengganti logo pilihannya dengan logo yang ke tiga dengan nuansa kuning dan coklat. Ares menjelaskan bahwa video dan foto sudah selesai dan hanya tinggal proses penyerahan. Ares juga memperlihatkan hasil kerja kami untuk ‘TinyTreats Delight’, sepuluh foto dan dua video dengan watermark logo merah muda. Sayangnya Bu Lin tampak tidak puas karena tidak semua varian kue masuk dan menurutnya lebih cocok jika logo yang bernuansa kuning dan coklat. Lalu Ares yang mulai kesal mengungkit kejadian di toko kue, mengatakan bahwa Bu Lin dengan kesadaran penuh memilih sendiri logo merah muda dan dengan keputusan bersama bahwa hanya enam varian yang tersedia saat itu yang dikembangkan menjadi materi. Mendengar itu Bu Lin mulai marah dan mengungkit-ungkit poin yang tertulis dalam Mou, dia berfokus pada jumlah varian yang sepuluh.
“Lu tunggu di sini, biar gua coba ngomong,” pintaku pada Ares.
“Kalau bukan perempuan, udah gua ajak gelut tuh orang!” ujar Ares geram.
Aku menemui Bu Lin yang duduk tegap pada sofa sambil menyilangkan kedua tangan dan kakinya. Wajah etnis Tionghoa-nya merengut masam membuat matanya yang sudah sipit kini tampak hanya segaris. Model kacamata cat-eyes yang dia gunakan semakin menambah kesan keangkuhan. Sepatu merah muda hak runcing tingginya membuatku berfikir bisa saja hak itu melukai kepalaku jika kali ini dia justru menjadi lebih emosi. Aku mengambil jus kemasan pada display cool case yang terletak berhadapan dengan sofa yang dia duduki.
“Minum dulu, Bu,” ujarku sambil memaksakan senyum ramah.
“Jadi gimana? Harus sesuai MoU, dong? Kalian ini gak profesional!” Bu Lin berseru sambil menghempaskan gulungan Mou pada meja. Jus kemasan itu tidak dia sentuh bahkan tidak dia lihat sama sekali. Cara bicara nya yang khas orang cina ini sejujurnya semakin membuatku jengkel.
Aku berusaha mempertahankan sikap tenang dan terkendali. Menghindari memberikan respon emosional yang dapat memperburuk situasi. Dengan menarik nafas perlahan sambil berpikir bagaimana membujuknya, Bu Lin menatapku sinis.
“Udah fit sekarang, ya Bu? Udah bisa lanjut bikin empat varian ini. Boleh saya lihat?” aku mencoba menarik simpatinya dengan sedikit berempati. Empat kue itu masih tersegel di dalam kotak.
“Boleh,” jawabnya singkat sambil membuka kotak kue.
Perpaduan wangi vanilla, mentega dan cokelat memenuhi ruangan seketika. Aroma khas toko kue. Dilihat-lihat kue di dalam kotak ini memiliki tampilan menarik, “Wah!”
Bu Lin dengan cepat menutup kotak kue itu, “Jadi gimana? Pembicaraan kita belum tuntas,” kini nada suara Bu Lin terdengar lebih rendah namun masih tegas. Sesekali dia memperbaiki posisi kacamatanya yang turun setiap kali dia berbicara. Jujur saja, kacamata itu terlalu besar untuk wajahnya yang hanya selebar telapak tanganku.
“Ibu mau lihat sekali lagi hasil foto dan video yang udah jadi?” bujukku.
“Ck! Saya tuh bukan kurang puas sama hasil nya. Saya kecewa karena kue ini tidak masuk materi,” Bu Lin menepuk-nepuk pelan kotak kue di meja.
“Jadi untuk hasil materi sudah memuaskan ya, Bu?”
Bu Lin hanya mengangguk pelan dan kikuk. Dia mulai meraih jus kemasan dan menancapkan sedotan dengan pelan lalu menyeruputnya.
“Saya juga mau mengganti logo ke yang ini,” Bu Lin menunjuk logo kuning-coklat pada layar handphone nya.
Jika mengikuti teori warna, kuning-coklat lebih cocok dan lebih menggiurkan untuk pilihan warna pada logo makanan terlebih jenis kudapan yang kebanyakan menggunakan bahan utama coklat dan telur atau mentega. Namun situasinya kali ini berbeda, Bu Lin sendirilah yang menentukan pilihan pada logo merah muda. Lalu aku mengingat sesuatu, “Bu, sebelumnya maaf, saya ingat alas kursi di toko ibu berwarna sama dengan logo yang sudah jadi ini. Ada satu sisi dinding pada toko ibu berwarna merah muda. Jadi kalau menurut saya, logo ini akan lebih cocok dengan nuansa di toko,” paparku hati-hati.
Dia diam sebentar, meletakkan jus kembali pada meja dan mengangguk-angguk, “benar juga,” ujarnya. Bu Lin melihat kakinya dan tersenyum, “saya suka pink, sepatu saya hari ini juga pink, makanya kemarin spontan tanpa melihat dua logo lainnya langsung menunjuk logo dengan warna kesukaan saya. Tapi kemarin saya minta pendapat teman-teman, kata mereka lebih bagus kuning dan coklat.”
“Pink memang bagus, Bu. Cocok juga sama interior di toko,” ujarku kemudian.
Tapi gak cocok sama sekali dengan temperamen ibu.
Bu Lin manggut-manggut, jus miliknya sudah habis lalu dengan inisiatif sendiri aku mengambil minuman lain. Jika tadi aku memilihkannya jus mangga, kini aku memberinya jus guava –merah muda, pink!
“Jadi untuk yang empat ini gimana? Kan harusnya sepuluh varian?” tanyanya pelan. Sudah tidak ada emosi lagi dalam nada bicaranya. Akhirnya dia bisa berbicara dengan normal. Jus guava itu dia minum.
Aku berusaha menjelaskan sebaik mungkin, bahwa kami meminta maaf atas kesalahpahaman, bahwa akan memakan waktu lagi untuk mengambil gambar dan melakukan proses pengeditan. Mengatakan bahwa Bu Lin tidak rugi apapun jika menerima materi yang sudah jadi, totalnya tetap sama dengan yang ada di MoU, terlebih pilihan foto lebih variatif karena enam kue menjadi sepuluh foto. Tentu dua video yang berdurasi tiga puluh detik itu menampilkan lebih lama tiap produk sebab hanya dibagi menjadi tiga kue dalam satu video. Tidak lupa aku menawarkan bonus berupa buku menu digital jika empat kue ini dan kue-kue lainnya tetap menggunakan jasa kami sebagai penyedia materi iklan selanjutnya. Mendengar gagasan terakhir Bu Lin tampak senang.
“Kasih tau temen kamu tadi, yang sopan sama klien,” ujar Bu Lin sambil menerima video itu yang akhirnya dia minta disimpan di dalam flashdisk.
Aku hanya tersenyum dan mengucapkan maaf sekali lagi.
“Kue yang ini biar saya beli aja, Bu,” tawarku sebelum Bu Lin berangkat.
“Ambil aja buat kamu, ngapain beli, ini juga barang sampel,” ujarnya santai.
“Terima kasih, Bu.”
Dengan senyuman yang dipaksakan lebar, aku mengantarnya keluar. Suara ketukan hak tinggi dari sepatu pink-nya membuatku tidak tahan ingin segera menutup pintu.
Saat Bu Lin sudah membawa mobilnya pergi, Ares keluar.
“Jinak tuh ibu-ibu ama lu,” Ares kini tertawa singkat.
“Yah, lu Res, percuma cewek gonta-ganti kalau urusan begini masih gua yang turun tangan. Noh kue, makan,” aku menunjuk kue yang ditinggalkan Bu Lin.
“Dih, ogah gua, jadi gak selera,” Ares menolak dan melirik kue itu sambil bergidik ngeri,“jago amat lu. Kagak jadi kehilangan klien, malah dia lanjut kayaknya. Belajar dari mana lu ngolah perempuan?”
“Udah terlatih sejak dini. Dua di rumah.”
“Oh, iya juga, sekarang nambah satu di kost,” alis Ares terangkat dan menampilkan senyum usil.
Aku tertawa menggelengkan kepala.
Akhirnya, kue itu kami antarkan ke optik sebelah sebab Ares dan aku tidak terlalu suka makanan manis dan dengan alasan konyol aku tidak membawakan kue itu untuk Aruna: takut sifat Bu Lin pindah.
-oOo-
Suatu malam saat pulang dari studio, aku berjanji menjemput Aruna di rumah seorang teman. Dia dan teman-temannya bersama-sama mempersiapkan berkas untuk pengurusan surat registrasi jika ujian kompetensinya lulus. Aku tahu pasti Aruna akan lulus walau dia sendiri ragu. Sebelum sampai kost, kami berhenti pada kedai makan yang dulu aku ceritakan padanya sebagai salah satu lokasi shooting film terkenal –sekawan yang mendaki Gunung Semeru, tempat Aruna makan bubur ayam dulu. Kali ini Aruna yang memesan untukku, dia memilih martabak dan jus timun untuknya, sedangkan untukku dia memesan bubur ayam dan air mineral.
Suasana malam ini sedikit lebih ramai, pengamen lalu lalang dengan suara gitar yang dipetik sembarangan dipadukan dengan suara nyanyian penuh lengkingan. Luar biasa hasilnya, ribut memekak telinga.
“Gam? Aku di suruh balik ke panti sama Bu Hafsari dan Bu Sarah,” Aruna menatapku seolah mencari-cari bagaimana reaksiku mengenai pernyataannya barusan.
“Ini yang bikin lamunan kamu panjang semingguan? Yang katanya mau diomongin pas sampai kost tapi gak jadi-jadi?”
“Iya. Bu Sarah minta aku jadi tenaga sukarela di puskesmas deket panti,” ujar Aruna lagi.
“Ya bagus, dong. Jadi ntar kamu ada pengalaman kerja. Tapi bisa gitu sebelum lulus?” tanyaku penasaran. Aku senang mendengar gagasan ini. Entah apa yang dikhawatirkan Aruna mengenai hal sebaik ini.
Mendengar itu, dia cemberut. Melihat raut nya begitu, kira-kira aku tahu apa yang dia pikirkan tentang ini. Dia mungkin bertanya-tanya kesediaanku, perasaanku atau bahkan dia berharap aku melarangnya. Aku tidak tahan untuk tidak tertawa.
“Kok kamu malah ketawa, sih? Gak sedih gitu? Lama loh aku di Tangerang!” Aruna protes dengan pipinya yang menggembung.
“Hei, kenapa aku mesti sedih? Bagus dong, ntar kamu kalau ditanya HRD ‘Ada pengalaman kerja sebelumnya?’ Kamu bisa jawab, kan?” masih menahan tawa aku menyolek pipinya agar kembali ke ukuran semula.
“Aku uring-uringan mikirin ini, gak taunya kamu santai begini.” Aruna lagi-lagi menghembuskan napas. Namun kali ini dia mencoba menyuap martabaknya.
“Lagian juga Tangerang dekat, aku tahu alamat panti kamu. Kalau kangen, aku bisa datang.”
“Gak bisa seenaknya juga kamu bisa datang,” Aruna kini tampak kesal.
“Ya oke, ntar itu biar aku yang pikirin caranya. Tapi kalau kamu tanya aku sedih apa enggak, ya jawabannya enggak. Aku malah dukung. Tapi beda cerita kalau kamu tanya aku bakalan kangen atau enggak,” aku menyuap bubur ayam yang kali ini terasa lebih gurih dari biasanya. Suapan pertama.
“Jadi kamu bakalan kangen atau enggak?” selidik Aruna, nada bicaranya terdengar ketus.
“Yang tadi belum apa-apa bilang bakal nyusulin, siapa?” aku menaikkan dagu sambil tersenyum, membujuknya.
“Kamu,” imbuhnya sambil malu-malu.
“Nah…”
Aruna tertawa, sebenarnya tawanya cukup kuat, namun karena suara pengamen lebih mendominasi dan masih tampak asyik bernyanyi, akhirnya Aruna terlihat hanya sekedar membuka mulut saja.
“Jadi kapan kamu ke Tangerang?” aku menikmati suapan kedua.
“Seminggu lagi. Kalau ikutin maunya Bu Sarah,” Aruna tampak tidak selera makan, dia hanya memotong-motong martabak tanpa menyuap, tidak seperti biasa yang selalu semangat menghabiskan makanan.
Aku mengangguk, suapan ketiga masuk. Aruna diam, hanya suara pengamen, riuh pengunjung dan suara lalu lintas yang masuk ke telinga.
“Tiga minggu lagi, nemenin kamu ujian dulu, kalau maunya aku,” Aruna tiba-tiba bersuara.
Mengagetkan, sehingga suapan ke empat bubur ayam ini menyangkut di kerongkongan. Aku tersedak lalu segera meraih botol air mineral. Minum. Aruna menepuk-nepuk punggungku saat aku mulai batuk-batuk.
“Ini jauh bikin aku kaget daripada denger kamu mau kerja di puskesmas,” suaraku terputus-putus akibat masih mengatur nafas.
Bayangkan, Aruna yang sangat cemas dan panik setiap kehadiran Bu Sarah, dengan berani mempertimbangkan keputusan untuk menunda keinginan Bu Sarah demi aku. Bahkan jika Aruna mengatakan tidak bisa menungguku ujian, aku tidak mempermasalahkannya. Itu hanya ujian, semua mahasiswa melaluinya, tidak ada yang istimewa. Namun karena Aruna mempertimbangkan hal itu, membuatku merasa bahwa momen itu merupakan momen spesial dan aku semakin harus menunjukkan hasil yang maksimal.
“Kamu gak apa-apa?” Aruna menatapku lekat. Telapak tangan kecilnya itu masih menepuk-nepuk punggungku. Aku mengangguk, meyakinkan padanya bahwa aku sudah tidak apa-apa.
“Cieh, yang uring-uringan takut ninggalin pacarnya?” aku menyikutnya pelan. Kini dia mulai menyantap martabaknya dengan lahap, mungkin karena hatinya sudah lapang telah menyampaikan hal yang membuatnya berpikir panjang.
“Ya, iya lah. Aku denger dari Gina, kapannya aku lupa. Dia bilang kamu ke bar malem-malem. Dia pulang, kamu belum pulang. Udah gitu gak ngabarin aku,” Aruna menggerutu.
Aku mengusap-usap dahi sambil mengingat situasi itu. Ah! Saat Ares bercerita soal Trisna dan berakhir mabuk. Gina di sana bersama pacarnya.
“Ooohh, itu. Aku bareng Ares. Gak mabuk, kok. Kamu waktu itu di Tangerang. Lagian entah kenapa sejak pacaran sama kamu, Tangerang jadi susah sinyal, ya? Kamu gak pernah chat, nelpon, jarang banget. Aku juga kadang chat gak nyampe apa gimana? Jarang banget di bales,” aku menggodanya. Aruna menahan senyum dengan susah payah. Dia terus begitu tanpa menjawab.
“Iya, iya. Aku paham kok,” aku kembali menyuap makanan. “di bar itu aku cuma duduk aja sambil cerita, itu pas lagi nyari-nyari tempat buat studio. Capek gak dapet-dapet. Istirahat sambil ngemil.”
“Yakin gak nungguin cewek?” Aruna mengangkat alisnya. Tatapannya sudah cukup menginterogasi.
“Lah? Kamu bukannya khawatirin aku mabuk? Lebih khawatirin ada cewek lain di sana?”
Aruna mengangguk cepat dan bersungguh-sungguh menunggu jawaban. Aku tertawa melihat dia yang begitu apa adanya, “Gak ada, kalau ada pun pasti mendekatnya ke Ares,” aku berpangku dagu menatap Aruna, mengusap kepalanya. Ternyata bisa juga dia mengkhawatirkan hal seperti itu. Mau bagaimanapun perempuan itu sudah kodratnya cemburu. Bahkan Siti Hawa, sebagai wanita satu-satunya di dunia saat itu, tetap cemburu karena Adam pulang terlambat. Entah bagaimana cara Adam membujuk Siti Hawa, aku jadi penasaran.
-oOo-
Matahari sore masih hangat. Ruangan depan terasa gerah karena cahaya matahari tampak masih terang menembus pintu kaca. Ares hari ini lebih banyak diam dari pada biasa. Di studio, kami terkadang membicarakan hal tidak penting saat shooting lalu tertawa bersama, termasuk sesekali membicarakan Bu Lin, kini dia diam dengan muka masam. Rokok nya lebih cepat habis karena sering kali dia keluar di cuaca panas untuk menghisapnya sambil mondar-mandir dan tegak pinggang. Aku yang melihatnya dari dalam sudah kesal duluan. Terkadang dia berbicara pada diri sendiri, suatu bentuk afirmasi. Berulang kali dia terdengar bergumam , “ini harus jadi, harus berhasil.”
Sore pukul lima, kami baru bisa istirahat. Sebelumnya saat siang Kak Ami datang dengan membawa berita baik, perusahaan garmen menyetujui bekerjasama dengan kami, sebab menurut cerita Kak Amy, orang yang menggantikan pekerjaanku tidak memenuhi harapan target tim kreatif dan pemasaran. Selain itu, Kak Amy memang dikenal tegas dan lugas. Hanya orang-orang yang kuat mental yang sanggup bertahan dengan kritikan-kritikan yang dilontarkannya.
Aku minum cola dengan santai. Berbeda dengan Ares, tanpa menyentuh minuman kaleng di depannya, dia mengusap-usap wajah dengan kasar, menghempaskan punggung pada sofa.
“Lu hari ini kenapa, dah?” aku mulai bertanya karena dia tidak juga tampak mulai bercerita. Kami berhadapan dengan pemisah meja persegi kecil setinggi lutut, di meja itu juga minuman kaleng Ares mulai berembun membasahi permukaan meja kaca ini.
“Gam, bisnis ini harus berhasil, harus bikin kita kaya,” ujarnya sambil memajukan badannya, duduk tegak dan tangannya bertumpu pada kedua paha.
“Dimana-mana juga orang buka usaha pengennya gitu. Ada apa sebenarnya?”
“Lu liat gak muka orang tua gua, apalagi bokap pas kita grand opening? Suram! Keliatan banget terpaksa buat datang. Terus parahnya lagi, kemarin gua baru pulang, denger bokap telponan sama oom gua yang anaknya kerja di Singapur itu, masa gua dibilang tukang poto? TUKANG POTO!!! Sadis gak tuh?” Wajah Ares merah, alis tebalnya nyaris menyatu ke tengah. Dia bahkan memukul meja saat mengatakan ‘tukang poto’ dan menghentakkan salah satu kakinya ke lantai dengan kuat. Lalu dia memijat-mijat dahi tampak lelah sekali.
Sudah lama aku tahu sejak Ares bercerita bahwa untuk masuk jurusan DKV butuh perdebatan panjang dan menyakitkan dengan kedua orang tuanya. Harapan kedua orang tuanya, Ares masuk jurusan teknik di salah satu universitas negeri yang terkenal di Yogyakarta bersama sepupunya yang kini telah bekerja di Singapura. Aku hanya diam, enggan berkomentar dan justru menatapnya yang kini tampak benar-benar marah.
“Dia kira megang kamera itu main-main apa? AH!” Ares melepaskan ikat rambutnya dengan sekali hentakan, mengacak-acak rambut panjangnya lalu berbaring di sofa, dengan salah satu lengan menutup kedua matanya.
“Gua gak pulang dulu, deh. Gua tidur di studio aja,” ucapnya lirih.
“Yaa terserah,” aku tidak mau dan tidak bisa ikut campur jika ini urusan dengan orang tuanya. Lagipula Ares tidak butuh saran, dia hanya butuh pelampiasan.
“Terus proyek tugas akhir gua, gak maju-maju. Lu udah mau ujian, gua editing aja belum.”
“Lu boleh libur, kok kalau memang mau fokus ke tugas akhir,” tawarku.
“Ntar, deh gua pikirin,” jawabnya lemah
Hening cukup lama, aku menghabiskan coke sambil membalas pesan dari Aruna, dia mengatakan akan menghabiskan buku bacaannya di kamarku sebab kamarnya terlalu berisik akibat dentingan bunyi khas pertukangan pada gedung sebelah. Aruna juga mengirimkan foto lembaran buku dan suasana kamarku sebagai latar belakangnya. Aku tersenyum melihat handphone.
“Terus Trisna juga,” Ares masih menyambung ceritanya. Mendengar itu, aku merasa tidak pantas tersenyum dalam situasi ini. Aku segera meletakkan handphone tepat di samping, tertelungkup pada sofa.
“Kenapa Trisna?”
“Ya kalau di bandingin, si tukang poto ini dan dokter, lu kalau jadi cewek pilih yang mana?”
“Kagak tau,” jawabku santai, “gua mana bisa bayangin jadi cewek.”
“Ah! Kocak!” Ares mengangkat lengan yang menutupi matanya, melirik tajam sebentar, lalu kembali tangan itu menutup matanya lagi.
“Udah, ah. Gua mau lanjut kerjaan, lu istirahat aja dulu.”
Ares benar-benar memutuskan tidak pulang. Sesaat jam operasional studio berakhir, dia mengatakan akan melanjutkan sisa pekerjaan yang tidak bisa aku selesaikan sendirian karena menjelang malam Ares hanya berbaring di sofa.
“Lu aman?” aku melihat Ares yang tampak masih kusut. Sambil mengemas-ngemas barang ke dalam ransel aku mengawasinya yang tengah jalan dengan menyeret kaki menuju toilet. Ares menjawab dengan anggukan.
Memang, dukungan orang terdekat, terlebih dari orang tua mempunyai pengaruh besar dalam membangun kepercayaan diri dan menumbuhkan semangat. Orang tua Ares –yang sesekali aku temui, sebenarnya orang baik, sopan dan terkesan profesional sebagai orang tua, walau tidak setuju Ares menempuh pendidikan dengan jurusan yang bertentangan dengan pilihan orang tuanya, tetap saja secara konsisten mereka memenuhi kebutuhan finansial Ares. Bahkan jika Ares tidak mengambil freelance, dia masih bisa kuliah dengan tenang. Namun yang Ares butuhkan tidak hanya dukungan finansial, dukungan emosional justru tidak kalah penting. Nenek Ares, ibu dari ayahnya, satu-satunya keluarga yang mendukung keputusan Ares. Seingatku Ares pernah mengatakan bahwa orang tuanya menganggap uang yang mereka gunakan untuk Ares selama kuliah DKV adalah suatu bentuk investasi yang harus kembali dengan keuntungan berkali-kali. Saat itu aku terkejut mendengarnya. Bagi Ares ini sudah cukup melelahkan, apalagi sekarang dia harus berhadapan dengan tatapan menekan kedua orang tuanya setiap kali pulang.
“Jangan lupa kunci rolling door,” ujarku saat Ares sudah keluar dari toilet. Dia tampak lebih segar sehabis membasuh wajah dan kembali mengikat rambutnya rapi. Ares mengacungkan jempolnya tinggi lalu mulai mempersiapkan alat untuk melanjutkan pekerjaan. Aku meraih ransel dan bersiap pulang.
Berbeda saat siang dan sore tadi, angin malam kali ini terasa lebih dingin, sepertinya tengah malam nanti akan hujan. Arloji menunjukkan pukul sepuluh malam tepat saat aku menaiki anak tangga pertama. Aku berpapasan dengan seorang tetangga, Dion namanya, seorang anak SMA yang tinggal pada lantai satu. “Bang, apa kabar?” tanyanya. Lalu kami bercerita dan berbasa-basi di tangga sebentar. Dion menanyakan tentang jurusan yang aku ambil, dia mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan pada kampusku. Lantas aku menceritakan hal-hal penting yang perlu dia tahu. Dion menanggapi dengan baik, namun samar-samar pandanganku terasa buram, badan terasa lebih dingin dan ada sesuatu dari perut yang menyesak ke atas menyentuh kerongkongan.
“Bang! Lu lagi sakit? Pucet amat!” Dion memperhatikanku dengan seksama. Suara Dion menyadarkanku yang mulai pusing.. Aku pucat?
“Kapan-kapan lanjut, ya, Yon!” ucapku segera, menyadari bahwa tubuh terasa tidak baik-baik saja.
Badanku terasa gemetar.
Desakan dari perut membuatku mual dan ingin muntah.
Walau pandangan samar aku masih bisa menguatkan kaki melangkah hingga kamar.
Kunci kamar tidak bisa diputar, ada sesuatu yang mengganjal pada sebaliknya. Aku menyadari, Aruna masih di dalam dan kuncinya tergantung. Aku benar-benar sudah tidak tahan ingin segera muntah dan tanpa sadar memukul-mukul pintu dengan kasar. Aku tidak sanggup memanggil Aruna. Rasanya isi perutku akan keluar jika aku mulai membuka mulut.
Aruna membuka pintu dan wajahnya kalut seketika melihatku. Aku langsung masuk tanpa membuka sepatu dan segera menuju kamar mandi.
Benar, aku muntah tapi tidak ada yang aku keluarkan, bahkan air pun tidak. Berkali-kali tekanan dari perutku memaksa aku mengeluarkan sesuatu, tapi selalu tidak berhasil. Kedua tangan terasa bergetar memegang wastafel. Punggung nyeri. Tubuh yang sudah dingin ini bertambah dingin dan kini basah sebab keringat. Aku yang pusing dan lemas memilih duduk pada lantai kamar mandi.
Aruna ikut duduk berjongkok mengusap pelan pundakku.
“Gam, di sini dingin. Kita pindah dulu ke kamar, yuk?” Aruna membujuk dengan berusaha meraih lenganku.
“Sebentar lagi,” jawabku lemah dan tengah memgumpulkan serpihan-serpihan sisa tenaga. Aku melipat lutut ke dada, kepalaku berpangku pada lengan yang kudekap.
“Sekarang aja, aku udah siapin air hangat,” Aruna membujuk pelan.
Aku berusaha berdiri dengan tenaga yang belum terkumpul semua, Aruna membantu. Lalu berjalan diiringi Aruna melepas ransel yang baru aku sadari masih tergantung pada punggung.
Aku duduk lemas pada sisi kasur sambil membuka sepatu dengan mengandalkan kelihaian kaki.
“Naikkan kaki kamu ke kasur. Lantainya dingin karena aku nyalain AC tadi,” ujar Aruna sambil menyerahkan segelas air hangat.
Aku menurut saja, menaikkan kaki dan meminum air hangat. Aruna tampak sibuk dengan remote AC, mengatur suhu ruangan. Kemudian dia keluar sambil membawa sepatuku dan dia letakkan di rak biasa. Lalu kembali lagi dengan sebungkus tisu besar dan kotak P3K miliknya. Aku diam memperhatikan Aruna yang lalu lalang sambil masih kelelahan akibat muntah yang dipaksakan.
“Buka baju, Gam,” pintanya tiba-tiba sambil menyeka keringat pada wajah, leher dan tanganku. Aku terperangah, lalu melihatnya dengan tatapan yang membingungkan.
“Hah?”
“Baju kamu basah keringatan. Keringat dingin. Buka sekarang daripada badan kamu makin dingin,” papar Aruna kini yang tampak sibuk mencari-cari sesuatu dari kotak P3K.
“Kalau gitu kamu sana dulu, balik badan,” suaraku terdengar parau.
“Duhh, kamu lama banget, keburu masuk angin ntar!” Aruna yang geram kini bersiap membukakan bajuku.
“I-Iya-iya. Aku aja…,” cegatku cepat.
Sejujurnya ini terasa canggung. Aku bahkan tidak pernah bertelanjang dada di hadapan Marwa. Kini harus membuka baju dan disaksikan oleh Aruna. Namun Aruna tidak tampak kikuk, bahkan sangat santai seolah sudah menjadi pemandangan yang biasa. Ah, tiba-tiba aku mengingat bahwa mungkin saja dari praktek lapangannya dia telah banyak menyaksikan pria-pria bertelanjang dada dengan segala kemungkinan. Mengetahui dia yang sudah terbiasa, memang mengurangi canggung namun perasaan lain muncul –cemburu.
“Aku buka lemari, ya?” Aruna mengambil baju ganti. Dia mendekat dan duduk lagi pada kasur, membantuku memasang baju. Lalu setelah itu dia memintaku membelakanginya, aku menurut saja. Tahu-tahu tangannya masuk melalui sela baju untuk mengusap punggungku dengan minyak angin. Telapak tangan kecil itu bisa menjadi kuat saat-saat seperti ini. Bahkan sepertinya Aruna sengaja memberikan sedikit tekanan pada punggungku, membuatku ingin bersendawa. Dan, iya, aku sendawa.
“Kamu makan terakhir jam berapa tadi?” tanya Aruna sambil menambahkan minyak angin.
Aku mengingat-ingat. Lalu aku menyadari bahwa hari ini aku belum makan sama sekali. Aku memilih diam, cukup ragu untuk segera menjawab pertanyaan Aruna. Dia pasti akan kesal.
“Gam?” Aruna mendesak.
Aku mengusap wajah, bersiap menerima omelan, “belum.”
“Belum makan malam?”
Aku diam. Aruna masih mengusap punggung. Dia menepuk-nepuk untuk mengingatkanku agar segera menjawab. Aku menelan ludah, bersiap terkena ujaran masif mengenai kesehatan –lagi.
“Belum makan sama sekali,” ucapku pelan sambil menahan cemas.
Tiba-tiba Aruna mendorong punggungku kuat, membuat tubuhku terhuyung ke depan hingga dahi nyaris menabrak tembok.
Aku bahkan takut untuk protes karena tindakannya yang semena-mena, bagaimanapun aku ini pasien.
“Dah, hadap ke aku, sini,” ujar Aruna ketus.
“Bakal didorong lagi, nggak?” tanyaku dengan takut-takut menoleh ke belakang, dan benar, tatapannya menekan dan mulutnya itu meruncing seolah siap menasehatiku habis-habisan.
“Lihat nanti,” ujar Aruna kesal.
Aku perlahan kembali pada pada posisi awal. Meluruskan kaki dan punggung bersandar.
Aruna memintaku menghabiskan air selagi masih hangat.
“Kok bisa gitu, lupa makan,” dia bergumam sendiri sambil menyelimuti kakiku. Keahliannya sebagai perawat dipadukan dengan perhatiannya sebagai pacar membuat Aruna lebih terlihat sebagai seorang ibu. Pemandangan ini sangat lucu. Aku menyamarkan senyuman dengan menutup mulut menggunakan gelas.
Setelah itu dia mengusap perutku dengan tangannya yang telah dibubuhi minyak angin. Kali ini terasa geli, badanku meliuk kiri dan kanan menahan sensasi menggelitik. Aruna bergeming. Aku berusaha bersikap sewajarnya agar tidak terlihat berlebihan lagipula aku takut akan dimarahi.
“Tiga hari lagi kamu ujian … jaga kondisi badan,” ucapnya datar dan terus fokus pada usapan.
“Iya…,” jawabku sambil masih menahan geli.
“Seminggu lagi aku ke Tangerang. Kamu kalau begini terus gimana aku bisa tenang?” Alis Aruna bertaut, menunjukkan kekhawatiran.
“Iya …”
“Pokoknya makan teratur. Jangan tunggu kosong baru makan, itu malah gak baik.”
“Iya …”
“Baru beberapa hari lalu aku ingatin, udah kejadian,”
“Bener …”
Aruna menghela nafas.
Aku tersenyum dengan lemas.
“Bener segala. Kamu ih! Jangan iya-iya-iya, tapi gak dikerjain. Kalau kamu tadi sampai muntah cairan kuning, bahaya!” Aruna marah dan sejujurnya tampak menyeramkan dengan cara yang imut. Aneh. Aku sendiri juga heran, kenapa bisa ada perempuan yang marah tapi masih menggemaskan.
“Runa, maaf tadi aku gedor pintu sampai kamu kaget, ya?”
“Aku yang salah, aku ketiduran, Gam.”
Aku manggut-manggut. Wangi khas minyak angin yang menyegarkan memenuhi ruangan, perlahan rasa tidak nyaman mulai hilang. Badanku sudah mulai hangat. Perutku sudah mulai nyaman. Aku tidak lagi gemetaran.
“Runa?”
“Hmm?” dia membubuhkan sekali lagi minyak angin itu dan kembali mengusap perutku.
“Ini curang.”
“Apanya?” Aruna berkernyit.
“Masa cuma aku yang di pegang-pegang?”
Aruna mengatup bibirnya, menatapku sinis dan usapan itu kini berganti menjadi cubitan kuat.
“Aww! Iya! Ampun! Bercanda. Bercanda.”
“Ngomong gitu lagi, aku cubit lebih kuat!” Aruna marah dengan muka perlahan merona merah.
Ah! Dia malu!
Saat Aruna merasa aku sudah cukup baik, dia membuatkan telur dadar dan disuguhkan dengan nasi hangat.
“Makan perlahan, kunyah yang benar.”
Katanya sambil mengusap-usap kepalaku saat aku sedang menyuap.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden









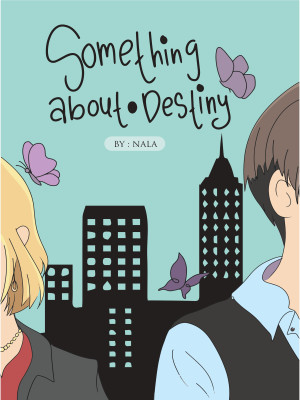



Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)