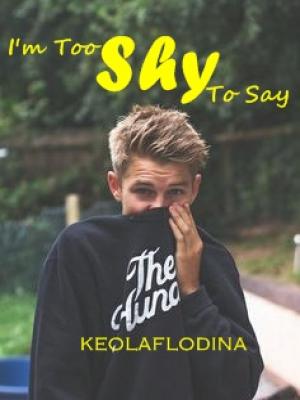Kamis siang. Itu artinya Annika bisa bersantai di kasurnya sambil membaca buku dan memakan stik biskuit coklat. Jajan terakhirnya yang ia bawa dari rumah. Annika sedikit ragu untuk memakannya tadi. Namun, sebentar lagi akhir bulan. Lalu sekardus penuh makanan akan datang dan membuatnya bisa merasakan makanan lain selain makanan asrama.
“Aku bawa banyak formulir prefek, nih. Tadi Kak Atina minta aku bantu bagiin. Ada yang mau?” tanya Sheila pada anak-anak yang sedang mengobrol di lantai. Ia mengeluarkan berlembar-lembar kertas dari dalam tas.
“Mau satu dong, Shei. Eh, satu lagi buat Lumi,” kata Gladys.
“Aku juga mau.”
“Aku mau juga.”
Menjadi prefek merupakan jabatan yang bergengsi di Aqiela Ru’ya. Lencana biru itu memberimu banyak kewenangan, seperti boleh keluar di jam malam, boleh keluar dari area sekolah di saat-saat tertentu, dan memberimu kewenangan yang memberikan beberapa orang bangga.
“Nika, kamu ngga mau?” tanya Sheila setelah memberikan beberapa kertas pada Gladys dan teman-teman lain.
“Huh? Oh, ngga.”
“Beneran?” tanya Sheila meyakinkan. “Aku mau bagiin ke kamar lain soalnya.”
“Beneran. Bagiin aja.”
“Oke,” kata Sheila, lalu memperhatikan Annika lebih detail. “Kamu belum lepas seragammu. Nanti lecek, loh.”
“Kan mau dicuci.”
“Hmm, tetep aja—ya udah, deh.”
Annika melanjutkan membaca novel saat Sheila pergi keluar kamar. Ia benar-benar terserap dalam kisah spionase sampai-sampai tak sadar kalau dua jam telah berlalu. Kepalanya pusing saat matahari dari kaca jendela menyapa matanya. Anya tidur siang. Gladys sedang menyapu kolong meja belajar. Sheila tengah menulis sesuatu di atas ranjang. Suasana lengang sekali, waktu yang sempurna untuk tidur siang.
Seragamnya mulai terasa tak nyaman. Annika pun melepasnya, menyisakan kaos lengan pendek yang melindungi tubuhnya saat ini. Ia berguling lagi di kasurnya dan berniat untuk menggeser tirai saat terdengar teriakan di lorong. Suaranya tidak begitu jelas. Sampai seseorang membuka pintu kamar sambil tersedu dan berjalan cepat ke ranjangnya.
“Danila, kamu kenapa?”
Danila duduk di tepi ranjangnya sambil menutupi muka. Bahunya tersengal-sengal. Wajahnya merah sekali. Tangannya sedikit gemetar. Bercak-bercak berwarna hijau menodai seragamnya. Danila adalah teman paling manisnya yang tak akan menyakiti benda mati sekali pun. Tetapi kenapa ada orang yang tega membentaknya sampai seperti ini?
“Ada apa, Danila? Tadi siapa yang teriak gitu ke kamu?” tanya Sheila, mengabaikan buku diarinya yang masih terbuka lebar di ranjangnya.
Gladys datang dan memeluk bahu Danila. “Tadi siapa yang bicara gitu ke kamu? Kamu pasti kaget banget.”
Danila mengelap matanya. Wajahnya sangat merah. Ia melihat teman-temannya dengan mata merahnya, lalu bergumam, “Maaf.”
“Maaf kenapa? Kamu ngga salah apa-apa.”
Danila mengerjapkan matanya, mencoba terlihat tenang. Meskipun sudut matanya berkilauan dengan air mata yang ingin turun. “Ah, kalian tadi pasti mau tidur siang.”
“Oh, jangan pikirin itu, Danila. Kamu nggak apa-apa?” kata Gladys.
“Nggak apa-apa. Tadi aku yang salah. Aku bikin bukunya ketumpahan susu. Ngga terselamatkan. Aku ngga tau mau tanggung jawab gimana selain bilang kalau aku bisa menyalinnya. Tapi dia malah makin marah. Gimana ya, supaya dia ngga kesal denganku lagi?”
“Kamu ngga sengaja, kan?” tanya Annika.
Danila diam sebentar, lalu berbicara lirih, “Nggak tahu. Aku habis ada pertemuan klub dan aku nemu ide baru untuk rajutanku selanjutnya. Aku terlalu semangat sampai lari naik tangga. Aku ngga lihat ada orang yang turun tangga. Dan jadilah begini. Harusnya aku engga lari-lari, kan? Ustazah Medina selalu bilang ngga baik buru-buru. Kalau aku engga buru-buru, pasti kejadian ini ngga akan terjadi.”
“Kamu ngga sengaja,” tegas Sheila. “Iya memang ngga boleh lari-lari di tangga. Tapi kamu nggak sengaja menabrak dia dan bikin bukunya basah. It’s okay. Seenggaknya kamu udah minta maaf dan coba tanggung jawab. Setelah kalian berdua tenang, coba minta maaf lagi.”
Danila mengangguk-angguk. “Pastinya. Aku merasa sangat bersalah.”
“Dari tadi kamu nggak bilang dia siapa, Dan?”
“Oh, iya?” kata Danila, lalu diam sejenak, lalu berkata, “Ah, aku enggak enak mengatakannya …”
Gladys makin penasaran. Ia menanyakan kandidat nama anak-anak yang ia duga memarahi Danila. Sheila menahan Gladys dengan tegas, “Kalau Danila engga mau jawab, jangan ditanyain terus. Danila, ganti baju dulu aja lalu direndam di mesin cuci. Takutnya engga hilang nodanya dari seragam. Yuk aku temenin, aku juga mau nyuci soalnya.”
Sementara itu, Annika memandang bekas tumpahan susu yang berwarna hijau. Tunggu, susu warna hijau? Satu-satunya orang yang senang bereksperimen dengan rasa susu yang ia kenal adalah Kiara. Tapi … nggak mungkin, kan? Kiara selalu menyukai Danila. Kiara selalu bersikap baik dan berbicara dengan riang pada gadis itu.
Namun, kalau diingat-ingat, suara di lorong itu benar-benar mirip Kiara.
Beberapa hari terakhir mereka jarang bertemu. Tugas yang banyak dan kelas yang berbedalah yang menyebabkannya. Kiara juga sudah tiga kali menolak ajakannya untuk bermain. Kiara pasti punya masalah, karena ia bukanlah gadis yang akan berteriak keras pada orang lain.
Annika turun dari kasurnya, lalu menyelinap pergi saat Sheila dan Danila tengah bersiap-siap mencuci. Ia berjalan menuju kamar satu dan mengetuk pintu.
Seorang gadis membuka pintu. Namanya Runa. Salah satu teman klub musiknya. Ia pemain flute. Ia tengah menyisir rambutnya yang baru terurai dari kepangan.
“Eh, Annika. Ada apa?”
“Mau cari Kiara. Kamu lagi main salon-salonan?” tanya Annika saat melihat bintang-bintang di rambut Runa.
“Iya. Lihat di sana, salonnya Lucily masih buka. Mau?” kata Runa sambil menunjukkan sekumpulan gadis yang tengah bergantian menata rambut. “Oh—Kiara engga ada. Tadi habis—anu … sama Dani, dia langsung ganti baju dan buru-buru pergi. Serem banget ya, Kiara kalau marah. Kita semua bener-bener kaget. Dani gimana?”
Annika terpaku. ‘Jadi tadi beneran Kiara?’ Ia mengerjap, lalu menjawab, “Dani udah ngga apa-apa. Lagi sama Sheila sekarang. Kiara pergi ke mana?”
Runa mengangkat bahu. “Enggak tahu. Tadi bawa buku tebel banget. Kiara lagi ada masalah, ya, Nik? Soalnya dia sensitif banget sekarang. Anehnya, dia sering belajar sampai tengah malam pakai senter. Sayang banget matanya.”
“Umm—nggak tahu,” kata Annika, tiba-tiba merasa kalau jarak telah melebar antara dirinya dengan Kiara. Semua orang benar, berpisah kamar adalah kutukan. Sahabat yang sebelumnya sangat dekat kemudian menjadi seseorang yang bahkan kabarnya saja mereka tak saling tahu. “Ya udah deh, kalau ngga ada. Makasih, Runa.”
Annika berjalan kembali ke kamar dengan pikiran-pikiran memenuhi kepalanya. Ia tak mau menerima begitu saja kutukan itu. Persahabatannya dengan Kiara adalah hal yang paling berharga yang ia temukan di Aqiela Ru’ya. Ia akan membuktikan bahwa pemisahan kamar tak akan menjadikan mereka menjauh.
Annika memakai jilbab dan kerudungnya, kemudian turun menuju lantai satu. Ia memakai sandalnya. Sekarang ia perlu menemukan Kiara dengan petunjuk buku-buku di tangannya. Tujuan yang paling jelas adalah perpustakaan.
Setibanya di perpustakaan, Annika mencari satu persatu ruang belajar yang ada di sana. Ruang belajar itu memiliki dinding transparan, sehingga Annika mudah melihat ke dalam. Akhirnya ia menemukan Kiara, yang tengah berkutat pada bukunya di ruang belajar paling ujung. Lembar-lembar kertas berserakan di hadapannya.
Annika membenamkan bibir, lalu membuka pintu ruangan. Kiara mendongak.
“Hai,” sapa Annika.
“Hai.”
“Kamu ngga apa-apa?”
“Aku benar-benar kesal.”
“Oh,” ucap Annika, lalu ia duduk di samping Kiara. “Kamu bisa katakan padaku.”
“Danila menabrakku. Buku catatan sejarahku sampai basah kuyup oleh susu. Saat ini sedang kujemur di rooftop. Aku berencana akan menulis ulang dan menambahkan beberapa catatan lagi, padahal tugas juga banyak sekali.”
“Kalau begitu tidak usah dicatat ulang.”
“Mana bisa begitu? Bukuku akan mengembang dan bau roti dan aku akan kelihatan seperti orang yang sembrono.”
“Nggak ada yang anggap seperti itu, Ra. Ah, kalau kita mengeringkannya dengan benar sekarang pasti nggak akan mengembang. Ayo ke asrama lagi.”
“Aku baru sampai di sini—loh, memangnya caraku salah?”
“Yep. Papa pernah kasih tahu cara mengeringkan buku. Ayo sekarang. Sebelum bukunya kaku kayak kerupuk. Kamu punya tisu? Kita akan butuh banyak tisu.”
Baru saja datang ke perpustakaan, keduanya keluar lagi. Annika membantu membawa setumpuk kertas Kiara. Mereka naik ke rooftop sesampainya di asrama Manna. Buku tulis gadis itu diletakkan di atas pagar, dan kelihatan menyedihkan dengan air susu yang menetes-netes.
“Gini caranya, tisunya ditaruh tiap beberapa halaman. Kamu dari belakang, ya,” kata Annika sambil memberikan tisu ke Kiara.
Mereka bekerja sama mengeringkan buku. Saat sebuah tisu sudah terlalu basah, maka segera diganti. Tak lama kemudian, buku itu sudah tak lagi meneteskan susu. Annika berkata kalau buku itu dibiarkan berdiri dulu di hembusan angin. Yang untungnya, lokasi Aqiela Ru’ya membuat suplai angin memadai.
“Wah, sama sekali engga mengembang. Kamu punya banyak trik, ya?” ucap Kiara yang telah lebih ceria.
“Papa ajarin aku udah dari TK, karena bukuku suka ketumpahan air minum. Aku selalu praktekin ini tiap tahun waktu SD. Jadi tenang aja, buku kamu ditangani sama tenaga profesional,” kelakar Annika.
Kiara tertawa. Ketegangan di wajahnya telah menghilang. Annika jadi ikut senang. Meskipun ia masih mengkhawatirkan Kiara. Buku-buku tebal, mata panda, berlembar-lembar kertas latihan soal, semuanya seperti bukan Kiara. Perkataan Runa tadi juga mengganggunya. Sebagai gadis rasional, tak mungkin Kiara merelakan kesehatan matanya untuk belajar sampai tengah malam. Ketika diingat-ingat pula, sudah tiga minggu Kiara tak mengajaknya berolahraga. Biasanya Kiara selalu mengajaknya bermain kasti, bulu tangkis, atau lacrosse di lapangan belakang asrama setiap hari Jumat.
Namun, Annika juga tahu bahwa Kiara jadi rajin belajar itu juga bagus. Nilai kelas empat termasuk nilai yang dipertimbangkan untuk masuk ke universitas unggulan. Mayoritas teman-teman lain juga belajar dengan lebih rajin. Annika menimbang-nimbang bagaimana sebaiknya ia menyampaikan kecemasannya.
“Sekarang aku sangat merasa bersalah pada Danila. Dia pasti menangis,” kata Kiara.
“Iya, dia nangis.”
“Aku benar-benar merasa bersalah. Kalau dia masih nangis saat mau tidur malam nanti dan mengutukku, lalu bertekad tak akan bicara padaku lagi, aku akan sangat sedih. Ya ampun, tega sekali aku meneriakinya seperti tadi. Dia kaget mendengar suaraku sampai melompat seperti kelinci. Dia nggak tahu kalau ada aku di balik tangga. Aku memarahinya karena lari di tangga, padahal tadi kita dari perpustakaan ke sini juga lari.”
“Insya Allah Dani bakal maafin, kok. Dia sadar itu salahnya dan ngga salahin kamu sama sekali. Dia bahkan ngga menyebutkan namamu sama sekali di kamar tadi.”
“… Baik banget dia …”
Buku Kiara sudah hampir kering. Annika membuka halaman-halaman yang masih lembab supaya angin bisa mencapainya. Ia menipiskan bibir, lalu berkata, “Nanti Dani ke sini buat jemur baju. Kamu tunggu aja di sini lalu minta maaf. Kamu bisa jelasin kenapa kamu membentaknya seperti itu. Maksudku, Danila selalu menganggap kamu ramah dan tenang dan ceria.”
“Hah … ngga tau, ya. Aku merasa kemampuanku sangat kurang. Aku ngga pintar di pelajaran apa pun. Aku merasa harus mengejarnya dengan belajar seserius mungkin di setiap waktu luang. Sampai-sampai aku membentaknya seperti itu padahal dia engga sengaja.”
“Huh? Nilai kamu kan lumayan bagus, Ra.”
“Rata-rata delapan. Ngga ada yang menonjol.”
“Nilai kita sama. Menurutku kamu harus santai sedikit. Pasti bisa pelan-pelan mengejar kalau kamu memang merasa tertinggal.”
“Tapi nilai Pianomu hampir selalu sempurna.”
Annika mengerutkan dahi. Nilainya dengan Kiara memang hampir sama, sih, tapi kebanyakan Kiara yang memimpin. Seperti Matematika, Fisika, atau Geografi. Mereka terdiam selama beberapa saat sambil memisahkan halaman-halaman buku catatan Kiara.
“Aku mau daftar jadi prefek juga. Menurut kamu gimana?” tanya Kiara. “Bekerja di bawah Kak Regina bakal menyebalkan, sih, dia perfeksionis. Tapi pasti banyak pengalaman yang akan didapat.”
“Bagus! Menurutku kamu bakalan cocok. Oh, bidang apa yang kamu inginkan?”
“Um—belum aku pikirin, sih. Cuma yakin banget mau daftar. Ayo daftar juga, Nik!”
“Nggak, deh. Pasti bakal sibuk.”
“Iya pasti. Tapi bakal berpengaruh waktu cari universitas nanti.”
“Oh, iyaa?” tanya Annika. Jujur saja, Annika belum terpikir apa yang ia akan lakukan setelah lulus dari Aqiela Ru’ya. Tiga tahun adalah waktu yang lama. Annika sedikit tergoda juga, apalagi Kiara juga melakukannya. Mereka biasanya selalu bersama-sama.
“Iya. Kampus-kampus besar menilai anggota prefek punya nilai lebih.”
Tapi membayangkan tanggung jawab yang akan ia pikul membuatnya mengurungkan diri. Ia juga tak punya kelebihan apa pun. Bahkan namanya saja tak disebut dalam pemilihan ketua kamar. Sementara banyak gadis-gadis yang lebih pintar dan berkepribadian baik dibanding dirinya. Untuk apa mendaftar kalau nantinya akan kalah? “Nggak, Ra, aku beneran engga minat.”
“Ya udah deh. Doain aku yaaa semoga aku bisa diterima.”
“Iyaaa,” kata Annika sambil menyentuh kertas buku tulis Kiara. “Oh, udah kering, nih. Nanti sampai di kamar langsung ditindih pakai buku tebal supaya tetap tipis.”
“Okee. Makasih yaa. Ehh …”
Mendengar suara Kiara yang aneh, Annika menoleh juga, mengikuti arah pandang Kiara. Rupanya Danila dan Sheila. Mereka berpandangan dengan kikuk, kemudian Danila dan Kiara berbicara bersamaan.
“Kiara, maaf ya—”
“Dan, aku minta maaf ya, soal—”
Annika tersenyum. Senang bahwa konflik hari ini telah berakhir dengan damai.


 floricialy
floricialy