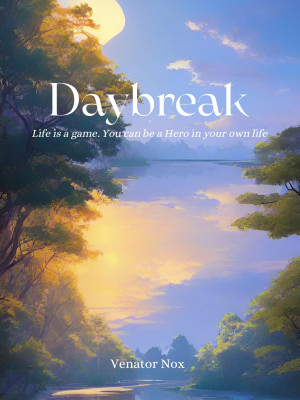“Teteh pasti sengaja, ya?” Tisha menyambut kedatangan sang kakak dengan tuduhan ketus.
Riana yang baru melepas jaket jadi mengernyit. “Sengaja apa?”
Tisha berdecak. “Itu, si pengunjung setia. Sikapnya terlalu baik. Teteh pasti sengaja milih orang kayak gitu buat aku deketin, kan?!”
Riana menahan senyum jail. “Lha, emangnya kamu mau bersama-sama dengan orang yang nakal? Nanti lebih susah, lho, pendekatannya.”
“Ya ....” Suara pembuka Tisha yang semula lantang seketika melemah tatkala menyadari kalimat jebakan sang kakak. “Enggak gitu juga!”
“Terus?”
“Itu ....” Tisha menggigit bibir bawah. “Ya, aku enggak mau deketan sama orang nakal,” serunya cepat di awal, lalu ragu-ragu, “ta-tapi ... enggak sebaik Kak Sawala juga. Dia itu ... ah, gila, pokoknya kelewatan banget baiknya.”
Riana menopang dagu dengan wajah condong ke arah Tisha. “Ngapain aja dia emang?”
Tisha menghela napas. Punggungnya lemas, jatuh ke sandaran. “Tadi dia tuh ....”
***
Dua salam menutup aktivitas mereka yang melaksanakan salat. Tisha segera bangkit sembari melepas mukena. Tanpa melipat ataupun mengembalikannya ke tempat semula, dia memilih pergi dengan membiarkan perlengkapan salat milik musala sekolah itu tergeletak tak beraturan. Sebab, pikirnya nanti juga akan digunakan oleh orang di kloter selanjutnya, maka biar mereka saja yang membereskannya.
Begitu mendudukkan diri di serambi untuk memakai sepatu, Tisha baru ingat bahwa dia ke sana tidak sendirian. Tadi dia ditarik sosok pemilik sepatu di sebelahnya. Namun, sekarang di mana sosok itu?
Tisha memutar kepala. Matanya awas meneliti sekitar pintu yang ramai dengan keluar masuknya orang-orang. Setelah beberapa saat menajamkan penglihatan, akhirnya Tisha berhasil menangkap keberadaan Sawala di dekat sebuah pilar, sedang bercengkrama dengan tiga gadis yang sebelumnya sempat berpapasan di persimpangan.
Tentang tiga gadis itu, ternyata mereka adalah alasan Sawala terlihat berlebihan di mata Tisha. Jadi, Sawala membawa banyak mukena karena ingin menyiapkannya untuk mereka. Jadi, begitu datang ke musala, tiga gadis itu tidak perlu repot-repot mencari tempat ataupun berebut mukena, karena Sawala sudah sangat berbaik hati untuk melakukannya lebih dulu, dan itu–setahu Tisha–tanpa diminta.
Tisha bergidik membayangkan jika memang benar semua yang Sawala lakukan adalah hasil inisiatif sendiri. Sangat menyeramkan! Sebab, Tisha sendiri jika dimintai bantuan akan lebih mengambil sikap pura-pura tak mendengar atau beralasan sedemikian rupa untuk menghindar. Seperti saat melihat anak yang jatuh dulu.
Tisha kembali membalikkan tubuh, memasang sepatu tanpa terlebih dahulu menggunakan kaos kaki. Dengan pikiran yang masih melayang-layang, mengherankan sikap Sawala, Tisha mengikat talinya malas-malasan.
Tidak lama dari itu, Tisha mendengar seseorang berdeham. Begitu mendongak, dia mendapati Sawala yang berdiri dengan wajah berseri tengah memandangnya. Canggung, Tisha pun membalasnya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Kemudian saat Sawala makin dekat, Tisha menggeser duduknya, memberi ruang karena berpikir Sawala juga akan duduk untuk mengenakan sepatunya.
Namun, perkiraan Tisha hanya benar separuh. Sawala memang mendekat untuk duduk di sisi Tisha, tetapi tujuannya bukan untuk mengenakan sepatu. Sawala malah menginjak bagian atas sepatunya–menjadikan alas untuk kakinya yang telah berbalut kaos kaki bersila, kemudian dia mengorek-ngorek tas punggungnya.
Tisha yang sudah selesai dengan tali-talinya hanya bisa memperhatikan hal itu lewat sudut mata. Dia memang cukup penasaran dengan apa yang sedang kakak kelasnya itu cari, tetapi segan–atau lebih tepatnya gengsi–lebih mendominasi. Tidak mau disebut orang kepo.
Di saat Tisha sudah mulai jemu dan mengalihkan pandangannya ke rumpun bunga kertas beraneka warna di sisi-sisi musala, Sawala malah menggeser tubuh hingga kembali tak berjarak dengan Tisha. Mereka duduk teramat dekat, sampai lengan Tisha dan Sawala bersentuhan. Tisha menoleh, merasa tidak nyaman. Namun, Sawala malah menunjukkan deretan giginya.
“Ini buat kamu!” Seperti tak memedulikan raut wajah Tisha, Sawala malah menunjukkan sebungkus roti kacang.
Karena Tisha hanya diam, Sawala menyipitkan mata. “Eh, apa kamu alergi kacang?”
Tisha menggeleng. Dia adalah pemakan segala, tidak memiliki alergi pada makanan apa pun. Akan tetapi, kini dia sedang ragu. Haruskah menerima pemberian itu? Dia takut Sawala memiliki maksud tersembunyi di balik aksinya berbagi makanan sejak pertama jumpa tadi.
Tanpa ba-bi-bu Sawala malah meraih tangan Tisha dan meletakkan bungkusan itu di atasnya. “Buat ganjel perut. Udah rawan cacing ngedrum jam segini tuh. Apalagi sebelum salat tadi kamu udah geleng-geleng kepala kayak yang pusing, harus segera diisi amunisi yang kayak gitu tuh.”
Tisha hanya bisa tertegun. Tangannya yang baru dilepaskan Sawala rasanya seperti membeku.
“Ayo, dimakan!” titah Sawala pelan di tengah-tengah kesibukannya menyobek bungkus roti miliknya.
Tisha menghela napas tertahan. Meski diliputi bermacam kekhawatiran, pada akhirnya dia membuka plastik itu dan berusaha melahap isinya. “Terima kasih.” Semoga saja aku akan baik-baik saja. Harapnya dalam hati.
“Kembali kasih.”
Tisha menelan ludah melihat Sawala menarik sudut bibirnya sangat lebar. Apa dia tidak khawatir bibirnya sobek, ya?
Sampai beberapa menit kemudian, ketika rotinya sudah habis, Tisha hampir saja menjatuhkan bungkusnya ke halaman musala. Namun, colekan Sawala menghentikannya. Ketika Tisha memandangnya, Sawala malah menengadahkan tangan kanan. Tisha jelas heran. Apa jangan-jangan dia menginginkan bayaran atas rotinya?
“Bungkusnya.” Lagi, seperti cenayang Sawala selalu dapat menebak isi kepala Tisha yang penuh pertanyaan.
“Oh, ini.” Dengan kaku Tisha menyodorkan plastik.
Begitu menerimanya Sawala segera melipatnya bersatu dengan bekasnya, kemudian tanpa kata dia bangkit dan berjalan beberapa meter ke sisi lain yang dilengkapi dengan tong sampah.
Tisha menelan ludah susah, kok Sawala serajin itu? Padahal kan membuang sampah di mana saja nantinya tetap akan dibersihkan penjaga sekolah.
“Maaf, ya, Dek.” Begitu kembali ke sisi Tisha, Sawala membuka percakapan.
Tisha mengangkat sebelah alis. Kenapa lagi ini Sawala? Kok hobi banget minta maaf, sih?
“Maaf kita belum bisa pulang sekarang.”
Di tengah segala tanya yang menggentayangi kepalanya, Tisha hanya bisa membuka mulut. “Hah?”
“Itu, kita agak nantian pulangnya, ya.”
“Oh, nunggu mukena Kakak dulu, ya?” Tisha asal menebak karena tadi dia tak melihat Sawala membawa keluar mukenanya.
“Iya ....”
Belum sempat Sawala memperpanjang ucapan, terdengar kasak-kusuk orang keluar. Segera Tisha dan Sawala bangkit, menjauh beberapa langkah untuk memberi ruang pada yang akan mengenakan sepatu.
Melihat Sawala sudah menerima kembali mukenanya, Tisha bersiap mengenakan helm dan hendak mengayunkan kaki untuk beranjak dari sana.
Namun, Sawala mencekal pergelangan tangan kanan Tisha. “Sebentar lagi, Dek.”
Tisha mengernyit. “Masih ada yang ditunggu, Kak?”
“Ada yang harus aku urus di dalam. Jadi, minta tolong tunggu dulu sebentar lagi, ya,” pintanya sembari mengarahkan dagu ke teras yang tadi mereka tempati, seolah mengisyaratkan agar Tisha kembali menunggunya di sana.
Akhirnya Tisha hanya bisa mengangguk. “Iya.”
Saat Sawala sudah masuk, Tisha yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan kakak kelasnya itu memilih tak mengikuti perintah untuk duduk di semula, dia malah berdiri di dekat jendela untuk mengintip. Hasilnya, Tisha dapati Sawala sedang memilah-milah mukena sesuai pasangannya, kemudian melipat dan menata dengan rapi di lemari.
Jadi, yang menata mukena itu bukan penjaga sekolah, melainkan Sawala? Seketika Tisha berucap, “Ini gila!”
***
Bibir Riana berkedut. Namun, sekuat mungkin dia berusaha menahan tawa demi menjaga suasana tetap serius, tidak mau membuat Tisha merasa diledek. “Diambil positifnya aja atuh. Dengan orang yang kamu dekati itu bukan sosok nakal, berarti kamu bakal lebih aman, enggak akan dijahili.”
“Tapi enggak gini juga, Teh!” Tisha mendengkus, mengentakkan kaki, lalu pergi ke kamar.
Riana tersenyum simpul. “Semoga kamu tertular sikap positifnya, Dek.”


 salwariamah
salwariamah