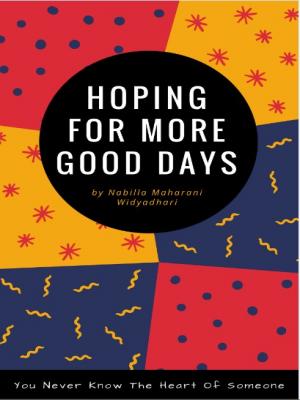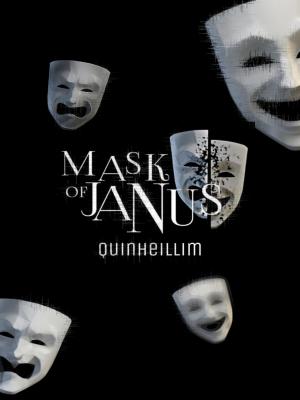Mengarang naskah drama tidak semudah menulis cerita di blog. Mirip, tapi masih banyak bedanya. Kalau tidak ada Kak Vira yang jadi sering kutandangi kamarnya untuk minta saran dan deadline dari panitia, barangkali penulisanku ini macet tak lanjut-lanjut gara-gara aku sulit membayangkan kondisi panggung.
Perihal kenapa baru di tahun ini diadakan pentas drama, adalah karena Dies Natalis kali ini adalah pesta berlian. Usia asramaku tahun ini tujuh puluh lima tahun, alias tiga perempat abad. Selain pentas drama, akan diadakan rangkaian acara besar lainnya—yang betul-betul besar-besaran. Reuni akbar, mulai dari angkatan tertua yang masih bisa dihubungi sampai yang baru lulus tahun lalu; kunjungan ke rumah mantan karyawan yang sudah purna tugas; ziarah ke makam para suster yang pernah mengabdi di asrama; dan pengabdian masyarakat yang istilah kerennya, live in. Pentas drama sendiri akan digelar pada saat reuni akbar, jadi sebagian besar penontonnya bakalan alumni warga asrama dari berbagai angkatan beserta keluarganya.
Tema cerita dalam drama itu sederhana saja: kehidupan berasrama. Hanya saja, bagaimana merangkum yang sederhana itu menjadi kisah menarik, membuatku terus-menerus kepikiran. Harus ada sebuah pengantar yang nendang.
Ketika di minggu itu tiba masa berpuasa bagi teman-teman yang beragama Islam, aku mendapat ide. Semuanya bermula dari tingkah si Belang, kucing asrama. Makhluk Felis domesticus itu mengintai di bawah meja ketika lauk sahur disiapkan sore hari sebelum puasa hari kedua. Senampan tempura hangat, pasti habis diangkat dari wajan kalau menilik aromanya. Aku sedang akan berangkat ke kampus untuk latihan PSM dan mau meletakkan kotak bekalku di meja makan agar nanti diisikan oleh teman yang bertugas saat makan malam. Tak lupa sebuah pesan manis dari sticky notes tertempel di tutupnya,
“Ashira titip makan malam ya, terima kasih, God bless you.”
Sudah tiga tahun kulakukan ini hampir tiap hari (tiap sore lebih tepatnya), paling banyak lima hari dalam seminggu, saking seringnya aku pulang melewati jam makan malam. Beruntung sekali bisa minta tolong teman di asrama untuk mengambilkan jatah makan malamku, sehingga pulang-pulang aku tidak perlu kelaparan dan bingung cari makan.
Si Belang masih mengintai ketika kotakku sudah bertengger di meja makan. Kuusir dia menjauh dari nampan tempura yang menggoda.
“Shoo! Shoo!”
Kucing itu ngacir ke luar, menuju kebun mawar. Aku pun bergegas melewati dapur dan berpamitan, lalu beranjak—bukan ke parkiran sepeda, tapi langsung ke pagar asrama. Karena ceritanya Markus mau menjemputku, jadi aku juga sudah menyiapkan helmku sendiri.
Saat sepeda motor Markus mencapai asramaku, di kejauhan aku mendengar bunyi terompet. Aku menoleh dan menyipitkan mata.
Si Pengingat sedang berjongkok di kebun mawar dan di hadapannya berdiri si Belang yang tampaknya menggeram. Astaga, Fidelia itu meniup terompetnya untuk seekor kucing! Bukan main.
“Ada apa, Ra?” tanya Markus sambil membuka kaca helmnya.
“Nggak apa-apa. Yuk, berangkat.”
Ngapain juga aku harus mencegah seekor kucing mencuri?
*
Rupanya, seusai latihan PSM, Markus mentraktirku. Hari itu, dia mendapat gaji pertamanya dari hasil mengasisteni praktikum di rumah sakit.
“Wow. Selamat, ya.” Aku sendiri belum pernah jadi asisten praktikum karena kurasa aku tak sanggup membagi waktu antara menulis laporanku sendiri versus menilai laporan orang. Lagipula, terlalu banyak yang menyalin begitu saja, seperti yang pernah kubahas dengan Dian. Aku bisa gila nanti kalau menemukan plagiarisme di sana-sini di laporan yang kuperiksa.
“Makasih.”
Aku tak bertanya berapa gaji asisten praktikum di Fakultas Kedokteran, tapi sepertinya angkanya cukup besar kalau melihat ke mana Markus membawaku.
“Kalau tahu mau ke tempat elegan kayak gini, tadi pakai baju yang agak bagusan, deh,” gerutuku yang pakai kemeja kotak-kotak sederhana dan denim hitam.
“Sori. Dadakan sih kepikirannya,” Markus membalas sambil nyengir. Dia sendiri pakai kaos kerah dan celana denim juga. “Kapan-kapan kita ke sini lagi deh, dengan baju yang oke.”
Tempat itu berupa restoran taman yang luas dengan sebuah kolam berhiaskan lampu di tengahnya, dan ada temaram cahaya lilin di setiap meja. Oh, ya, ampun. Seandainya saja aku tidak sedang ada tumpukan laporan praktikum yang menunggu untuk dikerjakan—seperti yang kubilang pada Markus begitu kami mengempaskan pantat di kursi masing-masing—aku bakalan dengan senang hati menghabiskan berjam-jam di sini. Oh, dan jangan lupakan, ada batasan jam malam.
Markus paham dan tak keberatan. Kami hanya setengah jam di situ, lalu pesan makanan untuk dibawa pulang, dan betulan pulang ke asrama. Pulang dengan perut kenyang dan hati penuh rasa terima kasih pada Markus, aku baru teringat aku sudah titip makan malam di asrama. Ya sudah lah, biasanya awet; jadi masih bisa kumakan untuk pagi hari. Nanti bisa kutitipkan masuk magic jar supaya terjamin bebas dari basi, bersama makanan untuk sahur teman-teman. Dulu, di zaman OSPEK juga begitu; sarapan untuk kami yang OSPEK di kampusku memang disiapkan sejak malam sebelumnya karena harus datang ke kampus pagi-pagi buta.
Sampai di asrama, ternyata tinggal sisa beberapa menit menjelang jam malam. Pak satpam sudah ancang-ancang menutup pagar dan Markus pamitan dengan buru-buru disertai senyuman bersalah. Aku beruntung tak perlu menulis namaku di buku Pulang Terlambat. Akan sungguh memalukan nusa dan bangsa.
Begitu sampai di meja makan, kudapati Kak Vira dan Kak Sita sedang kasak-kusuk serius. Di meja itu hanya tinggal kotak bekal milikku seorang—kemungkinannya antara tidak ada orang lain yang titip makan malam atau yang titip itu sudah pada mengambil jatah masing-masing. Sisa makan malamnya sendiri sudah dibereskan semua.
“Halo, Kak,” sapaku pelan-pelan sembari meraih kotakku, segan kalau sampai mengganggu pembicaraan mereka. Keduanya menoleh.
“Oh, hai, Ra,” sahut Kak Vira dengan nada mengambang. Kak Sita sedang cemberut, raut mukanya keruh sekali, dan tampaknya dia hampir menangis.
“Kamu baru pulang?” Kak Vira lagi yang berbicara.
“Iya, Kak. Ini tadi aku titip makan malam.” Aku menjeda, menangkap atmosfer yang tidak enak. “Ada apa, Kak?”
“Lauk sahurnya untuk besok, berkurang,” sahut Kak Sita, suaranya pecah. Dia terisak pelan lalu mengibaskan tangan di depan wajahnya. “Aduh, untung aku udah buka puasa.”
Kulihat objek yang mereka bicarakan, nampan berisi tempura yang tadi sore baru matang, isinya tinggal separuh. Seketika tubuhku terasa dingin; masa si Belang betulan mencuri, dan sebanyak itu pula?
Kak Vira berkata, “Udah, jangan nangis, Sit. Coba kita beli bentar di luar ....”
“Tadi pagarnya udah mau ditutup, Kak,” selaku. “Ini, jatah makan malamku ambil aja, Kak. Sama ini, aku ada dibeliin makanan juga. Tenang aja, ini halal, kok, Kak. Tadi aku udah makan malam di luar.”
Kedua seniorku itu terdiam, sebelum Kak Sita mendesah lega dan Kak Vira menyeringai lebar.
“Wah, makasih banyak, ya, Ra.”
“Alhamdulillah, makasih ya. Kamu baik banget, Ra.”
“Mumpung ada rezeki, si dia,” balasku sambil tersenyum malu-malu.
“Wah wah, bilangin makasih ke dia ya,” ujar Kak Vira.
“Siap, Kak.”
“Tapi, siapa coba, yang ngambil? Jahat banget nggak, sih ...?” keluh Kak Sita. “Mana Bu Feni selalu bikin lauk sahur pas sejumlah kita yang Muslim, nggak peduli lagi halangan apa nggak. Tapi ini tinggal segini, coba.”
Kak Vira menghitung-hitung dengan jari. “Kalau semuanya puasa, ada empat orang yang nggak dapat jatah.”
“Anu,” gumamku. “Kak, tadi sore waktu aku mau berangkat, si Belang tuh kayaknya udah ngincer tempura-nya. Waktu baru aja mateng dan ditaruh di meja.”
Kedua mahasiswi yang setahun lebih tua dariku itu terbelalak.
“Astaga! Si Belang?” seru Kak Sita.
“Pantesan banyak tepungnya yang berceceran di lantai tadi,” timpal Kak Vira sambil berpikir-pikir.
“Berarti bener si Belang, ya, Kak.” Kalimatku seperti mencari pembenaran. Fidelia tadi betulan memperingatkan kucing itu! Dan, aku malah balik badan dan berangkat tanpa rasa bersalah, padahal aku juga mendengar bunyi terompetnya. Kuingat lagi laporan praktikumku yang memanggil-manggil untuk dikerjakan; bagaimana teman-teman yang tidak kebagian jatah sahur ini bisa tahan sampai buka puasa besok sore padahal masih harus kuliah seperti biasa? Apalagi kalau mungkin ada yang harus lembur tugas malam-malam sepertiku?
“Ck ck ck,” gerutu Kak Sita. “Nakal banget si Belang!”
“Harus hati-hati, nih, kalau nyimpan makanan,” balas Kak Vira. “Berarti tadi Bu Feni juga lupa masukin ke magic jar, ya. Soalnya ini senampan ada di sini sejak makan malam.”
“Ya udah, Kak. Yang penting buat sahur besok udah ada. Besok ingetin Bu Feni aja.”
Malam itu aku melembur laporan praktikum sambil ngemil biskuit—yang kubeli bareng Elena—dan berpikir, bahwa teman sekamarku yang tambun itu ada benarnya juga. Logika tidak akan bisa jalan tanpa logistik yang adekuat. Mahasiswi-mahasiswi ini juga perlu logistik di bulan puasa, makanya perkara lauk sahur yang berkurang pasti membuat geger.
*
“Harta yang paling berharga, adalah keluarga.
Istana yang paling indah, adalah keluarga.
Puisi yang paling bermakna, adalah keluarga.
Mutiara tiada tara, adalah keluarga.”
Lagu Keluarga Cemara perlahan menghilang, disusul sebuah suara yang bernarasi,
“Keluarga Kasih Sayang, itulah namanya, sebuah asrama yang sudah berusia tiga perempat abad. Namun, benarkah sudah menjadi keluarga penuh kasih bagi para penghuninya?”
Suara cericip burung menyelinap masuk. Suara narator yang sama terdengar lagi,
“Betapa damainya pagi yang cerah itu. Udara sejuk meski lembab sehabis diguyur air dari langit. Namun, hal itu tak berselang lama. Keributan di sebuah kamar mengusik kedamaian.”
“Yaaaah. Sepatu gue lupa gue ambil dari jemuran kemarin, dan semalem hujan deras banget. Basah semua deh. Ugh, kenapa juga hari ini harus hari Senin sih? Mana gue masuk jam tujuh!”
“Duh, duh, Meta .... Kok, ya bisa lupa, gimana, sih?”
“Huu. Komentar lo nggak membantu, tauk!”
“Yeee, lagian kaki lo gede, Met, nggak kayak kaki gue yang mungil. Mau bantu dengan pinjemin sepatu pun gue nggak bisa.”
“Eh, sudah, sudah. Kalian ribut apa, sih?”
“Ini lho, Kak. Si Meta sepatunya basah, habis dicuci, lupa dimasukin semalam. Tahu sendiri hujannya deres kayak gitu.”
“Owalah, ckckck. Coba deh tanya si Lola kamar sebelah. Kayaknya kakinya seukuranmu dan setahuku dia Senin nggak ada jadwal kuliah. Coba pinjam ke dia.”
“Eh, Kak Lola? Bukannya Kak Lola yang kecil mungil pakai kacamata itu, ya?”
“Husy, ngawur. Itu Kak Prita. Kalau Kak Lola tuh tinggi besar kayak polwan!”
“Hayoo, masa sama tetangga kamarnya belum hapal? Udah sebulan di asrama, lho!”
“Duh, ampun, iya deh, Kak. Ya udah, aku ke sebelah dulu, ya. Keburu telat!”
Sebuah lagu instrumentalia piano bernuansa mellow menyela.
“Meta yang anak tunggal dan baru pertama kali berpisah dari orang tua mulai sadar bahwa ada bagusnya juga tinggal di asrama. Teledor menjemur sepatu, tak serta-merta berarti bolos kuliah karena bisa pinjam sepatu teman asrama. Untungnya, ukuran kakinya Meta dan Kak Lola memang sama. Tadinya dia pikir asrama mirip dengan penjara dan bahwa dia adalah korban keputusan sepihak dari orang tuanya yang memaksanya masuk dengan ultimatum: Tak boleh kuliah di Kota Pelajar kalau tidak tinggal di asrama!”
Berikutnya, lagu yang lebih ceria.
“Guys, makan siangnya ayam goreng!”
Bunyi langkah kaki yang berderap-derap menggema di lorong, disertai cekikikan dan teriakan penuh semangat.
“Hari Selasa siang, menu istimewa di asrama. Sayangnya, Meta ada kuliah sampai sore dan lupa menitipkan kotak bekal pada teman sekamar. Begitu pulang, dia merutuki diri karena lupa, padahal uang sakunya tinggal sedikit.”
“Duuuh. Mau makan apa nih gue?”
“Meta, kamu baru pulang, ya?”
“Eh? Eh, iya, Kak. Tadi siang lauknya ayam, ya?”
“Iya. Kamu belum makan?”
“Hehe ... belum, Kak. Mau titip tapi lupa. Aku lihat udah habis ayamnya.”
“Iya nih, soalnya sisa lauk dikasih ke bapak-bapak karyawan. Dikirain sudah pada ambil semua.”
“Yaaaah.”
“Eh, kamu ambil aja jatah ayamku. Ini aku tadi titip bekal, tapi tadi ada dosenku syukuran dilantik jadi Profesor. Jadi, aku udah makan di kampus tadi.”
“Waaah. Beneran, Kak?”
“Bener, nih! Kamu banyak tugas, ‘kan, tiap hari nulis laporan terus. Nanti nggak bisa mikir kamu, kalau logistik nggak terpenuhi.”
“Aaaaa. Makasih banyak ya, Kak. Memang bener. Logika nggak akan jalan tanpa logistik!”
Rekaman yang setengah jadi hasil hibrida suara anak asrama dan lagu latar itu berhenti. Aku tersenyum senang di depan laptop; lewat drama ini memang akan kupopulerkan motto hidup Elena yang tersayang.
Aku sudah menyelesaikan naskahnya; bersama divisi acara dari panitia Dies Natalis, sudah menentukan para pemerannya; didampingi Kak Vira, sudah latihan dan rekaman setengah jalan lalu hasilnya kuedit sekalian.
Kalau sudah sampai di tahap ini, kupikir semuanya akan selesai dengan baik. Tapi aku salah; karena di hari sebelum digelarnya reuni akbar itu, bunyi terompet si Fidelia muncul lagi. Suaranya keras dan menggema dengan aneh; ingat ceritaku pada Kak Vira tentang arsitektur bangunan aula yang kurang bagus?
Terang saja aku deg-degan, aku yang saat itu sedang memegang sapu untuk bantu membersihkan ruangan aula yang akan dipakai reuni. Beberapa hari terakhir, asrama memang kedatangan banyak orang yang akan mempersiapkan acara besar esok hari. Bahkan di hari itu, yang kebetulan (atau sudah direncanakan) adalah hari Sabtu, operasi bersih-bersih asrama kami diganti dengan bersih-bersih dan menghias aula. Semua mahasiswi yang tidak ada jadwal kuliah atau keperluan di kampus wajib ikut membantu; ini merupakan tradisi turun-temurun dan Suster Eva mencatat siapa saja yang memang tak bisa ikut, jadi, kalau namanya tidak ada di daftar Suster tapi tidak tampak juga batang hidungnya di aula, bisa dipastikan nanti sore orang yang bersangkutan mendekam di dapur untuk memarut jahe!
Sambil meneruskan menyapu di sebelah selatan aula (sementara ada empat atau lima orang lain yang juga memegang sapu di berbagai sudut saking luasnya aula ini), aku celingukan mencari pertanda adanya pencuri juga si Fidelia yang pertama. Tak tampak pria gempal itu di mana pun—di lantai dan di kursi-kursi, paling tidak. Aku nyaris terbahak sendiri mendapati si Pengingat sedang nongkrong di ambang jendela yang terbuka.
“Tin!” panggilku pada Kristin yang sedang merangkai bunga dengan sekelompok anak yang lain. Dia mengangkat kepala dan aku menunjuk sekilas ke arah jendela.
Kristin tersenyum kecil melihatnya. Berikutnya, sama sepertiku, dia mengedarkan pandangan mencari gerak-gerik pencuri. Tapi kami tak menemukan apa-apa. Semua orang memang sedang bergerak di area kerja masing-masing. Pak Teguh si tukang kebun bahkan juga membantu memasang pot-pot kecil ke sebuah tiang hias yang akan ditempatkan di kiri-kanan panggung, sampai aku ngeri sendiri di dalam hati menyaksikan pria berumur itu memanjat-manjat tiang. Kulihat juga Andika, anak Pak Teguh yang masih SMP, mondar-mandir sambil mengangkuti barang-barang besar menggunakan troli.
Tiba-tiba saja, kudengar suara merdu si Bocah Hakim menyanyikan lagu Mary Had a Little Lamb dan dengan kaget kusadari dia sedang duduk di tiang penyangga langit-langit.
Dari tempat setinggi itu, aku tahu suaranya bakal menggema ke seluruh ruangan, tapi, siapa yang bisa mendengar? Hanya aku dan Kristin, setahuku, dan si pencuri—yang berarti sedang melakukan pencuriannya kalau Fidelia sudah sampai di pekerjaan yang kedua.
Kemudian, kulihat juga rupanya pencuri yang dimaksud: dua-tiga mahasiswi baru, warga asrama tahun pertama, sedang kasak-kusuk sambil membawa botol minum masing-masing—kami memang disuruh menyiapkan sendiri minuman secukupnya agar tidak dehidrasi, dan di akhir kerja bakti nanti akan ada logistik yang dibawa Bu Feni dan kawan-kawan ke aula.
Mereka tampaknya mengendap-endap berjalan keluar aula. Apa mereka mau kabur duluan dari kerja bakti ini? Segera mataku berkeliaran lagi, mencari sosok Suster Eva atau Rani, teman angkatanku yang jadi ketua panitia Dies Natalis. Yang kudapati malah Suster Caecilia, rekan Suster Eva yang diperbantukan di asrama selama mempersiapkan rangkaian acara Dies Natalis. Beliau lebih muda dari Suster Eva, lebih mendekati definisi milenial alias anak zaman now, dan beliau sekarang sedang tunduk meneliti ponselnya di dekat salah satu pilar di sisi timur aula.
Duh, rupanya anak-anak baru itu mencuri kesempatan saat Suster Caecilia sedang tidak mengawasi. Aku bergegas menuju ke sana, hendak terang-terangan menanyai mereka mau pergi ke mana. Masa ke toilet berombongan begitu? Ini pasti mau kabur. Pekerjaan masih banyak, halo!
Salah satu dari mereka, kalau tak salah namanya Anna, melihatku yang setengah berlari ke arah mereka, dan dia berbisik pada teman-temannya. Kupercepat langkahku sembari menghindari troli besar penuh pot tanaman tinggi-tinggi yang sedang didorong Andika. Di detik itu dia berhenti mendorong, mungkin karena melihatku mau melintas di jalurnya.
“Permisi, ya,” ujarku terburu-buru.
“Awas Kak—” seru putra Pak Teguh itu.
Aku tak melihat genangan air yang sudah separuh terlindas roda troli. Kakiku menginjak genangan itu, kemudian tubuhku seperti melayang dengan gerakan lambat sebelum jatuh dengan debam keras.
Aku baru sadar rasanya sakit ketika orang-orang sudah berkerumun dan bicara bersamaan.
“Ra? Kamu nggak apa-apa?”
“Aduh, belum sempat dipel dari tadi.”
“Apa sih yang tumpah di sini?”
“Bukan air dari pot-pot ini, kah?”
“Ashira. Kamu baik-baik aja?”
Aku benci ini. Mengapa rasanya familier sekaligus berbeda? Baru beberapa saat yang lalu Markus menanyaiku seperti itu, aku yang ada di posisi lemah seperti sekarang, tapi sakit yang ini terkonsentrasi di pantat dan telapak tanganku yang pertama-tama menghantam lantai. Suara-suara orang di sekitarku mengabur, digantikan sebuah suara parau yang menusuk telinga.
Kulihat si wanita Fidelia sedang berdiri di seberang ruangan, mulutnya berkomat-kamit dan buku di tangannya terbuka. Dia berdiri menghadap ke pintu. Para ‘pencuri waktu’ itu telah berhasil kabur di tengah keributan yang kuciptakan tanpa sengaja.
Kristin meraih tanganku dan aku mengerjap. “Kubantu berdiri. Kamu bisa?”
Aku mengangguk, mengembuskan napas panjang yang ternyata telah kutahan sedari tadi. Di bagian belakangku masih terasa nyeri yang berdenyut dan aku belum bisa langsung berdiri di usaha pertama. Kakiku lemas dan tanganku gemetaran. Jantungku berdebar-debar mengiringi reaksi tubuhku yang terlambat. Kudengar Suster Caecilia bicara pada Pak Teguh atau yang lain untuk menggendongku bila diperlukan.
“Nggak perlu, Suster,” tolakku. Kak Ribka ikut membantuku berdiri dan untungnya berhasil. Memalukan sekali kalau aku sampai harus digotong-gotong sampai kamar gara-gara terpeleset sedikit.
“Ini kenapa, ya, bisa ada genangan air di sini?” omel Suster Caecilia sambil berkacak pinggang. Alisnya yang tergambar rapi berkerut, mulutnya merengut.
“Kayaknya langit-langitnya bocor, Suster,” lapor Andika sambil mengamat-amati plafon.
“Oh, iya. Semalam hujan deras, ya.” Suster Caecilia kemudian menatapku. “Ashira, kamu istirahat aja, ya. Nanti biar makan siangmu diambilkan teman kamar.”
“Tapi, habis ini ada gladi resik untuk drama, Suster,” bantahku sok kuat.
“Ya, nanti biar Vira aja yang mendampingi latihan,” balas Suster Caecilia. “Ayo, Suster temani ke kamar.”
Apakah hanya perasaanku, atau Suster Caecilia juga enggan ikut bersih-bersih dan melihat ada kesempatan untuk menghindarinya berkat aku? Entahlah. Aku bukan si Hakim Fidelia. Biarawati pun seorang manusia.


 roux_marlet
roux_marlet