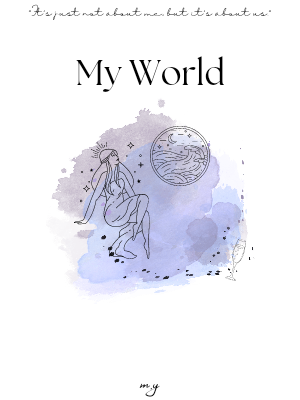Almira
Dua minggu terakhir berasa seperti duduk di ujung tebing.
Sedikit saja aku melakukan kesalahan, seluruh usahaku di posisiku sekarang akan runtuh seketika. Ingatan buruk dari pandangan mereka yang meremehkan kemampuanku terus mengejarku setiap kali aku berhenti untuk beristirahat. Jadi aku memutuskan untuk terus bekerja.
Bahkan panggilan telepon dari Mama selalu aku tolak dengan alasan sedang sibuk menyelesaikan proyek pertamaku. Padahal sebenarnya aku tidak ingin diingatkan lagi tentang Tante Tari atau siapa pun dari keluarga Mama sekarang. Aku hanya perlu fokus menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat dan semaksimal mungkin agar bisa bebas sepenuhnya dari cengkraman mereka.
“Ami, kamu butuh istirahat.”
Kak Felice menahan lenganku yang otomatis menghentikan gerakan tanganku di atas keyboard.
“Nanggung kak… Sepuluh bab lagi, deh!” tawarku.
Aku memandang dokumen yang sudah penuh dengan catatan rapat evaluasi konsep cerita. Satu lagi tahap yang harus aku lakukan sebelum naskah diperiksa kembali oleh Fandi dan akhirnya bisa dicetak. Jika mengikuti timeline project di awal, seharusnya di akhir minggu ini alias minggu ke-empat adalah proses pencetakan naskah.
“No,” jawab Kak Felice tegas. “Kalau editornya tidak fokus, hasil evaluasinya juga tidak maksimal. Banyak detail yang terlewat dan malah berakhir harus mengulang prosesnya lagi. Jadi, lebih baik lo istirahat dulu sebentar.”
Aku memandang jam di layar laptopku, masih dua jam sebelum waktu pulang. Aku pun menutup laptop lalu mengangguk, menyetujui nasihat Kak Felice.
Ia tersenyum lalu mengeluarkan dua energy bar dari kantung jaketnya. Ia menyodorkan satu ke arahku. “Nih, hari ini rasa coklat.”
“Thanks, kak.” Aku segera menggigit batang balok kecil di tanganku, mengingat kembali kapan terakhir kali aku merasakan makanan berat.
Aku merindukan makanan di lantai 26, tetapi terlalu sibuk untuk turun ke bawah saat makan siang. Andin bahkan sempat membawakan aku nasi goreng di kotak makannya tetapi aku hanya bisa menghabiskan setengahnya karena tidak memiliki selera makan. Sisanya aku bawa pulang dan menjadi menu makan tengah malamku. Setelah itu aku terlalu sungkan untuk menerima kotak makan siang darinya atau dari Luna dan Nisa. Aku berkilah kalau Kak Felice dan aku sudah memesan makanan pesan antar untuk makan siang.
Nyatanya? Antara aku mendekam di depan layar laptop sementara Kak Felice menyantap bekal makan siangnya. Tapi aku lebih sering bersembunyi di dalam bilik paling pojok kamar mandi di lantai kantorku. Meneliti setiap alur cerita naskah Mbak Dewi atau membaca naskah baru yang perlu aku sortir sambil menunggu Kak Felice selesai makan siang di bawah.
Pathetic, I know. Tapi demi hasil yang maksimal, semuanya akan aku lakukan.
Ruang rapat Doyle lengang sejenak. Hanya ada suara gemerisik plastik dan kunyahan energy bar di dalam ruangan. Entah sejak kapan ruangan ini sudah menjadi markas resmi untuk Kak Felice dan aku. Dari rapat online dengan Mbak Dewi untuk memastikan progress revisi, evaluasi naskah revisi berdua, atau bertiga jika Fandi sudah selesai mengoreksi naskah.
Tiga rapat tim terakhir juga dilakukan di ruangan ini. Ngomong-ngomong soal rapat tim, di dua rapat terakhir aku mendapati dua boks besar cinnamon rolls di atas meja. Saat aku menatap pria yang aku curigai sebagai pelaku, ia hanya menatapku memelas. Sepertinya ia ingin meminta waktu untuk berbicara padaku, atau mungkin untuk meminta maaf. Tapi aku selalu menghindar setiap kali ia terlihat ingin memulai percakapan denganku.
Kalau ditanya apakah aku akan memaafkannya, aku akan menjawab–
“So,” tegur Kak Felice tiba-tiba, menarik pikiranku kembali ke ruang rapat. “How is it going these days? Sudah sejauh mana lo beradaptasi dengan pekerjaan ini?”
“Sejauh mana ya …” Aku berpikir sejenak. “Kalau soal pekerjaan secara garis besar saya sudah mengerti dan cukup terbiasa sih, kak. Cuma mungkin kalau ada special case di dalam project selanjutnya, saya bakal butuh pertolongan dari kakak.”
Ia tertawa kecil, lalu beranjak dari kursinya setelah meremas menjadi satu plastik bekas bungkusan camilan kami tadi. “Of course lo bisa ganggu gue kapan aja.”
“Jadi saya mengganggu nih, Kak?”
“Nggak. Gue malah senang dapat anak bimbing yang banyak tanya semacam lo. Hidup gue di kantor jadi lebih rame aja, nggak melulu berkutat dengan bacaan naskah baru.”
Kini giliranku tertawa. “Kak Felice memang terbaik!”
“Lo harus lebih sering muji gue deh, Mi. Sebagai bayaran bimbingan gue sebagai mentor.”
Kami tertawa lagi. Suasana lengang yang melelahkan berubah menjadi menyenangkan. Perasaanku menjadi lebih ringan dan siap untuk fokus membaca naskah revisi ketiga dari Mbak Dewi. I think I really need a little rest.
Aku baru saja berniat membuka laptopku saat Kak Felice kembali bertanya. “Kalau dengan lingkungan kerja gimana? Lo nyaman, ada yang mengganggu lo?”
Sepertinya pertanyaan terakhir merujuk ke orang itu. Tapi aku tidak ingin memikirkan tentang dia saat ini. “Hm, sejauh ini sih nyaman. Tidak ada yang mengganggu secara langsung sih, Kak.”
Bahkan aku merasa pandangan menekan orang-orang di sekitarku perlahan menghilang. Entah karena aku sudah berubah kebal menghadapi pandangan penuh kekaguman berlebihan begitu juga dengan pandangan mencela dari beberapa orang. Atau karena mereka sudah lelah sendiri dengan sikap diamku selama ini.
“Then, that’s good.” Kak Felice tersenyum lagi. Aku bisa melihat kelegaan di wajahnya, sepertinya ia khawatir aku merasa tidak nyaman sejak insiden terakhir kali.
Ia melanjutkan, “Last word, Mi. Gue cuma mau mengingatkan kita bekerja dalam tim, bukan hanya gue dan lo, tapi dengan semua divisi. Jadi jika ada masalah, lo harus bisa mengkomunikasikan hal yang menurut lo harus diperbaiki dan bisa menerima hal yang lo harus perbaiki. Jangan menghindar dan hadapi semuanya.”
Seperti biasa Kak Felice terlalu peka dengan orang di sekitarnya. Aku tersenyum singkat lalu mengangguk.
“Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi sisa halaman yang perlu diperiksa.”
Jam menunjukkan pukul sembilan saat aku mencapai halaman terakhir naskah Perempuan Berambut Api. Tiga jam terlewat dari waktu pulang kantor seharusnya.
Aku meregangkan tangan lalu membangunkan Kak Felice yang terlentang di atas deretan kursi di sampingku.
Ia terperanjat dari tidurnya, mengerjap-ngerjapkan mata sebelum melihat jam di ponselnya.
“Lho, sudah jam sembilan? Gue sudah tidur lebih dari satu jam, kenapa lo nggak bangunin gue?”
Aku menguap. “Kakak kelihatan enak banget tidurnya. Saya jadi tidak enak mau bangunin.”
Ia menggelengkan kepala lalu beranjak dari tidurnya. “Ya udah. Lo sudah selesai cek sampai ending ceritanya kan? Menurut lo plotting ceritanya sudah aman, nggak ada detail misteri yang bocor di awal kan?”
Aku menunggunya duduk kembali sebelum menjawab. “Yup. Sedikit informasi tentang clue misteri di awal, lalu dialog-dialog yang mengarahkan kecurigaan ke beberapa tokoh juga sudah oke. Pengungkapan misteri di akhir sudah oke juga, ada unsur surprising tapi tetap masuk logika.”
“Menurut gue juga begitu…” Ia menjawab di tengah kuapannya. “Terus, menurut lo tokohnya sudah realistik? Apa ada tokoh yang karakternya perlu didalami lagi?”
Aku menggeleng. “Menurut saya sudah pas sih informasi tiap karakternya. Karakter Agni juga tidak tertutup tokoh lainnya, jadi sesuai dengan konsepnya sebagai tokoh utama.”
“Great! Then we’re done here!” Seru Kak Felice gembira.
“Kita beres-beres dulu sebelum pulang, yuk!” Aku menyambut ajakannya dengan semangat.
Akhirnya aku pulang, kasurku sayang!
Niatku untuk berlama-lama memeluk guling digagalkan alarm dari ponselku yang terus berbunyi. Dengan malas aku meraba meja nakas di sebelah kasur dan mematikan alarm. Seperti biasa, aku menyeret badanku untuk turun dari tempat tidur. Bukti aku ingin merasakan detik-detik terakhir dari hangatnya selimutku. Pagi ini lebih berat dari biasanya karena aku hanya sempat menghabiskan dua jam meringkuk di dalam selimut.
Setelah terduduk bersimpuh di lantai, aku mulai meregangkan badanku dimulai dari tangan. Lalu berdiri perlahan dan menaik turunkan kaki beberapa kali. Dengan kesadaran yang hampir penuh, aku berjalan ke kamar mandi tepat di pojok kanan kamarku lalu langsung menyiram wajahku dengan air dingin.
“Alright! Semangat penuh untuk hari ini!” Aku mengepalkan tangan ke hadapan cermin di kamar mandi, menyemangati diriku.
Itu adalah seluruh ritual yang aku lakukan setiap pagi.
Tentu diikuti dengan memilih baju yang cocok dengan suasana hatiku. Hari ini aku ingin terlihat percaya diri, jadi pilihanku jatuh pada celana merah maroon model pipa yang aku padukan dengan blazer berwarna senada dan blus putih. Aku mengikat setengah dari rambut hitam bergelombangku dan sisanya aku biarkan tergerai. Final touch, make up, lipstik merah dan eye liner lebih tebal dari biasanya. Tidak lupa aku mengeluarkan stiletto lima senti berwarna merah untuk aku kenakan. Voila!
Alarm ponselku berdering lagi, seakan menyuruhku untuk segera memesan ojek online dan berangkat ke kantor.
Aku melihat layar ponsel saat mematikan alarm dan mendapati kiriman gambar dari kedua orangtuaku yang berpose serasi dengan tangan terkepal lalu diikuti dengan pesan menyemangatiku hari ini. Ujung bibirku terangkat melihat ekspresi canggung Papa yang aku yakin dipaksa Mama untuk berpose seperti itu. I miss them.
Aku membuat catatan dalam hati untuk menghubungi mereka lewat video call hari ini. Setelah itu aku buru-buru keluar dari kamarku di lantai satu dan naik ke motor ojek online pesananku.
“Ami, lo udah di kantor aja.”
Sapaan Andin mengagetkanku yang baru saja sampai di lobi kantor.
“Kamu juga.” Aku melihat arloji di tanganku dan heran karena Andin sudah datang jam delapan. Tidak biasanya. “Tumben sudah datang pagi-pagi begini. Ada kerjaan?”
Ia menggeleng, lalu menguap. “Bukan. AC di apartemen gue mati, jadi gue buru-buru ke kantor buat ngadem.”
Aku lantas tertawa mendengar alasannya itu. “Seriusan kamu, Din?”
“Iyalah! Kalau panasnya Jakarta nggak disertai polusi udara yang tebalnya bukan main sih gue bakal santai aja buka jendela dan menikmati udara lantai sepuluh. Masalahnya sekali gue buka jendela gue langsung bersin-bersin seharian. So, no thanks. Lebih baik aku langsung ke kantor aja buat ngadem.”
Lift terbuka di lantai 27 dan kami segera berjalan keluar bersama.
Andin yang baru saja selesai menggerutu soal panasnya udara Jakarta segera duduk di sampingku. “Gue mau lanjut tidur dulu, Din. Bangunin gue satu jam lagi ya, gue mesti submit kontrak penulis ke mentor gue.”
Ia menguap lagi, menelungkupkan kepalanya di atas meja dengan lipatan kedua tangannya sebagai bantal lalu tertidur.
Aku ikut menguap. Tarikan dari meja untuk dijadikan alas tidur lebih kuat dari biasanya. Mataku semakin berat merasakan semilir angin pendingin ruangan. Kenapa aku jadi ikut-ikutan ingin tidur juga seperti Andin?
Untungnya Kak Felice datang di waktu yang tepat. “Pagi Ami! Hari ini kita rapat di ruangan biasa ya. Gue sudah kirim undangan email buat lo dan anggota tim lain, kan?”
“Sudah kak. Kemarin kan saya sudah kakak minta cek sebelum dikirim.”
“Oh iya juga, gue nggak fokus.” Ia mengangguk sembari memijit batang hidungnya. “Semangat deh, Mi! Habis rapat ini kita bisa tidur pulas sampai weekend selesai.”
“That’s exactly my plan, Kak!” Rencanaku adalah menikmati empuknya tempat tidur sepuasnya dan melanjutkan bacaan buku fiksi sejarah yang baru aku beli atau aku bisa menonton film animasi kesukaanku di Netflix. Semua tergantung dari lancar tidaknya rapat hari ini.
Ditambah faktor persetujuan ketua tim kami. Semoga Bu Eri menerima hasil editorial kami.
Kak Felice berjalan ke mejanya di baris ketiga dan langsung mengeluarkan kotak makan. Aku jadi teringat kotak makan kuningku yang terlantar di rak piring. Mungkin setelah proyek Mbak Dewi selesai aku bisa kembali memasak makan siang atau camilanku sendiri.
“Mi, lo sudah sarapan belum? Mau coba bubur gue nggak?” tanya Kak Felice sedikit berteriak.
“Tidak usah, Kak. Saya sudah makan kok.” Makan camilan tengah malam sebelum tidur kemarin, maksudnya.
Untungnya hari ini Kak Felice tidak peka seperti biasanya, karena dia terlihat sudah mengangguk-angguk sambil membuka kotak makannya yang berisi bubur. “Oke. kalau begitu gue makan ya!”
Aku mengacungkan jempol dari mejaku, menahan raungan protes dari perutku. Tidak, waktu luang ini bisa aku gunakan untuk memeriksa kembali catatan progress terakhir naskah sebelum aku memaparkannya di rapat nanti. Aku akan mengisi perutku nanti setelah selesai rapat.
Atau setidaknya begitu yang aku rencanakan.
Karena hal terakhir yang aku ingat setelah rapat ditutup hari itu adalah gelap.


 wrtnbytata
wrtnbytata