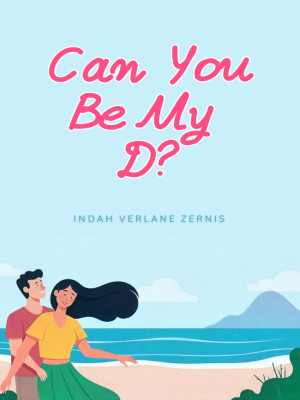Sebenarnya, sudah sejak lama aku mengumpulkan sebagian uangku untuk kukirimkan pada Nenek dan Kakek di Surabaya. Sekaligus berkeliling kota sendirian di malam hari. Mengunjungi Kenjeran dan jembatan barunya, bersantai di kaki jembatan Suramadu seraya meminum secangkir kopi dan menatap anak-anak kecil yang asyik bermain, serta berdiam diri di sudut kafe sambil menulis ataupun membuat sketsa.
Namun, setelah bertemu dengan gadis yang kini tengah membenarkan flat shoes atau bedebah namanya itu di belakangku, aku perlu berkali-kali mengingatkan diriku sendiri untuk bersabar. Tahun ini aku pergi bersamanya, sesuai perintah Ibu agar gadis itu tidak merasa kesepian. Sedangkan Ibu dan Kumala tetap di rumah, menyelesaikan pesanan jajanan tradisional orang-orang untuk dikirimkan ke warung-warung terdekat.
Kami sampai di stasiun Surabaya Kota dan berniat menunggu angkutan umum ketika ia yang di sampingku berkata, “Aku mau naik becak.”
“Hah?”
Ia menunjuk para tukang becak yang menawarkan tenaga pada para penumpang, tersenyum lebar. “Aku mau naik becak, Radi. Masa gak boleh?” Meski bertanya, ia tetap menarik tanganku paksa menuju salah satu dari tukang becak yang dengan sigap menghampiri kami.
“Becaknya, Mbak, Mas.”
Ia mencolek-colek pinggangku, menatapku penuh harap. Ternyata masih ada wanita yang sudi menaiki becak. Menghela napas, kutatap pria berkulit cokelat yang sekiranya berusia akhir empat puluhan di hadapanku. “Kapas Madya ya, Pak.”
“Oh, nggeh, nggeh, Mas. Monggo.” Di sampingku, Ara mulai menjejak pijakan dan naik di atasnya. Ia melebarkan senyuman menatapku yang memosisikan diri di sampingnya.
Melewati jalanan di depan Pasar Atom, ia menggerakkan mata menjamah setiap hal yang ia dapatkan. Beberapa kali ia melongokkan mata antusias seperti anak kecil sungguhan. Kutarik lengannya menyuruhnya diam. “Jangan lebay, ah.”
“Ih, ini kan pertama kali aku ke sini. Kenapa nggak boleh?” Ia mengerutkan keningnya dan kembali menolehkan kepala, menatap beberapa warga tionghoa yang berlalu-lalang di trotoar. Tak lama, ia memejamkan mata, lantas merangkul lenganku dan merangsek di sampingku. Sebelum kutarik tangannya agar membebaskan lenganku, ia malah semakin mempererat cengkeramannya. Matanya terbuka, menatap bangunan-bangunan lama dan baru yang berjajar di pinggir jalan. “Kamu tahu kenapa aku pilih naik becak?” Kutatap ia tanpa berniat menjawab. “Naik beginian jauh lebih leluasa menikmati Surabaya buat orang yang pertama kali ke sini seperti aku. Apalagi ada kamu. Setiap lekuk tubuh Surabaya dua kali lipat indahnya.”
Dari mana ia belajar mengatakan hal seperti itu? Aku perlu melengoskan muka dan menyumpahi jantungku yang lagi-lagi berdebar hebat. Bila sikapnya terus menerus seperti ini, sungguh tidak bagus untuk kesehatan jantung. Memori perihal malam itu merangsek secara tak sopan di pikiranku. Aku tidak berdusta soal kesalahan. Maksudku, memang salah. Tidak seharusnya kami seperti itu. Lihatlah, aku dan dirinya berbeda. Ia seperti jelmaan dewi yang diutus Tuhan ke bumi sedangkan aku hanyalah cacing yang menyembul keluar dari dalam tanah. Segala hal tentang kami berbeda. Ia pantas mendapatkan yang lebih baik dariku.
Jangan berbicara omong kosong yang klise dan menjijikkan seperti itu. Sebenarnya kau juga menginginkannya. Sudut pikiranku yang lain berkata begitu, semakin membuatku merasa aneh.
Kutatap ia yang masih mengedarkan pandangan ke segala arah. Berkali-kali kuperingatkan diriku sendiri bahwa ia hanya main-main. Termasuk dengan kalimat yang diucapkannya tadi. Ia pasti sering melakukannya untuk pria lain dan mantan-mantannya. Ia tidak akan serius mengatakan itu padaku.
Kalau dia memang serius, berarti kau perlu menyalahkan dirimu sendiri karena melihatnya seperti penjahat cinta. Lagi-lagi suara di dalam otakku berusaha mengacak-acak isinya.
“Jancuk.”
Refleks, Ara di sampingku menoleh dan mendelikkan mata. “Kamu misuhin siapa? Aku?”
“Hah? Enggak kok!”
Tangannya terkepal dan meninju lenganku. “Nggak ada siapa-siapa ya di sini. Kecuali kalau kamu lagi dongkol sama Bapak di belakang. Atau kamu ngambek gara-gara kuajak naik becak?”
“Ngaco deh, sumpah. Aku cuma capek aja,” dustaku. Ia mencibir dan melengos, kembali menggenggam telapak tanganku yang tetap terbuka tanpa membalas genggamannya. Perlahan kugerakkan tangan membalas genggaman itu. Ketika ia menolehkan kepala menatapku dengan pandangan tak percaya, kubuang muka menatap tempat lain. Apa pun selain bertemu matanya.
Ya, benar. Ini semua tidak salah. Ini semua benar.
***
Turun dari becak, Radi berjalan mendahuluiku dan menghambur masuk ke dalam rumah sederhana bernuansa cokelat itu. Ia melepas sepatu dan meneriakkan salam sebelum benar-benar masuk ke dalam. Dari dalam muncul sepasang tua dengan wajah menenangkan. Nyaris semua rambutnya telah beruban.
“Mak, Bapak, ini teman Radi. Aku disuruh Ibu bawa dia ke sini juga.”
Melepaskan masker, kuhampiri mereka berdua dan mencium punggung tangannya. “Panggil Elin saja, biar lebih enak.”
Wanita tua di sampingku tersenyum. Entah mengapa aura yang terpancar dari matanya mengandung kemisteriusan serta kemegahan asing yang membuatku merinding. “Nama yang cantik, secantik orangnya.”
“Di, ayo bikin kopi. Wis suwi ora ngopi bareng.” Di samping, Radi dibawa masuk ke dalam bersama Kakeknya dengan tawa membahana. Tinggal aku bersama Neneknya di sini.
“Nenek Mandalika, jaga-jaga bila Radi belum memberitahumu,” ujarnya tiba-tiba, mengundang tawa kami berdua. Meletakkan tas kamera di atas meja, kususul ia dan duduk di kursi kayu. “Mau Nenek buatkan minuman? Kamu pasti lelah.”
“Ah, tidak usah, Nek. Saya tadi sudah minum.”
Lantas, wanita itu kembali duduk. “Bagaimana? Betah tinggal di rumah Kinar?”
“Kinar?”
“Anakku. Ibunya Radi.”
“Ah ya, Tante Kinar. Betah, Nek. Suasananya asri sekali di sana,” ujarku, mengabaikan fakta bahwa wanita ini tahu bila aku menetap sementara di rumah Tante Kinar.
Tak lama, Radi memunculkan batang hidungnya bersama nampan dengan dua cangkir kopi dan dua gelas minuman dingin. Ia melempar pandangan padaku. “Minum dulu.” Lantas, ia kembali bergabung bersama Kakeknya.
“Kalau cinta, utarakan saja.” Menoleh, wanita itu memandangku dengan senyuman yang tak ia hilangkan sama sekali. Mengapa aku merasa ia mengetahui segala isi hatiku? Kukaitkan rambut ke belakang telinga, merasa rikuh oleh tatapannya yang tajam melebihi belati. “Terlihat dari matamu, Nduk.”
“Ah, apa sangat jelas, Nek?”
Tawanya membahana. Menyambar tanganku dan mengelus-elusnya, seperti layaknya nenek kepada cucunya. Ia menatap mataku lurus-lurus, tertegun, melirik sekilas pada telapak tanganku. Lantas melempar pandangan lagi padaku. “Pantas saja hawanya sejak tadi berbeda. Radi, anak itu, membawa pemilik calon kisah besar rupanya.” Kusunggingkan senyuman meski tak tahu maksud dari kalimat-kalimatnya.
“Dia anaknya jutek banget sama aku, Nek. Nggak ada manis-manisnya.” Kekehanku keluar, bersamaan dengan tatapan yang dilesatkan Radi dari arah depan.
“Raja Jalaludin Akbar bersikap jahat pada istrinya, Jodha, hanya karena belum menyadari bahwa ia telah sungguh mencintai istrinya dengan sepenuh hati.” Ia kembali mengusap punggung tanganku. “Mereka butuh waktu untuk menyadari perasaan masing-masing, Nduk.”
Memasuki senja, Radi dan Kakeknya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Berjalan masuk, Nenek Mandalika disambut rengkuhan suaminya dari samping. Dan pada saat itu, dunia seolah-olah berputar di bawah kakiku, membuatku kelimpungan ketika percakapan singkat mereka tertangkap pendengaranku.
“Dua calon bintang di langit kelam sedang diutus Tuhan. Takdir tengah menjalankan misi serupa tentara untuk negaranya. Kedua bintang itu akan bersinar terang ketika tiba hari di mana takdir menyelesaikan tugasnya.”
Di samping, Kakek itu menyahut, “Benarkah? Itu berarti, mereka akan menemukan hakikat abadi. Penciptaan mereka nyaris seperti ditiupkannya angin pada musim gugur. Ada untuk menjatuhkan daun-daun kering, hanya untuk menumbuhkan daun baru pada ranting-ranting.”
“Dan nama mereka akan disublimkan ke telinga-telinga menjelang terpejamnya mata. Dieja melalui bibir ke bibir, dan dikenang agar terus hidup pada gumpalan agar-agar di dalam tempurung.”
“Ya. Seperti itu.”
*
“Ajak aku ke spot-spot bagus, dong.” Radi, yang menyelonjorkan kaki seraya memainkan ponsel mengabaikan kalimat ajakanku. Fokusnya tetap tertuju pada gawai di tangannya.
Kuhampiri ia dan merebut ponselnya, membuatnya mendesis. “Kenapa sih? Balikin.”
“Kamu nggak dengar aku bilang apa? Ajak aku cari spot-spot bagus.”
“Enggak ah. Ogah. Capek.”
“Masa nggak ngapa-ngapain aja ngaku capek?!”
“Ya capek aja pokoknya. Balikin sini hapeku.”
“Nggak.” Kuposisikan ponselnya di depan mukaku. “Ada apaan sih kok kayak gak rela hapemu kuambil?” Mengintip isi pesan WhatsApp miliknya seperti waktu itu, kutemukan pesan yang sama dari kontak bernama Sara. Kendati kontakku tak ia lepas dari kontak yang tersemat, tetap saja batinku menggeruduk kesal. “Wah, Sara ini siapa sih? Pacarmu ya? Ngaku deh.”
“Enggak. Balikin, Ara.”
“No.” Kusembunyikan ponselnya di belakang punggungku. Kudongakkan kepala padanya yang berdiri tepat di depanku seraya berkacak pinggang. Mengembuskan napas, ia memilih berbalik dan kembali ke tempat tidur.
“Ya udah. Kalau gak mau balikin, aku juga gak mau ngajak keluar.”
Spontan kutempelkan ponsel pada dahinya, “Nih. Makan tuh hape!” Radi terbahak-bahak alih-alih mengaduh kesakitan.
Ia benar-benar ingin kutendang keluar!
Meski begitu, ia menepati kalimatnya dan membawaku entah ke mana. Berbekal motor milik kakeknya, kini aku bisa kembali duduk di belakang punggungnya seraya menghirup dalam-dalam aroma parfumnya. Seperti biasa, kuselundupkan tanganku pada saku jaketnya. Tersenyum usil, kudekatkan mukaku pada ceruk lehernya, mengendus-endus aromanya seperti kucing ketika mengendus makanan. Tak lama, ia bergidik geli.
“Kamu ngapain sih anjir? Geli ini.”
“Salah sendiri kamu wangi.”
Obrolan mati hingga ia memberhentikan motornya di tempat tujuan. Ada beberapa warung kopi yang padat pembeli. Kulempar tatapan pada anak-anak muda berpakaian mini yang berkumpul entah membahas apa. Radi membawaku pada warung dengan meja lesehan, sehingga kami dapat merasakan semilir angin malam dari laut dan pemandangan jembatan yang memanjang indah di depan sana. Untung saja ini bukan Jakarta. Bisa-bisa Mama akan menyeretku pulang bila mendapatiku nongkrong di warung pinggiran begini.
Ini pengalaman pertamaku. Dan aku akan sangat menikmatinya, bersamanya.
Kukeluarkan kamera dari dalam tasnya, lantas berdiri untuk mencari angle yang bagus. Kudecakkan lidah kagum melihat tangkapanku sendiri. Tak diragukan lagi, jembatan itu bukan lagi jembatan terpanjang, tapi juga indah. Lampunya yang bergerak menyala bergantian itu memanjakan mataku. Puas mendapatkan bidikan objek, aku kembali duduk di depan Radi yang menatapku lurus-lurus.
“Bagus, Di. Makasih ya.”
“Cantik.”
“Hah? Apanya?”
Di depanku, ia berjengit kaget dan membuang muka. “Suramadu. Cantik, kan?” Kuulas senyuman samar. Selagi ia memandangi laut, kupotret wajahnya dan membuatnya menolehkan kepala. Namun ia tak memprotes tindakanku. Tumben sekali ia?
“Dulu, aku sering ke sini sama Ayah. Tapi semenjak beliau nggak ada, aku nggak pernah lagi ke sini. Sebelumnya aku berencana ke sini sendirian sewaktu kunjungan ke Kakek Nenek. Tapi, rencana ternyata berubah. Ini kali pertama aku kembali lagi ke sini,” ia mengangkat kepalanya, memandangku, “sama kamu.” Kurasakan jantungku berdetak di luar kendali. Lantas, kuletakkan kamera di atas meja. Memilih memusatkan perhatian padanya.
“Kamu pasti kangen sama dia.”
Ia menatapku, lantas terkekeh-kekeh. “Ya iyalah. Anak mana yang nggak kangen sama bapaknya? Apalagi beliau udah sama Tuhan.”
“Tuhan pasti menjaganya, Radi.”
Kopi pesanan kami datang. Ia menjamah cangkir kopinya dan melingkarkan telapak tangannya di tubuh cangkir itu sebelum berkata, “Ayah selalu bilang ke aku untuk berani di setiap kondisi. Sewaktu anak tetanggaku menangis menjerit-jerit di samping mayat ibunya, Ayah bilang ke aku nggak boleh seperti itu.”
“Kenapa?”
“Nggak seharusnya kita menyikapi kematian orang yang disayang dengan sebuah tangisan. Karena memang bukan begitu cara kita merayakan kebebasan seseorang dari keterikatan duniawi. Aku nyaris nggak menangis hari itu. Tapi pada akhirnya aku luluh di bawah air mata Ibuku sendiri, Ra. Ternyata aku belum seberani itu.” Ia larikan pandangannya kepada laut lepas. “Ayahku mati dengan bekas luka tembakan di kepalanya selama masa perantauan, dan buat aku trauma dengan itu. Itulah kenapa aku mandeg tengah jalan.”
Jadi itu alasannya bergantung pada semua tulisan dan lukisannya. Kupandang ia dengan perasaan sesak. Melihatnya tertunduk menyembunyikan air matanya, aku beranjak memindah posisi di sampingnya. “Menangislah kalau kamu memang membutuhkannya, Radi.” Ia mengangkat kepala, menatapku. Detik berikutnya, kedua lengannya merengkuh tubuhku dalam pelukan erat. Tangisannya pecah dalam pelukanku.
***
Malamnya, aku berdiri di halaman depan mengulang bagaimana tanpa ragu-ragu kupeluk tubuh mungilnya dan menangis. Kukatakan padamu, aku menangis di depannya! Aku tak pernah menangis di depan orang lain selain Ibu dan Kumala. Dan tadi, aku bahkan tanpa berpikir dua kali memeluknya erat seperti itu, menumpahkan segala emosi dan rindu yang telah lama terpendam.
Tapi, aku lega. Meski aku merasa sedikit malu, di sisi lain aku lega karena pada akhirnya aku bisa menangis. Tak terhitung berapa lama aku tak menunjukkan sisi rapuhku pada orang lain. Sampai hari ini. Di depan gadis yang tak henti-hentinya membuat perasaanku diliputi hal aneh yang bahkan aku tak tahu sebutannya.
Keadaan di luar sudah sepi. Lampu-lampu teras tetangga lain sudah dimatikan. Berbalik, kututup pintu dan memilih masuk ke dalam. Aku berniat mengambil bantal di dalam kamar seperti yang biasa aku lakukan ketika kudapati Ara duduk menyelonjorkan kaki bersama laptopku di pangkuannya. Di telinganya sudah terpasang earphone.
“Kamu lagi ngapain?”
Menoleh, ia tersenyum lebar padaku. “Film kamu banyak lho. Udah nonton Bumi Manusia? Aku lagi nonton ini.”
“Udah baca bukunya. Belum filmnya.”
“Sini deh. Nonton sama aku.” Ia menyodorkan satu earphone kepadaku. Duduk di sampingnya, kuterima earphone itu dan memasangnya di sebelah telinga. Ia posisikan laptop di atas pangkuan kami.
Selama menonton, ia tak bergerak sama sekali. Sebenarnya, aku tahu bagaimana alurnya melalui buku yang kubaca. Namun aku bersedia menemaninya menonton. Sesekali ia mengumpat ketika tiba adegan yang membuatnya kesal. Namun, sebenarnya yang terngiang-ngiang di kepalaku adalah kalimat yang disublimkan Pramoedya Ananta Toer melalui Jean Marais.
“Cinta itu indah, juga kebinasaan yang mungkin membuntutinya. Orang harus berani menghadapi akibatnya.”
“Cinta itu indah, terlalu indah yang bisa didapatkan dalam hidup manusia yang pendek ini.”
Bahkan setelah film selesai dengan durasi selama itu, kalimat-kalimat itu berputar memenuhi kepalaku. Kupandangi gadis di sampingku yang menghela napas berat. “Ah, kok sad ending ya?”
Ya, benar sekali. Cinta itu indah, bahkan meskipun pada akhirnya akan binasa. Aku telah bertindak seperti pengecut dengan memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya bila aku mengizinkan perasaan ini tetap tumbuh. Aku hanya tidak berani menghadapi akibatnya dengan mengambinghitamkan kesalahan. Namun pada akhirnya bukan rasa yang salah, melainkan diriku.
Aku telah salah mengabaikan debar aneh yang selama ini kurasakan. Aku mengabaikan kalimat-kalimatnya. Aku mengabaikan perhatiannya. Aku mengabaikan segala hal tentangnya hanya agar tak terjatuh ke jurang terdalam. Bahkan yang lebih jahat lagi, aku telah menolaknya. Menghancurkan harga dirinya hingga tercecer di lantai.
Dan kali ini, aku akan memilih tindakan yang benar. Aku tak akan menyalahkan apa pun. Aku akan ada untuknya, sama seperti ketika ia ada untukku.
Kutatap ia yang tengah merenung dengan pandangan lekat-lekat. “Kamu ingat kalimat Jean Marais?” Tanyanya dengan bisikan pelan. Lantas, ia menoleh menatapku. Kuanggukkan kepala sebagai jawaban. “Kenapa kamu nggak bisa jadi manusia yang berani, Radi?”
“I’ll do it.”
“Do what?”
Kusematkan rambutnya ke belakang telinga, “Be brave for you.”
Untuk beberapa detik, ia menatapku tanpa berkedip. Lantas, ia menampar pipiku. Namun aku tidak mengaduh, semuanya memang salahku. “Kamu pernah nolak aku sekali ya. Dan kenapa ini tiba-tiba? Kalau niatmu mau ngerjain, mending kamu keluar sana dan jangan ganggu aku.” Ia menutup laptop dengan kasar, lantas meletakkannya di atas meja samping tempat tidur. Usai itu, ia merosotkan diri dan bersiap tidur membelakangiku.
“Maaf.” Ara tak berbalik meski mendengar suaraku. “Aku tahu kamu kecewa malam itu. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa, dunia kita beda.” Spontan, ia beranjak bangun dari tidurnya. Memelototkan mata padaku.
“Beda kamu bilang? Udah gila ya? Emangnya salah satu dari kita ini hantu? Emang bener ya, kamu ini pengecut yang bersembunyi di balik kata beda.”
“Iya. Oke. Aku tahu. Aku tahu aku sempat bertindak pengecut. Dan aku minta maaf atas kesalahanku, Ra. Tapi, kalau emang semuanya udah berubah di matamu, nggak apa. Kita bisa terus jadi teman seperti ini.” Kuacak-acak rambutnya sebelum beranjak berdiri. Aku tahu penyesalan semacam ini sudah terlalu terlambat. Oleh karena itu aku akan melepasnya bila itu memang keinginannya. Namun, ketika langkahku mencapai pintu untuk membukanya, kutemukan keberadaan tangan lain yang menutupnya mendahuluiku.
“Kamu beneran udah gila ya?” Tangannya terlipat di depan dada. “Gini aja deh, intinya, kamu menolakku?”
“Enggak juga. Tapi kalau kamu masih dendam sama aku soal malam itu, aku bisa mundur dan—” Kalimatku terpotong ketika satu tamparan—lagi—mendarat di pipiku. Ia benar-benar ingin membunuhku atau bagaimana?
“Goblok.” Ia mengembuskan napas kesal. “Kamu bahkan nggak tanya ke aku dan seenak jidat bilang aku nggak mau? Sumpah ya, manusia goblok di dunia ini ya kamu.” Ia mendorong keningku dengan telunjuknya.
“Aduh, Ra. Sakit,” bisikku gaduh.
Ia menatapku garang. Namun pada akhirnya memilih menyerah dan berjalan mendekat ke arahku. Tangannya merayap dari dada menuju pipiku. Dituntunnya kedua lenganku untuk memeluk pinggangnya. Mendongakkan kepala, ia berbisik di depan bibirku, “Kita reka ulang adegan malam itu. Kalau kamu mendorongku menjauh lagi, aku pastikan percakapan malam ini nggak akan terulang buat ke depannya.” Lantas ia raup bibirku dalam lumatan panjang sebelum aku sempat menjawab kalimatnya. Secara instingtif, kubawa ia semakin merapat pada tubuhku.
Aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama, Ara.
Kusublimkan kalimat itu melalui bahasa tubuh. Bahwa aku tak akan melepasnya. Bahwa tak akan kusudahi ciuman ini.
Ia mengalungkan lengan pada leherku, kurasakan tengkukku ditekan dan memperdalam ciuman kami. Kudorong tubuhnya hingga menempel pada pintu. Kulepas pagutan ketika ia mulai kehabisan napas. Dahi kami menempel satu sama lain dengan napas terengah-engah. Kularikan kecupanku pada kedua kelopak matanya.
“Kamu nggak bakal lagi tidur di luar, kan? Di luar dingin.”
Mata kami bertemu. Aku melepas tawa mendengar kalimatnya baru saja. Menghentikan tawa, kubelai pelan sebelah pipinya. “Sure. As you wish, my sugar bee.” Lantas kubawa ia dalam pelukanku. Selang beberapa detik, ia mendongakkan kepala lagi. Menatapku dengan mata anak kecil yang mengharapkan sesuatu. “Ada apa?”
“Bisa sekali lagi?” Pertanyaannya, yang meski singkat, tak mampu membendung tawaku untuk menyembur keluar. Detik berikutnya ia menggigit bawah bibirku merasa kesal. Kekehanku keluar sebentar di sela-sela ciuman kami.
Ketika ia semakin memperdalam pagutannya, kurasakan jantungku bagai genderang yang ditabuh. Ia menjelma seperti iblis yang tak main-main dengan mangsanya. Tak lama, ia melompat dan melingkarkan kaki jenjangnya di sekitar pinggangku yang dengan sigap kutangkap agar ia tak terjatuh. Kubawa tubuhnya dalam gendonganku dan kurebahkan di atas kasur. Kupandang kedua matanya di bawahku ketika kami melepas pagutan untuk mengambil napas. Tangannya terulur membelai pipiku. Bibir kami kembali bersinggungan.
Kini, aku akan dengan berani mencintainya dengan segala hal yang membuntut seperti sebuah ekor di belakangnya. Tentunya tanpa sederhana.
*
Ruang tamu Nenek dikunjungi oleh kawan lamaku yang juga bagian dari kampung ini. Setelah mengetahui bahwa aku menyempatkan diri ke sini, ia mampir dan mengobrol ngalor ngidul. Sedangkan Ara yang merasa diabaikan memilih berada di dalam bersama Nenekku. Kawanku, Sapta, bersama rokok di apitan jarinya yang menyadari keberadaan gadis di rumah, melongokkan kepala penasaran.
“Heh, itu siapa? Pacarmu?”
Menolehkan kepala, kulihat Ara yang tertawa bersama Nenek di depan televisi. Lantas kuanggukkan kepala pada Sapta. “Iya.”
Kudengar suara Kakek membahana. “Gitu aja kemarin Bapak tanya nggak ngaku dia, Sap. Katanya cuma teman.”
Memang teman. Kami adalah teman sebelum menit-menit perdebatan tentang perasaan semalam yang membuat apa pun yang kami rasakan semakin tumbuh. Kami memang teman, sebelumnya. Sesudah ini, aku tak yakin akan melihatnya hanya sebagai teman. Kecuali teman hidup.
“Kamu kapan pulangnya, Di?”
“Belum tahu. Besok kayaknya.”
“Udahlah di sini aja seminggu ke depan.”
“Matamu.”
Tawa Sapta membahana di dalam ruangan. Mendapati sekotak soliter di atas nakas, Sapta menyambar benda itu dan mengajak kami memainkannya. Di sela-sela permainan kami, Ara dan Nenek merangsek bergabung bersama kami sekadar menonton, lalu pada saat itu Kakek mengatakan kalimat-kalimat yang hampir tak lagi kudengar di telinga. Sewaktu kecil, samar-samar kuingat bahwa Kakek dan Nenek berbicara tentang sesuatu yang gagal kumengerti di usia sekecil itu. Jangan berharap lebih, bahkan di usia ini aku yakin aku gagal memahaminya.
Kartu Kakek menunjukkan delapan keriting. Ia berkata, “Dan lalu, kidung para malaikat yang ditiup ke bumi serupa doa-doa manusia yang dilepas ke langit bebas. Tuhan mendengarnya, dan kemudian Dia gerakkan tangan-Nya.”
Sapta memandang Kakek dan aku bergantian. Kuberi kode padanya agar diam saja dan melanjutkan permainan. Di samping Nenek, Ara menatapku dengan alis terangkat naik. Kakek dan Nenek seperti memiliki bahasa pribadi apabila pembahasan mereka bersifat rahasia. Itu masih dugaanku. Memangnya apa lagi alasan di balik terlontarnya kalimat-kalimat janggal itu selain pesan rahasia?
Baru saja kupikirkan, suara Nenek dari samping Ara yang memandang kami lurus-lurus terdengar. “Bukan tanpa alasan Tuhan meniupkan ruh melalui puncak ubun-ubun mereka. Kini, kedua bintang itu menerima kemilau yang sama sekali asing. Tanpa bertanya pada Tuhan dan malaikat eksistensi akhir yang menjelma mata-mata di ujung jubahnya.”
Permainan masih berlanjut dengan kalimat janggal mereka. Kukulum senyuman melihat ekspresi Ara yang ketakutan di sana. Kartu Kakek menunjukkan tiga belas hati. dan ia tertawa, membahana, bahkan aku dapat melihat kilau bahagia di matanya. Lantas ia kembali berkata, “Bahkan pintu-pintu surga dan neraka terbuka. Para malaikat dan iblis melayang mengabarkan pada Tuhan dari dimensi ketiadaan bahwa sepasang kejora tengah menerima ikatan tali kekang-Nya. Terbentuk untuk masa depan dan berjalan ke belakang. Yang mengejutkan adalah mereka yang tidak kebingungan.”
Permainan berakhir dengan kemenangan berada di tangan Kakek. Usai itu, aku meminta ijin kepada Nenek membawa pergi putri cantiknya untuk kuajak jalan-jalan. Wanita itu memberikan Ara kepadaku lengkap dengan senyuman penuh artinya. Berjalan menuju motor, ia menarik kemejaku dan menghentikan langkahku. “Kakek sama Nenekmu tadi ngomongin apaan sih? Kemarin aku juga begitu. Dan nggak bisa memahami kalimat Nenekmu.”
Kularikan jemariku mengusap bibirnya, mengecup sudutnya sekilas. “Nggak apa-apa. Mereka memang misteri yang nggak bakal bisa dipecahkan.”


 valentina
valentina