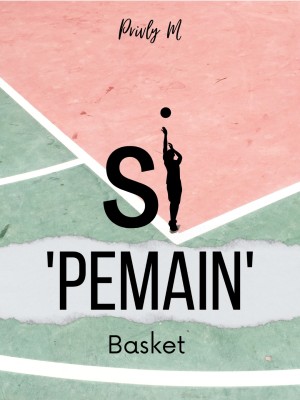Kami kembali pulang setelah lewat tengah malam. Melewati jalan Tanggulangin dan sepanjang tembok besar di samping rel kereta, aku dibuat penasaran dengan bangunan itu. Namun kusimpan pertanyaanku untuknya nanti. Sama seperti sebelumnya, Radi dan Dirja berpisah di persimpangan.
"Tadi, tembok panjang sepanjang jalan apaan?" Tanyaku di dekat telinganya.
"Tembok apaan?"
"Yang tadi. Habis lewat rel kereta, Rad."
"Etdah itu bukan tembok. Itu tanggul lapindo. Masa nggak tahu?"
Lapindo? Sebesar itu? Kudecakkan lidah beberapa kali. "Ternyata itu yang namanya lapindo. Kok makin luas ya?"
"Ya iyalah. Lumpurnya nggak berhenti keluar." Kami sampai di rumah dengan keadaan sunyi senyap seperti biasa. Membuka pintu, ia bersuara pelan, "Sampai sekarang pun belum ditemukan caranya biar lumpur panas itu berhenti."
Memang. Dulu, pada tahun terjadinya semburan, aku masih ingat betapa kurasakan kemalangan para korban. Tanpa tahu letaknya, aku bergidik ngeri melihat semburan itu. Namun, dari waktu ke waktu, berita perihal semburan lumpur panas tersebut tak lagi terendus media. Pemerintah memutuskan angkat tangan lantaran tak ada cara yang bisa digunakan. Sementara itu, korban-korban masih banyak yang menuntut keadilan.
"Aku penasaran. Kalau tanggul itu jebol, apa tragedi bakal terulang lagi?" Bisikku lirih bertepatan ketika Radi mengambil bantal.
Ia mengamatiku sejenak. "Itu kalau, Ara. Tapi, ya, semua orang akan melihat pengulangan tragedi." Lantas, ia menyambar bantal dan keluar dari kamar.
Kini, aku seorang diri di dalam sini. Kulepas ikatan rambutku dan membuka-buka koper. Mencari baju tidur. Mendapatkannya, kulucuti pakaianku dan menggantinya dengan baju tidur. Usai itu, kuhempaskan tubuhku di atas kasur. Kupandangi ponsel dalam genggaman. Menimbang-nimbang untuk membuka akun media sosial atau tidak. Menggigit bawah bibir, kuhidupkan data seluler. Tak lama, pesan-pesan WhatsApp memberondong masuk dan meramaikan ponsel itu seketika.
Kuputar bola mata dan membuang napas. Kenzo, Mama, Papa, Anastasia, Marcell, dan beberapa kawan-kawanku. Mengabaikan pesan-pesan mereka, aku justru membuka pesan dari Papa dan membacanya.
Sweety Daddy: Zeline sayang. Hubungi Papa kalau kamu sudah merasa lebih baik ya.
Kularikan jemari membalas pesannya.
Reply: Zeline baik di sini. Sekarang aku lagi di rumah teman, dan belum terendus media.
Tak lama, keterangan di atas menunjukkan bahwa ayahku itu online.
Sweety Daddy: Papa boleh menelepon kamu?
Usai menimbang permintaannya, kudesahkan napas dan menekan opsi call. Tak sampai deringan ketiga, sudah kudengar suara Ayahku dari seberang sana.
"Zeline, astaga. Papa rindu banget, Nak. Kamu baik-baik saja? Kamu makan dengan baik?"
"Iya. Zeline di sini jauh lebih baik. Papa sama keluarga nggak perlu khawatir."
"Meskipun Papa nggak tahu keributan seperti apa yang terjadi denganmu dan Mamamu, maafkan dia ya. Papa tahu terkadang dia bersikap menyebalkan."
Kalimat Mama hari itu terputar kembali memenuhi pikiranku. Kularikan pandangan menuju langit-langit kamar. "Iya, nanti." Embusan napas Papa terdengar. "Pa?"
"Iya, Zeline?"
"Papa percaya cinta?"
Tawa ayahku berderai dan sampai di telingaku. "Tentu saja Papa percaya, Sayang. Kenapa memangnya?" Lucu sekali dustanya itu padaku. Aku tahu ia berbohong. Tetapi aku tak bertanya lebih lanjut. Detik berikutnya, suaranya terdengar lagi. "Zeline, apa kamu sedang jatuh cinta?"
Apa ia bilang? Bualan macam apa itu? "Enggak tuh. Papa sok tahu, kebiasaan."
Tawanya terdengar lagi, lebih membahana. Mana mungkin aku jatuh cinta. Lagipula, dengan siapa? Tawa Papa berhenti. Ia berdeham sebelum berkata, "Justru bagus kalau kamu jatuh cinta, Sayang. Tapi, cinta juga nggak selamanya indah. Sama seperti sebuah keputusan, cinta itu paket lengkap dengan semua risikonya."
Mataku memanas dan dadaku sesak, entah mengapa. Kukedipkan mata berulang kali agar tak menangis untuk saat ini. "Ya. Salam untuk Mama dan Kenzo ya, Pa. bilang kalau Zeline baik-baik aja."
"Iya, Sayang. Jangan terlalu lama di sana sendirian."
Mataku tertuju pada lukisan-lukisan di dinding ataupun di dekat meja. Kalimat Mama, Papa, dan wajah Radi terlintas mengacak-acak isi pikiranku. "Zeline nggak sendirian, Pa." Tak kusangka-sangka, air mataku jatuh membasahi pipi dan berakhir di atas bantal. "Aku tutup dulu ya. I love you."
"I love you too, Darling." Lantas, sambungan kuakhiri secara sepihak. Memilih untuk kembali offline.
Turun dari ranjang, aku berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Kupikir Radi sudah tertidur di ruang tamu sama seperti sebelumnya. Namun, tak kutemukan keberadaannya di kursi panjang. Ia berdiri bersandar pada birai pintu. Dari ponselnya yang tergeletak di atas meja, mengalun lembut sebuah lagu. Menyadari kehadiranku, ia berbalik badan. "Kok belum tidur?"
"Zeline, apa kamu pikir Mama menikahi Papamu dulu karena cinta?"
"Sama seperti sebuah keputusan, cinta itu paket lengkap dengan semua risikonya."
Kalimat-kalimat itu terputar kembali. Aku bahkan tak tahu ketakutan semacam apa ini. Dadaku sesak setiap kali mengingatnya. Yang pasti, satu kata itu kini di mataku, menjelma sesuatu yang cantik namun juga menyimpan kengerian.
"Ada apa?"
Bagaimana kalau tanpa kuduga-duga, aku akan jatuh cinta dan merasakan pedihnya? Tapi, bukankah sama seperti kalimat Papa, cinta memang memiliki risiko apa pun bentuknya? Kini, aku berdiri seperti anak kecil yang takut pada sesuatu. Sesuatu yang bahkan tidak ia tahu.
"Ara?"
Satu air mataku menetes. Kuangkat kaki berniat berjalan. Namun justru aku tengah menyeret kakiku menuju pemuda yang kini menatapku bingung di ambang pintu. Detik berikutnya, aku berjalan cepat menuju padanya.
Menubruk tubuhnya dengan satu pelukan erat dan dada sesak.
***
Beberapa buku dan sumber yang berbicara perihal berhentinya waktu sudah pernah kucumbu semua. Namun aku sering tidak percaya dengan teori itu. Dimensi mana yang bisa menghentikan waktu?
Namun, detik ini, malam ini, otakku yang—sok—rasional ini menemui kehancurannya. Aku perlu menyadarkan diri selama lebih dari dua puluh detik membingungkan itu dengan keterkejutanku sendiri lantaran dihadiahi sebuah pelukan erat. Kukatakan padamu sekali lagi, ini erat sekali. Aku bahkan merasa bahwa ia tengah dipinjami kekuatan Wara Srikandi.
Kurasakan adanya air mata yang merembes di bajuku. Ia menangis?
Suaranya yang sesenggukan menjawab pertanyaanku. Meski ragu, pada akhirnya kuangkat tanganku dan mengusap rambutnya perlahan. Diam-diam aku berdoa agar ia tak mendengar detak jantungku yang berdetak demikian hebatnya ini. Tak lama, ia mengangkat kepalanya dan memandangku. Bulu matanya yang lentik itu basah oleh air mata.
"Kamu kenapa sih?"
Matanya berkedip sekali, lantas pelukannya pada pinggangku mengendur. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Maaf," ujarnya. Lantas duduk di depan pintu. Matanya menjelajah keadaan di luar yang sunyi senyap selain suara jangkrik. Kuposisikan diri di sampingnya pula.
"Kalau mau cerita, cerita aja."
Ia menatapku beberapa detik, seolah-olah menimbang untuk membuka suara atau tidak. Lantas, ia melempar pandangan pada langit dan mengembuskan napas. "Aku nggak tahu." Lah? Ada apa dengannya? Ia menangis seperti anak kecil yang ketakutan namun mengaku tak tahu alasannya apa. Dia gila atau bagaimana? "Mungkin aku lagi kangen Papa. Mungkin juga aku lagi kecewa, atau bisa juga... khawatir. Aku nggak tahu. Cuma lagi pengin nangis aja."
"Itu namanya gelisah."
Ia mendesah, mengusap lengannya yang kedinginan. Setelah beberapa detik terdiam, ia mulai membuka suara. "Ada sebuah kalimat yang tiba-tiba bikin aku takut pada hubungan, Di." Pada akhirnya ia berani bercerita. "Aku bahkan takut mengambil risiko yang mungkin udah Tuhan sisipkan."
"Memang itu tujuannya, kan?"
"Apa?" Tatapannya ia lempar padaku dengan kening mengerut dalam.
"Itu, apa yang Tuhan sisipkan bahkan di setiap celah terkecil." Malam semakin menusuk-nusuk kulit. Apalagi di daerah dengan tumbuhan di mana-mana ini. Dinginnya justru berkali-kali lipat. Namun, untuk sejenak rasa dingin itu berkurang karena keberadaannya. "Tuhan harus menyelipkan suatu kejutan hanya untuk emosi manusia. Dan kita diciptakan memiliki emosi, Ara. Kalau kita tahu apa yang disiapkan Tuhan dan mengintip dari lubang pintu, kita nggak akan bisa merasakan entah bahagia entah sedih pada akhirnya. Bila kejutan itu menyedihkan, maka tujuannya memang untuk membuat kita menangis. Dan juga sebaliknya. Itu akan selalu menjadi hukum alam, Ara."
Ia mengamatiku tanpa berkedip, mencoba mencerna setiap kalimatku. "Jadi maksudmu, kita hanya perlu mengikuti jalannya?"
Tersenyum lebar, kuanggukkan kepala menjawab pertanyaannya. "Yap. Jadi kenapa harus terlalu dipikirkan?" Sebelum sempat ia membuka suara, bibirnya terkatup lagi. Matanya bergerak pada ponselku yang tergeletak di atas meja. Aku bahkan tak tahu sudah berapa buah lagu yang kuputar dari aplikasi YouTube. Mata gadis itu melebar, diikuti senyumannya.
"Kamu bisa dansa?"
"Heh?" Meski tak mengerti, kugelengkan kepala menanggapinya.
"Ini, lagunya. Dengerin deh. Musik ini biasanya kubuat dansa sama Papa." Detik berikutnya, ia menggenggam tanganku dan diajaknya berdiri. Meski bingung, aku menurut saja ketika satu tanganku ia tuntun pada pinggangnya, sedangkan yang satunya ia genggam. Ia berkata pelan di depan bibirku. "Dalam berdansa, perhatikan posisi bahu dan punggungmu. Tegak, dan jangan terlihat membungkuk." Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, kuturuti semua instruksinya. Sebenarnya, aku sedikit memahami gerakan-gerakan ini melalui film-film yang kutonton. Namun, kubiarkan saja ia mengoceh dan bertindak sebagai guruku. Kuulas senyuman samar. Ia mengangkat muka, matanya bersirobok dengan mataku. "Sekarang, pimpin aku."
Mulai kugerakkan kaki ke depan, ke samping kanan, mundur lagi, dan bergerak kembali ke samping kiri. Terus begitu dan berulang. Senyumanku tersungging begitu saja. Perhatianku tidak terfokus pada gerakan, melainkan matanya. Mata yang mungkin menandingi mantra sihir di dunia ini. Serta bibirnya yang serupa kuncup bunga mawar merah. Kujatuhkan ia ke depan dan menahan punggungnya. Mulutnya terbuka dengan senyuman lebarnya.
"Lihat deh. Kamu bisa!" Bisiknya gaduh. "Aku curiga kamu udah belajar banyak sebelum ini."
Kuangkat bahu dan mencebikkan bibir. "Sedikit."
"Praktiknya sama siapa?" Tatapannya dilesatkan kepadaku serupa cakram yang siap menebas leherku.
"Kok kepo?" Desisannya keluar mendengar balasanku. Kutahan tawa agar tidak menyembur dan membangunkan seisi rumah.
"Sekarang kamu bikin aku yakin kalau kamu pernah pacaran." Mendengar itu, spontan aku tertawa tertahan dan mendapatkan pelototan mata darinya. Dari mana ia mendapat pemikiran gila seperti itu? Jangankan melirik gadis desa, keluar rumah untuk bergaul saja jarang.
"Iya, pernah. Sama setan."
Ia mencubit tengkukku, membuatku mengaduh. Musik berganti dengan lagu Payung Teduh. Senyumannya mengembang. Ia menoleh sejenak melirik ponselku di sana. "Wah, Payung Teduh. Pas banget." Tepat ketika ia memalingkan muka, kuhapus keberadaan senyuman itu dengan bibirku.
Kuabaikan pikiran warasku yang mengatakan bahwa aku telah bertindak gila. Namun, aku malah membenarkan cara ini dari sudut lain pikiranku. Kutunggu ia menarik diri dan melayangkan tamparan. Tetapi justru kedua tangannya merayap menyusuri bahuku dan berakhir pada tengkukku, menekannya seolah-olah mengatakan agar tidak mengakhiri ciuman tak berkesudahan itu.
Untuk kali pertama dalam hidupku, kutemukan suatu malam yang hangat.
***
Ini sudah putaran kesepuluh dan aku sama sekali tidak memilih istirahat. Napasku terengah-engah di balik masker. Keringat mengucur deras dari dahi turun ke leherku. Selagi aku menyalurkan kekesalanku dengan berlari tanpa henti, Radi dan Kumala memilih beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Kakiku yang lelah tak merasakan lelahnya lantaran teredam hatiku yang terluka.
Baiklah, mari kita putar kejadian yang membuatku sebegini frustrasinya.
Dini hari tadi, ketika aku dan ia berdansa di ruang tamu, aku seakan-akan dibawa menyelami dunia yang sama sekali baru. Seiring mataku memejam dengan bibir kami yang bersinggungan, aku bahkan merasakan ketenangan surga beserta aroma padang bunganya. Perutku mendadak bagaikan dikelilingi kupu-kupu. Ketika kurasakan kakiku melemas, kukalungkan lenganku pada lehernya.
Dan aku dibuat begitu kehilangan ketika ia tarik wajahnya dariku. Bukan wajahnya saja, tetapi tubuhnya pula! Aku bahkan belum sempat mengatur pernapasanku yang memburu ketika ia berkata pelan, "Ra, ini salah."
"Kenapa?" Lengkap sudah terkuburnya harga diriku ke dalam dasar jurang paling dalam dengan melempar pertanyaan itu, bahkan setelah ia dengan tak berperasaannya melepas pagutannya.
"Nggak seharusnya kita kayak begini." Kepalanya ia tundukkan. Tak berani menatap mataku. Hanya Tuhan yang tahu apa isi kepalanya saat itu. Ia mengusap wajahnya gusar, "Maaf. Aku terbawa suasana."
Terbawa suasana ia bilang? Kurang ajar sekali. Tahu begitu detik ketika ia menjamah bibirku, kutendang saja ia. "Di—"
"Sebaiknya kamu tidur. Kumala ngajak lari pagi nanti."
Kutatap ia dengan pandangan terluka. "Kamu gila?" Bisikku di depan mukanya. Ia melemparkan pandangan ke arah lain, selain mataku tentu saja.
"Masuk ke kamar, Ara."
Ini benar-benar memalukan, kukatakan kepadamu. Menahan umpatanku untuknya agar tidak menyembur keluar dan berakhir membangunkan Ibu dan Kumala yang tengah tertidur, kutendang kakinya dan mendorong bahunya, membuat punggung pemuda itu menghantam dinding. Lantas, kuangkat kaki enyah dari hadapannya. Ia yang mencium, ia pula yang menolakku. Ketidakwarasan macam apa ini! Tapi, jangan panggil aku Zeline Arabella Ranupatma bila aku menyerah semudah itu. Ini baru permulaan, kau harus tahu.
Membanting pintu, kuhempaskan tubuhku di atas kasur sambil bersumpah di dalam hati akan menaklukannya, sampai mampus bila perlu. Kuhabiskan sisa dini hari itu dengan mata yang terjaga sampai pagi.
Kini, demi memuaskan rasa kekesalanku padanya, aku berlari lebih dari sepuluh putaran—tanpa henti—seraya memikirkan apa saja yang ia lakukan untuk membunuh harga diriku itu. Ia dan adiknya mengamatiku yang tetap berlari tanpa berhenti di bawah pohon. Kumala melemparkan senyuman lebar padaku. Sedangkan ia mengamatiku dengan ekspresi tak terbaca. Aku melengos tanpa melihatnya.
Baru saja aku melewati posisi mereka, lenganku ditarik seseorang. Menoleh ke belakang, kudapati Radi yang menatapku dengan kernyitan di dahi.
"Kamu perlu istirahat, Ra."
Mengangkat alis, kulirik tangannya yang mencengkeram lenganku. "Lepas. Ini sakit."
Meski tak melepaskannya, ia mengendurkan cengkeramannya seraya menatapku tak main-main. Sebelum aku—dengan kekeraskepalaanku—berbalik dan kembali berlari, tangannya merayap dan beralih menggenggam tanganku, menyeretku bersamanya.
"Kumala, ayo pulang!" Ia berseru memanggil adiknya. Gadis itu berdiri dan menghampiri kami. Meski raut wajahnya diliputi rasa penasaran, namun ia tetap tak berkomentar apa-apa.
Kami berjalan kaki untuk pulang. Kutarik tanganku dari genggamannya. Tanpa mengatakan apa pun, ia berjalan mendahului di depan. Di sampingku, gadis itu berbisik agar tak tertangkap pendengaran Radi. "Kalian berantem?" Kutempelkan telunjuk pada bibir menyuruhnya diam. Sedangkan Kumala hanya meringis.
Kami sampai di rumah lebih awal dan segera bersiap untuk pergi bersama kawan-kawannya Radi sesuai rencana semalam. Ketika aku membongkar-bongkar koper mencari baju ganti dan menyiapkan kamera untuk berjaga-jaga, Radi ikut membongkar isi lemarinya tanpa bersuara. Aku benci suasana seperti ini. Tak lama, Kumala melongok di ambang pintu.
"Mas Radi mau ke mana? Kencan ya?"
"Kalau ngomong jangan ngawur."
Kutaruh tas kamera di atas meja. "Ajak ajalah adikmu."
"Boleh?" Kumala menyambar, antusias.
"Boleh, dong. Ganti baju sana." Mendapatkan persetujuanku, Kumala berlari gesit dan menuju kamarnya untuk menyiapkan diri. Kuamati wrap top putih sebatas lengan dan Jamaica short yang kubaringkan di atas kasur. Lantas, aku berdiri menghadap Radi yang memainkan ponsel di depan lemari dengan pakaian yang disandarkan pada bahunya. "Kamu mau tetep di sini dan gabung ganti baju sama aku?"
Menoleh, ia berdecak kesal dan meletakkan ponsel di atas meja, lantas angkat kaki dari sana. Sepeninggalnya, kukulum senyuman samar. Aku mendesah lega di depan kaca lantaran dipertemukan kembali dengan pakaian kesayanganku. Melepaskan ikat rambutku, kulirik ponsel Radi yang ia tinggalkan di atas meja. Boleh, kan, aku iseng sebentar? Boleh, dong.
Kujamah ponsel itu—yang untungnya tidak terkunci sama sekali—dan membuka aplikasi WhatsApp. Tidak ada yang spesial. Aku bahkan sempat tak percaya bahwa pemuda itu jujur perihal tak pernah pacaran. Kucari opsi tambahkan kontak dan mencatat nomorku sendiri di dalam sana. Kikikan geliku terdengar ketika kukirim pesan pada nomorku dan kusematkan. Kularikan mataku melihat pantulan diriku sendiri di depan cermin, lantas mengangkat ponsel di depan wajahku dan menangkap satu potret. Usai mengunggahnya di status, tak lama, ada satu kontak perempuan yang membalas unggahan itu.
Sara: Siapa ini, Rad?
Namun aku tak sempat membacanya lantaran suara ketukan di pintu terdengar. Cepat-cepat kukembalikan benda itu ke tempatnya berasal.
"Kamu ganti baju atau simulasi mati, sih? Lama amat."
"Udah!"
Tak lama, pintu terbuka dan menampakkan sosoknya dalam kaus hitam berlengan panjang dan celana sebatas lutut. Ia mengamatiku seraya mengangakan mulut. "Kenapa sih hobimu pakai celana pendek?"
Kuputar bola mata dan mencibir di depan mukanya. "Nggak usah banyak omong ya. Kita masih marahan." Kukalungkan tas kameraku pada lehernya dan mendengar desahan putus asanya sebelum aku beranjak pergi dari sana.
***
"Eh, Dirja, fotoin aku di sini dong!" Gadis itu berseru menghampiri Dirja dan menyodorkan kamera padanya, lantas melangkah di antara tetumbuhan teh, berpose. Bagaimanapun gayanya berfoto, ia tetap terlihat menawan. Mungkin karena pekerjaannya sebagai model. "Lagi, Ja!"
Kudecakkan lidah dan menghampirinya, lantas memasangkan masker menutupi wajahnya. "Jangan sembarangan. Di sini banyak orang." Lantas kutinggalkan ia mendesis di belakang.
Kami naik ke atas jalan yang terbuat dari kayu. Membentuk sebuah persegi di tengahnya. Di setiap sudutnya terdapat persegi kecil yang dilengkapi kursi untuk bersantai. Dari sini dapat kulihat pemandangan serba hijau sejauh mata memandang. Di sampingku, Ara sibuk memotret sana sini. Dari kami berlima, hanya adikku dan dirinya yang antusias. Mirip anak kecil yang baru dibelikan sebuah mainan. Sesekali gadis itu meminta Pras atau Dirja memotretnya bersama Kumala. Senyumanku terulas samar. Ia berjalan menghampiriku dan mengangsurkan kameranya.
"Fotoin kita berempat, dong." Senyumannya melebar, menghapus keberadaan senyumku seketika. Meskipun begitu, kuturuti permintaannya dan membidikkan kamera pada mereka berempat. Kuambil beberapa jepretan dengan pose yang berbeda-beda. "Bentar. Satu lagi. Fotoin kita bertiga!" Kualihkan kamera dari depan wajahku. Apa pula maksudnya itu? Sementara Kumala berjalan menjauh melihat-lihat, Ara menyiapkan pose bersama Pras dan Dirja. Ia merangkul kedua lengan pemuda di sisi kanan dan kirinya. Menghela napas, kubidik objek di depan sana dengan suara petir menyambar di atas kepalaku. Usai itu, kuhampiri ia dan mengangsurkan kamera di depan mukanya. "Nggak bisa biasa aja ya, Mas?"
"Nggak."
Setelah puas mendapatkan bidikan objek sebanyak-banyaknya, kami turun dari jalanan kayu tersebut dan menukar kupon—yang kami dapat setelah membeli tiket—dengan teh yang masih mengepul di tea house. Kami perlu mengantre terlebih dahulu. Di depanku, Ara melingkarkan lengannya pada leher Kumala. Sementara aku ditugaskan untuk membawa tas kameranya di belakang. Di dalam tea house ada banyak pengunjung yang duduk santai seraya mendengarkan musik indie yang diputar.
Ada beberapa pengunjung pria yang melirikkan matanya, mencuri pandang pada gadis di depanku. Bila aku tak mengenal sopan santun, sudah kucolok mata mereka dengan jari-jariku. Mendekatkan bibir di telinga Ara, aku berbisik pelan. "Lain kali kalau keluar jangan pakai celana pendek." Ia berbalik dan menatapku sekilas. Melengos.
Setelah mendapatkan teh, kami memilih menggelar tikar kecil di halaman berumput karena kursi di dalam tea house sudah penuh. Baru saja aku mendesah lega karena pada akhirnya bisa duduk, suara Ara kembali membahana.
"Radiii. Fotoin aku di nama jalan yang itu dong! Bagus tuh," ajaknya, menarik-narik lenganku agar bersedia menuruti permintaannya. Sepertinya ini adalah bentuk pembalasan dendamnya kepadaku. Menahan dongkol, kudesahkan napas berat dan beranjak berdiri. Di sampingku, Dirja dan Pras tampak menahan senyum geli.
Sialan.
Ia berdiri di depan tanda bertuliskan Jl. Kenangan. Di bawah garisnya, tertuliskan Aku Sama Dia. Kukernyitkan dahi membacanya. Tulisan macam apa itu?
"Cepetan, Radiii."
"Iyaaa anjir."
Mengaktifkan kamera, kubidik ia yang berpose sebanyak-banyaknya di depan sana. Selama ia tak melepaskan maskernya, aku akan baik-baik saja. Sebelum aku mematikan lagi kameranya, ia berseru sambil menunjuk rumah yang berdiri di belakangnya. "Fotoin di sana, yuk!"
"Enggak."
"Yah. Ayolah, Diii."
"Kamu nggak mau baterai kameramu habis, kan?" Ia terdiam. Hendak enyah dari hadapannya, ia menahan lenganku dan berseru memanggil Dirja. Mau apa lagi ia? Menyambar kamera dari tanganku, ia memberikan benda itu kepada Dirja.
"Fotoin aku sama Radi." Spontan kutolehkan kepala memandangnya. Namun ia bersikap biasa saja. Di samping, ia merangkul lenganku seraya berbisik mengancam, "Jangan lupa senyum atau aku buka maskerku dan kukasih ke kamu." Wah, ancamannya begitu sekali. Daripada membuat kehebohan yang akan merepotkan kami semua nanti, kuputuskan untuk mengikuti permintaannya. Kupikir setelah lebih dari lima tangkapan kamera, ia akan berhenti. Namun, tidak sampai di situ. Ia malah melompat naik ke punggungku, spontan kutangkap kakinya agar tak terjatuh.
"Kamu ngapain sih?" Bisikku gaduh.
"Jangan protes dan senyum aja di depan kamera biar cepet." Kubuka mulut hendak memprotes ketika ia melepaskan maskernya. Di depan, Dirja melongo dan cepat-cepat membidik kami. Setelah keinginannya terpenuhi, ia turun dari punggungku dan memasang kembali maskernya. Secara instingtif aku berdiri di depannya agar ia tak dikenali kerumunan. Matanya bertemu dengan mataku.
"Kamu udah gila ya?"
Dari matanya yang menyipit, aku tahu bahwa ia tengah mengulas senyuman. "Aku nggak mau kalau foto sama kamu, wajahku tertutup. Karena aku nggak suka. Look, nggak ada yang mengenaliku." Sebelum ia berbalik menuju Pras dan Kumala, ia seolah-olah teringat sesuatu. "Ah ya. Terima kasih perlindungannya." Dan lantas ia berlalu pergi dengan langkah panjang-panjang. Aku yakin ia menertawiku saat ini.
Di sampingku, Dirja mengalungkan tas kamera setelah memasukkannya ke dalam. "Kamu ada sesuatu sama dia?"
"Hah?"
"Lho, status WhatsApp kamu itu apa?"
"Status apaan anjir?" Dengan gusar, kurogoh saku celanaku dan menarik ponsel. Ada banyak pesan-pesan yang memberondong masuk. Entah pesan grup ataupun pribadi. Aku melongo untuk beberapa saat melihat unggahan fotonya di depan kaca kamarku sendiri. Menggeser layar, mataku melotot ngeri melihat kontak yang tersemat di atas bersama pesan test contact yang sudah terkirim. Dirja yang mengintip di samping terkekeh-kekeh dan menepuk-nepuk punggungku, berlalu pergi mendahuluiku.
Kulempar pandangan pada Ara yang tengah mengobrol bersama Kumala. Lantas kembali menatap nama kontak yang membuatku ingin mengerang detik ini juga.
Ara Sayang.
***
Lewat jam makan malam kami baru sampai di rumah setelah mampir sejenak di rumah makan. Radi membungkus nasi pula untuk ibunya. Turun dari mobil, kulambaikan tangan pada Pras dan Dirja, mengatakan terima kasih pada mereka untuk hari ini. Mereka membalas lambaian tanganku sebelum berlalu pergi.
"Capek, nggak, La? Mandi sana." Gadis itu berjalan dengan langkah menyeret dan masuk ke rumah mendahului kami. Usai tak kudapati lagi Kumala, lenganku ditarik Radi dan membuatku berhenti. Kutatap ia dengan alis terangkat naik. Ia menyodorkan layar ponselnya padaku.
"Ini apa?" Oh, ia sudah tahu rupanya.
"Apaan? Aku, kan, cuma nyimpen kontakku. Buat jaga-jaga kalau nanti aku ada apa-apa." Ia mendesah tanda menyerah.
"Kamu kan di rumah terus. Ada apa gimana coba."
"Ya mungkin ada kejadian tak terduga? Kecelakaan, mungkin?"
"Kalau ngomong jangan ngawur." Matanya menatapku tak main-main. Menghela napas, ia mengusap rambutnya. "Perlu banget ya disemat begitu?"
"Jangan dilepas!"
"Perlu banget unggah foto?" Tak kujawab pertanyaan sarkastisnya. Sebelum ia berlalu mendahuluiku, kubuka suara dan menghentikan langkahnya.
"Kenapa? Takut cewekmu marah?" Berbalik, ia menatapku dengan alis berkerut tak mengerti. "Siapa? Sara?" Teringat lagi di dalam pikiranku nama kontak yang kali pertama mengomentari unggahan foto itu.
"Ngaco."
Hendak ia berlalu masuk ke dalam rumah, kutinju pinggangnya dan berjalan mendahului. Sementara itu, kudengar pisuhannya di belakang.
"Bu. Radi bawa makanan." Suaranya terdengar dari luar.
"Oalah. Ibu sudah makan kok, le. Kamu sudah makan?"
"Udah. Tadi. Makanya aku bungkus buat ibu."
Kulongokkan kepala dari dalam kamar. Ibu tersenyum manis madu padaku. "Elin suka tadi jalan-jalannya?"
Merangsek mendekati wanita itu, aku tersenyum lebar. "Suka, Bu. Zeline nggak pernah lihat yang begituan di ibu kota."
"Panggil Ara aja, Bu. Nama Zeline atau bahkan Elin itu jelek," sahut Radi yang berjalan memasuki kamarnya.
"Hush. Lambemu jangan ngawur."
Lantas ia tertawa di dalam sana. Kualihkan perhatianku kembali pada wanita di depanku. "Besok aku tunjukin ya fotonya ke Ibu. Bagus-bagus lho."
Wanita itu terkekeh, mengusap rambutku pelan. "Iya, Nduk. Sana, ganti baju dan istirahat ya. Kamu pasti lelah sekali."
Terakhir, sebelum berlalu pergi, kucium pipi wanita itu dan membuat tawanya membahana. Radi yang mengintip dari dalam kamar memutar bola mata. Masuk ke dalam, kucubit pinggangnya dan membuatnya mendesis.
"Etdah. Kamu kira nggak sakit?"
"Contoh tuh Ibumu. Nggak kayak kamu, nggak ada manis-manisnya." Mengeluarkan kamera dari dalam tas, kuisi daya benda itu di atas meja.
"Sok tahu. Teori dari mana itu?"
Berbalik, kutatap ia seraya berkacak pinggang. "Kamu kalau ngomong sama aku jutek banget. Aku heran, apa Tuhan kasih satu persen kelembutan pas nyiptain kamu?"
Perlahan, ia berjalan mendekat. Aku perlu mendongakkan kepala padanya ketika ia semakin memotong jarak di antara kami. Tangannya terulur, menyematkan rambutku ke belakang telinga. Beralih ke pipi dan berhenti pada leherku, lantas memajukan wajah tepat di dekat leher dan telingaku. Ini gila. Mengapa napasku tercekat?
"Mandi sana, baumu kayak kambing." Lantas, ia berbalik dan meninggalkanku yang melongo sendirian.
"RADIII!!!"


 valentina
valentina